Opini
Opini: Sumpah Pemuda dalam Tsunami Literasi
Sejatinya, kekuatan suatu bangsa selalu mengakar pada kualitas nalar dan kepekaan rasa generasi mudanya.
Oleh: Yogen Sogen
Penulis Buku “Di Jakarta Tuhan Diburu dan Dibunuh” & “Nyanyian Savana.” Menyukai dunia sastra dan politik. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN).
POS-KUPANG.COM - Setiap 28 Oktober, denting sejarah kembali nyaring, memanggil setiap jiwa untuk mengambil jeda, memaknai seruan magis pemuda-pemudi yang mengikrarkan “satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan.”
Sumpah Pemuda, sebuah kristalisasi cita-cita, berdiri tegak melampaui zaman sebagai tiang penyangga ke-Indonesia-an.
Namun, di tengah nyaringnya peringatan itu, ada getir yang tak terhindarkan dan melahirkan sebuah pertanyaan relfektif: sebagai pewaris nyala api pemuda 1928, mampukah kita memastikan generasi hari ini cakap membawa obor peradaban?
Sejatinya, kekuatan suatu bangsa selalu mengakar pada kualitas nalar dan kepekaan rasa generasi mudanya.
Baca juga: Opini: Sumpah Pemuda, Nasionalisme dan Bahasa
Hari ini, kabar-kabar pilu yang diungkapkan oleh Frans Pati Herin di Kompas pada 19 September 2025, mengenai “Darurat Literasi di NTT,” adalah alarm yang tak boleh diabaikan, ia harus masuk sebagai bagian dari perenungan Hari Sumpah Pemuda.
Media Kompas turut menghimpun beragam kemelut literasi, mulai dari siswa SMA yang belum lancar membaca, para siswa yang sekadar mengeja huruf namun kesulitan merangkai kata apalagi kalimat panjang, disertai minimnya intonasi dan tanda baca.
Kondisi serupa juga terjadi pada lulusan perguruan tinggi. Realitas tersebut menyuguhkan sebuah ironi, bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah kemunduran struktural.
Bahkan, Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, secara jujur turut mengakui rendahnya kemampuan literasi dan numerasi anak-anak NTT, kian mempertegas bahwa persoalan ini bukanlah riak kecil, melainkan tsunami yang mengancam masa depan generasi mendatang.
Ia juga berharap, Anggaran Rp 2,3 triliun yang dialokasikan dari APBD NTT untuk sektor pendidikan mestinya memantik sebuah perjuangan sungguh-sungguh dari para guru dan tenaga kependidikan.
Sebab, anggaran hanyalah bahan bakar dan mesinnya adalah jiwa dan dedikasi.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti yang secara terbuka mengakui kondisi literasi di Indonesia saat ini memprihatinkan.
Data yang diungkapkannya sangat mencengangkan, bahwa sebanyak 75 persen anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca, tetapi ironisnya, tak memahami apa yang mereka baca.
Ini bukan sekadar gagal membaca, tapi gagal menalar. Kita melahirkan generasi yang secara teknis melek huruf tetapi buta makna.
Realitas ini dipertegas oleh temuan global. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menyebutkan Indonesia menjadi negara dengan urutan kedua dari bawah terhadap literasi dunia.
Laporan UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen, yang berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca.
Angka ini adalah tamparan telak bagi kita yang mengklaim diri sebagai bangsa besar.
Kita seolah melenyapkan sejarah, bahwa republik ini berdiri atas ketajaman literasi para pejuang.
Masalah ini, kata Mendikdasmen Mu’ti, disebabkan adanya kesenjangan kualitas hasil belajar antarwilayah, sebuah ketimpangan akut dan struktural.
Hal ini menjadi tantangan fundamental pendidikan di Indonesia yang perlu dibenahi bersama.
Mu’ti mengatakan perlu ada intervensi lebih untuk mengatasi berbagai ketertinggalan, terutama di sebagian kawasan, khususnya Indonesia bagian timur, persis seperti yang tercermin dari kabar Darurat Literasi di NTT.
Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia justru berada di atas negara-negara Eropa.
Bahkan, menurut laporan World Population Review 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan produksi buku terbanyak kelima di dunia, yakni dengan 135.081 judul buku diterbitkan setiap tahunnya.
Ironi ini harusnya menggugah kesadaran kita, bahwa kita rajin memproduksi buku, tetapi masyarakat kita tidak membacanya.
Kuantitas penerbitan ternyata tidak menjamin kualitas nalar. Kita lebih cerewet di media sosial, tetapi lupa mempertajam nalar.
Membaca sebagai Ritual Komunal
Secara pribadi, saya masih menyimpan memori tentang bagaimana jiwa dan dedikasi itu pernah membentuk sebuah generasi.
Saya ingat betul, saat SD di SDK Lewotala, Kabupaten Flores Timur, ketika lonceng istirahat berbunyi, kami diarahkan guru-guru masuk ke perpustakaan.
Di ruangan itu, tersedia buku-buku cerita bergambar, seperti kisah Nabi Yunus dan Ikan Paus yang masih segar dalam ingatan ini.
Ada pula legenda dan cerita-cerita rakyat yang menari-nari dan merangkai imajinasi.
Kami dipersilakan untuk memilih buku-buku yang tersedia, kemudian mencari tempat di area sekolah untuk membaca.
Tepat di belakang sekolah, ada beberapa pohon beringin yang rimbun berdiri kokoh.
Saya memilih duduk di bawahnya, akarnya menjadi tempat duduk paling nyaman. Kami belajar bersama napas alam yang asri.
Satu pesan yang menjadi makna cerita ini adalah kami didoktrin oleh guru-guru untuk tiada istirahat tanpa membaca.
Waktu itu, membaca bukan sekadar rutinitas, melainkan ritual komunal. Kami membaca sembari bersuara agar saling mengoreksi intonasi dan tanda baca, mengolah rasa, membangun imajinasi liar, dan bertukar cerita.
Suasananya tampak seperti saling mendongeng. Hal-hal sederhana inilah yang menciptakan ‘romantika pendidikan’ yang mendasar, memastikan kami tumbuh dengan pondasi huruf dan angka yang kuat, mengasah kepekaan dan daya nalar.
Dan ketika kini datang kabar buruk dari NTT, seperti yang diungkap oleh para pegiat literasi dan bahkan pemimpin daerah sendiri, itu menunjukkan ada sesuatu yang koyak dalam tenun pendidikan kita, sebuah situasi yang tidak baik-baik saja.
Ini adalah sebuah kemunduran yang perlu kita koreksi bersama, apalagi di tengah derasnya gelombang teknologi digital yang mendikte ruang dan waktu kita.
Dalam situasi pelik ini, kita semua diajak untuk meneguhkan kembali semangat literasi.
Bagaimanapun juga, sejarah republik ini adalah sejarah ‘keberaksaraan’.
Pada tiap narasi perjuangannya para pemuda, tak lepas dari pemikiran bernas, mereka menyatu bersama buku dan pena.
Mereka menulis dan berdebat lewat tulisan melalui koran-koran dengan berbagai bahasa, sekalipun ada yang menulis di bawah tanah, dalam tekanan kolonial.
Literasi dalam Sejarah Perjuangan Bangsa
Setelah perdebatan penting dalam lintasan sejarah literasi dan identitas nasional Indonesia yang ditandai dengan deklarasi kebangsaan 1928, di tahun 1930 akhir menjelang kemerdekaan, Soekarno dan Mohammad Natsir berpolemik sengit melalui tulisan, seputar nasionalis sekuler dan nasionalis Islami.
Dalam rentang yang sama, muncul pula polemik kebudayaan antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Pramoedya Ananta Toer mengenai orientasi kebudayaan Indonesia yang dikenal sebagai Polemik Kebudayaan.
Polemik ini berpusat pada ide modernisasi yang digagas oleh STA melalui majalah Poedjangga Baroe.
Contoh-contoh historis tersebut menegaskan, bahwa sejarah perjuangan yang lahir dari darahnya pemuda Indonesia telah menyatu dengan alam literasi sejak dahulu kala.
Sementara Presiden Prabowo Subianto juga orang yang sangat dekat dengan buku, kita melihat, setiap kali Prabowo berkunjung ke luar negeri, pasti menyempatkan untuk membeli buku, dan pada waktu senggang banyak dihabiskan untuk membaca.
Presiden kedelapan ini juga mengaku bahwa perpustakaan adalah tempat favoritnya.
Bahkan, saat berpidato dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana UKRI, Bandung, Sabtu (18/10/2025), ia mengaku masih kerap belajar dengan membaca buku sekitar dua sampai empat jam setiap hari.
Ironisnya, saat ini arus digital telah merasuk ke segala lini kehidupan, merenggut waktu yang seharusnya digunakan anak-anak untuk belajar mengenal huruf dan angka secara organik, mengolah rasa, membangun kepekaan dan imajinasi.
Kita didikte oleh algoritma yang semakin mengenal kita, sementara kita kian kehilangan waktu untuk kembali ke dalam diri.
Kemampuan menalar yang organik dan pemikiran yang jernih dibabat habis oleh keputusan-keputusan mesin yang membuat kita berhenti berpikir kritis.
Kita kadang berpikir bahwa teknologi ini memampukan kita melihat segalanya, ia seperti mendekap kita lebih erat ketimbang orang-orang yang kita sayangi, padahal, ia sesungguhnya bukan ‘maha mengetahui’ sebab, imajinasi dan pikiran kita adalah tembok yang tak mampu ditembus oleh alat ini.
Literasi Melampaui Iman Digital
Sumpah Pemuda tidak sekadar dimaknai sebagai persatuan teritori, melainkan tentang persatuan pikiran, nalar dan peradaban.
Bagaimana mungkin kita bersatu sebagai bangsa jika kemampuan dasar untuk memahami dunia, yakni literasi kian tergerus?
Kita jangan terlampau jumawa mengklaim bahwa kecerdasan teknologi digital dan AI semata-mata membawa dampak baik. Tanpa daya nalar yang kuat, ia adalah bom waktu.
Menjadikannya sebagai “iman digital,” di mana kita menyerahkan segala keputusan pada mesin sebagai hakim atas kehendak kita adalah bencana dan awal dari kebodohan massal di masa depan.
Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari kesadaran kaum muda. Hari ini, kesadaran itu harus kembali digelorakan melawan kemunduran nalar.
Kita tidak hanya bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, tetapi kita harus bersumpah untuk bernalar satu dan berliterasi satu, karena hanya dengan persatuan nalar yang kokoh, kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat peradaban, bukan sebagai tirani yang membonsai pikiran.
Lebih dari itu, krisis literasi yang telah menjadi tsunami ini menuntut kita untuk kembali ke akar, kembali pada dedikasi para guru yang mengajarkan membaca sebagai ritual suci, sebagai pintu gerbang menuju kedalaman makna.
Anggaran triliunan yang digelontorkan negara tidak akan berarti tanpa menyalakan semangat dan komitmen untuk menjadikan setiap anak bangsa, di NTT maupun di manapun, cakap membaca dan menalar, tidak sekadar mengeja huruf tanpa menyentuh kedalaman maknanya.
Dengan demikian, tantangan ini adalah tantangan kolektif, sebuah panggilan untuk mengoreksi diri dan berjalan bersama, memastikan api Sumpah Pemuda 1928 tidak redup di tengah kegelapan makna, sebab, Sumpah Pemuda yang sejati adalah ketika generasi penerusnya mampu menyalakan obor peradaban dengan nalar yang tajam dan hati yang peka.
Selamat memaknai Sumpah Pemuda dalam reruntuhan dan puing-puing literasi. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News















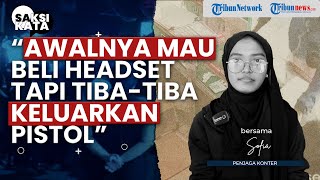





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.