Opini
Opini: DPR dan Luka Kolektif Rakyat
Di lapangan terlihat para demonstran membawa spanduk dengan slogan "Bubarkan DPR" dan "Rakyat Menderita, DPR Bermewah-mewah."
Oleh: Adrianus Dini
Mahasiswa Magister Fikom Universitas Padjadjaran Bandung
POS-KUPANG.COM - Gelombang demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa wacana kenaikan tunjangan anggota DPR hingga ratusan juta rupiah bukan semata-mata merupakan isu fiskal, melainkan juga masalah moral dan etika politik.
Rakyat marah, kecewa, dan merasa dikhianati oleh lembaga yang mereka harapkan akan mewakili kepentingan mereka dan berjuang untuk kesejahteraan mereka. Kemarahan ini bukanlah isapan jempol semata.
Di lapangan terlihat para demonstran membawa spanduk dengan slogan "Bubarkan DPR" dan "Rakyat Menderita, DPR Bermewah-mewah."
Hal itu menunjukkan ketidakpercayaan akut dari masyarakat terhadap parlemen.
Baca juga: Pengamat Politik Undana Angkat Bicara Tentang Polemik Kenaikan Tunjangan DPR RI
Isu ini patut dieksplorasi lebih lanjut karena berkaitan dengan legitimasi politik DPR sebagai representasi rakyat.
Tanpa kepercayaan publik, demokrasi adalah struktur kosong tanpa fondasi.
Peningkatan kesejahteraan anggota legislatif yang tidak proporsional di tengah penderitaan ekonomi masyarakat tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga mempertebal jurang yang sudah ada antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili.
Ketimpangan Upah dan Luka Ketidakadilan
Data yang dirilis oleh Indonesia Budget Center (2024) menunjukkan bahwa seorang anggota DPR menerima penghasilan bulanan lebih dari Rp 70 juta, belum termasuk tunjangan perjalanan, rumah dinas, staf ahli, hingga jatah kendaraan dan fasilitas lainnya.
Hal ini sangat kontras dengan pendapatan mayoritas masyarakat Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Februari 2024, sekitar 9,36 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pengeluaran per kapita perbulan hanya Rp 550.000 (BPS 2024).
Kondisi kontras inilah yang membuat rakyat geram. Kita barangkali masih ingat, Krisdayanti, salah satu anggota DPR pernah secara terbuka mengungkap bahwa gajinya sebagai anggota DPR mencapai Rp 70 juta, dan jika ditambah dengan tunjangan lainnya melebihi Rp 300 juta per bulan (Kompas.com, 2021).
Pernyataan itu kini kembali dipantik oleh isu kenaikan tunjangan fantastis DPR, sehingga publik beranggapan bahwa anggota DPR lebih sibuk mempertebal dompet daripada bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Demonstrasi sebagai Suara yang Tersumbat
Aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR tidak terjadi dalam kehampaan. Ini adalah bentuk “politik jalanan” ketika saluran perwakilan rakyat formal dianggap gagal (Tilly, 2004).
Rakyat merasa suara mereka tidak didengar, dan sebagai tanggapan mereka turun ke jalan untuk mengekspresikan keresahan mereka.
Di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, para demonstran secara kompak menyuarakan protes mereka terhadap ketidakadilan.
Dalam demonstrasi tersebut, pengunjuk rasa menuntut agar DPR membatalkan rencana kenaikan tunjangan dan menegaskan agar anggaran negara diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi pangan.
Bahkan, dalam tuntutan mereka, beberapa kelompok menyebut "Bubarkan DPR", sebuah ekspresi ketidakpercayaan ekstrem terhadap lembaga legislatif.
Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi antara DPR dan rakyat.
Ketidakadilan ini muncul karena DPR mengambil sikap yang lebih defensif dan tidak berusaha terlibat dalam dialog terbuka.
Padahal, legitimasi politik dibangun tidak hanya melalui pemilu tetapi juga melalui komunikasi berkelanjutan dengan publik (Habermas, 1996).
DPR dan Tugas yang Terabaikan
DPR seharusnya ditugaskan untuk mengawasi pemerintah, membuat undang-undang pro-rakyat, dan merumuskan anggaran yang adil.
Dalam Undang Undang MD3 disebutkan bahwa DPR mencakup dan menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Namun, dalam praktiknya, publik sering disajikan dengan berita mengenai rendahnya kehadiran anggota DPR hingga kasus korupsi yang melibatkan legislator.
Kesenjangan antara fungsi ideal DPR dan kenyataan ini menimbulkan krisis legitimasi.
Ketika DPR sibuk mengatur kenaikan tunjangan mereka sendiri, publik bertanya-tanya apakah lembaga ini masih harus dianggap sebagai representasi rakyat?
Komunikasi yang Hilang
Masalah terbesar DPR bukan soal uang semata, tetapi juga soal komunikasi politik yang buruk.
Di tengah arus protes, yang diperlukan bukan sekedar penjelasan normatif, melainkan komunikasi yang empati, terbuka dan transparan.
Mereka harus mengakui ketidaknyamanan publik, membuka data alokasi anggaran dan secara transparan menjelaskan alasan kenaikan tunjangan yang diusulkan.
Tanpa transparansi seperti itu, kebijakan akan terus dibingkai sebagai bentuk arogansi.
Dalam teori komunikasi politik dikatakan bahwa respons yang tertutup atau defensif hanya akan memperburuk krisis kepercayaan (McNair, 2018).
Sebaliknya komunikasi yang mengutamakan partisipasi publik, konsultatif dan transparansi akan mengurangi ketegangan.
Sayangnya, pola komunikasi DPR sering merepresentasi jurang yang luas antara elit dan rakyat ketimbang kedekatan seorang perwakilan dengan rakyatnya.
Alasan Isu Ini Harus Menjadi Sorotan
Usulan kenaikan tunjangan DPR bukan masalah nominal rupiah semata. Kondisi ini mencerminkan kegagalan elit politik untuk memahami realitas penderitaan rakyat.
Isu ini mengingatkan kita pada krisis representasi, yaitu ketika seorang wakil rakyat tidak lagi sejalan dengan kebutuhan rakyat (Pitkin, 1967).
Jika situasi ini dibiarkan, ketidakpuasan semacam ini dapat bergeser ke arah delegitimasi total terhadap demokrasi.
Oleh karena itu, dengan membahas isu ini, secara bersamaan kita mengadvokasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila.
Dalam ranah komunikasi politik, membahas masalah ini juga berarti menyerukan transparansi dan partisipasi aktif yang berfungsi sebagai dasar bagi demokrasi deliberatif.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Gelombang protes yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR adalah peringatan bagi demokrasi Indonesia.
Hal ini menunjukkan betapa meningkatnya krisis kepercayaan publik pada lembaga legislatif.
Kenaikan tunjangan di tengah kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia Adalah bentuk pengkhianatan demokrasi secara moral.
Alih-alih berlomba-lomba untuk menaikkan tunjangan, DPR seharusnya memprioritaskan integritas mereka dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
DPR harus kembali ke fungsi utamanya yaitu merumuskan kebijakan pro-rakyat, mengawasi pemerintah dengan cermat dan membangun komunikasi politik yang empati.
Saran konkret:
- Transparansi Anggaran: Publikasikan di situs resmi DPR secara terbuka, setiap komponen remunerasi termasuk gaji, tunjangan, dan tunjangan keuangan lainnya.
- Reformasi Internal: Segera menangguhkan atau membatalkan rencana kenaikan tunjangan sampai standar hidup rakyat membaik.
- Dialog Publik: Menyelenggarakan forum dialog terbuka dengan serikat pekerja, mahasiswa dan masyarakat sipil untuk membahas kebijakan penganggaran fiskal.
- Etika Komunikasi: Anggota DPR perlu menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam komunikasi empatik, alih-alih menjaga jarak yang arogan untuk mengurangi kesenjangan antara diri mereka dan masyarakat.
Pada akhirnya, rakyat hanya mencari keadilan. Ketika seorang petani sulit mendapatkan penghasilan 100.000 rupiah sehari, adalah keterlaluan bagi perwakilan rakyat untuk menuntut tunjangan hingga ratusan juta.
Demokrasi pasti akan runtuh jika para elit lebih sibuk memperkaya diri sendiri ketimbang memperjuangkan kesejahteraan warga negara yang mereka wakili. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News

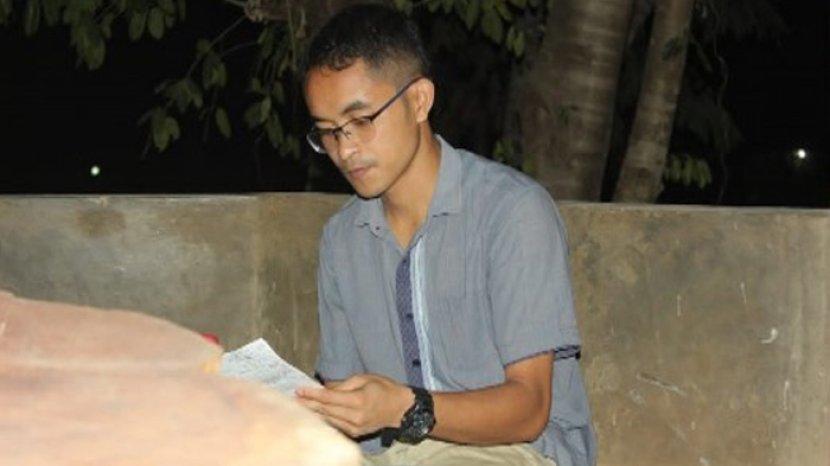













![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.