Opini
Opini: Pertarungan Narasi Kuasa vs Nurani Publik di Kasus Prada Lucky
Fokus harus dikembalikan pada keadilan bagi Prada Lucky sebagai hak publik, bukan sekadar urusan internal TNI.
Oleh: Danang Novika Ruswantara
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM - Tragedi kematian Prada Lucky Saputra Namo menjadi simbol luka kolektif dan ujian bagi negara dalam memenuhi rasa keadilan.
Ketika nyawa seorang abdi negara muda melayang akibat dugaan penyiksaan oleh lebih dari 22 seniornya, nurani masyarakat terkoyak.
Sebuah respons dari Korem 161/Wira Sakti kemudian dipersepsikan oleh sebagian masyarakat memperbesar kemarahan publik akibat dugaan minimnya kepekaan atas suasana duka.
Langkah tegas Kodam IX/Udayana baru-baru ini menjadi sorotan tajam. Berdasarkan laporan Tribunnews.com, Pelda Chrestian Namo, ayah dari mendiang Prada Lucky, dilaporkan secara resmi oleh Kodim 1627/Rote Ndao ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) IX/1 Kupang pada Rabu (5/11/2025).
Baca juga: Opini: TNI, Disiplin, dan Bayangan Keadilan yang Menjauh
Pelaporan ini terkait dugaan pelanggaran disiplin serius, yakni hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah pada tahun 2018.
Pertanyaan penting secara akademis: apakah timing pelaporan ini merupakan bagian dari penegakan aturan yang konsisten, ataukah sebuah langkah komunikasi yang berpotensi kurang sensitif terhadap konteks duka dan tuntutan keadilan publik?
Timing, Presepsi Publik, dan Analisis Teoritis
Pihak TNI sebenarnya telah memberikan penjelasan resmi. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Widi Rahman, S.H., M.Si., menegaskan bahwa proses hukum terhadap Pelda Chrestian Namo merupakan bagian dari penegakan disiplin internal TNI.
“Perlu kami tegaskan bahwa proses hukum terhadap Pelda Chrestian Namo murni karena pelanggaran disiplin prajurit. Hal ini tidak ada kaitannya dengan kasus lain,” ujarnya kepada awak media di Denpasar, Bali.
Pernyataan ini penting untuk menegaskan posisi institusi. Tentu saja, publik perlu menghormati jalannya proses hukum, baik terhadap 22 tersangka maupun terhadap Pelda Chrestian Namo, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi semua pihak.
Dari perspektif komunikasi krisis, langkah ini menimbulkan dua kemungkinan interpretasi.
Pertama, TNI konsisten menegakkan disiplin, sebagaimana dinyatakan Kapendam.
Kedua, publik bisa jadi mempersepsikan timing ini sebagai upaya pengalihan isu karena momentumnya yang bersamaan dengan puncak perhatian media terhadap kasus penyiksaan.
Meskipun TNI telah memberikan penjelasan resmi, tantangannya adalah mengelola persepsi publik yang cenderung melihat kaitan kausal dalam peristiwa yang berdekatan.
Secara teoretis, bagaimana publik membaca manuver ini dapat dipahami melalui lensa Framing (Entman, 1993).
Langkah ini, baik sengaja atau tidak, berpotensi berfungsi sebagai “Defensive Framing”, upaya yang dapat dipresepsikan mengalihkan fokus dari substansi kasus kekerasan sistemik menjadi isu moralitas pribadi keluarga.
Hasilnya, publik seolah dipaksa terdorong bertanya “mengapa prajurit bisa disiksa hingga meninggal?” menjadi “apakah ayah korban melanggar aturan?”.
Ini mengingatkan pada strategi diversion (pengalihan) “Red Herring”, yakni melempar isu yang tampak tidak relevan untuk mengalihkan perhatian dari isu utama.
Meski Kapendam menegaskan "tidak ada kaitan", di benak publik, kaitan itu bisa tercipta otomatis karena momentumnya.
Lebih jauh, persepsi publik kini dapat mencerminkan apa yang dalam teori Restorasi Citra William Benoit (1995) disebut sebagai strategi “Attacking the Accuser”.
Ketika institusi terdesak, respons defensif yang paling berisiko adalah mencoba meruntuhkan kredibilitas pihak yang menuntut pertanggungjawaban.
Harapannya, jika sang ayah dianggap "cacat moral", suaranya akan kehilangan gaung.
Hierarki Penderitaan dan Resistensi di Ruang Digital
Namun, di era digital, strategi semacam ini justru berisiko menjadi bumerang.
Publik hari ini memiliki literasi yang cukup tinggi untuk mendeteksi potensi manipulasi narasi.
Netizen beroperasi dengan "hierarki penderitaan" yang jelas bahwa kehilangan nyawa anak akibat penyiksaan berada di puncak hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggaran disiplin orang tuanya.
Upaya mengatur sorotan publik ke arah moralitas individu akhirnya terpatahkan oleh kontra-agenda warganet.
Media sosial pun menjadi arena resistensi, sebuah public sphere modern (Habermas, 1989) di mana masyarakat menolak dikendalikan oleh narasi tunggal.
Alih-alih memperbaiki citra, langkah ini justru memicu Streisand Effect yaitu upaya menutupi sesuatu yang malah membuatnya makin viral.
Hasilnya, simpati publik terhadap keluarga korban membesar, sementara kredibilitas institusi menurun.
Kekuasaan, Putar Haluan, dan Pendekatan Empati
Meminjam kacamata Michel Foucault, pelaporan resmi oleh Kodim Rote Ndao di momen krusial ini dapat dibaca sebagai praktik disciplinary power dimana kekuasaan yang bekerja untuk mendisiplinkan mereka yang menentang otoritas.
Namun, publik kini mampu membaca bahwa instrumen disiplin terkadang digunakan untuk menutupi ketidakadilan yang lebih besar.
Tantangan persepsi publik ini perlu dikelola dengan putar haluan strategi komunikasi.
Langkah pertama adalah Crisis Containment dengan melakukan decoupling (pemisahan tegas) antara kasus pidana 22 tersangka dengan riwayat disiplin keluarga.
Fokus harus dikembalikan pada keadilan bagi Prada Lucky sebagai hak publik, bukan sekadar urusan internal TNI.
Selanjutnya, diperlukan pendekatan "Empati". Institusi dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui bahwa meskipun penegakan disiplin penting, timing-nya mungkin dipresepsikan kurang peka terhadap suasana duka.
Publik perlu melihat pimpinan hadir sebagai "pengayom" yang ikut terpukul atas kehilangan nyawa prajuritnya, bukan sekadar birokrat penjaga aturan.
Mengembalikan Nurani Komunikasi Publik
Kasus Prada Lucky adalah cerminan tentang bagaimana lembaga negara kerap salah memahami komunikasi yaitu bukan sebagai jembatan empati, melainkan alat kendali.
Di tengah krisis, publik tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kejujuran.
Kematian Prada Lucky bukan hanya tragedi personal, tetapi ujian bagi komunikasi publik militer bahwa apakah akan terus berlindung di balik hierarki kekuasaan, atau mulai menatap masyarakat dengan kesetaraan moral.
Ketika negara menekan suara korban, media sosial akan memperkuatnya. Keadilan mungkin tertunda, tetapi dalam ruang publik digital,kebenaran sulit dibungkam.
Analisis atas krisis komunikasi ini tidak boleh berhenti sebagai kritik semata.
Jika kebenaran terbukti sulit dibungkam, maka langkah selanjutnya adalah membangun jalan bagi kebenaran itu untuk memandu perbaikan.
Mengembalikan "nurani komunikasi" yang sejati menuntut langkah konkret dari semua pihak.
Bagi TNI, langkah yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi prosedur komunikasi krisis agar lebih transparan dan empatik, serta memisahkan tegas pesan disiplin internal dari kasus pidana.
Institusi perlu menginisiasi dialog terbuka dengan keluarga korban dan publik.
Kepercayaan hanya akan pulih jika proses hukum terhadap 22 tersangka berjalan transparan, adil, dan hasilnya dikomunikasikan secara terbuka.
Di sisi lain, keluarga dan publik berperan mengawal kasus ini melalui advokasi hukum yang damai dan proporsional, menghindari polarisasi.
Penting bekerja sama dengan lembaga advokasi (misal: Komnas HAM, LBH) agar pengawalan ini tidak hanya menjadi konsumsimedia, tetapi juga berdampak pada perbaikan sistem perlindungan prajurit di masa datang.
Upaya-upaya ini adalah jembatan untuk menggeser "pertarungan narasi" menjadi "kolaborasi mencari keadilan".
Dengan langkah konkret dan empati, suara Prada Lucky tidak hanya akan hidup dalam gema solidaritas, tetapi juga dalam reformasi institusi yang lebih adil dan manusiawi. (*)
(Disclaimer: Opini dalam tulisan ini merupakan pandangan dan analisis akademis pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap resmi institusi FISIP Universitas Nusa Cendana, tempat penulis bernaung.)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Danang Novika Ruswantara
Chrestian Namo
Prada Lucky Namo
penganiayaan
Tentara Nasional Indonesia
Hukum dan Keadilan
Opini
prajurit
| Opini: Dari Sampar, Covid-19 hingga Rabies di Nusa Tenggara Timur |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Asrul.jpg)
|
|---|
| Opini: Pahlawan dan Politik Ingatan |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Ferdinandus-Jehalut1.jpg)
|
|---|
| Opini: Hari Pahlawan dan Krisis Kesadaran Sejarah |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Inosensius-Enryco-Mokos1.jpg)
|
|---|
| Opini: Menenun Harapan dari Tanah Luka, Perempuan dan Logika Tambang di Timur |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Try-Suriani-Loit-Tualaka3.jpg)
|
|---|
| Opini: Ketika Kabupaten Manggarai Belum Benar-benar Siap Melawan Rabies |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Aldo-Corason1.jpg)
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Danang-Novika-Ruswantara1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Hamzah-Baharudin.jpg)






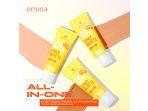


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Ferdinandus-Jehalut1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Danang-Novika-Ruswantara1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Asrul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Adrianus-Ngongo3.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.