Opini
Opini: Menenun Harapan dari Tanah Luka, Perempuan dan Logika Tambang di Timur
Pemerintah menjanjikan tambang sebagai jalan keluar dari kemiskinan, menawarkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Oleh : Try Suriani Loit Tualaka
Peneliti Junior di Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)
POS-KUPANG.COM - “Kemajuan sering diukur dari seberapa dalam tanah digali, bukan dari seberapa banyak kehidupan yang tumbuh di atasnya.”
Ungkapan ini terasa nyata di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana tambang kerap dijadikan simbol kemajuan dan kesejahteraan.
Namun di balik jargon pembangunan, tanah-tanah adat retak, air mengering, dan perempuan penjaga sumber-sumber kehidupan terdesak oleh logika ekonomi yang mengubah alam menjadi komoditas.
Selama dua dekade terakhir, industri ekstraktif telah menggurita di wilayah ini: dari mineral, batu gamping, emas, hingga mangan, semua digali atas nama pembangunan.
Baca juga: Opini: Ketika Kabupaten Manggarai Belum Benar-benar Siap Melawan Rabies
Pemerintah menjanjikan tambang sebagai jalan keluar dari kemiskinan, menawarkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Namun realitasnya menunjukkan hal yang berlawanan. Data dari Media Indonesia (2019) mencatat bahwa dari 353 perusahaan tambang logam dan nonlogam yang terdaftar di NTT, hanya 23 yang memenuhi syarat administrasi, teknis, dan keuangan untuk beroperasi.
Laporan lain menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT tak sampai dua persen, tepatnya sekitar 1,34 persen (Floresa.co, 2014).
Bahkan pemerintah daerah sendiri mengakui tidak memiliki data pasti mengenai potensi cadangan mangan yang selama ini dijadikan komoditas unggulan (KatongNTT.com, 2023).
Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa tambang bukanlah jalan menuju kesejahteraan, melainkan jalan menuju krisis ekologis dan sosial.
Yang tersisa di banyak wilayah hanyalah lubang-lubang besar, konflik sosial, dan hilangnya ruang hidup masyarakat.
Di tengah luka itu, perempuan menenun harapan bukan dari benang dan kapas semata, tetapi dari perlawanan terhadap logika pembangunan yang meminggirkan mereka, serta dari keyakinan bahwa tanah bukan sekadar sumber daya, melainkan sumber kehidupan.
Ekstraktivisme yang Sama, Lanskap yang Berbeda
Meski kontribusinya kecil terhadap ekonomi daerah, jejak sosial dan ekologis industri tambang di NTT sangat besar.
Di berbagai wilayah seperti Lengko Lolok, Luwuk, Poco Leok, hingga Nausus, masyarakat adat kini menghadapi ancaman kehilangan tanah ulayat, sumber air, dan ruang hidup yang selama ini menopang keberlanjutan komunitas.
Di Manggarai Timur, izin tambang batu gamping diberikan di wilayah tangkapan air yang vital bagi pertanian dan kebutuhan rumah tangga warga.
Di Poco Leok, proyek panas bumi yang diklaim sebagai “energi hijau” justru menimbulkan keresahan karena berada di wilayah ulayat dan ekosistem pegunungan yang menjadi sumber air utama.
Sementara di Nausus, Timor Tengah Selatan, aktivitas penambangan marmer dua dekade silam meninggalkan jejak luka yang belum sembuh: bukit-bukit batu dipotong, aliran air terganggu, dan kawasan hutan kecil yang dulu menjadi nadi kehidupan berubah menjadi lahan gersang.
Pola kemunculan dan warisan tambang ini memperlihatkan bagaimana logika ekonomi ekstraktif terus menembus ruang hidup masyarakat adat tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber air, serta nilai-nilai kultural yang melekat pada tanah.
Pola serupa juga terlihat di Kalimantan Timur, terutama di wilayah Sanga-Sanga yang telah lama menjadi pusat tambang batu bara.
Sejak masa kolonial hingga kini, daerah ini terus dieksploitasi dengan dalih pembangunan nasional dan penyediaan energi bagi industri.
Namun di balik kontribusi besarnya terhadap pendapatan negara, yang tersisa bagi masyarakat lokal hanyalah kerusakan ekologis dan kemiskinan struktural.
Lubang-lubang tambang menganga di antara permukiman dan sawah, mencemari sungai, serta menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga.
Lanskap yang dahulu hijau kini berubah menjadi padang tandus penuh genangan air asam tambang.
Skalanya mungkin berbeda, tetapi polanya sama: di Kalimantan, eksploitasi berlangsung di tengah sumber daya yang melimpah; di NTT, ia dijalankan di atas tanah yang kering dan rapuh.
Dua lanskap berbeda yang diikat oleh logika yang sama ekstraktivisme yang memuja pertumbuhan ekonomi sambil menanggalkan keseimbangan antara manusia dan alam.
Dalam keduanya, tubuh perempuan dan tubuh bumi mengalami luka yang serupa: keduanya dieksploitasi, dijadikan alat produksi, dan disisihkan dari ruang pengambilan keputusan.
Dari sinilah, perlawanan tumbuh pelan, tapi pasti dari tangan-tangan perempuan yang menenun kehidupan kembali di atas tanah yang luka.
Negara di Persimpangan: Antara Modal dan Kehidupan
Di tengah luka ekologis yang membentang dari pesisir hingga pegunungan, negara tampak gamang menentukan arah: berpihak pada kehidupan atau tunduk pada logika modal.
Wacana transisi energi dan pembangunan hijau yang gencar dikumandangkan kerap menjadi tameng moral untuk menutupi pola lama eksploitasi sumber daya alam.
Di lapangan, yang terjadi bukan transformasi menuju keadilan ekologis, melainkan reproduksi krisis dengan wajah baru.
Di NTT, tambang mangan meninggalkan lahan-lahan mati dan petani tanpa penghidupan.
Di Kalimantan Timur, lubang-lubang tambang batu bara yang dibiarkan menganga menjadi kuburan bagi anak-anak dan masa depan yang hilang.
Negara hadir bukan sebagai penjaga kehidupan; pemberi izin yang tuli terhadap suara rakyat, berbicara tentang kesejahteraan sambil menutup mata pada penderitaan ekologis yang diciptakannya sendiri.
Keadilan ekologis berhenti di tataran wacana, sementara ketimpangan sosial dan kerusakan alam terus dilegalkan atas nama pembangunan.
Kenyataan ini menyingkap paradoks paling mendasar dalam politik pembangunan Indonesia: negara yang seharusnya menjadi pelindung ruang hidup justru bersekutu dengan kekuatan ekonomi yang merusaknya.
Di balik jargon “investasi” dan “pertumbuhan,” terselubung relasi kuasa yang timpang antara korporasi, birokrasi, dan warga.
Pemerintah daerah yang menggantungkan harapan pada pendapatan tambang sering menukar keberlanjutan dengan janji palsu kemajuan, sementara pemerintah pusat meminjam narasi nasionalisme ekonomi untuk melanggengkan proyek ekstraktif berskala besar.
Ketika sumber daya terkuras dan modal angkat kaki, yang tersisa hanyalah lanskap luka: tanah yang rusak, air yang tercemar, dan masyarakat kehilangan pegangan hidup.
Dalam konteks ini, ketidakadilan ekologis bukan sekadar kegagalan kebijakan lingkungan, melainkan bentuk pengkhianatan negara terhadap mandat konstitusionalnya untuk melindungi kehidupan manusia dan alam dari keserakahan yang disamarkan sebagai pembangunan.
Namun, di tengah absennya negara sebagai pelindung kehidupan, justru dari ruang-ruang lokal tumbuh kekuatan baru yang menantang logika dominan itu: perempuan.
Di tengah tekanan proyek-proyek ekstraktif yang menggerus ruang hidup, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus yang pertama bangkit untuk melawan.
Ketika tanah dirampas dan air tercemar, beban kehidupan sehari-hari dari menyediakan pangan, air, hingga menjaga kesehatan keluarga jatuh di pundak mereka.
Tetapi dari luka dan keterpinggiran itu lahir kekuatan politik baru yang berakar pada pengalaman tubuh dan ingatan ekologis perempuan.
Perempuan-perempuan adat di NTT dan Kalimantan Timur menolak dipinggirkan oleh logika pembangunan maskulin yang mengukur kemajuan dari seberapa banyak tanah digali, bukan dari seberapa banyak kehidupan yang dipelihara.
Mereka menjadikan praktik menenun, berkebun, merawat air, dan menjaga hutan sebagai bentuk perlawanan yang tak hanya simbolik, tetapi juga politis, menegaskan hak atas ruang hidup dan kedaulatan ekologis.
Dalam perjuangan mereka, makna “pembangunan” direbut kembali: bukan sebagai proyek menggali dan menguasai, melainkan sebagai upaya merawat kehidupan.
Perlawanan perempuan di ruang-ruang lokal ini menjadi pengingat bahwa transformasi ekologis tidak akan lahir dari kebijakan yang dikuasai modal, tetapi dari tangan-tangan yang setia menjaga bumi dari ambisi mereka yang ingin memilikinya.
Menenun Perlawanan, Merawat Kehidupan
Dari Mollo di pegunungan Timor hingga Poco Leok di Flores dan Sanga-Sanga di Kalimantan Timur, jejak perjuangan perempuan memperlihatkan wajah paling nyata dari keadilan ekologis yang tumbuh dari bawah.
Di Mollo, Mama Aleta Baun perempuan adat Molo memimpin ratusan perempuan menenun di lokasi tambang marmer sebagai bentuk perlawanan damai terhadap perusahaan yang merusak batu dan sumber air di tanah mereka.
Aksi menenun di tengah deru mesin tambang menjadi simbol kekuatan perempuan yang mengubah kerja keseharian menjadi tindakan politik: sebuah cara menegaskan kasih terhadap bumi dan hak untuk hidup layak di tanah sendiri.
Dalam satu momentum bersejarah, para perempuan adat bahkan melakukan aksi bertelanjang dada tindakan yang amat berani dalam budaya lokal untuk menunjukkan betapa bumi mereka telah dilucuti dan dilukai.
Bagi mereka, tanah bukan sekadar benda mati, melainkan tubuh ibu yang memberi kehidupan.
Gerakan ini kemudian mengguncang kesadaran publik dan memaksa negara serta korporasi mundur; perjuangan Mama Aleta diakui dunia melalui penghargaan Goldman Environmental Prize pada tahun 2013.
Di Poco Leok, perempuan-perempuan Manggarai menghadang proyek panas bumi yang diklaim sebagai energi hijau.
Bagi mereka, Poco Leok bukan lahan eksploitasi, melainkan ruang spiritual tempat leluhur bersemayam sekaligus sumber air yang menopang kehidupan banyak desa.
Mereka menegaskan bahwa tidak ada energi yang benar-benar “hijau” bila dibangun di atas perampasan ruang hidup dan penghancuran relasi ekologis.
Sementara di Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, perempuan menghadapi ancaman batu bara yang tak pernah usai: merawat anak-anak di tengah debu tambang, mengorganisir aksi menuntut reklamasi lubang maut, serta menagih tanggung jawab negara atas kerusakan yang mencabut kehidupan mereka.
Dalam kisah-kisah ini, perlawanan perempuan bukan sekadar keberanian moral, tetapi pengetahuan ekologis yang diwariskan turun-temurun dan dijalankan dalam praktik keseharian cara menegaskan bahwa menjaga bumi berarti menjaga masa depan umat manusia.
Kini, ketika krisis iklim kian nyata di NTT ditandai oleh kemarau panjang, gagal panen, dan kelangkaan air bersih konsekuensi dari model pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam tampak semakin telanjang.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa NTT merupakan salah satu provinsi dengan jumlah hari tanpa hujan terpanjang di Indonesia, mencapai lebih dari 150 hari per tahun di sejumlah kabupaten.
Kondisi ekstrem ini diperparah oleh deforestasi, degradasi lahan akibat aktivitas tambang, dan hilangnya tutupan vegetasi yang selama ini menjadi penyangga ekosistem air.
Di banyak tempat, masyarakat menghadapi sumur yang mengering, sawah yang retak, dan udara yang kian panas sementara izin tambang baru terus diterbitkan atas nama investasi dan kemajuan.
Ironisnya, di tengah krisis ekologis yang kian genting, pemerintah masih menatap tambang sebagai “solusi”, seolah menggali lebih dalam berarti memperbaiki nasib rakyat.
Padahal, dari sanalah akar krisis bermula: ketika alam direduksi menjadi komoditas, dan kesejahteraan diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan dari keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan.
Pembangunan yang Merawat, Bukan Menghancurkan
Di tengah krisis yang kian menekan, perempuan dari Mollo, Nausus, Poco Leok, hingga Sanga-Sanga di Kalimantan Timur tampil sebagai penjaga kehidupan.
Mereka menolak tambang bukan karena menentang pembangunan, tetapi karena memahami bahwa pembangunan sejati tidak boleh menghancurkan sumber kehidupan.
Ketika tanah retak dan air menghilang, mereka menenun, menanam, dan menjaga alam sebagai wujud cinta pada masa depan.
Gerakan perempuan tambang di NTT memperlihatkan wajah lain dari pembangunan yang berakar pada solidaritas, kemandirian, dan penghormatan terhadap alam.
Dari perjuangan mereka, kita belajar bahwa kesejahteraan tidak diukur dari angka investasi, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
Dalam tangan perempuan, pembangunan menemukan kembali maknanya: bukan sebagai proyek ekonomi, melainkan tindakan merawat kehidupan.
NTT tidak membutuhkan lebih banyak tambang, melainkan arah pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan hidup.
Pengalaman panjang menunjukkan bahwa industri ekstraktif hanya meninggalkan luka di tanah dan di hati masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu berhenti menjadikan tambang sebagai simbol kemajuan, dan mulai menata ulang visi pembangunan yang berkeadilan ekologis serta melibatkan perempuan dan komunitas lokal sebagai penjaga kehidupan.
“Bagi masyarakat NTT, tanah bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan rahim kehidupan tempat manusia dan alam tumbuh berdampingan.” (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
| Opini: Ketika Kabupaten Manggarai Belum Benar-benar Siap Melawan Rabies |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Aldo-Corason1.jpg)
|
|---|
| Opini: TNI, Disiplin, dan Bayangan Keadilan yang Menjauh |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Vitalis-Wolo2.jpg)
|
|---|
| Opini: Pembahasan APBD 2026 di Tengah Pemotongan Transfer Ke Daerah |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Wily-Mustari-Adam.jpg)
|
|---|
| Opini: Ketika Narasi Jadi Peluru, Politik Hobbesian di Media Sosial |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Ilustrasi-media-sosial-123.jpg)
|
|---|
| Opini: Urgensi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Nusa Tenggara Timur |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Dody-Kudji-Lede2.jpg)
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Try-Suriani-Loit-Tualaka3.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Hamzah-Baharudin.jpg)






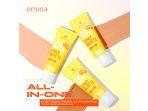


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Ferdinandus-Jehalut1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Danang-Novika-Ruswantara1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Asrul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Adrianus-Ngongo3.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.