Opini
Opini: Resistensi Lokal Terhadap Proyek Geotermal di NTT, Belajar dari Berbagai Kajian
Faktor lain yang mewarnai kuatnya resistensi adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pengelola proyek dan pemerintah.
Oleh: Emanuel Bria
Peneliti Ekonomi Politik Sumber Daya Energi dan Mineral
POS-KUPANG.COM - Di dalam kerangka pembangunan energi bersih dan terbarukan di Indonesia, provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) sering disebut sebagai daerah dengan potensi energi hijau yang melimpah.
Salah satunya adalah geotermal atau panas bumi yang ditawarkan pemerintah sebagai solusi energi masa depan karena ramah lingkungan, dapat memenuhi kebutuhan listrik dan mendorong pembangunan daerah.
Namun demikian, upaya untuk memaksimalkan sumber daya energi geotermal di NTT tidak berjalan mulus. Gerakan resistensi masyarakat lokal dan Gereja Katolik makin menguat.
Hal tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa geotermal yang merupakan salah satu sumber energi hijau menjadi sumber konflik dan resistensi di akar rumput?
Berikut beberapa catatan berdasarkan berbagai studi terkait konflik dan resistensi masyarakat lokal terhadap proyek-proyek energi dan mineral di berbagai negara yang sekiranya relevan sebagai bahan refleksi bersama dan masukan bagi semua pemangku kepentingan untuk konteks NTT.
Studi-studi terkait konflik sumber daya (resource conflict) di berbagai tempat seperti yang dilakukan Marta Conde (2015) dan sebagainya mengangkat beberapa hal berikut sebagai akar atau sebab-sebab utama penolakan dan resistensi masyarakat lokal terhadap proyek-proyek energi dan mineral.
Pertama, benturan antara metabolisme ekonomi subsistensi versus ekstraksi
Di dalam studi konflik sumber daya, masuknya proyek-proyek energi dan mineral sering ditandai dengan adanya "clash of metabolisms"—benturan antara dua model ekonomi dan pola hidup yang sangat berbeda.
Misalnya di NTT, masyarakat lokal terutama para petani dan masyarakat adat menjalani kehidupannya dengan pola subsistensi yakni bertani, beternak dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung untuk menopang kehidupan harian.
Bagi para petani kecil dan masyarakat adat, tanah, air dan alam bukan hanya sebuah komoditas ekonomi namun sumber pangan, air minum, obat-obatan alami dan juga ruang kebudayaan dan spiritual.
Sementara proyek-proyek energi termasuk yang bersih dan terbarukan dijalankan dengan logika industri skala besar yang membutuhkan lahan yang besar untuk pembangunan proyek termasuk berbagai infrastruktur penunjangnya sehingga menyebabkan perubahan tata lahan.
Hal tersebut dapat mendisrupsi tatanan hidup masyarakat lokal yang subsisten dan membuat mereka tersingkir secara permanen dari tanah-tanah mereka sendiri.
Dalam situasi seperti itu, resistensi masyarakat lokal sesungguhnya digerakan oleh insting manusia yang sangat purba yaitu bertahan hidup (survival).
Kedua, kurangnya partisipasi dan hak masyarakat lokal untuk menentukan nasib sendiri
Di dalam berbagai studi, resistensi terhadap proyek-proyek energi berskala besar muncul karena tiadanya partisipasi masyarakat lokal yang bermakna, misalnya ketika mereka hanya dilibatkan untuk sosialisasi proyek dengan komunikasi satu arah namun hak mereka untuk menentukan apakah sebuah proyek dapat berjalan atau tidak di wilayahnya, tidak diakui.
Padahal sesuai kaidah Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendekatan pembangunan berkelanjutan, masyarakat yang tingggal di wilayah terdampak berhak untuk menentukan arah pembangunan yang hendak mereka tempuh.
Kosongnya ruang demokratis ini menjadikan masyarakat lokal merasa ditinggalkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut hidup matinya mereka sendiri dan resistensi menjadi satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh.
Ketiga, kompensasi ekonomi tak setara dengan kerugian ekologis dan sosial
Praktik umum yang kerap dilakukan oleh korporasi dan pemerintah untuk meredakan gerakan resistansi masyarakat lokal adalah kompensasi finansial.
Namun, pengalaman di berbagai negara menunjukan bahwa nilai uang tunai tidak pernah sebanding dengan kerugian kehilangan tanah warisan, sumber air bersih, dan keberagaman hayati yang menopang kehidupan harian mereka.
Kompensasi uang, apalagi yang bersifat satu kali, tidak cukup untuk memulihkan daya dukung lingkungan ataupun relasi sosial yang rusak akibat ekspansi proyek industri energi berskala besar.
Dalam jangka panjang, kerugian sosial-ekologis ini dapat menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru, rusaknya relasi sosial dan budaya, bahkan bisa menambah jumlah pengangguran di pedesaan karena basis ekonomi subsistensi mereka seperti pertanian telah hilang.
Keempat, ketidakpercayaan terhadap negara dan korporasi
Faktor lain yang mewarnai kuatnya resistensi adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pengelola proyek dan pemerintah.
Hal ini dapat muncul dari pengalaman langsung masyarakat atas janji-janji pembangunan, lapangan kerja, atau fasilitas publik yang diungkapkan pemerintah maupun korporasi, namun tidak pernah benar-
benar diwujudkan.
Di sisi lain, beban kerusakan lingkungan dan dampak sosial justru lebih dirasakan masyarakat.
Ketidakpercayaan ini diperburuk oleh lemahnya transparansi atau keterbukaan informasi dan sulitnya akses warga pada data-data teknis proyek.
Selama perusahaan dan pemerintah gagal membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan setara, maka resistensi masyarakat lokal niscaya akan terus menguat.
Kelima, ketiadaan ruang aspirasi dan representasi
Allard dan Banks (2003) serta sejumlah studi yang lain menunjukan bahwa di banyak wilayah yang kaya akan sumber daya energi dan mineral, termasuk daerah-daerah terpencil seperti di NTT (resource frontier), negara tidak hadir secara efektif sebagai pelindung hak-hak rakyat.
Mekanisme-mekanisme formal negara baik itu lewat jalur legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tidak hadir sebagai mekanisme partisipatoris-deliberatif yang memungkinkan rakyat menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka.
Jika masyarakat kehilangan ruang aspirasi, sarana pengaduan, dan akses kepada wakil politik, maka jalan satu-satunya yang rasional untuk menyuarakan kepentingan mereka adalah melalui aksi protes, mobilisasi gerakan, dan perlawanan terbuka.
Menuju model pembangunan energi yang berkeadilan
Konflik sosial dan resistensi masyarakat terhadap pembangunan energi geotermal di NTT, merupakan sebuah fenomena yang perlu dilihat, dibaca dan didengarkan dengan serius oleh pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Inilah isyarat penting bahwa model pembangunan energi seperti geotermal di NTT harus berubah.
Kuncinya adalah mengakui, menghargai, dan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek pengambilan keputusan, bukan objek pembangunan.
Dialog yang setara dan terbuka, memastikan perlindungan hak masyarakat lokal atas tanah dan pembagian manfaat yang adil haruslah menjadi prasyarat bagi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan energi di NTT.
Membuka ruang demokrasi di tingkat tapak bukan hanya menyehatkan proses pembangunan energi, tetapi juga meminimalkan konflik sosial dan membuka ruang bagi adanya transisi energi bersih dan terbarukan yang benar-benar adil.
Akhirnya, resistensi masyarakat lokal di NTT terhadap proyek geotermal perlu dilihat sebagai sebuah pernyataan yang kuat: energi bersih dan terbarukan hanya layak dikejar jika ia juga adil bagi mereka yang hidup paling dekat dengan sumber dayanya. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News















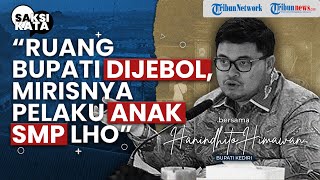





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.