Opini
Opini: AI, Agama dan Ego Digital, Membaca Polarisasi Moral Lewat Lensa Jonathan Haidt
Salah satu dari sekian banyak fenomena adalah maraknya foto maupun video berbasis AI, yang memadukan manipulasi suara dan visual dengan tujuan
Oleh: Berno Jani
Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere - NTT
POS-KUPANG.COM - Belakangan ini teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi produsen konten yang masif, cepat, dan nyaris tanpa batas.
Salah satu dari sekian banyak fenomena adalah maraknya foto maupun video berbasis AI, yang memadukan manipulasi suara dan visual dengan tujuan hiburan, sindiran, maupun provokasi.
Namun, ketika unsur agama dimasukkan tanpa tanggung jawab etis, maka yang muncul adalah bentuk penistaan terhadap agama. Seperti foto memdiang Paus Fransiskus yang bersekutu dengan Lucifer maupun tokoh agama lainnya.
Konten semacam ini, alih-alih menjadi alat kreatif untuk mengekspresikan pendapat, justru memantik konflik sosial yang memecah-belahkan prinsip persatuan dan toleransi.
Di sinilah pentingnya membangun literasi etika digital. Literasi bukan hanya soal melek teknologi, melainkan juga soal bagaimana manusia memperlakukan teknologi sebagai cerminan nilai dan tanggung jawab.
Ketika meme AI digunakan untuk menyentuh ranah keagamaan atau identitas spiritual tertentu, maka timbulah permusuhan.
Dalam menanggulangi problematika ini, saya memakai pemikiran Jonathan Haidit.
Jonathan Haidt menyebut fenomena ini sebagai bagian dari “tribalisme digital”, di mana media sosial memperkuat loyalitas kelompok dan memicu polarisasi.
Ia menegaskan bahwa AI harus tetap memperhatikan kebijaksanaan moral yakni bagaimana menjaga ekspresi tetap dalam batas yang tidak melukai keyakinan orang lain.
Kendatipun bangsa Indonesia mengedepankan kebebasan berpendapat, tetapi prinsip saling menghormati dan menjaga harmoni antarumat beragama harus tetap dijunjung tinggi.
Menjaga Kebebasan Beragama
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya dalam bentuk foto atau video meme, telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga kebebasan beragama dan kerukunan umat di Indonesia.
Foto atau video meme AI memungkinkan manipulasi visual dan audio terhadap tokoh atau simbol keagamaan secara realistis yang kerap dikemas dalam bentuk humor, sindiran, atau bahkan ejekan terbuka.
Hemat saya, kebebasan berekspresi di sini sudah “melampaui batas” karena menjadi sumber konflik yang terwujud dalam bentuk penistaan agama apabila isi foto atau video yang merendahkan ajaran, simbol, atau tokoh agama tertentu.
Salah satu contoh dari bentuk penistaan agama ini adalah munculnya pelbagai meme Paus Pransiskus dan Paus Leo XIV yang bersekutu dengan setan.
Selain itu, pada 21 April 2025, setelah wafatnya Paus Fransiskus, Presiden AS Donald Trump memicu kontroversi global dengan memosting gambar AI dirinya mengenakan jubah Paus di platform Truth Social.
Tindakan ini menuai kecaman dari Gereja Katolik, dengan Konferensi Katolik Negara Bagian New York menyebutnya penghinaan, sementara media Italia mengecam Trump sebagai "megalomania patologis."
Meskipun Trump mengklaim ingin memberi penghormatan kepada Paus, kritik muncul terkait kesopanan dan etika. Beberapa sekutu Trump membela tindakan tersebut sebagai humor.
Tegangan antara Trump dan Gereja Katolik, terutama terkait kebijakan imigrasi, telah berlangsung lama.
Hubungan ini turut memengaruhi konklaf 2025, dengan beberapa kandidat dari AS yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan Gereja Katolik.
Bangsa Indonesia sendiri melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, tetapi bukan berarti bebas tanpa batas.
Negara juga berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama dengan membatasi ekspresi yang berpotensi memecah belah atau menyinggung keyakinan pihak lain.
Video meme AI digunakan untuk memalsukan suara tokoh agama, meniru bacaan kitab suci dengan suara tidak pantas, atau menyampaikan pesan keagamaan yang diselewengkan secara digital dapat dikategorikan sebagai penodaan agama dalam perspektif hukum nasional.
Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pelaku penistaan agama melalui video AI dapat dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tahun 2016.
Namun, penerapan hukum ini menghadapi tantangan teknis, seperti anonimitas pembuat konten, kecepatan penyebaran di media sosial, dan kurangnya kesadaran digital masyarakat.
Meskipun beberapa kasus penistaan agama telah berujung pada proses hukum, banyak pelaku, terutama dari kalangan remaja, tidak memahami bahwa apa yang mereka anggap sebagai "konten hiburan" sebenarnya dapat memicu konflik sosial dan masuk dalam ranah pidana.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi AI dengan memperkuat regulasi digital, meningkatkan literasi media, serta membangun kesadaran etika global di ruang publik virtual.
Video atau foto meme AI yang dibuat selalu menyangkut nilai-nilai hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk secara agama.
Tanpa pengawasan yang tepat, kebebasan ekspresi melalui AI dapat menjadi alat provokasi dan penghinaan terhadap agama yang mengancam stabilitas sosial dan hukum di Indonesia.
Jonathan Haidt dan Urgensi Literasi Moral dalam Era Digital
Jonathan Haidt adalah seorang psikolog sosial asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena pendekatannya dalam memahami moralitas, agama, dan politik.
Lahir pada 1963 di New York dari keluarga Yahudi keturunan Rusia-Polandia, Haidt menempuh studi filsafat di Yale dan meraih gelar Ph.D. di bidang psikologi dari University of Pennsylvania.
Kini ia menjabat sebagai profesor etika di New York University (NYU), serta mendirikan dua lembaga penting: Ethical Systems dan Heterodox Academy, yang menekankan pentingnya etika dan keberagaman pandangan di ruang publik.
Pemikiran Haidt banyak dikenal melalui tiga bukunya: The Happiness Hypothesis (2006), The Righteous Mind (2012), dan The Coddling of the American Mind (2018).
Ia menyoroti bahwa moralitas manusia lebih digerakkan oleh intuisi emosional daripada logika, dan bahwa komunitas moral terbentuk dari nilai yang diyakini sejak dini.
Dalam The Righteous Mind, ia menjelaskan mengapa orang baik bisa terpecah karena agama dan politik, sementara dalam The Coddling mengeritik bagaimana generasi muda yang terlalu dilindungi justru menjadi rapuh dalam menghadapi perbedaan.
Pemikiran Haidt sangat relevan dalam konteks literasi digital saat ini, di mana kemampuan teknis saja tidak cukup.
Literasi digital harus menyentuh ranah etika dan moralitas, terutama ketika teknologi seperti AI mulai digunakan untuk memproduksi konten manipulatif yang menyentuh isu agama dan identitas.
Literasi digital, menurut berbagai ahli dan kebijakan pemerintah, mencakup keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyaring informasi, hingga tanggung jawab sosial dalam menyebarkan konten.
Dalam konteks ini, pendekatan Haidt menekankan pentingnya empati, dialog lintas nilai, serta kesadaran bahwa ekspresi digital tidak terlepas dari konsekuensi moral di dunia nyata.
Melek digital bukan hanya soal menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana seseorang menavigasi ruang digital dengan kompas moral yang kuat.
Menggabungkan literasi digital dengan psikologi moral ala Haidt dapat menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga dewasa secara etika dan sosial.
Sementara itu, di Indonesia, generasi digital yang biasa disebut gadget generation, hidup dalam banjir informasi tanpa cukup filter moral.
Riana Mardina (2017) menegaskan literasi digital haruslah bersifat multiliterasi, yaitu perpaduan antara kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, serta memahami dimensi hukum dan sosial.
Tanpa itu, pengguna internet mudah rentan menjadi produsen dan konsumen konten bermasalah seperti hoaks dan penistaan agama yang bermuara pada perpecahan.
Penelitian Terttiaavini dan Tedy Saputra (2022) menunjukkan bahwa pelajar dapat diajak memahami etika digital lewat pelatihan kreatif seperti membuat konten literasi melalui Tik-Tok dan Canva.
Namun, pemahaman ini masih terbatas. Padahal, tanpa etika digital, alat secanggih apa pun bisa berubah menjadi senjata yang melukai nilai dan identitas orang lain.
Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda bukan hanya perlu melek digital, tapi juga berhati digital.
Mereka harus belajar memilah informasi seperti seorang editor berita dan bertindak di ruang digital dengan kesadaran hukum dan moral.
Literasi digital tanpa etika hanyalah alat tanpa kompas. Maka, pelajar masa kini harus diarahkan menjadi agen perubahan bukan hanya follower tren, tetapi pencipta narasi baru yang cerdas, beradab, dan kritis.
Dengan membangun kesadaran ini, kita bisa melahirkan generasi yang tak hanya terkoneksi, tapi juga terarah dalam ruang digital yang luas dan liar.
Membaca Fenomena AI Melalui Lensa Jonathan Haidt
Konflik digital bernuansa keagamaan, seperti kasus viralnya meme berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan narasi dan visualisasi tokoh-tokoh agama secara manipulatif, menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia masih belum menyentuh akar terdalam dari persoalan.
Dalam salah satu kasus, AI digunakan untuk menciptakan meme video yang menarasikan penistaan terhadap agama tertentu, yang kemudian menyebar luas di media sosial dan memantik kemarahan publik.
Permasalahan ini bukan sekadar soal teknis atau etika penggunaan media, melainkan berakar pada benturan nilai moral dan keyakinan yang dihidupi oleh masing-masing agama.
Ketika pengguna media sosial menilai konten hanya dari sudut pandang moral kelompoknya sendiri, tanpa ruang bagi pemahaman terhadap nilai kelompok lain, maka konflik menjadi tak terelakkan.
Pemikiran Jonathan Haidt dalam psikologi moral memberikan kerangka konseptual
yang sangat relevan untuk memahami fenomena semacam ini.
Haidt menjelaskan bahwa moralitas manusia lebih banyak digerakkan oleh intuisi emosional dibandingkan nalar rasional.
Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini membentuk “komunitas moral” yang memperkuat identitas kelompok dan membenarkan berbagai tindakan untuk melindungi nilai tersebut, termasuk tindakan yang menyudutkan atau bahkan menyakiti kelompok lain.
Ini menjelaskan mengapa meme AI yang dianggap "hiburan" oleh satu kelompok bisa dipersepsikan sebagai penghinaan oleh kelompok lainnya, karena masing-masing beroperasi dalam lanskap moral yang berbeda dan cenderung absolut.
Pendekatan Haidt menunjukkan bahwa peningkatan literasi tidak cukup hanya berupa pelatihan teknis atau himbauan etis.
Literasi digital harus dikembangkan menjadi literasi etika berbasis empati dan dialog lintas nilai.
Pemerintah dan institusi seperti KOMINFO dapat mengambil inspirasi dari pendekatan ini untuk merancang program literasi yang tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga mengasah sensitivitas moral dan kemampuan memahami keberagaman nilai di ruang digital.
Salah satu bentuknya adalah menciptakan platform interaktif untuk diskusi antarumat beragama secara daring yang edukatif dan bebas konflik.
Tentu saja penerapan konsep ini tidak mudah. Masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sikap eksklusif atau terkungkung dakam kebenarannya sendiri, dan ruang digital sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperbesar jurang perbedaan.
Namun, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya literasi digital dan etika AI memberi harapan bahwa pendekatan berbasis nilai ini bisa ditanamkan secara bertahap.
Haidt tidak mengajak menyamakan semua nilai, tetapi mendorong keseimbangan dan dialog.
Ini adalah fondasi penting untuk membangun dunia digital yang inklusif, bijak, dan tetap menghargai keragaman keyakinan di tengah derasnya gelombang teknologi.
Kesimpulan
Sekarang kita dihadapkan pada pilihan: menjadi pengguna pasif yang larut dalam sensasi teknologi, atau menjadi warga digital yang bijak dan beretika.
Foto atau video meme AI yang bernuansa keagamaan merupakan cerminan rapuhnya kesadaran moral kita dalam bermedia.
Jonathan Haidt mengingatkan bahwa moralitas bukan dibangun dari logika semata, tapi dari intuisi dan nilai yang terpatri sejak dini.
Apabila ruang digital terus dibiarkan sebagai medan pertempuran ego dan kepercayaan tanpa empati yang lahir bukanlah kemajuan, melainkan polarisasi yang kian mencengkram kedamaian kita.
Saya mengajak anak muda atau siapa pun yang membaca tulisan ini untuk tidak mudah percaya terhadap informasi. Sudah saatnya kita memahami perbedaan sebagai kekayaan.
Teknologi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai kemanusiaan harus tetap diutamakan. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Berno Jani
Mahasiswa IFTK Ledalero
Opini Pos Kupang
POS-KUPANG. COM
Jonathan Haidt
kecerdasan buatan
Donald Trump
| Opini: Amnesti, Abolisi untuk Hasto dan Lembong, Runtuhnya Sebuah Hegemoni? |

|
|---|
| Opini: Pesan Terkuat Rekonsiliasi dan Restorasi Reputasi Melalui Kongres Persatuan PWI |

|
|---|
| Opini: DPRD Dalam Cengkraman Oligarki |

|
|---|
| Opini: Joko Widodo, Dedy Mulyadi dan Feodalisme |

|
|---|
| Opini: Elaborasi Pendidikan Bermakna, Mengembalikan Jiwa dalam Ruang Kelas |

|
|---|










![[FULL] Pakar: Indonesia Terlibat Israel Caplok Gaza, Deal-dealan dengan Trump Obati 2.000 Korban](https://img.youtube.com/vi/5sKhHBVJjUg/mqdefault.jpg)

















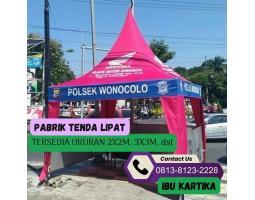
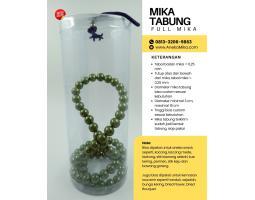







Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.