Opini
Opini : Co-Management untuk Geothermal Flores, Mungkinkah?
Peraturan Pemerintah khusus tentang Co-Management Geothermal dengan Masyarakat Adat diperlukan untuk memberikan pedoman.
Oleh: Maria Dolorosa Bria, S.Pi., MEnv.Sc
- Pengurus KoalaNTT (Komunitas Alumni Australia NTT)
- Bekerja di Bapelitbangda Rote Ndao
POS-KUPANG.COM - Flores, pulau dengan potensi geothermal 776 MW, seharusnya menjadi kunci transformasi energi nasional Indonesia. Namun faktanya, Flores telah menjadi arena paradoks pembangunan berkelanjutan di era modern.
Di persimpangan antara target energi terbarukan nasional Tahun 2025 untuk mencapai 23 persen dan visi jangka panjang 70 % di 2045, pengembangan geothermal Flores menghadapi dilema multidimensional antara kepentingan nasional dan resistensi lokal yang mengakar kuat.
Bagaimana mengejar waktu yang berlomba dengan dampak perubahan iklim sambil menghadapi resistensi yang mengakar dalam - mulai dari petani yang mempertahankan sawah dan kebun hingga Uskup dan para Romo yang dari altarnya juga berusaha mempertahankan tanah warisan yang harus dijaga kesucian dan kelestariannya.
Harus ada jalan tengah! Salah satunya, dengan mengadopsi model co-management pengelolaan geothermal dari New Zealand. Mengapa New Zealand?
Pengembangan dan pengelolaan geothermal di New Zealand menunjukkan model co-management yang unik dengan masyarakat Indigenous Māori, yang dapat menjadi contoh terbaik bagaimana mengintegrasikan hak-hak indigenous dengan pengembangan energi berkelanjutan.
Tuaropaki Trust, Contoh Co-Management Terbaik
Contoh paling sukses dari model co-management di New Zealand adalah Tuaropaki Trust yang mengelola Mokai Geothermal Power Plant. Tuarapaki Trust mengakui dan menerima Konsep Kaitiakitanga milik suku Māori sebagai dasar co-management.
Konsep Kaitiakitanga secara sederhana digambarkan bahwa suku Maori menganggap diri mereka sebagai kaitiaki (guardians) dari sumber daya geothermal (waiwhatu), dengan rasa tanggung jawab budaya dan spiritual yang mendalam untuk memastikan perlindungan yang tepat.
Selama berabad-abad, suku Māori telah mengakui dan memanfaatkan energi geothermal alami untuk berbagai tujuan, menganggap area ini sebagai sumber penyembuhan, penghidupan, dan kekuatan
Konsep kaitiakitanga ini menjadi fondasi filosofis dalam model co-management, dimana masyarakat Māori tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengelola aktif sumber daya geothermal.
Kelompok suku Māori memiliki rangatiratanga penuh (kontrol dan otoritas) atas tanah dan sumber daya mereka sebelum kedatangan Eropa di Aotearoa (New Zealand). Sebagai kaitiaki, mereka memiliki metode pengelolaan dan pengembangan sumber daya sendiri.
Model Tuaropaki Trust menunjukkan bahwa masyarakat indigenous (Maori) bukan hanya perlu "didengar" dalam konsultasi formal, tetapi harus "dilibatkan" sebagai mitra penuh dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan strategis proyek geothermal. Pembangkit listrik Tuaropaki saat ini menghasilkan 113 MW listrik yang menjadi sumber listrik Kota Hamilton.
Bisa kita lihat bagaimana co-management berbeda dengan pendekatan konvensional yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif. Model co-management memberikan kontrol langsung kepada komunitas lokal atas sumber daya mereka.
Di Flores, ini berarti mengakui hak-hak adat masyarakat atas tanah dan sumber daya geothermal, serta menciptakan struktur kepemilikan yang memungkinkan partisipasi aktif dalam manajemen operasional.
Apakah regulasi kita memungkinkan untuk itu? Mari kita lihat.
Implementasi co-management model Tuaropaki Trust milik New Zealand di Flores memerlukan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kerangka penilaian proyek, menciptakan mekanisme sharing yang adil, dan membangun kapasitas lokal untuk pengelolaan teknologi geothermal.
Dengan demikian, geothermal tidak lagi menjadi eksploitasi sumber daya, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Flores.
Beberapa regulasi memberikan fondasi yang memadai untuk penerapan co-management, namun terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum yang ada dengan kebutuhan implementasi co-management yang efektif.
Sejauh mana regulasi di Indonesia dapat mengakomodasi model partisipatif yang memberikan kontrol langsung kepada masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya geothermal, terutama di Flores?
Kerangka regulasi Indonesia sebenarnya telah menyediakan beberapa instrumen hukum yang dapat mendukung implementasi co-management, meskipun dengan keterbatasan yang signifikan.
UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menjadi regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan dan pengusahaan panas bumi, termasuk aspek peran serta masyarakat.
Namun, konsep "peran serta masyarakat" dalam undang-undang ini masih berkutat pada level konsultasi dan sosialisasi, belum mencapai tingkat co-ownership atau co-management seperti yang dipraktikkan di New Zealand melalui model Tuaropaki Trust.
Sementara itu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui desa adat dengan kewenangan pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.
Pengakuan ini memberikan basis hukum yang kuat untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka, termasuk geothermal.
Tantangan Struktural dan Agenda Reformasi Regulasi
Meskipun terdapat fondasi yang mendukung, implementasi co-management menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Keterbatasan skema kepemilikan menjadi hambatan utama. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 mempertegas bahwa pengusahaan panas bumi harus memiliki Izin Panas Bumi (IPB) dan dilakukan oleh pemegang IPB.
Regulasi ini belum mengakomodasi skema kepemilikan bersama atau trust model seperti yang berhasil diterapkan di New Zealand. Hal yang paling mendasar adalah belum adanya framework khusus untuk co-management antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Regulasi di Indonesia saat ini masih menggunakan paradigma top-down yang menempatkan negara sebagai pemilik tunggal sumber daya alam, berbeda dengan model co-management yang mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat.
Implementasi co-management yang efektif memerlukan reformasi regulasi yang komprehensif dan bertahap. Revisi UU No. 21 Tahun 2014 menjadi prioritas utama dengan menambahkan pasal khusus tentang co-management dengan masyarakat ada dana tau masyarakat lokal, mengatur skema kepemilikan bersama atau trust model, dan memberikan mekanisme partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis.
Penyusunan peraturan pelaksana baru juga menjadi kebutuhan mendesak. Peraturan Pemerintah khusus tentang Co-Management Geothermal dengan Masyarakat Adat diperlukan untuk memberikan pedoman operasional yang jelas.
Demikian pula Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Bersama untuk Geothermal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat dalam Proyek Energi akan memberikan instrumen hukum yang lebih spesifik.
Harmonisasi regulasi sektoral menjadi kunci keberhasilan implementasi. Sinkronisasi antara UU Panas Bumi, UU Desa, dan UU Lingkungan Hidup perlu dilakukan untuk menghindari konflik norma.
Integrasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam semua regulasi terkait juga menjadi keharusan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi.
Strategi Implementasi Bertahap dan Roadmap Strategis
Meskipun reformasi regulasi komprehensif memerlukan waktu yang tidak singkat, terdapat beberapa peluang implementasi yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka regulasi yang ada.
Skema kemitraan antara pemegang IPB dengan masyarakat adat dimungkinkan dalam regulasi saat ini, meskipun belum sampai tingkat co-ownership penuh. Model ini dapat menjadi stepping stone menuju co-management yang lebih komprehensif.
Pemerintah juga dapat mengeluarkan regulasi khusus seperti Peratuan Presiden untuk menjadikan Flores sebagai pilot project co-management geothermal.
Pendekatan pilot project memberikan ruang untuk eksperimentasi dan pembelajaran sebelum diadopsi secara nasional. Pemanfaatan UU Desa Adat juga dapat dimaksimalkan sebagai basis hukum untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan geothermal.
Implementasi co-management memerlukan roadmap strategis yang jelas dengan target-target yang realistis. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada maksimalisasi skema kemitraan dalam kerangka regulasi yang ada sambil membangun kapasitas masyarakat adat dan melakukan advokasi untuk reformasi regulasi.
Jangka menengah difokuskan pada advokasi untuk revisi UU Panas Bumi dan pembuatan Peraturan Pemerintah khusus co-management.
Periode ini juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi pilot project dan penyesuaian model berdasarkan pembelajaran lapangan.
Dalam jangka panjang, target utama adalah pembentukan UU khusus tentang Co-Management Sumber Daya Alam dengan Masyarakat Adat yang dapat menjadi payung hukum komprehensif untuk implementasi co-management di berbagai sektor, tidak hanya geothermal.
Kesimpulan
Co-management bisa menjadi sebuah opsi ‘jalan tengah’ untuk keberlanjutan Project Geothermal di Flores.
Pembelajaran dari New Zealand menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat, melindungi nilai-nilai budaya, dan memastikan manfaat social ekonomi yang equitable.
Tanpa adanya jalan tengah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, proyek geothermal di Flores berisiko menciptakan "green sacrifice zones" alih-alih menjadi katalis pembangunan yang sesungguhnya. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS















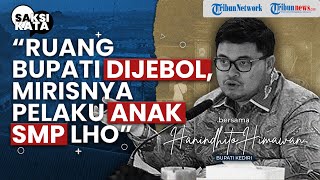





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.