Opini
Opini: Mengkaji Ulang Kebijakan Pemaketan
Sebab, saat ini problematika usaha jasa konstruksi Indonesia telah mewujud menjadi bersifat struktural dan sistemik di semua lini.
Oleh: Habde Adrianus Dami
Pengamat Kebijakan Publik, Pengurus Gapensi NTT
POS-KUPANG.COM - Pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur.
Pada, masa kepemimpinan Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur di APBN terdongkrak 156,2 persen dari Rp177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 422,7 triliun (2024).
Selain itu, ada skema penyediaan pembiayaan atau sindikasi pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi BUMN dan swasta.
Persoalannya, semakin meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur belum memberikan dampak langsung terhadap perkembangan pelaku usaha jasa konstruksi di daerah.
Sebab, saat ini problematika usaha jasa konstruksi Indonesia telah mewujud menjadi bersifat struktural dan sistemik di semua lini.
Bentuk konkret dari problematika usaha jasa konstruksi ini dapat ditelusuri dari indikator peran kontraktor lokal yang masih rendah dalam pembangunan infrastruktur nasional di daerah.
Salah satu yang perlu menjadi sorotan adalah kebijakan pemaketan (konsolidasi) pengadaan barang dan jasa.
Pertanyaannya, apakah urgensi kebijakan konsolidasi pengadaan? Barangkali, lebih jauh ada semacam asumsi yang tidak komprehensif dan minimnya ruang dialog pemangku kepentingan dalam manajemen pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, perlu koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lapisan pemerintahan, sektor publik dan swasta melalui terobosan, inovasi dan prudent dalam pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur nasional di daerah, agar lebih efektif dalam implementasinya.
Konsolidasi pengadaan
Dalam teori ekonomi kontemporer, pasar diakui berpotensi mengalami kegagalan.
Meskipun demikian, hal ini tidak bisa dijadikan alasan utama bagi hadirnya intervensi pemerintah, sebab campur tangan pemerintah juga tidak terlepas dari risiko kegagalan yang boleh jadi akan kian memperparah dampak kegagalan pasar.
Di satu sisi ada keinginan kuat untuk mengatasi kegagalan pasar melalui campur tangan pemerintah. Tetapi pada saat yang bersamaan, obat dari penyakit itu boleh jadi malah berbalik menjadi racun ganas yang dapat mematikan.
Sebagaimana kebijakan konsolidasi pengadaan adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang sejenis di suatu daerah bahkan antar daerah.
Salah satu implikasi konsolidasi pengadaan yang dapat dikemukakan di sini adalah pekerjaan konstruksi di NTT justru didominasi pelaku usaha yang berasal dari luar NTT (nasional).
Berbagai distorsipun terjadi, seperti meningkatnya jumlah kontraktor lokal yang berguguran karena tidak dibarengi dengan distribusi pekerjaan yang proporsional;
Meningkatnya jumlah sub pekerjaan yang berhenti operasi dalam mata rantai pekerjaan konstruksi; Terbukanya peluang menyusutnya lapangan pekerjaan; dan meningkatnya pengangguran di daerah.
Akumulasi dari distorsi usaha jasa konstruksi di atas, timbullah masalah baru anjloknya kelas menengah. Akibat lanjutannya, seperti: rendahnya daya beli yang ditunjukkan pelemahan indeks keyakinan konsumen. Fakta ini, mengganggu siklus perekonomian daerah maupun nasional.
Sehingga, upaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha daerah tidak tercapai dan memengaruhi total factor productivity. Isu ini memantik reaksi dan kritik keras dari sejumlah pihak terutama pelaku usaha jasa konstruksi di daerah.
Tentu pemerintah berdalih bahwa manfaat konsolidasi pengadaan adalah Pertama, mendapatkan barang dan jasa value for money; Kedua, mengurangi jumlah aktivitas pengadaan; Ketiga, mengurangi risiko pengadaan;
Keempat, meningkatkan posisi tawar pengguna jasa sebagai pembeli. Narasi argumentasi yang digunakan masih bersifat umum, dan tidak memiliki segmentasi ke daerah.
Pada titik ini, ada satu hal menarik yang jarang kita sadari, bahwa konsolidasi pengadaan tetap menimbulkan paradoks pembanguan dalam konteks desentralisasi pembangunan daerah.
Sebab, tidak bisa tidak, rumusan sistem perekonomian daerah selalu tidak pernah lepas dari gabungan dua entitas kelembagaan ini (baca: pasar dan non pasar).
Meskipun disadari kebijakan konsolidasi pengadaan tidaklah timbul dalam suatu kevakuman ruang hampa. Ia selalu dipengaruhi konfigurasi sosial-ekonomi-politik yang berlaku pada suatu tempat dan kurun waktu tertentu.
Telaah eksistensi kebijakan konsolidasi pengadaan dan dunia usaha ditengarai ada pola hubungan, dan mekanisme kerja, untuk saling memanfaatkan kebijakan tersebut berada di balik tabir, bersifat ekstra legal dan rahasia, serta berada di bawah karpet sistem formal, yang sarat dengan tujuan oportunistik.
Oleh karena itu, bagi pemerintah yang intervensionis, insentif untuk berinovasi dalam kebijakan konsolidasi pengadaan tidak hanya didorong oleh motif pencarian keuntungan pemerintah pusat semata, tetapi juga didorong semangat yang menyebarkan manfaat bagi pelaku usaha jasa konstruksi di daerah.
Tegasnya, dalam menganalisis proses kebijakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (regulasi dan distribusi) serta sejauhmana kemanfaatan kebijakan.
Kebijakan inklusif
Mekanisme pasar tidak dapat dengan sendirinya mengatasi persoalan-persoalan kompetisi antara pelaku ekonomi. Hal itu disebabkan oleh risiko kegagalan pasar yang cukup tinggi akibat tidak sempurnanya informasi pasar yang secara inheren melekat dalam mekanisme pasar.
Pasar dalam pengertian ini mesti dibedakan dengan gambaran tempat atau lokasi. Dalam perspektif teori ekonomi, pasar jauh lebih abstrak dari yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari (misal, Pasar Naikoten, Pasar Oebobo, mal).
Karena itu, pasar tidak selalu dapat menyediakan barang publik. Di sini, pemerintah dapat menyelesaikan masalah barang publik ini dengan menyediakannya sendiri melalui mekanisme swakelola atau pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang dan jasa untuk menyediakan barang publik tersebut.
Ada hubungan kontraktual antara principal dengan agents, yang membentuk kesepakatan tentang harga dan jumlah atau jenis barang dan jasa yang ingin ditransaksikan.
Di balik itu, pertimbangan kenapa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui mekanisme tender adalah, pertama, supaya barang yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas dengan harga yang lebih bersaing. Kedua, barang dan jasa tersebut diperoleh sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Walaupun begitu, standar norma dan persyaratan kualifikasi yang tidak realistis serta kebijakan pemaketan berkontribusi signifikan terhadap daya saing kontraktor lokal.
Karena itu, pemerintah perlu membentuk kebijakan yang inklusif, sebagai instrumen yang sangat vital untuk memastikan peran pelaku usaha jasa konstruksi di daerah melalui regulatory review.
Dimaksudkan untuk menilai ulang seluruh UU, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan daerah. Mengapa? Karena pemerintah bertindak sebagai regulator ketika pasar mengalami kegagalan dan pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan aktif dalam rangka mempromosikan kegiatan pembangunan.
Proses regulatory review menghasilkan rekomendasi untuk mengubah seluruh produk kebijakan yang selama ini memfasilitasi praktek monopoli dan eksklusivitas pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
Pelembagaan regulatory review berbasis pada tiga pilar yaitu persaingan usaha yang sehat, pelayanan publik, dan berdimensi desentralisasi pembangunan daerah.
Kedua, reformasi struktur pasar tidak untuk mematikan pelaku usaha jasa konstruksi yang sudah ada, tetapi memperkuat bahkan juga ikut mendorong munculnya pelaku usaha baru di setiap sektor.
Sebab, apabila kue ekonomi itu bisa dinikmati oleh banyak orang, maka akan bisa menggerakkan roda ekonomi daerah untuk berputar lebih cepat lagi.
Sayangnya, konsep ekonomi pasar sosial ini tidak sepenuhnya dipahami para pengambil kebijakan pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, kegiatan ekonomi lebih bersifat parsial dan hanya dilihat dari sisi profitabilitas dan pragmatisme saja.
Ketiga, perubahan perilaku pelaku usaha jasa konstruksi untuk menjaga persaingan usaha sehat, demikian juga kinerja unit layanan pengadaan barang dan jasa.
Keempat, posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mestinya mengambil langkah konstruktif yang mendorong fleksibilitas dalam melindungi pelaku usaha ekonomi daerah.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu memainkan peran penting dalam meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelaku usaha ekonomi. Pemerintah harus mampu melindungi pelaku ekonomi yang lemah dari kompetisi dalam mekanisme pasar pengadaan barang dan jasa.
Lugasnya, pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan masa depan kelompok kepentingan tertentu. Juga, tidaklah elok kalau pemerintah lebih fokus pada kontraktor nasional, sebaliknya mengabaikan peran kontraktor daerah. (*)







































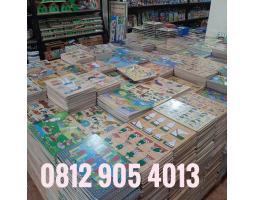


Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.