Opini
Opini: Kita Butuh Polisi yang Tidak Gagap Hukum
Gagasan ini bukan sekadar wacana elitis yang menjauhkan institusi kepolisian dari rakyat, melainkan respons terhadap realitas pahit.
Oleh: Aziz Ramba Wudi
Alumnus Fakultas Filsafat-Unwira Kupang,Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM - Dalam salah satu sidang Komisi III DPR RI pada 26 Mei 2025, Hinca Panjaitan melontarkan kalimat yang menohok "Hukum itu ilmu, bukan naluri."
Pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menyasar tepat pada salah satu kelemahan mendasar institusi kepolisian Indonesia yakni minimnya pemahaman teoritis dan akademis dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Usulannya sederhana namun radikal. Syarat minimal menjadi polisi haruslah lulusan sarjana (S1), khususnya dari bidang hukum, sosiologi, psikologi, dan kriminologi.
Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, dengan argumen bahwa polisi yang mengemban tugas penegakan hukum harus memahami ilmu hukum, psikologi, kriminologi dan sosiologi.
Baca juga: Harumkan Nama Polri, Kapolres Alor Raih Penghargaan Inspiring Profesional and Leadership Award 2025
Gagasan ini bukan sekadar wacana elitis yang menjauhkan institusi kepolisian dari rakyat, melainkan respons terhadap realitas pahit.
Sejumlah kasus telah mencoreng nama baik Polri dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari kekerasan berlebihan saat mengamankan aksi demonstrasi, pemerasan, suap, hingga keterlibatan dalam jaringan narkoba.
Problem struktural yang dihadapi POLRI saat ini berakar pada sistem rekrutmen dan pendidikan yang terlampau singkat.
Penerimaan anggota polisi jalur Sekolah Polisi Negara (SPN) Bintara dan Tamtama berlangsung dengan pendidikan kilat, masing-masing 7 bulan dan 5 bulan.
Dalam rentang waktu itu, calon polisi diharapkan menguasai tidak hanya keterampilan fisik dan prosedur operasional, tetapi juga memahami kompleksitas hukum, dinamika sosial, dan psikologi manusia.
Hasilnya bisa ditebak. Aparat yang turun ke lapangan kerap kali hanya bersenjatakan prosedur baku tanpa kemampuan membaca konteks, berempati pada korban, atau memahami implikasi hukum dari tindakannya.
Membandingkan profesi polisi dengan profesi lain yang juga bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak kiranya relevan.
Seorang dokter tak mungkin diizinkan mempraktikkan ilmunya tanpa menempuh pendidikan medis bertahun-tahun.
Seorang pengacara tak akan pernah diperkenankan beracara di pengadilan tanpa gelar sarjana hukum dan lulus uji advokat.
Mengapa polisi, yang keputusannya bisa merampas kemerdekaan seseorang, bahkan dalam kondisi tertentu bisa mengambil nyawa, justru cukup dibekali pelatihan beberapa bulan?
Hinca Panjaitan menggunakan analogi yang tajam. polisi yang tidak memahami hukum ibarat dokter yang tidak paham anatomi.
Keduanya sama-sama berbahaya. Dokter tanpa pengetahuan anatomi bisa salah diagnosis dan membunuh pasien.
Polisi tanpa pemahaman hukum bisa salah tangkap, menyiksa tersangka, atau justru membiarkan pelaku kejahatan berkeliaran karena ketidakmampuan membangun berkas perkara yang solid.
Dalam kedua kasus, korbannya adalah masyarakat yang seharusnya dilindungi.
Tentu saja, usulan ini akan menuai resistensi. Ada kekhawatiran bahwa persyaratan S1 akan mempersempit akses bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk bergabung dengan institusi kepolisian.
Ada pula argumen pragmatis bahwa Indonesia membutuhkan banyak polisi dalam waktu singkat, sehingga tak mungkin menunggu lulusan sarjana.
Namun, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah kita menginginkan banyak polisi dengan kualitas meragukan, atau polisi yang lebih sedikit namun profesional?
Max Weber, sosiolog Jerman yang pemikirannya menjadi fondasi teori organisasi modern, menekankan pentingnya birokrasi rasional dalam institusi negara.
Dalam hal ini Weber mau menegaskan bahwa institusi publik seperti kepolisian harus dijalankan berdasarkan keahlian teknis, bukan sekadar otoritas tradisional di mana kekuasaan atau segala tindakkan hanya didasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan lama dan otoritas individual.
Birokrasi yang profesional, menurut Weber, menuntut pegawai yang direkrut berdasarkan kualifikasi akademis dan kompetensi yang terukur, bukan berdasarkan hubungan kekerabatan atau pertimbangan politis.
Weber mengingatkan bahwa organisasi modern yang efektif memerlukan spesialisasi pengetahuan dan pembagian kerja yang jelas.
Dalam konteks kepolisian, ini berarti setiap aparat harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang tugasnya—apakah itu hukum pidana, investigasi kriminal, atau dinamika sosial masyarakat.
Tanpa fondasi pengetahuan yang kuat, birokrasi akan berubah menjadi mesin yang kaku dan tidak rasional, di mana keputusan diambil berdasarkan kebiasaan atau kekuasaan semata, bukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan terukur.
Polisi tanpa pendidikan memadai, dalam kerangka Weberian, akan menjadi aparatus yang tidak rasional dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Meningkatkan syarat pendidikan menjadi S1 bukan berarti mengubah polisi menjadi akademisi yang menghabiskan waktu di belakang meja.
Justru sebaliknya, polisi dengan latar belakang pendidikan yang kuat akan lebih mampu beradaptasi dengan kompleksitas masyarakat modern.
Mereka akan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan mediasi ketimbang kekerasan, lebih mampu membangun kepercayaan publik ketimbang menebar ketakutan, dan lebih mampu bekerja sama dengan institusi lain dalam sistem peradilan pidana.
Profesionalisme sejati tidak dibangun dalam waktu singkat. Ia memerlukan fondasi pengetahuan yang kokoh, etika yang terinternalisasi, dan kemampuan berpikir kritis yang terasah.
Kalau kita serius ingin mereformasi Polri, maka reformasi itu harus dimulai dari gerbang masuk. siapa yang boleh menjadi polisi, dan apa yang harus mereka ketahui sebelum diberi seragam dan senjata api.
Tanpa itu, segala perubahan struktural lainnya akan sia-sia, karena kelemahan mendasar tetap ada di level individual.
Usulan Hinca Panjaitan mungkin terdengar idealis, bahkan utopis. Namun, dalam konteks krisis kepercayaan publik terhadap kepolisian, idealisme semacam ini justru yang paling realistis.
Sebab, tidak ada jalan pintas menuju profesionalisme. Dan profesionalisme, pada akhirnya, bukan pilihan, ia adalah keharusan bagi institusi yang mengklaim dirinya sebagai pengayom masyarakat. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Aziz-Ramba-Wudi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Dody-Kudji-Lede2.jpg)













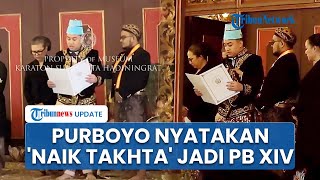





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.