Opini
Opini: Elaborasi Pendidikan Bermakna, Mengembalikan Jiwa dalam Ruang Kelas
Pembelajaran akan lebih bermakna ketika informasi baru dikaitkan secara substantif dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik.
Oleh: Heryon Bernard Mbuik
Dosen Manajemen Pendidikan, Universitas Citra Bangsa Kupang - Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM - Dalam hiruk-pikuk kurikulum dan asesmen nasional, kita sering lupa bahwa esensi pendidikan bukanlah akumulasi pengetahuan, melainkan transformasi manusia.
Dalam perspektif John Dewey, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, bukan sekadar persiapan untuk hidup (Dewey, 1916).
Artinya, jika proses pendidikan tidak menyentuh pengalaman hidup, nilai, dan kebermaknaan, maka kita sedang menciptakan ruang belajar yang kosong jiwa sekalipun penuh dengan materi.
Istilah pendidikan bermakna bukan sekadar jargon, melainkan sebuah pendekatan filosofis dan pedagogis yang berakar pada relasi antara pengetahuan dan pengalaman personal siswa.
David Ausubel (1963) mengemukakan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna ketika informasi baru dikaitkan secara substantif dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik.
Namun, makna tidak hanya tumbuh dari aspek kognitif, tetapi juga dari keterlibatan emosional, sosial, dan spiritual.
Pendidikan yang Kehilangan Arah
Realitas pendidikan kita saat ini menunjukkan paradoks. Di satu sisi, teknologi berkembang pesat, kurikulum diperbarui, dan berbagai program penguatan kompetensi diluncurkan.
Namun di sisi lain, ruang-ruang kelas terasa makin asing dan terasing. Siswa hadir secara fisik, tetapi tidak secara mental.
Guru hadir sebagai penyampai materi, tetapi tidak lagi menjadi penuntun makna.
Paulo Freire menyebut gejala ini sebagai “banking education” pendidikan yang memperlakukan siswa sebagai tabungan kosong yang harus diisi oleh guru.
Tidak ada dialog, tidak ada kritik, tidak ada kebebasan untuk tumbuh (Freire, 1970).
Model ini menjauhkan kita dari pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan.
Fenomena ini juga dikritisi oleh Gert Biesta (2020), yang menegaskan bahwa pendidikan bermakna bukan hanya tentang mencapai hasil belajar (learning outcomes), tetapi menyangkut formation yakni pembentukan identitas, karakter, dan tanggung jawab sosial.
Ketika pendidikan direduksi menjadi sekadar kompetensi teknis, maka dimensi etis dan eksistensial siswa hilang dari pandangan.
Mengapa Pendidikan Sering Tak Bermakna?
1. Kurikulum Tekstual dan Terfragmentasi
Kurikulum kita sering kali berorientasi pada penguasaan konten dan capaian kognitif yang terfragmentasi.
Menurut Sugrue & Day (2021), kurikulum semacam ini cenderung melupakan integrasi nilai, pengalaman hidup, dan keterkaitan lintas bidang.
Akibatnya, siswa kesulitan mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata mereka.
2. Dominasi Penilaian Kuantitatif
Sistem asesmen yang terlalu menekankan angka telah mengubah orientasi belajar menjadi kompetisi, bukan proses pemaknaan.
Brookhart (2020) menyatakan bahwa asesmen bermakna seharusnya memfasilitasi refleksi dan pemahaman mendalam, bukan sekadar mengukur hafalan.
3. Ketimpangan Relasi Guru-Siswa
Dalam banyak ruang kelas, relasi guru-siswa masih bersifat vertikal dan otoritatif.
Padahal, menurut Nel Noddings (2021), pendidikan bermakna tumbuh dalam relasi pedagogis yang etis dan penuh kasih.
Guru bukan hanya pemberi instruksi, tetapi harus menjadi “pribadi yang peduli” ( a caring teacher).
4. Minimnya Integrasi Konteks Lokal
Di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, kita menemukan fakta bahwa pengetahuan lokal, kearifan budaya, dan bahasa ibu jarang dijadikan bahan ajar.
Padahal, meaningful learning menuntut keterhubungan dengan konteks konkret siswa (McLellan & Dewey, 2022). Tanpa ini siswa merasa asing di ruang belajarnya sendiri.
Menuju Pendidikan yang Bermakna dan Kontekstual
Pendidikan yang bermakna harus mengubah ruang kelas dari tempat pengajaran menjadi ruang perjumpaan: antara guru dan siswa, antara ilmu dan kehidupan, antara nilai dan praksis.
1. Kontekstualisasi Materi Ajar
Guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang berakar pada realitas sosial dan budaya lokal.
Ini selaras dengan pendekatan place-based education yang ditekankan oleh Gruenewald & Smith (2020), yaitu mengaitkan pembelajaran dengan komunitas dan lingkungan sekitar siswa agar lebih relevan dan bermakna.
2. Proyek Sosial dan Inkuiri Reflektif
Pendekatan seperti project-based learning dan service learning memungkinkan siswa mengintegrasikan pengetahuan dengan tindakan sosial.
Ini sejalan dengan prinsip Thomas & Brown (2020) bahwa belajar tidak berhenti di ruang kelas, tetapi berlanjut dalam interaksi dan kontribusi sosial.
3. Refleksi sebagai Strategi Inti
Membiasakan siswa untuk menulis jurnal, berdiskusi secara terbuka, dan mengevaluasi proses belajar akan menumbuhkan kesadaran diri dan kedalaman berpikir.
Ini sesuai dengan gagasan Mezirow (2009) tentang transformative learning yakni pembelajaran yang mengubah cara pandang melalui refleksi kritis.
Peran Guru: Mengajar dengan Kebermaknaan
Guru adalah aktor utama dalam membangun pendidikan bermakna. Namun, guru tidak bisa bekerja sendiri.
Diperlukan ekosistem sekolah yang mendukung, budaya kolaboratif, serta pengakuan terhadap kompleksitas peran guru.
Parker J. Palmer (2017) menekankan bahwa kualitas pengajaran tidak ditentukan oleh metode, tetapi oleh keutuhan pribadi sang pendidik. “We teach who we are,” tulisnya.
Artinya, pendidikan bermakna lahir dari guru yang otentik yang hadir secara utuh, dengan hati yang terbuka, dan niat untuk melayani.
Kesimpulan: Menghidupkan Kembali Jiwa Pendidikan
Pendidikan bermakna bukanlah retorika. Ia adalah kebutuhan mendesak di tengah krisis makna yang melanda dunia pendidikan modern.
Kita tidak bisa terus-menerus mengejar keterampilan abad 21 tanpa memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh dengan hati yang sehat, pikiran yang reflektif, dan jiwa yang terhubung dengan dunia sekitarnya.
Jika tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, maka pendidikan bermakna adalah jalan yang harus ditempuh. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang benar.
“Pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan.” (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Heryon Bernard Mbuik
Universitas Citra Bangsa
Opini Pos Kupang
John Dewey
pendidikan bermakna
guru dan murid
Nusa Tenggara Timur
| Opini: Prada Lucky dan Tentang Degenerasi Moral Kolektif |

|
|---|
| Opini: Drama BBM Sabu Raijua, Antrean Panjang Solusi Pendek |

|
|---|
| Opini: Kala Hoaks Menodai Taman Eden, Antara Bahasa dan Pikiran |

|
|---|
| Opini: Korupsi K3, Nyawa Pekerja Jadi Taruhan |

|
|---|
| Opini: FAFO Parenting, Apakah Anak Dibiarkan Merasakan Akibatnya Sendiri? |

|
|---|

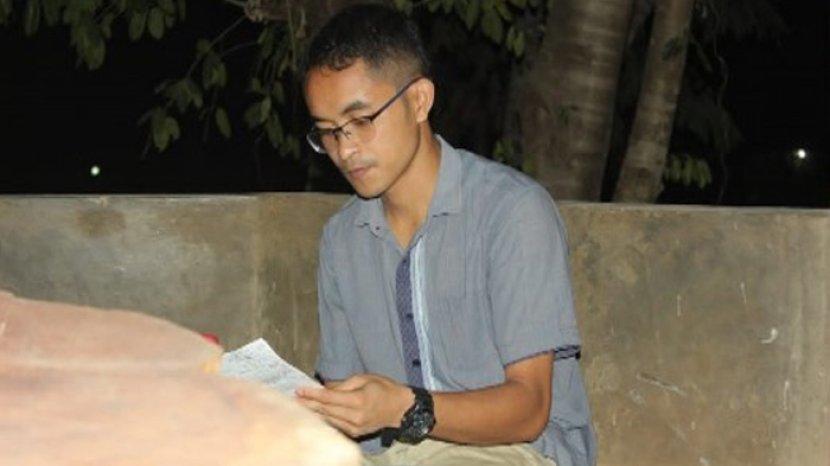








![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.