Opini
Opini: Mencari Hati yang Enggan Membenci di Balik Puing-puing Gereja Keluarga Kudus Gaza
Pastor paroki, Gabriel Romanelli, salah satu dari ketiga korban yang tewas, dikenal dekat dengan mendiang Paus Fransiskus.
Oleh: Hendrikus Maku, SVD
Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
POS-KUPANG.COM - Kompas.id edisi 18 Juli 2025 11:10 WIB menurunkan berita dengan judul: “Serangan Israel Hancurkan Gereja Katolik Keluarga Kudus (GKK) di Gaza: Tiga orang tewas dan 10 orang terluka, termasuk pastor paroki,... Israel menyalahkan peluru tank yang nyasar. Vatikan menyerukan gencatan senjata”.
Laraswati Ariadne Anwar, sang penulis berita menerangkan bahwa serangan militer Israel menghancurkan satu-satunya gereja Katolik di Jalur Gaza pada 17 Juli 2025, jam 10.20, setelah misa pagi.
Anwar mengutip salah satu sumber yang melaporkan bahwa di GKK itu, ratusan warga Palestina berlindung dari perang Hamas-Israel selama 21 bulan terakhir.
Pastor paroki, Gabriel Romanelli, salah satu dari ketiga korban yang tewas, dikenal dekat dengan mendiang Paus Fransiskus.
Sebelum wafatnya, Fransiskus kerap berbincang dengan Romanelli melalui sambungan telepon untuk menanyakan kondisi para pengungsi di Gaza, terutama anak-anak.
Anwar juga melaporkan respons Paus Leo XIV terhadap tragedi di GKK.
Pengganti Mendiang Paus Fransiskus, dari Vatikan mengirim ucapan belasungkawa kepada para korban serangan. Leo menyerukan agar gencatan senjata antara Hamas dan Israel disegerakan.
”Saya sangat berharap adanya dialog demi mencapai perdamaian atas konflik yang sudah terlalu lama ini,” ucap Paus Leo.
Mencari Hati yang Enggan Membenci
Di Gaza, bahkan tempat ibadah tak lagi punya hak untuk tenang. GKK, satu-satunya gereja Katolik di wilayah itu, dihantam oleh tank Israel.
Para korban berjatuhan, di antaranya ada lansia yang sedang menjalani terapi psikososial. Betapa menyedihkan.
Dari video dan foto yang beredar di berbagai medsos, terlihat di antara puing-puing, ada salib yang berdiri miring.
Salib itu seakan sedang mengaduh: “Di manakah Tuhan ketika manusia ciptaan-Nya kehilangan rasa kemanusiaan?”
Ada banyak narasi yang dibangun pascaserangan maut yang mematikan di GKK. Israel menyebutnya kesalahan teknis.
Sementara itu, Patriarkat Latin Yerusalem menyebutnya serangan langsung.
Dunia menyebutnya tragedi. Tetapi Gaza menyebutnya: rutinitas. Pertanyaan yang menggelitik kita adalah: Kalau rumah ibadah pun diserang, masih adakah religiositasmu, wahai penyerang yang beragama?
Bagi warga Gaza, GKK bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah tempat perlindungan bagi Muslim dan Kristen, anak-anak penyandang disabilitas, dan lansia yang tak punya tempat lain.
Itu artinya, ketika bom menghantam tempat itu, bukan hanya batu yang hancur, tetapi juga harapan, iman, dan rasa aman.
Moderasi yang Terluka
Serangan terhadap tempat ibadah (kapan pun dan di mana pun), adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai universal. Bukan hanya hukum internasional, tapi juga etika lintas agama.
Ketika tempat suci diserang, kita tak lagi berbicara soal konflik politik.
Kita berbicara soal kehilangan nurani. Tetapi, siapakah pribadi yang kehilangan nurani itu?
Ciri-ciri pribadi yang kehilangan nurani adalah sebagai berikut. Pertama, tidak peka terhadap penderitaan orang lain.
Orang yang kehilangan nurani cenderung tidak terganggu oleh penderitaan, kesedihan, atau ketidakadilan yang dialami orang lain. Mereka bisa melihat tragedi tanpa rasa iba.
Kedua, menghalalkan segala cara. Mereka rela melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, kekuasaan, atau ideologi, tanpa peduli terhadap dampak sosial yang akan ditimbulkan dari suatu tindakan tertentu.
Ketiga, retorika tanpa empati. Orang yang kehilangan nurani acap kali menggunakan bahasa yang dingin, merendahkan, atau menyalahkan korban.
Mereka bisa membenarkan kekerasan dengan dalih politik, agama, atau keamanan.
Keempat, menolak dialog dan refleksi. Mereka yang kehilangan nurani tidak sudi mendengarkan pandangan berbeda, apalagi melakukan introspeksi.
Mereka menutup diri dari kritik dan cenderung membenarkan diri sendiri secara mutlak.
Kelima, kehilangan rasa bersalah. Orang yang kehilangan nurani tidak merasa bersalah atas tindakan yang menyakiti orang lain.
Mereka bahkan bisa merasa bangga atau puas atas penderitaan yang ditimbulkan. Dan keenam, tidak menghargai nilai-nilai universal.
Pribadi yang kehilangan nuraninya selalu kontra keadilan, kasih sayang, hak asasi manusia, dan martabat hidup. Mereka bisa menyerang tempat ibadah, rumah sakit, atau sekolah tanpa rasa bersalah.
Serangan yang menyasar GKK di Gaza mungkin tidak punya korelasi langsung dengan perbincangan terkait moderasi beragama.
Namun demikian, sebagai bagian integral dari literasi keagamaan, maka tidaklah berlebihan kalau poin itu disenggol dalam permenungan “mencari hati yang enggan membenci”.
Beberapa korelasi dari serangan terhadap GKK dengan gagasan moderasi beragama adalah sebagai berikut.
Pertama, moderasi beragama menjunjung tempat ibadah sebagai zona damai (dar al-salam).
Moderasi beragama mengajarkan bahwa tempat ibadah, baik gereja, masjid, sinagoga, atau apa pun namanya adalah ruang suci yang harus dilindungi dari kekerasan.
Serangan terhadap GKK di Gaza menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip ini, dan menjadi contoh ekstrem dari radikalisasi kekuasaan yang mengabaikan nilai spiritual.
Kedua, moderasi menolak kekerasan atas nama agama atau politik. Serangan tersebut bukan hanya menyasar bangunan, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual.
Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan, apalagi yang dilakukan terhadap kelompok minoritas.
GKK di Gaza merupakan simbol solidaritas lintas iman, tempat Muslim dan Kristen berlindung bersama.
Ketiga, serangan yang menyasar GKK di Gaza mesti menjadi alarm global untuk menghidupkan kembali “bara api” moderasi.
Insiden di Gaza bisa menjadi momentum bagi komunitas internasional dan lintas agama untuk:
(1) Mengafirmasi pentingnya perlindungan terhadap minoritas dengan dalil aqli: “mayoritas mesti melindungi minoritas”, (2) mendorong dialog antaragama sebagai jalan damai, dan (3) mengedukasi publik bahwa agama bukan alat kekuasaan, melainkan jalan kasih dan keadilan.
At last but not list, (keempat), moderasi beragama adalah penjaga nurani.
Ketika tempat ibadah diserang, itu bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal hilangnya nurani kolektif.
Moderasi beragama mengajak kita untuk menjaga nurani itu dengan empati, refleksi, dan keberanian untuk bersuara.
Apa itu Moderasi Beragama?
Moderasi beragama (religious moderation) adalah sebuah konsep, sikap, dan cara beragama yang menekankan keseimbangan dan keadilan, memahami dan menjalankan ajaran agama secara moderat, agar terhindar dari sikap ekstrem kiri maupun kanan.
Pribadi yang moderat selalu menghargai ajaran agama sendiri, sekaligus menghormati agama lain dengan prinsip keadilan, keseimbangan, cinta tanah air, akhlak inklusif, dan keterbukaan terhadap keragaman.
Konsep ini menjadi landasan yang kuat untuk memelihara harmoni di tengah masyarakat yang multikultural.
Moderasi beragama tidak membenarkan anggapan bahwa “semua agama sama”.
Akan tetapi, moderasi beragama menjunjung tinggi kemanusiaan dengan dalil, semua manusia berhak dihormati dalam keyakinannya, sebuah pengakuan dan penghormatan yang jujur terhadap martabat manusia.
Dalam studi perbandingan agama, diperoleh titik temu. Misalnya dalam Islam, konsep wasathiyah (jalan tengah) menekankan keseimbangan antara keyakinan dan kemanusiaan, sementara dalam Kristen, kasih kepada sesama adalah hukum yang melampaui sekat-sekat identitas.
Literasi moderasi beragama mengajarkan bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan, keyakinan tidak perlu dibuktikan dengan kekerasan, dan bahwa ibadah orang lain bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa kita tidak sendirian.
Mengutip A.M. Romly (2025), “ Manusia tidak berada di ruang hampa. Sejak lahir ke dunia manusia hidup di suatu ruang yang dihuni pelbagai makhluk Tuhan. Manusia hidup berdampingan dengan alam dan sesamanya.”
Jadi dalam konteks tragedi GKK di Gaza, moderasi beragama jangan direduksir sebagai sekadar toleransi.
Moderasi beragama merupakan keberanian untuk berdiri di tengah, ketika dua kutub saling membakar.
Ia adalah suara yang berkata: “Tidak atas nama Tuhan.” Ia adalah tangan yang merangkul, bukan menunjuk.
Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau seseorang itu bukan sesamamu seiman, maka pandanglah dia sebagai saudaramu sekemanusiaan.
Mari Bangkit Bersama
Untuk menemukan hati yang enggan membenci di balik puing-puing GKK di Gaza, kita hari ini jangan hanya bisa mengecam, dan apalagi mengutuk.
Demi nilai-nilai universal: keadilan, kasih sayang, hak asasi manusia, dan martabat hidup, mari kita harus dan terus bergerak untuk:
(1) Melindungi tempat ibadah sebagai zona damai (dar al-salam), (2) mendorong dialog lintas iman dan budaya, dan (3) mengedukasi publik bahwa perang bukan solusi, dan bahwa agama bukan alasan untuk membunuh.
Sebab, apabila gereja bisa dihancurkan, maka masjid pun bisa. Jika salib bisa dibungkam, maka bulan sabit pun bisa dipatahkan. Dan jika kita diam, maka kita ikut membenarkan.
Tragedi GKK di Gaza mengajarkan kita satu hal yakni bahwa tempat paling suci bukanlah bangunan, tapi hati yang enggan membenci. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Hendrikus Maku
Gereja Keluarga Kudus Gaza
konflik Gaza
Opini Pos Kupang
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Israel
Palestina
Paus Fransiskus
Sri Paus Leo XIV
| Opini: Prada Lucky dan Tentang Degenerasi Moral Kolektif |

|
|---|
| Opini: Drama BBM Sabu Raijua, Antrean Panjang Solusi Pendek |

|
|---|
| Opini: Kala Hoaks Menodai Taman Eden, Antara Bahasa dan Pikiran |

|
|---|
| Opini: Korupsi K3, Nyawa Pekerja Jadi Taruhan |

|
|---|
| Opini: FAFO Parenting, Apakah Anak Dibiarkan Merasakan Akibatnya Sendiri? |

|
|---|

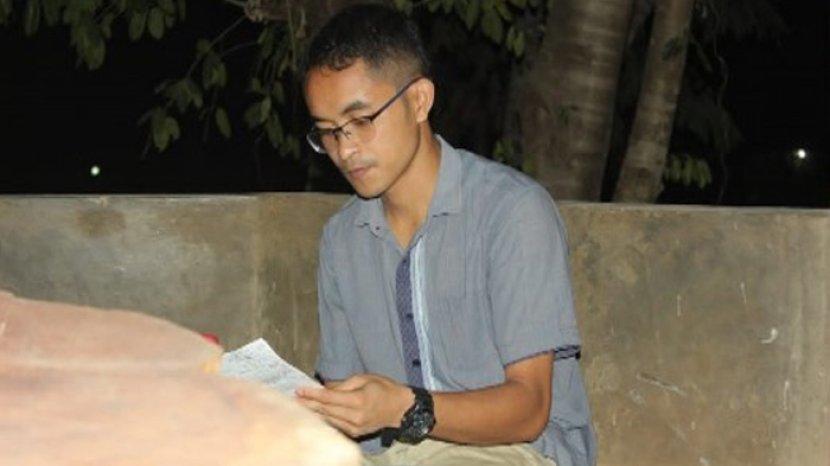








![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.