Opini
Opini: Akses Informasi yang Terbuka dan Krisis Etika Generasi Alfa
Akibatnya, alih-alih tercerahkan banyak pelajar justru terjebak dalam ilusi tahu — di mana informasi diterima mentah-mentah tanpa proses refleksi
Oleh: Soni Laiju Malana, M.Pd., C.GMC
Dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, dan Certified Growth Mindset Coach
POS-KUPANG.COM - Di era digital yang berkembang sangat pesat, revolusi informasi telah membuka pintu akses terhadap pengetahuan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI), algoritma pembelajaran mesin (Machine Learning), dan perangkat lunak pencarian canggih memungkinkan generasi alfa — mereka yang tumbuh bersama layar sentuh dan cloud — untuk menjangkau jutaan informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, kelimpahan ini justru membawa dilema epistemologis baru.
Head et al (2020) mencatat bahwa para siswa kini terjebak dalam lanskap informasi yang "melimpah namun membingungkan" di mana informasi tidak hanya datang dari sumber akademik, tetapi juga dari media sosial, konten algoritmik, dan mesin rekomendasi yang sering kali memperkuat bias.
Dalam konteks ini, kecepatan distribusi informasi tidak selalu sejalan dengan kedalaman pemahaman, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai katastropi pengetahuan.
Istilah ini mengacu pada fenomena ketika keterpaparan tinggi terhadap data justru membuat individu kebingungan memilah mana yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pedro et al. (2019) menyebut kondisi ini sebagai information overload, yakni situasi di mana manusia kewalahan memproses banjir data karena tidak memiliki cukup literasi kritis untuk mengevaluasi informasi secara sistematis.
Akibatnya, alih-alih tercerahkan, banyak pelajar justru terjebak dalam ilusi tahu — di mana informasi diterima mentah-mentah tanpa proses refleksi dan verifikasi.
Inilah ironi dari revolusi informasi: teknologi yang seharusnya membebaskan pengetahuan, justru menciptakan paradoks kebingungan epistemik.
Generasi Alfa dan Tantangan Literasi Digital
Generasi alfa, yaitu generasi yang lahir dan besar dalam ekosistem digital yang serba terhubung, menghadapi tantangan yang unik dan kompleks dalam hal literasi digital.
Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif perangkat digital sejak usia dini, tetapi juga terbiasa dengan kehadiran teknologi cerdas seperti asisten virtual, algoritma personalisasi, dan media sosial berbasis AI.
Namun, kemahiran teknologis yang tinggi tidak otomatis diiringi dengan kedewasaan dalam menyikapi dampaknya.
Sebagai pendidik, tantangan utama kita bukan sekadar memperkenalkan alat atau aplikasi baru, melainkan membentuk fondasi literasi digital yang etis dan kritis.
Penelitian Hristovska (2023) menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat literasi digital tinggi sekalipun masih menunjukkan kelemahan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan etika, terutama ketika berhadapan dengan konten manipulatif atau informasi yang bias secara algoritmis.
Fekete et al. (2025) menambahkan bahwa ketidaksadaran terhadap bagaimana algoritma bekerja telah membuat sebagian besar anak muda menjadi korban dari apa yang disebut “ bubble informasi” atau ruang gema digital (echo chamber), di mana mereka hanya terpapar pada pandangan yang memperkuat keyakinan mereka sendiri.
Dalam konteks ini, pendidikan harus melampaui ranah kognitif menuju pembentukan karakter moral.
Literasi digital tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga sebagai seperangkat nilai, seperti tanggung jawab, integritas, dan empati dalam dunia maya.
Maka, transformasi kurikulum yang menekankan pada pemahaman terhadap bias data, privasi digital, serta implikasi sosial dari penggunaan AI menjadi sangat mendesak untuk diprioritaskan demi membekali generasi alfa sebagai warga digital yang cerdas sekaligus bijaksana.
AI dan Krisis Etika dalam Pendidikan
Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dalam dunia pendidikan membawa kemudahan luar biasa dalam akses, analisis, dan distribusi informasi.
Namun, kemudahan ini sekaligus membuka ruang bagi krisis etika yang semakin kompleks.
AI tidak lagi sekadar menyajikan data secara netral, tetapi juga mampu menciptakan narasi, mengedit gambar dan suara, bahkan menyusun argumen yang meyakinkan tanpa keterlibatan manusia.
Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap integritas informasi, terutama ketika sistem AI digunakan untuk menghasilkan konten tanpa pengawasan etik dan literasi digital yang memadai.
Usman et al. (2024) menekankan bahwa fenomena deepfake—konten video atau suara palsu berbasis AI yang sulit dibedakan dari yang asli—telah merambah dunia akademik, mengancam kredibilitas sumber dan membingungkan siswa dalam membedakan fakta dan fiksi.
Sementara itu, penelitian Kassymova et al. (2023) menunjukkan banyak sistem pendidikan global belum memiliki kerangka kebijakan yang memadai untuk menangani kompleksitas etika penggunaan AI di ruang kelas.
Dalam situasi ini, guru dan pendidik tidak dapat lagi berperan pasif sebagai pengguna teknologi; mereka harus menjadi penjaga kebenaran digital, yakni aktor yang mampu mengidentifikasi disinformasi, memahami cara kerja algoritma, serta membimbing siswa untuk mempertanyakan sumber informasi secara kritis dan etis.
Pendidikan abad ke-21 tidak hanya menuntut literasi digital, tetapi juga literasi moral dalam menghadapi teknologi yang memiliki potensi manipulatif.
Dengan demikian, kurikulum pendidikan harus diarahkan untuk membekali peserta didik dengan kesadaran bahwa tidak semua yang tampak sahih secara digital adalah benar secara faktual atau etis.
Empat Paradoks Pendidikan dalam Era AI
Dalam lanskap pendidikan yang semakin terdigitalisasi, pendidik dihadapkan pada empat paradoks utama yang menandai kompleksitas peran teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), dalam proses belajar-mengajar.
Pertama, keterbukaan akses versus ketertutupan pemahaman. Meskipun siswa kini memiliki akses nyaris tak terbatas terhadap sumber daya digital, hal ini belum tentu berbanding lurus dengan pemahaman makna.
Mihailidis (2018) menyebut kondisi ini sebagai bentuk paradoks literasi digital, di mana keterbukaan informasi justru mengaburkan kemampuan interpretatif karena minimnya pendampingan kritis.
Kedua, kecerdasan buatan vs kebijaksanaan manusia. AI memang mendorong efisiensi dalam manajemen kelas, personalisasi pembelajaran, dan penilaian otomatis, namun ia tak mampu menggantikan dimensi afektif dan etika dari relasi pendidik-peserta didik.
Nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, dan intuisi moral tetap eksklusif sebagai domain manusiawi.
Ketiga, kelimpahan data vs kelangkaan etika. Haider dan Sundin (2022) menegaskan bahwa meskipun data kini menjadi "mata uang baru" dalam dunia pendidikan, masih sedikit lembaga yang mengembangkan kurikulum etika digital secara komprehensif.
Akibatnya, siswa mahir dalam teknis penggunaan data, namun rentan terhadap penyalahgunaannya.
Keempat, efisiensi digital vs kehilangan konteks budaya. Standarisasi sistem berbasis AI berisiko mengabaikan konteks lokal dan kearifan budaya dalam pembelajaran.
Ketika algoritma global diterapkan secara seragam, praktik pendidikan lokal yang berbasis nilai komunitas bisa terpinggirkan.
Oleh karena itu, keempat paradoks ini perlu direspons dengan pendekatan pendidikan yang seimbang antara teknologi, etika, dan budaya lokal agar transformasi digital tidak menggerus fondasi kemanusiaan dalam pendidikan.
Tugas Pendidik: Menanamkan Etika sebagai Kompetensi Inti – Perspektif Umum dan Pendidikan Kristen
Di tengah era digital yang ditandai dengan information overload dan disrupsi nilai akibat kemajuan teknologi kecerdasan artifisial (AI), peran pendidik mengalami transformasi yang sangat fundamental.
Tugas utama guru bukan lagi semata menyampaikan pengetahuan, melainkan membentuk karakter, menanamkan etika, dan membimbing peserta didik agar mampu menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam dunia yang kian kompleks dan digital.
Memasuki era post-truth, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta, tetapi seringkali dikaburkan oleh persepsi emosional, opini viral, atau algoritma platform digital yang membentuk gelembung informasi (echo chamber).
Dalam kondisi ini, pendidikan yang mengabaikan aspek etika akan gagal menciptakan warga digital yang tangguh secara moral.
Etika dalam pendidikan digital tidak boleh hanya menjadi muatan lokal atau kurikulum tambahan, tetapi harus ditanamkan sebagai kompetensi inti dalam pembelajaran modern.
Fiannaca (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa calon guru yang dibekali pelatihan literasi media dan digital secara serius memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap tanggung jawab etis mereka.
Mereka cenderung lebih reflektif dalam membimbing siswa untuk memahami konteks, memverifikasi sumber, dan menyikapi informasi palsu atau bias secara kritis.
Cismaru et al. (2018) bahkan mengusulkan konsep digital intelligence—kemampuan mengintegrasikan literasi teknologi, penguasaan informasi, serta sensitivitas moral—sebagai bentuk kecerdasan baru yang harus dibangun dalam pendidikan masa kini.
Hal ini menegaskan bahwa kecakapan teknologi harus berjalan seiring dengan kesadaran akan dampak sosial, politik, dan spiritual dari penggunaannya.
Dalam konteks pendidikan Kristen, peran ini menjadi semakin mendalam dan transenden.
Sekolah Kristen tidak hanya bertanggung jawab dalam membekali siswa dengan kecakapan akademik dan digital, tetapi juga memikul amanat iman untuk membentuk manusia seutuhnya—secara intelektual, moral, dan rohani.
Etika tidak sekadar menjadi alat berpikir kritis, tetapi menjadi bagian dari panggilan untuk hidup dalam kebenaran, kasih, dan keadilan sebagaimana nilai-nilai Injil ajarkan.
Dalam surat Roma 12:2, Rasul Paulus menasihati agar kita “jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi,” yang dalam konteks pendidikan digital, dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menolak arus informasi yang menyesatkan dan hidup dalam terang kebenaran Kristus.
Guru dan pendidik Kristen dengan demikian dipanggil menjadi penjaga nilai dan penuntun moral di tengah dunia digital yang sarat godaan relativisme dan manipulasi data.
Mereka bukan hanya fasilitator teknologi, tetapi juga imam pengetahuan yang harus mengajarkan discernment (kemampuan membedakan yang benar dan salah), integritas, serta kasih terhadap sesama dalam ruang digital.
Kurikulum di sekolah Kristen harus mengintegrasikan pendidikan etika digital dengan nilai-nilai iman, bukan sekadar sebagai respon terhadap perubahan zaman, tetapi sebagai perwujudan dari visi besar: membentuk generasi alfa yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga berakar kuat dalam iman, etika, dan tanggung jawab sosial.
Dalam badai digitalisasi global, etika menjadi jangkar yang menuntun bukan hanya arah berpikir, tetapi juga arah hidup.
Membentuk Generasi Alfa yang Kritis dan Beretika – Sinergi Pendidikan, Kebijakan, Keluarga, dan Gereja
Generasi alfa adalah generasi pertama yang sepenuhnya akan menjalani kehidupan berdampingan dengan kecerdasan artifisial (AI), Internet of Things (IoT), dan otomatisasi dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, komunikasi, ekonomi, hingga pengambilan keputusan sosial.
Dalam konteks ini, tantangan utama pendidikan bukan lagi terbatas pada memperkenalkan teknologi, tetapi pada bagaimana membentuk individu yang mampu menggunakan teknologi secara etis, kritis, dan bertanggung jawab.
Pertanyaan kunci yang harus diajukan bukan lagi “sejauh mana anak-anak memahami teknologi”, melainkan “dapatkah mereka membedakan kebenaran dan kepalsuan, dan bertindak sesuai prinsip etika dalam ekosistem digital?”
Sebagaimana dijelaskan oleh Holmes dan Porayska-Pomsta (2023), pendidikan berbasis AI harus dilandasi oleh kesadaran akan dampak sosial, kultural, dan moral dari setiap interaksi digital yang dilakukan.
Implikasi dari tantangan ini bersifat multidimensional dan menuntut keterlibatanbanyak pihak.
Pertama, kebijakan pendidikan nasional harus mulai menempatkan literasi etika digital sebagai komponen inti kurikulum.
Ini berarti mengintegrasikan pengajaran tentang privasi data, tanggung jawab digital, dan implikasi moral penggunaan teknologi dalam semua mata pelajaran, bukan hanya dalam mata pelajaran teknologi informasi.
Kurikulum perlu didesain untuk memperkuat karakter siswa dalam menghadapi banjir informasi dan godaan algoritma yang mengutamakan keterlibatan, bukan kebenaran.
Pemerintah dan lembaga Pendidikan harus mempercepat regulasi dan pengembangan kompetensi guru agar mampu mengintegrasikan pembelajaran berbasis nilai dalam konteks digital yang terus berubah.
Kedua, peran orang tua sangat krusial dalam membentuk kebiasaan digital anak di luar lingkungan sekolah. Literasi teknologi di rumah harus disertai dengan literasi moral.
Anak perlu diajak berdialog tentang apa yang mereka lihat dan konsumsi secara daring, serta diberikan teladan tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.
Pendidikan karakter tidak dapat berlangsung hanya dalam institusi formal—keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam pembentukan integritas.
Ketiga, gereja dan komunitas iman memegang peranan vital dalam menanamkan nilai-nilai kekristenan di tengah transformasi digital.
Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat formasi moral. Dalam tradisi Kristen, kebenaran bukan sekadar fakta, melainkan sesuatu yang dihidupi dan diwujudkan dalam kasih dan keadilan.
Gereja dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar menggunakan teknologi demi pelayanan, kesaksian, dan karya kasih.
Sekolah Kristen, dalam hal ini, harus menjadi pelopor dalam menyinergikan pembelajaran teknologi dan pembinaan spiritualitas—mengajarkan siswa bahwa menjadi cakap digital tanpa akhlak adalah kehampaan moral.
Dengan sinergi antara kebijakan pendidikan yang berpihak pada nilai, keluarga yang aktif mendampingi, dan gereja yang konsisten membina, maka pendekatan holistic yang memadukan literasi teknologi, etika, dan iman dapat benar-benar terwujud.
Hanya melalui kolaborasi inilah kita mampu menyiapkan generasi alfa menjadi warga digital yang bukan hanya mahir dalam mengoperasikan teknologi, tetapi juga mampu menavigasi dunia dengan kebijaksanaan, empati, dan integritas.
Kesimpulan
Tulisan ini menyoroti tantangan besar dalam membentuk generasi alfa—generasi digital pertama—yang tidak hanya cakap dalam teknologi, tetapi juga matang secara etika dan moral.
Meskipun revolusi informasi dan kecerdasan artifisial (AI) menawarkan akses pengetahuan tanpa batas, realitas menunjukkan adanya katastropi pengetahuan, information overload, dan krisis etika akibat kurangnya literasi kritis dan moral dalam menyikapi arus data yang tak terfilter.
Oleh karena itu, pendidikan harus bertransformasi dari sekadar transmisi informasi menjadi proses pembentukan karakter yang berakar pada nilai.
Pendidik, khususnya di sekolah Kristen, dipanggil untuk mengintegrasikan literasi digital dan pembinaan iman dalam kurikulum, menjadikan etika sebagai kompetensi inti.
Selain itu, kebijakan pendidikan nasional, keterlibatan aktif orang tua, dan peran gereja sebagai Pembina nilai rohani menjadi elemen penting dalam menciptakan sinergi holistik.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, generasi alfa dapat dipersiapkan menjadi warga digital yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijak, kritis, dan bertanggung jawab. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Soni Laiju Malana
generasi alfa
kecerdasan buatan
algoritma
Opini Pos Kupang
POS-KUPANG.COM
Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang
| Opini: Pergeseran Makna Manusia sebagai Makhluk Politik, Dari Polis ke Platform |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Bernabas-Unab.jpg)
|
|---|
| Opini: Manusia, Makhluk yang Tak Pernah Selesai Berbahasa |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Yoseph-Yoneta-Motong-Wuwur.jpg)
|
|---|
| Opini: Catatan Filsafat Hukum atas Masalah Geotermal di Flores |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Fladimir-Sie.jpg)
|
|---|
| Opini: Dari Sumpah Pemuda ke Sumpah Sehat |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Prima-Trisna-Aji.jpg)
|
|---|
| Opini: Penjarahan yang Dilegalkan dan Tantangan bagi Indonesia |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Paskalis-Semaun.jpg)
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Algoritma-ilustrasi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/dr-Shinta-Widari-dan-Dr-Dewa-Putu-Sahadewa.jpg)








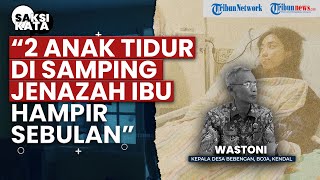
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Try-Suriani-Loit-Tualaka3.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/dr-Shinta-Widari-dan-Dr-Dewa-Putu-Sahadewa.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Yantho-Bambang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Kembo-Pieter1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Ester-Theresia-Clarita-Tallo.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.