Opini
Opini: Sudahkah Indonesia menjadi Rumah Aman Bagi Semua Agama?
Kejadian tersebut terjadi ketika rombongan pelajar yang berusia 10 hingga 14 tahun bersama pendamping mereka sementara mengadakan kegiatan retret.
Oleh: Gebrile Mikael Mareska Udu
Mahasiswa Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
POS-KUPANG.COM - Pada Jumat, 27 Juni yang lalu, bangsa Indonesia digemparkan dengan persoalan serius menyangkut sikap intoleransi antarumat beragama.
YD (56 tahun), pengelolah rumah singgah atau vila yang terdapat di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat mengungkapkan bahwa terjadinya perusakan fasilitas atas rumahnya oleh sekelompok warga setempat.
Kejadian tersebut terjadi ketika rombongan pelajar yang berusia 10 hingga 14 tahun bersama pendamping mereka sementara mengadakan kegiatan retret.
Para pelaku diperkirakan berasal dari umat mayoritas muslim karena pelajar yang mengikuti retret beragama Kristen.
Persoalan tersebut menjadi bukti hancurnya kerangka “kerukunan” hidup antarumat beragama di Indonesia.
Kondisi vila yang hancur berantakan menggiring kita pada pertanyaan yang mengusik hati nurani kita: apakah Indonesia sudah menjadi tempat aman bagi semua agama?
Kasus Cidahu mengartikulasikan rentannya pertarungan terbuka antara Kristen dan Islam, hilangnya sikap saling segan untuk menghormati satu sama lain.
Saking peliknya persoalan ini, pemerintah tidak tinggal diam untuk menemukan langkah solutif.
Kang Edi Mulyadi yang dikenal sebagai gubernur online hingga kini mendukung upaya pengusutan tuntas oleh pihak kepolisian atas masalah ini.
Memang, sikap intoleransi antarumat beragama merupakan suatu kecelakaan yang dahsyat bagi Negara Indonesia yang multikultural ini.
Hal itu tidak hanya dikarenakan adanya perbedaan keyakinan tetapi juga memicu kekerasan yang begitu cepat.
Kekerasan atas nama agama dapat memicu terjadinya kehancuran sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa ini.
Tidak mengherankan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan RI Ir. Soekarno sekaligus presiden pertama pernah mengusulkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ia mengatakan, “hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama.”
Bung Karno menyadari akan pentingnya kebebasan mengekspresikan kegiatan keagamaan bagi siapa saja tanpa adanya kekrasan terhadap yang lain.
Hanya saja Indonesia oleh segelintir orang tidak menghiraukannya. Agama justru dijadikan sebagai persaingan antara komunitas sosial di tengah masyarakat.
Sesungguhnya kita patut bersyukur bahwa tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang memiliki latar belakang keagamaan yang kompleks seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara heterogen, plural dan majemuk.
Misalnya saja dalam hal agama, di Indonesia diakui terdapat enam agama negara yakni Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Konghucu.
Agama memainkan peranan penting dalam menjaga etika dan moralitas bangsa. Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
Sayangnya pluralisme agama di negara kita tidak menjamin tindakan seseorang terhadap yang lain.
Banyak kejadian destruktif dari relasi antarumat beragama di Indonesia seperti kasus Sukabumi di atas.
Lantas apa penyebab sikap intoleransi antarumat beragama di Indonesia?
Prinsip Mayoritas dan Minoritas di Indonesia
Patut diakui bahwa fenomena konflik sosial di tengah masyarakat agama pluralistis disebabkan oleh pemahaman yang keliru akan prinsip mayoritas dan minoritas golongan agama.
Prinsip mayoritas dalam agama pertama-tama dipahami sebagai kelompok pemeluk agama tertentu dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan kelompok lain.
Dalam hal ini mayoritas umat muslim. Sedangkan minoritas itu mewakili kelompok pemeluk agama tertentu dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan kelompok mayoritas. Minoritas itu seperti umat Kristen, Budha dan seterusnya.
Lebih dalam pemahaman yang salah akan kedua prinsip itu tampak di dalam tiga poin berikut.
Pertama, agama mayoritas dijadikan sebagai dasar ideologi suatu bangsa. Dalam konteks ini ajaran dan identitas agama mayoritas sering dianggap sebagai identitas nasional yang mutlak.
Jika suatu kelompok masyarakat beragama islam, misalnya maka simbol-simbol keislaman diterima sebagai simbol negara sementara ekspresi agama lain — keberadaan gereja/rumah retret, pura, vihara—dianggap mengganggu harmoni masyarakat setempat.
Persis masalah intoleransi di Cidahu mengafirmasi pandangan tersebut. Masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan rumah retret apalagi kegiatan keagamaan Kristen yang dianggap “berlawanan” dengan mereka.
Kedua, prasangka mayoritas terhadap minoritas begitu pun sebaliknya. Prasangka yang dimaksud merujuk pada rasa superior kelompok mayoritas ketika berhadapan dengan kelompok minoritas.
Rasa superior mengarah pada sikap merasa benar, lebih sah, dan lebih berhak “bersuara” dalam ruang sosial dan keagamaan.
Sementara kelompok minoritas merasa inferior, tidak berdaya atau takut ketika berhadapan dengan kelompok mayoritas.
Prasangka inferior tersebut membuat kelompok harus “meminta izin” ketika menjalankan ibadah meskipun negara telah membuka ruang ekspresi sebebas-bebasnya oleh negara.
Ketiga, mitos dari mayoritas. Poin ketiga ini berangkat dari klaim bahwa kehidupan politik suatu bangsa amat ditentukan oleh suara mayoritas.
Bahwasanya suara mayoritas kerap menjadi penentu dalam ajang kontestasi elite politik.
Dalam praksis demokrasi memang benar bahwa suara terbanyak menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan umum atau keputusan politik.
Ironisnya, hal ini menciptakan mitos mayoritas di mana ada keyakinan bahwa mayoritas bukan hanya menentukan hasil politik tetapi juga menentukan nilai moral, kebenaran sosial dan kehidupan publik.
Padahal mitos ini mampu mengaburkan prinsip dasar demokrasi yang bukan hanya soal siapa yang terbanyak melainkan juga soal bagaimana melindungi yang lemah dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.
Tiga poin yang telah dijabarkan rentan menimbulkan sikap intoleransi dalam relasi antaragama.
Jika ketiganya dibiarkan begitu saja, cita-cita Bung Karno menjadi sia-sia belaka. Oleh karena itu kita perlu langkah solutif.
Kembali Ke dalam: Menuju Dialog Antariman
Bahaya prinsip mayoritas dan minoritas dalam keberagaman bangsa secara khusus dalam hal agama hanya bisa dihadapi dengan jalan dialog.
Secara sederhana dialog dipahami sebagai percakapan antara dua orang atau lebih yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai yang dimiliki masing-masing pihak.
Dialog juga berarti pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya.
Dalam konteks hubungan antaragama, dialog dapat didefinisikan sebagai suatu temu wicara antara dua atau lebih pemeluk agama yang berbeda, yang dilakukan dalam semangat saling menghormati untuk bertukar informasi, nilai-nilai keagamaan serta pengalaman iman masing masing.
Tujuan utama dialog ini adalah membangun sikap saling pengertian, mempererat hubungan antarumat beragama dan menciptakan kerja sama yang harmonis demi terwujudnya kerukunan dan perdamaian (Hendropuspito, 2002)
Kasus Cidahu menandakan bahwa dialog antarumat beragama di Indonesia tidak dihidupi dengan baik.
Sikap sombong, egois dan tertutup masih meracuni mentalitas setiap pribadi sebagaimana prinsip mayoritas dan minoritas.
Oleh karena itu, saatnya setiap pribadi dituntut untuk membangun kesadaran baru akan pentingnya dialog dalam kehidupan bersama.
Dialog mesti menciptakan suasana persahabatan/ persaudaraan untuk mendengar, menyapa dan bertukar pikiran dengan sesama. Dialog mengubah prinsip mayoritas dan minoritas menjadi kekeluargaan.
Semua pihak layak untuk dihormati dan dihargai. Akhirnya negara tercinta ini bisa menjadi rumah aman bagi semua agama. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Gebrile-Mikael-Mareska-Udu.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Deford-N-Lakapu.jpg)




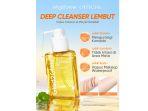


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Robert-Bala-ceramah.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Yoseph-Yoneta-Motong-Wuwur.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Christina-Kewa-Liku-Mahasiswa-ITB-Stikom-Bali-di-Jepang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Miky-Oktovianus-Smaut-Natun.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Adi-Ngongo.jpg)

![[FULL] Isi Pidato Gibran Bahasa Inggris di Indonesia-Afrika CEO Forum, Umumkan Bebas Visa & Komitmen](https://img.youtube.com/vi/pyJdIgq_xI8/mqdefault.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Adi-Ngongo.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/dr-Shinta-Widari-dan-Dr-Dewa-Putu-Sahadewa.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Try-Suriani-Loit-Tualaka3.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Dwison-Andresco-Renleeuw.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Yantho-Bambang.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.