Opini
Opini: Saat Cancel Culture Menguji Mimbar Kebebasan
"Cancel Culture" adalah cermin retak yang memantulkan kompleksitas interaksi kita di jagat maya, sekaligus menguji fondasi salah satu pilar demokrasi.
Oleh: Abner Paulus Raya Midara Sanga
Tinggal di Kota Kupang
POS-KUPANG.COM - Bayangkan sebuah panggung raksasa, terbentang luas tanpa batas, di mana setiap orang bisa berteriak, berbisik, atau bersenandung.
Inilah dunia digital kita, tempat suara-suara berlipat ganda, dan gema menyebar secepat kilat.
Namun, di tengah gemuruh itu, muncul sebuah fenomena yang bukan sekadar gema, melainkan dentuman palu yang menggema: "Cancel Culture".
Ini bukan lagi istilah asing; ia adalah "hukum rimba" baru di alam maya, di mana sebuah kalimat melenceng atau tindakan masa lalu bisa memicu badai boikot massal, mengikis reputasi, memutus tali pekerjaan, dan membungkam suara di atas panggung itu.
"Cancel Culture" adalah cermin retak yang memantulkan kompleksitas interaksi kita di jagat maya, sekaligus menguji fondasi salah satu pilar demokrasi: kebebasan berpendapat.
Apakah ia adalah pedang keadilan yang baru, atau justru tirai besi yang menelan perbedaan?
Ketika Ribuan Jempol Menjelma Palu Akuntabilitas
Dahulu kala, para "raja" panggung publik—selebriti, politisi, korporat kakap - seringkali seolah diselimuti jubah kebal.
Mereka bisa saja melontarkan bisikan kebencian, menyebarkan racun kebohongan, atau berdansa di atas etika tanpa banyak goresan. Kekuasaan adalah perisai mereka. Tapi kini perisai itu berlubang.
Media sosial telah meruntuhkan menara gading kekebalan, mengubah setiap gawai menjadi "mikrofon" dan setiap jempol menjadi "palu" yang siap mengetuk.
Dalam narasi ini, "Cancel Culture" adalah revolusi bisikan. Ia adalah kekuatan kolektif dari mereka yang sebelumnya terbungkam, kini memiliki megafon di genggaman.
Ketika sepotong komentar rasis, seksis, atau ujaran kebencian lainnya terkuak dari bibir figur publik, jutaan pasang mata dan ribuan jempol bersatu.
Tagar menjadi seruan perang, kampanye daring menjadi gerakan gelombang, menuntut pertanggungjawaban.
Ini adalah demokrasi yang bergejolak, di mana masyarakat sipil secara efektif menjadi "penjaga gerbang" moralitas panggung.
Skenarionya berulang: selebriti yang masa lalunya kelam terkuak, politisi yang ingkar janji diarak di linimasa, perusahaan yang berselimut praktik kotor tiba-tiba disorot lampu sorot.
Dalam setiap kasus, gelombang "cancel" memaksa mereka untuk berlutut, mengakui kesalahan, meminta maaf di hadapan publik, dan menanggung konsekuensi pahit.
Dari sudut pandang ini, "Cancel Culture" adalah cambuk yang mendidik, memaksa para penghuni panggung untuk lebih berhati-hati, lebih etis, dan lebih bertanggung jawab, membangun panggung yang lebih adil dan responsif.
Bayangan "Penyensoran Massal" di Balik Janji Akuntabilitas
Namun, di balik janji akuntabilitas itu, tersembunyi bayangan pekat yang mengancam napas kebebasan berpendapat. Salah satu yang paling menakutkan adalah "efek dingin" (chilling effect).
Bayangkan seorang seniman yang ingin melukis tema kontroversial, seorang ilmuwan yang ingin mengemukakan hipotesis tak populer, atau seorang warga biasa yang punya kritik tajam.
Ketakutan akan "dibungkam" oleh badai "cancel" bisa membekukan jemari mereka, membisukan lidah mereka.
Jika setiap perbedaan pandangan dianggap sebagai "ancaman" yang berpotensi menghancurkan karier, maka panggung diskusi publik akan menyusut, hanya menyisakan tepuk tangan untuk ide-ide "aman" dan selaras.
Ini adalah racun bagi masyarakat demokratis, yang hidup dari pertukaran gagasan yang bebas dan berani.
Masalah mendasar lainnya adalah ketiadaan proses peradilan yang adil. "Mahkamah" di media sosial beroperasi tanpa hakim, tanpa juri yang netral, dan tanpa hak pembelaan yang setara.
Informasi bisa saja dicomot, dipelintir, atau dicabut dari konteksnya, hanya untuk memicu amarah massa.
Sebuah tulisan lama yang tak lagi mencerminkan pandangan seseorang saat ini bisa digali kembali sebagai "senjata" pemusnah reputasi.
Proses ini, layaknya "pengadilan rakyat" di alun-alun digital, tak memberi ruang bagi individu untuk menjelaskan, menyesal, atau bahkan menunjukkan bahwa mereka telah bertransformasi. Dan hukuman yang dijatuhkan?
Seringkali tak sebanding. Sebuah karier yang dibangun dengan cucuran keringat puluhan tahun bisa hancur dalam semalam hanya karena satu cuitan yang blunder.
Lebih jauh, "Cancel Culture" cenderung meratakan kompleksitas diskusi.
Topik-topik yang rumit, yang butuh pemahaman mendalam dan nuansa, seringkali disederhanakan menjadi biner—hitam atau putih—demi kepentingan polarisasi.
Di panggung ini, emosi dan kemarahan seringkali memimpin, menenggelamkan rasionalitas dan analisis mendalam.
Ketika setiap kesalahan dianggap dosa tak terampuni, dan setiap perbedaan pendapat dianggap serangan pribadi, kita kehilangan kemampuan untuk berdialog konstruktif tentang isu-isu yang sebenarnya memerlukan akal sehat dan empati.
Menemukan Harmoni di Antara Dentuman dan Bisikan Digital
Jadi, bagaimana kita menavigasi labirin kompleks ini? Bagaimana kita menemukan melodi yang harmonis antara tuntutan akuntabilitas dan jaminan kebebasan berpendapat?
Kuncinya terletak pada kearifan digital dan etika komunikasi yang kokoh. Kita harus melatih diri menjadi "detektif" informasi, memeriksa fakta dari berbagai sumber, dan memahami konteks sebelum kita ikut melemparkan "batu" di keramaian daring.
Kita harus belajar membedakan antara "racun" ujaran kebencian (yang memang harus dibasmi) dan "madu" perbedaan pandangan (yang harusnya justru dirayakan).
Platform media sosial, sebagai "penjaga panggung," juga punya tanggung jawab besar.
Mereka harus berinvestasi pada moderasi konten yang lebih cerdas dan transparan, serta menciptakan mekanisme yang mendorong diskusi, bukan persekusi.
Algoritma mereka tak boleh lagi hanya mengejar viralitas, melainkan harus diarahkan untuk memupuk dialog yang sehat dan beragam.
Sebagai individu, kita juga perlu merefleksikan diri. Apakah tujuan kita adalah menghukum dan mempermalukan secara permanen, atau mendorong pertanggungjawaban, edukasi, dan kesempatan untuk berubah?
Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memberi ruang bagi individu yang tersandung, belajar dari kesalahannya, dan bangkit lagi.
Jika setiap kekeliruan, sekecil apa pun, berujung pada kehancuran total, maka kita berisiko menciptakan masyarakat yang lumpuh karena ketakutan, di mana kreativitas dan keberanian intelektual akan layu.
Di Indonesia, seperti di setiap sudut panggung dunia, kita menyaksikan bagaimana "Cancel Culture" bisa memengaruhi tokoh nasional hingga lokal, dinamika komunitas, atau bahkan hiruk pikuk politik.
Penting bagi kita untuk membangun budaya komunikasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas, tetapi juga melindungi hak setiap suara untuk berpendapat tanpa takut dibungkam secara tidak adil.
Kebebasan berpendapat tak berarti bebas dari kritik, tapi kritik itu sendiri haruslah konstruktif, membuka jalan bagi dialog, bukan sekadar menghakimi dan membinasakan. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News














![[FULL] Puncak Amarah Warga Pati Demo Desak Bupati Sudewo Lengser, Pakar: Ini Bisa Dipolitisasi](https://img.youtube.com/vi/ffnVtOw8wRU/mqdefault.jpg)

















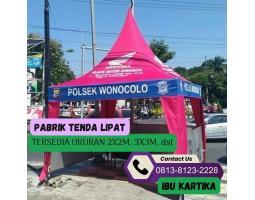
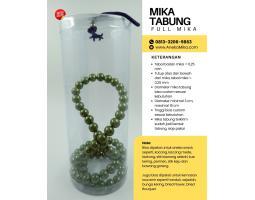







Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.