Opini
Opini: Dilema di Balik Konflik Lahan Nangahale Sikka
Klaim mencari pembenaran tentu saja wajar di tengah arus informasi yang tidak bisa terkontrol. Tetapi bagaimana sebaiknya memahami konflik ini?
Mengurai Konflik mencari Titik Temu
Oleh: Robert Bala
Diploma Resolusi Konflik Asia - Pasifik, Fakultad Ciencia Politicia, Universidad Complutense de Madrid Spanyol.
POS-KUPANG.COM - Video viral tentang pembokaran rumah tinggal warga di tanah milik PT Kristus Raja Keuskupan Maumere (KRISRAMA) cukup banyak mendatangkan tanggapan publik.
Di satu pihak, perusahaan milik keuskupan Maumere ini merasa telah melakukan pendekatan yang pas: pengumuman gereja, pengumuman pemerintah daerah, pendekatan dari orang perorang, termasuk somasi hukum.
Sementara itu pihak warga terdampak (meski dianggap sebagian kecil dan apalagi diprovokasi oleh aktor intelektual), tentu punya alasan yang tidak bisa dianggap sepeleh.
Minimal mereka mengulur-ulur waktu untuk memberi ruang untuk merancang kehidupan selanjutnya.
Klaim mencari pembenaran tentu saja wajar di tengah arus informasi yang tidak bisa terkontrol. Tetapi bagaimana sebaiknya memahami konflik ini?
Membiarkan klaim di tengah panasnya konflik hanya demi pembenaran akan menjauhkan masing-masing pihak dari solusi.
Penulis tidak berada pada satu posisi tetapi mencoba mengurai benang yang sudah terlanjur kusut yang bisa diharapkan menjadi celah menemukan solusi.
Penegasan PT KRISRAMA yang (telah dengan senang hati) menyerahkan kembali kepada Negara tanah seluas 543 Ha dari 868 Ha cukup banyak ditonjolkan untuk membuktikan betapa baiknya Gereja (baca: keuskupan Maumere).
Karena itu penyerobotan lahan oleh warga terhadap 325 ha yang dimiliki keuskupan tentu dianggap sesuatu yang di luar batas nalar.
Kebaikan gereja itu tentu bukan hanya itu. Di tahun 1926, saat Apostholik Vikariat Van de Klanis Soenda Elianden membeli tanah Amsterdam Soenda Compagn dari seharga 22.500 gulden, gereja juga ‘menghadiahkan’ 783 Ha kepada pemerintah Swapradja Sikka untuk kepentingan masyarakat.
Sampai di sini terasa lebih dari cukup untuk ‘membenarkan’ pengosongan lahan pada 22 Januari 2025. Yang jadi pertanyaan, apakah menjadikan tindakan ‘karitatif’ memiliki pendasaran yang cukup ataukah ketentuan UU tidak mengizinkan kepemilikan tanah yang sangat besar?
Ketentuan HGU (Hak Guna Usaha) diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU Agraria) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 misalnya hanya mengizinkan minimal 5 ha dan maksimal 25 ha. Kalau ada pengecualian tentu tidak sebanyak-banyak yang diinginkan.
Tetapi ada hal yang jauh lebih mendasar terkait kepemilikan ‘asli’. Bila tanah-tanah itu adalah milik Amsterdam Soenda Compagn tahun 1912, maka dari mana ia perolehnya?
Klaim bahwa tanah itu diduduki Belanda Belanda yang didukung oleh Nairoa Raja Kangae dari masyarakat adat setempat (Soge Natarmage dan Goban Runut) bisa menjadi salah satu tafsiran yang dipertimbangkan.
Dalam perspektif ini dan dalam semangat UU No No. 5 thn 1960, dan kemudian KEPPRES No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak-hak baru atas tanah asal Konversi hak-hak Barat maka ruang klaim ini terbuka.
Proses hukum untuk memvalidasi klaim tentu bisa dilaksanakan, dengan catatan semuanya harus sesuai koridor hukum.
Itu berarti penyelesaian tanah konflik atas tanah 325 h tentu saja melewati prosedur yang tidak mudah hal mana membutuhkan kesabaran dalam berdialog.
Sementara itu klaim atas dasar parsial tentu akan semakin menjauhkan dialog dan membuka konflik yang tentu saja tidak kita inginkan.
Mencari Titik Temu
Bagaimana bisa menyikapi konflik ini agar tidak menjadi berkepanjangan? Pertanyaan ini tentu tidak mudah dijawab.
Tindakan pengosongan lahan dengan menggunakan ‘cara-cara kekerasan yang dianggap lazim digunakan oleh pemerintah dengan korban rakyat sederhana, (sayangnya) dianggap biasa. Saat seperti itu masyarakat dikorbankan.
Beruntung, gereja selalu berdiri di kaum yang menderita. Tetapi dalam kasus Nangahale, hal itu menjadi bak benang kusut yang semakin kusam. Lalu bagaimana mencari titk temunya?
Pertama, pengalihan Hak Guna Usaha yang sudah memiliki ‘sejarah’ dan telah berada di bawah sebuah entitas resmi hanya bisa diklaim dari entitas resmi.
Dalam arti ini, apa yang dilakukan PT DIAG ( Keuskupan Agung Ende) yang kemudian menjadi PT KRISRAMA (setelah Keuskupan Maumere berpisah dari KAE), merupakan hal yang tepat untuk mengelola tanah selama 25 tahun berikutnya.
Pada sisi lain, kepemilikan gereja tidak bisa serta merta dianggap sebagai milik penjajah karena terbukti, pascakemerdekaan, gereja masih ada, malah makin berkiprah terutama di Flores.
Dalam perspektif ini, klaim warga atas nama pribadi tidak akan memiliki kekuatan yang cukup.
Meski demikian pihak gereja misalnya perlu mengapresiasi itikad baik untuk mengadvokasi masyarakat dan tidak terjerumus untuk mengategorikan mereka sebagai aktor intelektual.
Sangat disayangkan bahwa dalam mengurai persoalan, kerap gereja (Keuskupan Maumere) kurang sabar dan bijak mengeluarkan pernyataan yang tidak membantu pencerahan malah sebaliknya.
Kedua, penyerobotan lahan milik PT KRISRAMA oleh masyarakat untuk jangka waktu agaka lama menandakan bahwa selama itu pula tanah tidak dikelola sesuai peruntukkannya.
Hal ini menjadi catatan kritis bahwa perkebunan Nangahale untuk satu periode yang lama, terkesan tertinggal. Hal itu berbeda ketika masih di bawah pengawasan para bruder SVD yang memiliki dedikasi.
Sayangnya perhatian yang menjadi contoh itu hanya terjadi di Perkebunan Pati Ahu miliki SVD yang terawat sementara hal itu masih sangat jauh dari Nangahale.
Ini menjadi catatan sekaligus kritik tentang efisiensi penggunaan lahan. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Nangahale tetapi di banyak tempat.
Keuskupan mengklain sesuai sejarah sebagai ‘pemilik’, tetapi tidak terlihat konsistensi dalam penggunaan lahan. Perkebunan Hokeng bisa diambil menjadi contoh lain.
Ketiga. pengosongan lahan seperti yang dilakukan pada 22 Januari 2025 dengan menggunakan alat berat logikanya dilakukan oleh aparat hukum sebagai perintah pengadilan.
Hal itu mengandaikan adanya proses hukum resmi yang sudah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melewati langkah-langkah hukum.
Bila proses itu telah dilalui maka perintah pengosongan merupakan amanat yang mesti dilalui. Di sini gereja tampil elok.
Bukan ‘ia’ yang berada di depan atau bersama kerumuman menyerunduk rumah warga tetapi ia ‘duduk manis’ sementara aparat hukum yang melakukannya setelah semua pertimbangan dilalui.
Atas dasar pemahaman ini, maka pengosongan atas klaim menjadi pemilik sah merupakan tindakan yang tidak bisa diterima secara hukum.
Bahkan okupasi lahan yang berakibat pada molornya upaya pemanfaatan tanah bisa diproses secara hukum sehingga jangka waktu HGU itu bisa diperpanjang sesuai pertimbangan yang terjadi.
Karena itu klaim pihak PT KRISRAMA memberikan pembenaran diri sebagai ‘eksekutor’ adalah sebuah kekeliruan.
Mestinya keuskupan menjaga ‘image’ dengan berada di balik proses hukum dan bukan menjadi eksekutor pengosongan hal mana terjadi dan patut disayangkan.
Yang terakhir, kasus Nangahale sebenarnya hanya menunjukkan bahwa persoalan itu tidak ada di luar gereja tetapi ada di dalam gereja itu sendiri.
Singkatnya yang memerintah untuk mengosongkan adalah gereja (sebagai institusi), dan yang menderita juga anggota gereja itu sendiri. Di sinilah dilema.
Untuk menjawabi dilema ini tentu tidak mudah. Tetapi kisah ironis berikut bisa memberikan jejak untuk menilai.
Seorang sahabat pernah bercerita ia sangat terkesima dengan sebuah gambar di sebuah gereja di sebuah pulau terpencil.
Di dalam gereja itu terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan kedatangan para misionaris yang menumpani sebuah perahu. Jubah dan salib besar menandakan bahwa mereka akan datang membawa Kabar Gembira.
Di sisi lain, umat telihat menanti di pinggir pantai menunggu kedatangan para misionaris. Yang menarik dari gambar itu, ternyata Yesus berada di pantai bersama umat menunggu kehadiran para misionaris.
Lalu, di manakah Yesus berada dalam kasus Nangahale? Tidak mudah menjawabnya. Yang ada hanyalah dilema yang menyedihkan untuk dijawab. (*)















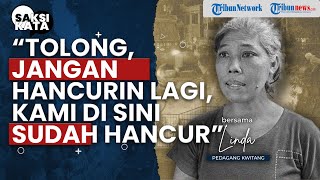




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.