Opini
Mendung Demokrasi
Konstitusi dengan mudah dikoyak untuk kepentingan sesat dan sesaat. Pilpres 2024 bukan tentang siapa presidennya.
Oleh: B Mario Yosryandi Sara
Aktivis HAM dan Pegiat Demokrasi
POS-KUPANG.COM - Setelah 25 tahun Reformasi 1998, Indonesia tampak masih belum berjarak jauh dari Orde Baru (Orba).
Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjelmah menjadi musuh bersama di masa Orba kelihatan malah semakin tumbuh subur pasca reformasi. Konstitusi dengan mudah dikoyak untuk kepentingan sesat dan sesaat. Pilpres 2024 bukan tentang siapa presidennya.
Ia bisa saja seorang prajurit militer, ia bisa juga seorang pengusaha, bisa dari habitus akademis, juga mungkin seorang yang memang memiliki pengalaman menjadi pemimpin pada skala yang lebih kecil dari sebuah negara.
Indonesia sebagai Negara-bangsa (baca; nation state), kita hanya bisa menerima untuk memilih Capres dari yang sudah dipilih koalisi antar Parpol.
Ambang batas 20 persen kursi di parlemen akhirnya menjebak kita, untuk sekadar memilih calon yang dipilihkan. Faktanya, tidak terdapat satupun partai politik yang bertanya terlebih dahulu kepada rakyat.
Tidak ada kesempatan rembug dengan rakyat, sehingga tak dapat dipastikan apakah rakyat setuju tentang calon presiden yang mereka usung. Namun itulah takdir kita sebagai rakyat.
Sebagaimana paradigma Budi Hardiman (2013) dalam bukunya yang berjudul “Dalam
Moncong Oligarki".
Ia menjabarkan harapan akan datangnya kepemimpinan yang kuat menjadi populer di Indonesia, khususnya di saat krisis, dan dalam demokrasi harapan itu akan tersalur sebagai pemberian suara kepada partai atau kandidat presiden yang dikira memenuhi harapan tersebut.
Bila demikian hal itu terjadi, Indonesia akan tetap berada dalam demokrasi, meski rezim yang bangkit dari demokrasi belum tentu melanjutkan demokratisasi.
Erosi Demokrasi
Isu regresi demokrasi sebetulnya telah menjadi perhatian para scholars dalam 10 tahun terakhir, lantas mengalami situasi yang mengkhawatirkan jelang Pemilu 2024. Terutama dalam aspek kemunduran dalam prosedur dan substansi kompetisi elektoral.
Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa hal, yaitu proses Pemilu yang sejak awal melekat dengan narasi kecurangan.
Contohnya, tahapan verifikasi partai politik serta fenomena penundukan lembaga penyelenggara Pemilu secara sukarela terhadap kekuatan politik di DPR, salah satu berkaitan dengan keterwakilan perempuan.
Selain itu fenomena juristocracy, yaitu pengalihan persoalan kebijakan legislasi ke pengadilan dan menantang masyarakat sipil melakukan aktivisme hukum.
Selanjutnya, ancaman erosi demokrasi oleh elit politik yang melakukan akumulasi kekuasaan sekaligus membajak demokrasi. Elit politik berjalan dalam gelombang populisme instrumental dan merekayasa persetujuan (baca; manufacturing consent) dengan narasi dia orang baik, dia adalah kita, dan lainya.
Jika berkaca dari teori psikologi politik, elit politik hari ini memenuhi karakteristik elit yang disebut ilmuwan politik Pareto (1968) sebagai elit dengan karakter rubah dan lion, yaitu elit inovatif, spekulatif, dan skeptis.
Berbeda dengan rezim sebelumnya, yang cenderung menekankan pada stabilitas dan keseimbangan. Namun tidak dengan elit politik hari ini, yang kian mengabaikan suara civil society. Fenomena tersebut lantas berkamuflase sebagai benalu demokrasi.
Terdapat pula autocratic legalism, yakni pembajakan mekanisme konstitusi untuk mendapatkan keuntungan dari dangkalnya demokrasi dan hukum. Sebagaimana hukum dijadikan alat penyelewengan instrumen kekuasaan.
Cara tersebut irasional dan kontradiktif dibandingkan penggunaan senjata, karena berdampak buruk bagi masyarakat luas.
Dalam koridor autocratic legalism tersebut, terdapat pelemahan empat institusi demokrasi di Indonesia, di antaranya KPK, DPR (fungsi pengawasan), masyarakat sipil (melalui aksi teror, intimidasi, dan doxxing), serta Mahkamah Konstitusi.
Erosi demokrasi tidak selalu bersumber dari elit politik. Ancaman demokrasi juga muncul dari masyarakat sipil. Dalam konteks politik akhir-akhir ini, suara kritis civic space, terkhusus di media sosial yang seringkali dibungkam oleh komunitas masyarakat sipil lainnya terutama buzzer.
Kondisi ini sangat ironi, dikarenakan masyarakat sipil selama ini diyakini sebagai agen utama demokratisasi, dan kritik terhadap kekuasaan tentu merupakan hal urgen demi terwujudnya demokrasi yang sehat.
Akan tetapi, disaat masyarakat sipil terkooptasi dan menjadi pendukung kekuasaan, hal tersebut secara perlahanakan mematikan kontrol publik. Fenomena ini menunjukan kepada kita jika demokrasi tidak pernah runtuh secara tiba-tiba, melainkan terjadi secara perlahan tanpa disadari.
Indeks Demokrasi
Berdasarkan laporan Global Freedom Score 2023 yang dirilis Freedom House, Indonesia menempati peringkat ke-58 secara global dan ke-9 di Asia Tenggara dalam daftar negara dengan indeks kebebasan dalam hak politik dan kebebasan sipil.
Kebebasan yang dimaksud didasarkan pada premis bahwa standar tersebut berlaku untuk semua negara dan wilayah, terlepas dari lokasi geografis, komposisi etnis atau agama, atau tingkat perkembangan ekonominya.
Jika kita berkaca pada data yang dirilis Economist Intellegence Unit (EIU), Indonesia mendapat skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022, dengan range indeks 0-10. Standar EIU mencakup lima kategori yakni, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, pemerintahan, partsisipasi politik, dan budaya politik.
Meski demikian, skor dari EIU masih stagnan atau tidak mengalami perubahan siginifikan dengan indeks demokrasi 2021. Sebab demokrasi Indonesia telah terkontaminasi demokrasi cacat (flawed democracy), hal ini dimaksudkan karena peringkat Indonesia pada level global menurun.
Semula 52 menjadi 54 dari total 167 negara. Kita terpaut jauh dengan peringkat pertama Norwegia (skor 9,81), diikuti Selandia Baru dengan skor 9,61, dan Islandia skor 9,52.
Sedangkan laporan V-Dem Institute dalam Democracy Report 2023 dijelaskan, sebanyak 43 persen jumlah populasi dunia saat ini hidup di negara-negara yang sedang mengalami kemunduran demokrasi.
Bahkan tingkat demokrasi secara global pada 2022 terdegradasi ke level yang sama dengan demokrasi pada 1986.
Situasi itu ditandai antara lain, represivitas pemerintah terhadap civil society, kebebasan berekspresi menurun, masifnya sensor terhadap media, dan memburuknya kualitas Pemilu.
Indonesia dalam 10 tahun terakhir, dari laporan yang sama, mengalami penurunan demokrasi bersama negara Asia Pasifik di antaranya India, Kamboja, Hongkong, Myanmar, Afghanistan, Bangladesh, Hongkong, Filipina, dan Thailand.
Mengutip Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Jakarta bertemakan “Jalan Asa Demokrasi di Negara Oligarki dapat disimpulkan ketiga rangkaian indeks demokrasi tersebut, selama dua periode Presiden Jokowi nyata membawa demokrasi mundur dalam era yang lebih culas ketimbang keterang-terangan rezim Orba.
Kemerdekaan berekspresi, berpikir, berpendapat, dan bermegosiasi terancam, dan ruang sipil menyempit.
Menjaga Asa Demokrasi
Demokrasi tak pernah terisolasi dari konteks dimana ia tumbuh. Demokrasi hanya dapat berfungsi jika terdapat keyakinan. Tidak perlu dijelaskan bahwa faktor tersebut bukan semata-mata kepercayaan atas dinamika bernegara, melainkan terhadap kekuasaan yang menjalankan fungsi demokrasi.
Dikarenakan demokrasi adalah pekerjaan bersama yang berlandaskan empati, rasa hormat, dan pengakuan, maka dibutuhkan tekad untuk bersatu.
Melalui “Iman Dalam Tantangan†Franz Magnis Suseno (2023) berpesan, dengan mendasarkan Indonesia pada Pancasila para founding fathers menyatakan tekad bahwa Indonesia hanya bisa bersatu apabila setia pada nilai-nilai kemanusiaan yang sejak ratusan tahun mereka hayati.
Di lain pihak bahwa mereka menghendaki suatu Indonesia yang menjadi negara bermartabat.
Oleh karena Indonesia adalah tempat dimana seluruh jiwa bangsa berada, maka siapa pun kita tentu memiliki obsesi untuk memberikan sumbangan terbaik bagi kelangsungan hidup bangsanya.
Obsesi yang didasari keyakinan demokrasi dijalankan dalam rangka bernegara, dan bernegara harus dijalankan dalam kerangka konstitusi.
Kita harus tegaskan, negara ini akan tegak untuk waktu yang panjang, sehari sebelum kiamat. Pelbagai rentetan peristiwa politik selama setahun belakangan, seyogianya menjadi bahan refleksi dan proyeksi demi Indonesia yang lebih baik.
Penting dikatakan potret suram di atas tidak mencerminkan seluruh realitas politis Indonesia, melainkan paling banyak hanya separuhnya, karena semenjak tumbangnya orde baru, masyarakat Indonesia tumbuh sebagai kekuatan yang memberi harapan akan Indonesia yang lebih baik. Dan api itulah yang harus dikuatkan, diperbesar dan dikobarkan. (*)




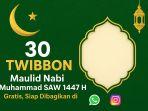









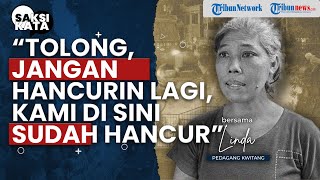




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.