Opini
Opini Paul Ama Tukan: Buzzer Politik dan Ruang Publik yang Bising
Buzzer yang dipahami adalah mereka yang menciptakan keributan/kebisingan dalam medsos. Dalam konteks politik dinamakan Buzzer politik.
POS-KUPANG.COM - Suksesi politik elektoral 2024 mendatang sudah dimulai. Belajar dari penelitian Murwani dan Elmada pada perhelatan Pemilu 2019, gerakan politik virtual tidak bisa dianggap sepele dan biasa.
Pasalnya, demokrasi berbasis digital menguasai panggung politik; transparansi dibangun tetapi serangan siber dengan dalih politik identitas sulit diibendung.
Saat itu (2019), dewan Pers mencatat terdapat 43.000 situs online yang ada di Indonesia. Namun, ironisnya hanya 300 situs yang terdaftar secara resmi.
Murwani dan Elmada (2019) menemukan bahwa sebagian situs online yang tidak terverifikasi pada dewan pers tersebut dikelola oleh para buzzer politik (Shidiq Sugiono, 2020:59). Penemuan yang sama pun terverifikasi dalam kontestasi politik bangsa pasca pemilu.
Baca juga: Opini Yohanes Bura Luli: Menjaga Marwah Politik Pemilu
Buzzer Politik, Apa itu?
Secara etimologis, kata Buzzer berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti bel, lonceng atau alarm.
Istilah ini secara harfiah berkonotasi positif yaitu penanda atau pengingat untuk melakukan kegiatan tertentu dengan maksud menarik perhatian massa.
Sedangkan secara praksis, kata Buzzer merujuk pada aktivitas pemasaran (marketing) yaitu orang yang mempromosikan produk perusahan tertentu di dalam media sosial untuk menggaet pembeli/pelanggan.
Namun, akibat penetrasi medsos dewasa ini, kata Buzzer kemudian mengalami pergeseran makna.
Seturut kamus Oxford, Buzzer diartikan sebagai “an electrical devices that makes a busing noise and is use for signalling”, sebuah perangkat elektronik yang membuat kebisingan untuk memberi tanda/sinyal.
Pengertian ini dijelaskan sebagaimana kata Buzzer itu dipakai untuk merujuk pada aktivitas membuat kebisingan (penggaung).
Diketahui dari defenisi Oxford ini, arti kata Buzzer berubah seturut adanya perkembangan media baru seperti Twitter yang didirikan pada 21 Maret 2006 oleh Jack Dersey, dkk.
Baca juga: Opini - Peran Elite Mematangkan Demokrasi
Buzzer yang dipahami sekarang adalah mereka yang menciptakan keributan/kebisingan dalam medsos. Dalam konteks politik dinamakan Buzzer politik (penggaung politik).
Di Indonesia, keterlibatan Buzzer mulai diketahui sejak tahun 2006 saat platform media sosial Twitter digunakan. Dalam dunia politik, Buzzer mulai ramai dibicarakan pada tahun 2012 saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.
Para Buzzer bermunculan bersamaan dengan relawan politik yang bekerja untuk kandidat yang didukungnya. Baru pada momen Pilplres 2014, Buzzer mulai digunakan secara luas untuk kepentingan politik (Rieka Mustika, 2020).
Dalam menjalankan aksi buzz politik, para Buzzer biasanya terbagi menjadi tiga kelompok (Juditha:2019). Pertama, Person in Charge dan PIC Support.
Bagian ini bertugas untuk merancang gerakan dan sasaran, mengatur strategi dan mengukur efektivitas pesan.
Kelompok kedua disebut Content Writer yaitu mereka yang menyusun narasi-narasi untuk disebarkan di forum-forum medsos.
Dan kelompok ketiga adalah admin yaitu mereka yang bertugas mengendalikan dan memantau semua strategi serta mempertajam isu-isu yang telah diposting ke ruang publik medsos.
Cara-cara lain yang akhir-akhir ini kerap dilakukan para buzzer ialah melalui link shering, virtual community untuk menciptakan trending topic seorang figur politik atau pasangan calon pemimpin dalam momen menjelang pemilihan elektoral.
Baca juga: Opini Silvester Sili Teka: Mengawasi “Ruang Hampa” Digitalisasi Pemilu
Belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 yang juga dikenal sebagai perhelatan demokrasi paling dramatis, isu agama berhasil dimainkan oleh para Buzzer untuk menurunkan reputasi pasangan Basuki Thajaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful.
Narasi tentang mayoritas-minoritas berhasil menjerat Ahok ke pengadilan dan berujung ke penjara.
Peran para Buzzer saat itu menjadi faktor kunci mengapa fragmentasi sosial di tengah masyarakat begitu kuat sehingga melumpuhkan reputasi Ahok secara drastis.
Para Buzzer, melalui gerakan secara virtual menyodorkan isu-isu agama untuk memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Di sini, para Buzzer politik diketahui menjalankan paling kurang tiga strategi komunikasi. Pertama, menyebarkan disinformasi secara massif sebagai serangan terhadap akuntabilitas media-media konvensional.
Tujuan utama penyebaran disinformasi ini ialah menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat agar fakta-fakta lapangan yang berhasil mempromosikan reputasi figur atau partai politik dapat secepatnya tereliminasi dari perhatian publik.
Kedua, amplifikasi pesan. Para Buzzer berusaha mengamplifikasi pesan sebanyak mungkin agar terbaca oleh algoritma internet.
Akibatnya, pesan-pesan akan terus booming dan trending dalam medsos sehingga narasi-narasi yang dilontarkan Buzzer politik selalu menempati urutan teratas pada halaman medsos.
Baca juga: Opini Yohanes Mau: Memonitoring Politisi Menjaring Pemimpin Berkualitas
Ketiga, strategi komunikasi dengan membangun percakapan pro-kontra melalui akun-akun bayangan. Strategi komunikasi ini dibuat seolah-olah dialektis dengan melontarkan narasi-narasi problematis dan bombastis. Tujuannya membuat publik penasaran.
Para Buzzer membuat banyak akun dengan maksud agar informasi yang diposting itu juga terkesan seolah-olah menuai beragam tanggapan dengan mengonfrontasi argumentasi-argumentasi yang paling mungkin masuk akal.
Pada akhirnya, para Buzzer sendiri yang membuat klaim-klaim atas informasi itu. Pada titik paling ekstrem, strategi politik dengan cara ini dapat berakibat pembeberan ranah privat lawan politik dan dengan demikian mencederai karakter individu, etnis dan golongan tertentu.
Buzzer Politik dan Komodifikasi Informasi
Pada Pilpres 2014 misalnya, figur Jokowi yang sederhana dan populis dijadikan komoditas para Buzzer untuk dipasarkan kepada publik.
Buzzer politik menjual kesahajaan individual Jokowi padahal kesahajaan individual itu sama sekali tidak bersentuhan dengan integritas dan komitmen untuk menyelamatkan ruang publik dari caplokan para oligark yang juga kerap berwajah sahaja.
Baca juga: Opini Albertus Muda, S.Ag: Revolusi Diri Wakil Rakyat
Adanya komodifikasi informasi oleh Buzzer politik terbukti mencederai demokrasi. Dengan menjalankan propaganda politik secara masif, ruang publik demokrasi sudah tercemar oleh persaingan yang tidak fair.
Persaingan ini mencerminkan bahwa nafsu politis tidak didasarkan pada bobot argumentasi rasional tetapi justru pada sentimentalitas sektarian yang berbasis modal.
Fenomena menguatnya Buzzer politik juga menjadi ketakutan sebagaimana perspektif Manuel Castels yakni ketakutan akan lenyapnya ruang publik yang dianggap telah bertransformasi ke dalam ruang siber (cyberspace).
Alasannya ialah kekuatan-kekuatan modal akan menjadi pelopor semua gerakan politik untuk mendistorsi dan menekan ruang publik.
Buzzer Politik dan Propaganda Politik
Perlu dicermati bahwa propaganda politik yang dilakukan Buzzer politik tidak hanya sebagai gerakan antitesis terhadap kekuasaan (baca: pemerintah).
Buzzer politik juga dapat merupakan gerakan yang dibiayai kekuasaan sebagai pihak yang seharusnya menentukan juntrung demokrasi.
Dalam penelitiannya tentang industri Buzzer politik di Indonesia, Shiddiq Sugiono menemukan bahwa pemerintah Indonesia pada tahun 2020 telah terindikasi membiayai para Buzzer politik untuk meredam gerakan oposisi.
Baca juga: Opini Dony Kleden: Sesat Pikir Politik Pendidikan di NTT
Padahal, gerakan oposisi sangat menentukan keberlangsungan demokrasi yang sehat karena melaluinya kebijakan-kebijakan dapat dipertimbangkan secara argumentative dan fair.
Penelitian Sugiono juga membuktikan bahwa efektivitas UU ITE yang mengatur transaksi informasi elektronik hanya menyasar pada oposan. Dengan kata lain, UU ITE hanya merupakan tameng untuk menutup resistensi pemerintah atas kontrol oposan.
Pada titik ini, Buzzer politik di Indonesia tidak hanya membajak demokrasi dari posisi eksternal tetapi juga lebih-lebih dari posisi internal kekuasaan. Buzzer politik adalah kaum “sofis” virtual yang menjalankan propaganda fiktif dan tentu mencaplok ruang demokrasi secara tragis.
Literasi Digital Dan Penguatan UU ITE
Di tengah gempuran kecepatan informasi yang kerap digunakan Buzzer untuk melancarkan propaganda, literasi digital diupayakan pertama-tama dengan cara menangguhkan setiap informasi yang diperoleh dan mengedepankan sikap check and recheck sumber informasi bersangkutan.
Identitas informan mesti dicermati agar sekurang-kurangnya memberi keyakinan sementara terhadap sumber sebuah informasi.
Kedua, dalam media digital, literasi diupayakan dengan kegiatan membaca sambil membandingkan. Dalam ruang siber, informasi-informasi bersileweran.
Literasi digital dilakukan dengan upaya komparasi terhadap satu informasi dengan informasi lain atau sumber lain.
Dengan kemudahan akses internet, setiap orang sebenarnya mesti membandingkan sumber-sumber informasi secara teliti. Media Massa mainstream berbasis digital adalah salah satu referensi yang bisa diandalakan dalam upaya komparasi informasi ini.
Baca juga: Opini Ovan Baylon: Hacker dan Kolonialisasi Digital
Ketiga, literasi digital diupayakan dengan meminimalisasi upaya digitalisasi semua segi kehidupan. Upaya ini memang agak kontradiktif tetapi merupakan sebuah cara untuk melihat dampak-dampak digitalisasi itu sendiri. Penetrasi Media Sosial adalah sebuah indikator bahwa semua segi kehidupan cenderung didigitalisasi.
Tawaran terakhir ialah penguatan UU ITE secara lebih egaliter dalam kehidupan berwarga negara. Penguatan ini mesti pertama-tama diupayakan oleh para penegak hukum; polisi, hakim dan jaksa.
Di Indonesia, hukum cenderung tumpul ke arah penguasa karena lemahnya komitmen para penegak hukum. Buzzer politik kerap menjadi suruhan para penguasa untuk membungkam oposisi.
Karena itu, penegak hukum mesti terbebas dari kepentingan apapun untuk menegakkan keadilan sebagaimana amanat undang-undang.
Menjelang Pemilu, ruang publik tak terkecuali ruang digital-virtual sedang “bising” oleh promosi figur dan parpol. Masyarakat mesti memiliki literasi digital dan politik yang memadai untuk tidak mudah terjebak dalam provokasi berbasis sara, etnis dan agama.
“Kebisingan” ruang publik penting dalam konteks menghidupkan dialektika epistemis tetapi tidak dalam konteks meniupkan sentimentalitas tanpa fakta.
Ruang publik jelang Pemilu mesti berbasis pada sikap egaliter dan nilai-nlai etis yang sejak awal menyatukan dan merawat Indonesia yang jamak ini. (Penulis adalah Anggota KMK dan Diskusi Filsafat Ledalero)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
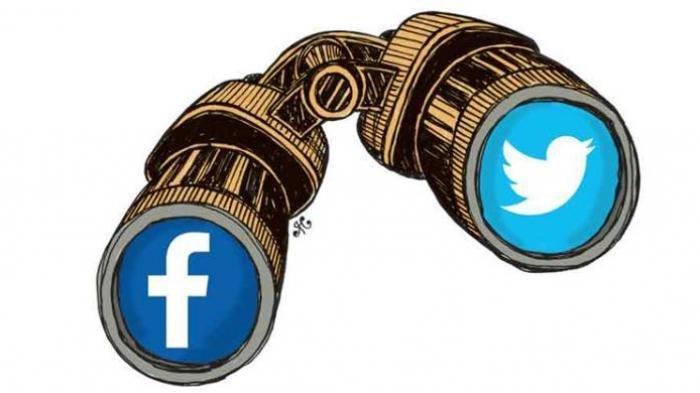












![[FULL] Gaya Blak-blakan Purbaya Lemahkan Pemerintah? Pakar: Hasan Nasbi Nggak Berhak Ikut Campur](https://img.youtube.com/vi/wD_dIYbA7Q0/mqdefault.jpg)




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.