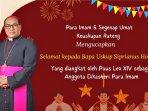BPK: Antara Suap dan Penodaan Integritas
Nilai integritas dan kredibilitas sebagai lembaga terhormat dan anti korupsi kini justru meninggalkan luka batin di
Oleh: Yandris Tolan
Tinggal di Desa Narasaosina, Adonara Timur
POS KUPANG.COM - Ibarat hujan sehari menghapus kemarau setahun. Itulah ungkapan yang sepatutnya dialamatkan kepada kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini. Segala usaha dan perjuangan hanya sia-sia dikenang rakyat kebanyakan.
Nilai integritas dan kredibilitas sebagai lembaga terhormat dan anti korupsi kini justru meninggalkan luka batin di benak publik. Serentak euforia publik dari Sabang hingga Merauke lantas bertanya, quo vadis Indonesia?
Kesejahteraan dan keadilan sosial yang menjadi harapan utama seluruh rakyat sedang dinodai suatu lakon korupsi yang dramatis. Sangat miris memang bila dibicarakan lebih komprehensif.
Baca: Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri Resmi Jadi Tersangka yang Ditangkap KPK
Sebab ruang kritik yang tercipta di kalangan masyarakat luas adalah konsep irasionalitas dan nihilnya nilai etis-moral yang sejatinya menjadi dasar nurani untuk membendung segala bentuk ketamakan yang melekat dalam diri para anggota BPK serta jaringan lainnya.
Indonesia dalam beberapa pekan terakhir disibukkan dengan berbagai persoalan. Di balik suhu sosio-politis yang bertendensi memecah-belah, lagi dan lagi kita harus kembali berurusan dengan fenomena "suap" yang merupakan bias dari korupsi.
Berbagai media melansir berita yang meninggalkan nada kausalitas serta menyekap daya imajinasi publik ke arah tafsiran retoris. Suatu tanda tanya yang sejatinya tak harus dibicarakan sebab BPK menjadi role model serta pemeran utama dalam usaha menjaga stabilitas dan kredibilitas kelembagaan publik lainnya.
Baca: Auditor BPK yang Ditangkap KPK Belum Lapor LHKPN Sejak 2014
Pada ranah ini, BPK dan fakta suap hadir sebagai skandal yang mencederai dan menodai integritas kelembagaan di benak publik. Berhubungan dengan fakta suap yang melibatkan BPK, saya ingin mengajak pembaca untuk mendalami lebih jauh tentang esensi dan substansi suap sebagai bias dari tindakan korupsi.
Antusiasme publik menyoal fenomena suap yang melibatkan BPK dalam beberapa hari belakangan mengingatkan saya tentang suatu opini yang ditulis Herry Priyono, dosen dan Ketua Program Studi Magister Filssafat pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Dalam ulasannya, beliau coba mendeskripsikan bagaimana kronologi sejarah kelam tentang suap yang pernah terjadi di Amerika Serikat puluhan tahun silam.
Baca: Diduga Ada Kaitan dengan Ahok, Pejabat BPK yang Kena OTT KPK Punya Jejak Mengejutkan
Sebelum tahun 1977, tidak ada undang-undang yang melegalkan apakah suap yang dilakukan perusahan Amerika Serikat (AS) kepada para pejabat negara-negara lain untuk memenangi kontrak bisnis merupakan korupsi. Dikisahkan bahwa sampai pertengahan tahun 1977 "terungkap sedikitnya 400 perusahan AS menyuap para pejabat pemerintah lain dengan jutaan dollar untuk memenangi kontrk bisnis di luar negeri.
Matarantai skandal yang bermula dari kisah Watergate (17 Juni 1972) sampai praktik suap yang luas tersebut telah memicu penetapan undang-undang antikorupsi yang disebut Foreign Corrupt Practices Act, yang kemudian ditandatangani Presiden Jimmy Carter, 19 Desember 1977.
Sejak saat itu, segala bentuk suap yang dilakoni perusahan AS kepada para pejabat, perantara, dan pelaku bisnis untuk tujuan apa pun dikategorikan sebagai korupsi (baca: Herry Priyono, Menggeledah Korupsi, dalam Tuhan, Manusia, dan Kebenaran, F.Budi Hardiman (edt), 2016: p.201).
Bertitik tolak dari sejarah kelam di atas, kita bisa menyimpulkan peran dan esensi hukum yang diberlakukan dalam berbagai ranah kehidupan bisa mengubah definisi tentang suatu aksi yang awalnya bukan korupsi menjadi korupsi. Meminjam pemikiran John T.Noonan Jr, padahal sudah cukup pasti bahwa suap (bribe) merupakan model paradigmatik korupsi dan dipandang sebagai kejahatan besar, bahkan sejak ribuan tahun (Herry Priyono, ibid.p.202).
Hemat saya, model paradigmatik sebagaimana diutarakan John Noonan mengindikasikan kerangka berpikir dalam menjustifikasi esensi serta makna substantif dari suap yang merupakan juga bagian dari korupsi. Fakta suap yang melibatkan pihak BPK dan beberapa anggota Kementerian Desa turut menstimulasi aspek rasionalitas publik untuk berpikir kritis menggugat fenomena korupsi.
Sejarah seperti diutarakan di atas adalah satu dari sekian juta kasus suap di dunia yang belum termediasi ke ranah hukum. Dari dan melalui sejarah, saya mengajak pembaca untuk menilai kembali pengertian substantif dari korupsi.
Memahami Esensi Korupsi
Secara etimologis, kata korupsi berasal dari kata bahasa Latin, corruptio (tindakan atau kondisi busuk, rusak dan merosot), kata kerja corrumpere (merusak, membusukan, mencemarkan), sementara corruptor artinya perusak, pemerdaya, penyuap (baca: Kamus Latin-Indonesia disusun oleh K. Prent; dkk, 1969: p.200).
Dari pengertian etimologis kita secara sederhana mengartikan bahwa merusak atau kerusakan adalah deskripsi tentang fenomena kehancuran secara fisik (bentuk dan keutuhan). Gambaran aspek sosial tercermin dalam fenomen kerusakan dari kemurnian hakiki. Sementara secara moral bisa mengindikasikan suatu bingkai kehancuran soal integritas dan tatanan. Di sinilah, penodaan integritas atas suatu lembaga bisa terjadi.
Penodaan integritas persis terjadi ketika BPK yang dipandang santun sebagai lembaga terhormat terlibat dalam pelbagai aksi yang bertentangan dengan nilai moral. Penodaan integrtas kelembagaan terjadi karena BPK menjadi pelaku protagonis di balik aksi suap. BPK seolah-olah mereduksi esensi korupsi yang menjunjung tinggi nilai moral label atau kalim etis-normatif sekaligus. BPK seakan melegalkan tindakan yang seharusnya tidak terjadi secara moral.
Hal ini mengindikasikan bahwa lakon dramatis berupa suap yang melibatkan BPK tak jauh berbeda dengan kisah puluhan tahun silam sebagaimana dialami Amerika Serikat. Di satu sisi, kepekaan sosial yang ditunjukan BPK dalam menerima suap untuk memenuhi aspirasi Kemendes berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian secara moral tak dibenarkan. Di sisi yang lain, tindakan BPK telah melanggar hukum.
Dari peristiwa ini, kemudian muncul banyak pertanyaan guna mempersoalkan tentang fenomena korupsi. Ada pihak yang bertanya begini, mengapa orang yang melakukan pencopetan uang tidak dikategorikan sebagai koruptor? Sementara ada pejabat negara yang menggelapkan dana diklasifikasikan sebagai aksi korupsi?
Sembari menyimak pertanyaan di atas, saya berpikir bahwa pertama-tama kita penting membedakan tentang aksi koruspi yang lebih melibatkan integritas personal dengan korupsi yang melibatkan integritas secara kelembagaan tertentu. Berpijak pada esensi pertanyaan publik ini, saya bisa menilai keterlibatan BPK menerima suap adalah aksi korupsi yang menodai integritas kelembagaan.
Sebab BPK secara struktural kelembagaan memiliki badan hukum dan karenanya segala aksi yang bertentendsi korup dinilai imoral. Berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan BPK saya menganjurkan agar negara tetap konsisten pada tata kelola hukum positif untuk menghukum secara bijak semua pelaku apabila terbukti bersalah. *