Opini
Opini: Ketika Komodo Disandera Kapital
Beginilah kisah Ketika Komodo bukan sekadar satwa purba, melainkan sandera dalam drama kapitalisme pariwisata.
Oleh: Aprianus Paskalius Taboen, S.Pd., M.Si
Dosen Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
POS-KUPANG.COM - Ada pepatah bilang, “Di mana ada gula, di situ ada semut.” Tapi di Taman Nasional Komodo, pepatahnya bisa jadi, “Di mana ada komodo, di situ ada investor.”
Ironisnya, yang datang bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk “menggigit” ruang hidup masyarakat adat.
Beginilah kisah Ketika Komodo bukan sekadar satwa purba, melainkan sandera dalam drama kapitalisme pariwisata.
Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar destinasi wisata kelas dunia.
Baca juga: Masyarakat Menggarai Barat Minta PT KWE Keluar dari Taman Nasional Komodo
Ia adalah rumah bagi satwa purba Varanus komodoensis yang hanya dapat ditemukan di wilayah ini, sekaligus ruang hidup masyarakat adat yang telah berabadabad berinteraksi dengan ekosistem sekitarnya.
Kontroversi mencuat ketika PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE) mendapatkan mendapatkan izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA) seluas 274,13 hektare di Pulau Padar melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.796/Menhut-II/2014.
Walaupun pihak perusahaan dan pemerintah menyebut pembangunan hanya akan memanfaatkan sekitar 15,375 hektare (5,64 persen dari total izin), gelombang penolakan publik tetap deras.
Dari perspektif sosiologi, kasus ini memperlihatkan ketegangan klasik antara logika kapitalisme pariwisata dengan nilai ekologis dan
hak masyarakat adat.
Relasi Kuasa dalam Ruang Konservasi
Dalam kacamata sosiologi lingkungan, konflik yang muncul di TNK bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga perebutan makna dan otoritas atas ruang konservasi.
Negara, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memegang legitimasi hukum untuk memberi izin investasi.
Di sisi lain, masyarakat adat atau komunitas lokal Labuan Bajo merasa sebagai pewaris kultural yang sah atas wilayah tersebut.
Ketika izin keluar tanpa keterlibatan penuh masyarakat, yang tampak adalah reproduksi ketidakadilan struktural yakni keputusan politikekonomi lebih berpihak pada kepentingan modal ketimbang partisipasi warga.
Sosiolog Anthony Giddens menyebut fenomena ini sebagai disembedding, yaitu keterputusan antara kebijakan formal dengan praktik sosial masyarakat sehari-hari.
Pulau Padar, bagi masyarakat adat, bukan sekadar ruang kosong untuk dikelola secara ekonomis, melainkan lanskap simbolik yang mengandung sejarah, nilai, dan spiritualitas.
Maka, masuknya PT KWE tanpa persetujuan kolektif dianggap sebagai bentuk perampasan ruang hidup (land grabbing) dalam format yang dilegitimasi oleh hukum negara.
Dilema Pariwisata dan Konservasi
Pemerintah berdalih bahwa pembangunan resort dan sarana wisata akan meningkatkan daya tarik TNK sekaligus menjaga kualitas konservasi.
Namun, pengalaman global menunjukkan bahwa intensifikasi pariwisata di kawasan konservasi sering berujung pada degradasi lingkungaan.
World Heritage Centre (WHC) dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) bahkan menetapkan standar ketat agar investasi tidak menggerus Outstanding Universal Value (OUV) TNK sebagai situs warisan dunia UNESCO.
Ironisnya, prinsip pariwisata berkelanjutan justru menekankan keseimbangan antara tiga dimensi yaitu lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi.
Di TNK, dimensi sosial-budaya tampak paling terabaikan. Penolakan dari DPRD Manggarai Barat, Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD), hingga akademisi lokal memperlihatkan bahwa proyek PT KWE cenderung dipersepsi sebagai “enklaf eksklusif” untuk wisatawan berdaya beli tinggi, alih-alih pariwisata inklusif yang berpihak pada masyarakat.
Jika ini dibiarkan, maka TNK berpotensi menjadi contoh green grabbing yakni praktik yang mengatasnamakan konservasi untuk membuka jalan bagi privatisasi ruang publik.
Hak Adat dalam Bayang-Bayang Kapitalisme Pariwisata
Konflik PT KWE menyingkap sebuah persoalan mendasar mengenai marginalisasi hak adat.
Masyarakat adat di Pulau Padar dan Labuan Bajo sudah berulang kali menyuarakan keberatan atas proyek ini. Mereka menilai bahwa keputusan izin PT KWE tidak melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
Padahal, prinsip ini diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).
Dalam praktiknya, kapitalisme pariwisata seringkali menjadikan masyarakat adat sekadar “ornamen budaya” untuk konsumsi wisata, bukan subjek utama pembangunan.
Sosiolog Pierre Bourdieu akan menyebut kondisi ini sebagai bentuk dominasi simbolik yakni masyarakat lokal diposisikan inferior di hadapan kekuatan modal, sehingga nilai budaya mereka tereduksi menjadi
komoditas.
Bila hak adat terus diabaikan, maka konflik horizontal hingga resistensi sosial berpotensi meningkat, mengancam stabilitas pariwisata itu sendiri.
Jalan Tengah, Pariwisata Berkelanjutan yang Berkeadilan
Opini publik yang menuntut pencabutan izin PT KWE sesungguhnya adalah refleksi keinginan masyarakat agar pariwisata di TNK berjalan sesuai prinsip berkelanjutan. Prinsip ini setidaknya mencakup tiga hal.
Pertama, pelestarian ekologi. TNK adalah habitat komodo dan ribuan spesies lain.
Pembangunan yang mengubah bentang alam, meski kecil skalanya, dapat memicu fragmentasi habitat, menurunkan kualitas ekosistem, serta meningkatkan tekanan terhadap satwa liar.
Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan dan dapat diakses publik, bukan hanya sekadar dokumen formal.
Kedua, keadilan sosial budaya. Masyarakat adat harus diposisikan sebagai mitra utama, bukan obyek.
Implementasi FPIC wajib dilakukan secara nyata, dengan memastikan masyarakat memahami risiko dan manfaat investasi.
Selain itu, model pariwisata berbasis komunitas (communitybased tourism) dapat menjadi alternatif yang lebih adil, di mana masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan, mendapatkan manfaat ekonomi, sekaligus menjaga kearifan lokal.
Ketiga, keberlanjutan ekonomi. Investasi memang penting, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi lokal, bukan hanya menyedot keuntungan keluar daerah.
Diversifikasi usaha wisata (seperti ekowisata berbasis desa, homestay, atau wisata budaya) bisa menjadi cara menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.
Belajar dari Kontroversi TNK
Kasus PT KWE di Taman Nasional Komodo adalah cermin dari dilema pembangunan di era pariwisata global.
Negara sering terjebak pada logika investasi besar sebagai jalan pintas meningkatkan devisa, sementara aspek ekologi dan hak masyarakat adat dipandang sekunder.
Padahal, kekuatan utama TNK justru terletak pada kelestarian alam dan keunikan budaya masyarakatnya.
Mengorbankan dua hal tersebut sama saja dengan meniadakan fondasi pariwisata itu sendiri.
Sosiologi mengingatkan kita bahwa konflik bukanlah sekadar gangguan, melainkan sinyal adanya ketidakadilan dalam struktur sosial.
Penolakan masyarakat atas PT KWE adalah peringatan bahwa pembangunan tanpa partisipasi sejati berisiko gagal secara sosial.
Jika pemerintah sungguh ingin menjadikan TNK sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, maka langkah pertama adalah memastikan pembangunan selaras dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, menjaga ekologi, menghormati budaya, dan memberdayakan masyarakat lokal.
Hanya dengan cara itu, pariwisata tidak menjadi mesin eksklusi, tetapi jembatan menuju keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
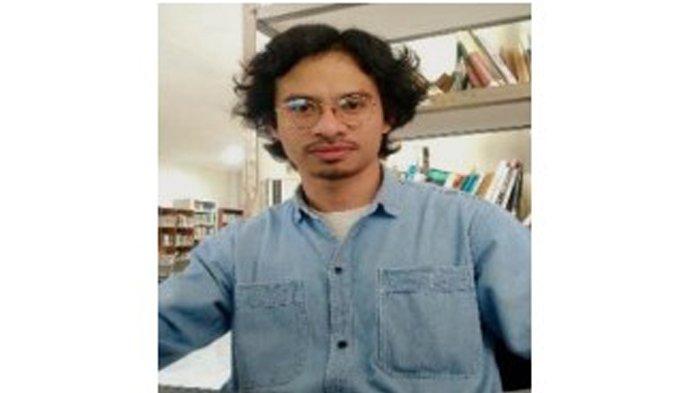














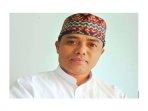




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.