Opini
Opini: Populisme Otoritarian Prabowo
Seperti sedang bermimpi, saya menyaksikannya seolah Prabowo sedang berkampanye dalam perhelatan pilpres.
Oleh: Ferdinandus Jehalut
Direktur Ranaka Institute dan Dosen Komunikasi Politik FISIP Undana Kupang - Nusa Tenggara Timur.
POS-KUPANG.COM - Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025) terkesan teatrikal.
Ia menunjukkan gaya khas populisme: menggebrak meja, mengecam “serakahnomic”, dan mengglorifikasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para anggota dewan merespons dengan tepuk tangan panjang dan tiga kali standing applause.
Ini situasi langka di gedung parlemen yang seolah memberi sinyal sudah digembosnya oposisi.
Semua narasi Prabowo Subianto terdengar merakyat. Retorikanya juga memikat.
Seperti sedang bermimpi, saya menyaksikannya seolah Prabowo sedang berkampanye dalam perhelatan pilpres.
Padahal saatnya rakyat butuh realisasi, bukan kampanye atau janji terus-menerus.
Kampanye permanen
Dalam komunikasi politik, hal semacam ini memang lumrah. Seorang pejabat publik yang terpilih melalui official elections biasanya secara konsisten menanamkan citra positif di benak konstituen melalui strategi permanent campaign.
Kampanye permanen adalah strategi kampanye politik yang tidak berhenti saat pemilu usai.
Pemerintah terus berkampanye sepanjang masa jabatan melalui komunikasi intens, survei opini, dan pencitraan publik (Kaid, 2004).
Strategi ini menurut Kaid punya keuntungan: menjaga kedekatan dengan masyarakat, membuat pemerintah lebih tanggap, dan menjaga pesan politik tetap konsisten.
Tujuannya ialah memenangkan hati dan pikiran warga setiap saat. Meskipun demikian, kampanye permanen sering fokus pada popularitas instan, mempolitisasi isu publik berlebihan, dan menggerus kualitas demokrasi karena ruang diskusi digantikan oleh retorika tanpa henti.
Kampanye permanen memberi lahan subur bagi populisme, karena retorika kerakyatan bisa terus direproduksi tanpa jeda demi mengokohkan legitimasi politik. Populisme seperti inilah yang kini ramai diperdebatkan.
Carlo Berti et al. (2024) menyebut populisme sebagai “penanda kosong”, istilah yang bisa dipakai siapa saja untuk menstigma lawan atau membungkus legitimasi diri.
Di Eropa, kata ini kerap bernuansa negatif, dilekatkan pada tokoh sayap kanan.
Di Indonesia, ia menemukan wajah khasnya dalam politik Prabowo (dan Jokowi).
Sejak 2014, Prabowo membangun citra diri sebagai “juru selamat bangsa”.
Retorikanya sederhana: bangsa ini dikhianati elit korup, rakyat harus diselamatkan, dan dirinya adalah prajurit setia.
Politik lalu dipersempit menjadi pertarungan moral antara rakyat sejati dan elit pengkhianat. Inilah pola klasik populisme (Meijers & Zaslove, 2020).
Namun, populisme Prabowo tidak berhenti pada retorika kerakyatan. Ia sarat dengan karakter otoritarian yang oleh Alberto Alonso-Fradejas (2021) disebut sebagai populisme korporat otoritarian.
Kekhasannya terletak pada retorika yang merakyat sambil membangun aliansi dengan elit negara dan korporasi besar.
Di Guatemala, populisme semacam ini membungkus ekspansi perkebunan dengan narasi pembangunan berkelanjutan.
Di Indonesia, janji kedaulatan pangan dan energi hijau dibungkus serupa, sementara jejaring oligarki bisnis menopang kekuasaan.
Gaya komunikasi Prabowo juga khas. Ia dekat dengan apa yang disebut Erik Bucy dkk. (2020) sebagai “populisme performatif”.
Dalam kampanye maupun pidato resmi, ia kerap melanggar norma kesopanan.
Humor kasar, gestur teatrikal, bahkan gebrakan meja dipakai untuk mencuri perhatian. Problemnya, publik menafsirkannya sebagai keaslian dan ketegasan, bukan kelemahan.
Namun, Paul Blokker (2023) mengingatkan bahwa populisme punya dua wajah: emansipatoris sekaligus otoritarian.
Di satu sisi, Prabowo membangkitkan rasa bangga nasional dan menyalurkan aspirasi warga yang merasa ditinggalkan pembangunan.
Di sisi lain, ia mempersempit ruang demokrasi dengan mengklaim diri sebagai satu-satunya representasi sah “rakyat”.
Ini sering dilakukannya, tetapi secara samar. Dari sinilah lahir apa yang bisa disebut populisme otoritarian Prabowo: retorika rakyat yang berujung pada konsolidasi kuasa dan penguatan oligarki.
Bahaya terbesar dari pola ini adalah erosi masyarakat sipil. Oposisi dilemahkan, media dipaksa beradaptasi, dan kritik dibungkam atas nama melawan elit. Demokrasi menyusut menjadi prosedur tanpa substansi.
Studi Berti et al. (2024) menunjukkan, media cenderung menormalisasi bahkan menyepelekan populisme.
Pola serupa kini terlihat di Indonesia. Pidato kenegaraan Prabowo pun lebih banyak dipuji sebagai gaya tegas, bukan dibaca sebagai tanda konsentrasi kuasa.
Tentu populisme tidak bisa ditolak begitu saja. Ia lahir dari krisis demokrasi: rakyat merasa tak didengar, lalu mencari figur yang dianggap mewakili mereka.
Namun, sebagaimana ditekankan Arato dan Cohen dalam analisis Blokker (2023), demokrasi harus terus didemokratisasi.
Ia tidak boleh direduksi menjadi loyalitas pada satu figur karismatik. Sebab kekuatan demokrasi terletak pada sistemnya, bukan figur tertentu.
Berdiri di persimpangan
Indonesia kini berada di persimpangan. Populisme Prabowo bisa menjadi energi positif jika benar-benar memperluas partisipasi rakyat.
Namun, jika wajah otoritariannya yang dominan—memperkuat oligarki, membatasi oposisi, dan menormalisasi kekuasaan tak terbatas—maka yang dihadapi bukan sekadar gaya komunikasi baru, melainkan kemunduran demokrasi.
Sejarah negeri ini berulang kali menunjukkan betapa mudahnya janji kerakyatan berubah jadi kedok kekuasaan absolut.
Oleh karena itu, masyarakat sipil, akademisi, dan media harus lebih kritis.
Tidak cukup berhenti pada label “populis”. Kita perlu bertanya: siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan ke mana arah demokrasi digiring? (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News














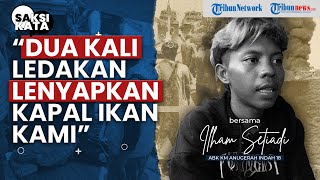




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.