Opini
Opini: Mencari Moderasi Lokal di Tengah Intoleransi
Lantas, apakah di tengah masifnya intoleransi, moderasi beragama tidak dapat dibumikan secara holistik di negeri ini?
Nilai-nilai ini hidup dalam tradisi, musyawarah adat, simbol kolektif, dan praktik keseharian.
Mereka mencontohkan Kalosara di masyarakat Tolaki, Bhinci-bhinci kuli di Buton, dan Siri' na pacce di Sulawesi Selatan.
Semuanya menanamkan penghargaan lintas kelompok, solidaritas, dan empati sosial.
Selain contoh tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) – tanah tempat kita hidup – telah lama menumbuhkan benih moderasi beragama melalui kearifan lokal, yang mampu menembus setiap generasi dan zaman. Tidak heran, NTT bahkan dijuluki Nusa Terindah Toleransi.
Julukan ini bukan tanpa alasan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2024 menempatkan NTT sebagai provinsi paling rukun di Indonesia, disusul Riau dan Kepulauan Riau di posisi kedua dan ketiga, serta Bali dan Papua di posisi empat dan lima.
Khusus di NTT, harus diakui bahwa di setiap pelosok desa, moderasi itu tumbuh melalui kearifan lokal yang terus hidup melintasi setiap generasi dan zaman.
Pengalaman empiris penulis di Kabupaten Alor, misalnya, menguatkan kesan itu. Saat Ramadan, teman-teman mengundang kami berbuka puasa.
Saat Natal, warga Muslim datang memberi selamat. Gotong royong membangun rumah ibadah pun dilakukan sejak dulu hingga kini. Dan, praktik-praktik moderasi lainnya yang tidak dapat diuraikan semua dalam tulisan ini.
Menariknya, dalam realitas keberagaman itu, tidak ada kelompok yang memasuki ranah dogma agama lain.
Semua menjaga batas, namun tetap membangun keakraban, persaudaraan dan harmoni sosial.
Semua ini dilakukan tanpa program negara atau modul pelatihan, melainkan murni dari nilai gotong royong, penghormatan, dan sikap saling menghargai yang diwariskan turun temurun.
Dari Lokal ke Nasional
Dalam realitas sosial yang “mewah” seperti itu, hemat penulis, moderasi lokal yang telah lama hidup melalui nilai-nilai kearifan lokal – seperti di NTT, Riau, Bali atau Papua – seharusnya tidak berhenti sebagai bahan survei atau ajang penghargaan semata, tetapi mesti diangkat menjadi role model praktik moderasi beragama di level nasional.
Sebab, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, moderasi sejati tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan, atau di forum-forum formal, melainkan tumbuh alami dari akar budaya masyarakat.
Karena itu, sudah saatnya negara belajar dari rakyatnya sendiri: dari desa yang membangun rumah ibadah bersama tanpa perintah, dan dari warga yang saling menjaga dan menghormati tanpa prasangka dan tuduhan.
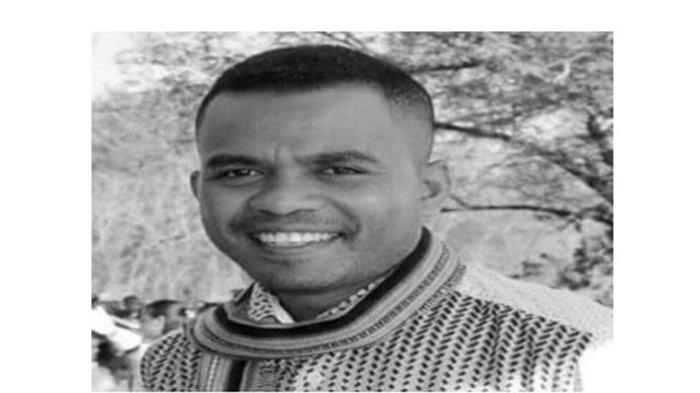


















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.