Opini
Opini: Meramal Masa Depan Resiliensi Inovasi Kebijakan Para Kepala Daerah
Kegagalan inovasi bukan sekadar perkara niat, melainkan akibat dari jebakan struktural yang menggerogoti dari dalam.
Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Dosen Pada Program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP Undana Kupang, Koordinator Program Studi Magister Studi Pembangunan Undana, Alumni Program Doktor Ilmu Administrasi Publik FISIPOL UGM
POS-KUPANG.COM - Di tengah kompleksitas pembangunan daerah, inovasi kebijakan menjelma sebagai mantra kepemimpinan yang menjanjikan.
Di Nusa Tenggara Timur, program seperti SABOAK di Kota Kupang dan OVOP di tingkat provinsi mencerminkan semangat membangun ekonomi lokal melalui pendekatan kreatif dan berbasis potensi desa.
Namun, studi-studi kebijakan publik mencatat banyak inovasi hanya semarak saat peluncuran, lalu redup karena gagal dilembagakan.
Ibarat panas-panas tahi ayam, program yang tidak ditopang sistem kelembagaan akan berakhir sebagai artefak politik, bukan instrumen perubahan.
Inovasi yang tak dilembagakan akan menguap menjadi simbol politik, bukan perubahan nyata.
Tanpa regulasi yang kuat, dukungan anggaran, kesiapan birokrasi, serta partisipasi publik sejak desain hingga implementasi, inovasi hanya akan menjadi narasi kosong.
Di sinilah pentingnya memahami bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada ekosistem yang menopangnya, bukan hanya ide brilian.
Tanpa itu, inovasi menjadi slogan kosong yang terjebak dalam logika palsu—sebuah “ false consciousness” ala Gramsci—di mana simbol kebaruan menutupi stagnasi struktural.
Dalam studi kebijakan publik, setiap inovasi perlu diuji bukan hanya melalui dampaknya yang instan, tetapi juga melalui resiliensi kebijakannya: apakah ia mampu bertahan melintasi rezim politik, apakah ia sanggup menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, dan apakah ia bisa menjangkau kelompok sasaran secara adil dan partisipatif?
Tiga Jerat Struktural yang Mengubur Inovasi
Kegagalan inovasi bukan sekadar perkara niat, melainkan akibat dari jebakan struktural yang menggerogoti dari dalam.
Pertama, warisan Old Public Administration (OPA) masih menjadi arus dominan birokrasi daerah.
Dalam logika Weberian ini, struktur pemerintahan dibangun atas dasar hierarki dan kepatuhan prosedural.
Kreativitas justru dianggap sebagai ancaman. Padahal, seperti dikatakan Osborne dan Gaebler (1992), pemerintah seharusnya bertindak sebagai katalis, bukan sekadar operator.
Ketika birokrasi tidak memberikan ruang untuk eksperimen, maka inovasi tak lebih dari suara di ruang hampa.
Kedua, ketiadaan governansi kolaboratif. Emerson et al. (2012) menegaskan bahwa kebijakan publik yang kokoh tumbuh dari partisipasi multipihak dalam arena deliberatif. Sayangnya, banyak inovasi di daerah digulirkan secara top-down.
Kelompok sasaran diposisikan sebagai objek pasif, bukan subjek pengambil keputusan.
Inilah yang melahirkan alienasi kebijakan: masyarakat merasa asing terhadap program yang seharusnya untuk mereka. Tanpa rasa memiliki, inovasi hanya menjadi proyek, bukan gerakan.
Ketiga, absennya manajemen perubahan. John Kotter (1996) mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa ujug-ujug diberlakukan.
Harus ada proses: membangun urgensi, menciptakan koalisi, menyusun visi, hingga melembagakan nilai baru.
Di banyak daerah, inovasi langsung diluncurkan tanpa transformasi budaya organisasi.
Akibatnya, ASN menjadi apatis, masyarakat bingung, dan sistem menolak perubahan secara halus namun mematikan.
Ketika Inovasi Menjadi Fatamorgana: Logika Palsu dan False Consciousness Apa yang terjadi ketika publik percaya bahwa inovasi telah hadir, padahal tidak ada perubahan berarti dalam pelayanan publik maupun kesejahteraan warga?
Inilah yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai false consciousness—kesadaran palsu yang dibentuk oleh simbol-simbol semu.
Inovasi menjadi sekadar nama program, aplikasi digital, atau baliho besar yang menghias kota. Tapi jika struktur, budaya, dan dampak tidak berubah, maka yang hadir bukanlah inovasi, melainkan fatamorgana kebijakan.
Contohnya bisa kita temukan di berbagai daerah. Program OVOP di NTT memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi desa, namun tanpa pendampingan produksi, akses pasar, dan pelatihan kewirausahaan, ia mudah kehilangan arah.
SABOAK, jika tidak didukung oleh regulasi perlindungan pedagang dan integrasi dengan promosi pariwisata kota, akan berakhir sebagai event musiman, bukan ekosistem yang tumbuh.
Kita bandingkan dengan Smart Kampung di Banyuwangi, sebuah inovasi yang lahir dari partisipasi warga, ditopang digitalisasi, dan dilembagakan lintas sektor.
Atau sebaliknya, kegagalan sebagian program Kartu Jakarta Pintar Plus akibat akurasi data dan kesiapan pelaksana yang lemah.
Dua kutub ini mengajarkan bahwa bukan nama atau teknologinya yang menentukan, tetapi bagaimana inovasi itu dirancang, ditanamkan dalam sistem, dan dijalankan secara inklusif.
Menuju Inovasi yang Berakar: Dari Simbol ke Sistem
Di tengah pergantian kepemimpinan daerah, momen ini menjadi peluang untuk merumuskan ulang cara kita memandang inovasi kebijakan. Inovasi tidak boleh lagi dilahirkan prematur di tengah rahim birokrasi yang belum siap.
Konsep metagovernance dari Kooiman dan Torfing menekankan bahwa kepala daerah harus bertransformasi dari penggagas program menjadi arsitek tata kelola. Ia harus mampu membangun ruang kolaborasi lintas aktor—antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas.
Langkah pertama adalah pelembagaan. Inovasi harus terhubung dengan sistem anggaran, RPJMD, dan kerangka evaluasi. Kedua, partisipasi warga bukan sekadar pelibatan simbolik, tapi ko-kreasi sejak awal.
Ketiga, pembangunan kapasitas ASN dan sistem insentif perlu dirancang agar birokrasi tidak menjadi penonton pasif.
Terakhir, inovasi harus dievaluasi bukan hanya dengan indikator kuantitatif, tetapi dengan menilai perubahan dalam perilaku, kesetaraan akses, dan ketahanan kelembagaan.
Seperti ditulis Gramsci: “The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born.”
Maka tugas kepala daerah adalah menyiapkan rahim birokrasi agar inovasi bisa lahir sehat, tumbuh dewasa, dan beranak pinak dalam sistem. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News















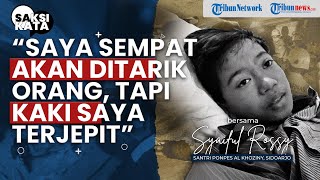





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.