Opini
Opini: Mau Tidak Mau Jadi PNS, Refleksi atas Ketergantungan Fiskal dan Struktural di NTT
Dalam struktur PDRB NTT, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial ternyata menempati posisi yang sangat strategis.
Oleh: Yesdi Christian Calvin, SST, MS
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
POS-KUPANG.COM - Tampaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS) adalah salah satu pilihan profesi paling populer bagi mayoritas pencari kerja di Nusa Tenggara Timur ( NTT).
Jika kita perhatikan lingkungan sekitar, besar kemungkinan kita memiliki keluarga atau kenalan yang bekerja sebagai PNS, atau setidaknya pernah mengikuti seleksi CPNS.
Tak jarang, percakapan sehari-hari pun sering diselingi kabar seputar formasi, “lolos passing grade”, atau “masih tunggu pengumuman SK”.
Mengapa banyak generasi muda terdidik “mau tidak mau” menjadi PNS?
Apakah kecenderungan ini semata-mata karena pandangan umum masyarakat NTT bahwa menjadi PNS adalah simbol kemapanan, kestabilan, dan cara paling realistis untuk mencapai kesejahteraan?
Untuk memahami kecenderungan ini secara lebih menyeluruh, kita perlu meninjau struktur perekonomian NTT melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Ketika Pemerintah Jadi Tulang Punggung Ekonomi
PDRB bisa dianalogikan seperti pendapatan sebuah rumah tangga dari seluruh jenis usaha yang dijalankan, misalnya berkebun, berdagang, atau menjadi tukang.
Setelah dikurangi biaya operasional seperti pupuk, bensin, atau sewa tempat, sisanya adalah keuntungan bersih.
Itulah gambaran sederhana dari PDRB: seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah dari aktivitas ekonominya.
Bila kita melihat struktur PDRB NTT, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial ternyata menempati posisi yang sangat strategis.
Dari 17 kategori lapangan usaha, sektor ini menempati peringkat ketiga penyumbang terbesar PDRB, hampir setara dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di posisi kedua yang menyumbang di kisaran 12 persen.
Angka ini memunculkan pertanyaan penting: apakah kontribusi besar ini mencerminkan kekuatan ekonomi, atau justru menunjukkan ketergantungan yang mengkhawatirkan?
Untuk menjawabnya, kita perlu membandingkan dengan konteks nasional dan regional.
Secara nasional, kontribusi sektor ini hanya sekitar 3,04 persen, dan di provinsi tetangga seperti NTB sekitar 5,82 persen, cukup jauh di bawah angka NTT yang mencapai 12,74 persen (BPS, 2025).
Di sisi lain, sektor-sektor produktif seperti Industri Pengolahan justru belum berkembang signifikan di NTT.
Kontribusinya terhadap PDRB hanya sekitar 1,4 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 18,98 persen dan masih lebih rendah dari NTB yang mencapai 3,87 persen.
Padahal, sektor Industri Pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong nilai tambah, membuka lapangan kerja formal, dan mempercepat transformasi struktural ekonomi.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa proses industrialisasi di NTT masih tertinggal jauh.
Dominasi sektor Administrasi Pemerintahan ini juga perlu dilihat dalam konteks lemahnya sektor utama lainnya.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, misalnya, masih menjadi penopang utama ekonomi NTT dengan kontribusi sebesar 28,87 persen terhadap total PDRB, hampir sepertiga dari keseluruhan.
Tetapi, besarnya kontribusi ini belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pelakunya.
Berdasarkan data BPS, sebanyak 70,73 persen rumah tangga miskin di NTT menggantungkan hidup dari sektor ini.
Ditambah lagi, fakta bahwa mayoritas pelaku pertanian berpendidikan rendah dan bekerja secara informal menunjukkan bahwa sektor ini masih dikelola secara tradisional.
Hal ini turut menjelaskan mengapa minat generasi muda terhadap usaha pertanian masih rendah.
Melihat situasi tersebut, idealnya struktur ekonomi suatu daerah tidak terlalu bergantung pada sektor primer seperti pertanian maupun pada belanja pemerintah.
Sebuah struktur ekonomi yang sehat dan berkelanjutan ditandai oleh pelebaran basis ekonomi yang merata, yakni melalui pertumbuhan sektor sekunder seperti industri pengolahan dan sektor tersier seperti jasa dan pariwisata.
Dalam Visi Indonesia 2045: Ringkasan Eksekutif yang diterbitkan oleh Bappenas pada tahun 2019, transformasi struktural yang berkualitas mengharuskan realokasi sumber daya ke sektor pertanian modern, manufaktur, dan layanan modern (termasuk ekonomi kreatif dan digital).
Inilah yang dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan.
Kemandirian Fiskal yang Masih Ilusi
Untuk memahami mengapa sektor Administrasi Pemerintahan terlihat dominan dalam struktur PDRB NTT, penting untuk menilik bagaimana kontribusi sektor ini sebenarnya dihitung.
Meski tidak menghasilkan barang dagangan, sektor ini memproduksi jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi yang dikonsumsi masyarakat dan masuk dalam output ekonomi daerah.
Nilai tambahnya umumnya dihitung dengan pendekatan nilai belanja pemerintah, terutama belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN) dan belanja barang dan Jasa (operasional).
Dengan kata lain, semakin besar belanja pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan operasional, semakin besar pula kontribusi sektor ini dalam PDRB.
Sayangnya, struktur belanja tersebut justru menunjukkan ketimpangan. Realisasi belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan ASN mencapai 39,77 persen dari total belanja daerah, jauh melampaui belanja barang dan jasa yang hanya 24,38 persen, apalagi belanja modal yang hanya 12,96 persen (DJPK Kementerian Keuangan, 2024).
Artinya, sebagian besar anggaran masih terserap untuk konsumsi birokrasi, bukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketika roda ekonomi digerakkan oleh belanja rutin pemerintah, ruang gerak sektor swasta semakin sempit.
UMKM dan wirausaha lokal sulit tumbuh karena pasar tidak cukup dinamis, sementara kreativitas dan inovasi terhambat akibat minimnya sistem pendukung yang memadai.
Orientasi belanja yang demikian juga berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Karena lebih banyak anggaran digunakan untuk belanja rutin (belanja pegawai) ketimbang membangun basis ekonomi produktif, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri pun menjadi terbatas.
Hal ini tercermin dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada tahun 2024 hanya menyumbang 11,41 persen dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, lebih dari 85,90 persen masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Ketimpangan ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penerimaan daerah belum berkembang signifikan, sehingga siklus ketergantungan fiskal terus berulang dan kemandirian fiskal pun masih jauh dari harapan.
ASN di Persimpangan: Pasif atau Progresif?
Karena sektor administrasi pemerintahan masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi NTT, pemerintah daerah perlu berperan lebih aktif sebagai fasilitator pembangunan.
Peran ini tidak cukup hanya sebagai penyalur dana pusat, tetapi harus berkembang menjadi pencipta ekosistem ekonomi lokal yang mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif.
Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendukung usaha, pembiayaan bagi UMKM, insentif investasi lokal, serta pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Penguatan konektivitas fisik dan digital juga harus menjadi prioritas utama, tidak hanya di kota besar, tetapi hingga ke wilayah tertinggal, agar pemerataan pembangunan benar-benar terjadi.
Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, transformasi ekonomi di NTT hanya akan menjadi wacana.
Anak-anak muda yang berpendidikan tinggi akan terus enggan mengabdi di NTT karena minimnya peluang karir di luar jalur birokrasi.
Bahkan bagi yang memutuskan untuk kembali ke NTT, banyak yang akhirnya memilih menjadi PNS, bukan karena cita-cita ideal, melainkan opsi paling realistis.
Perubahan memang tidak dapat terjadi dalam semalam, tetapi langkah awal bisa dimulai dari keberanian meninjau ulang struktur ekonomi secara jujur dan menyusun strategi yang berpihak pada potensi lokal.
Di sinilah peran ASN diuji: bukan sekadar menjadi beban fiskal, tetapi justru menjadi agen perubahan.
Di tengah keterbatasan dan tantangan, ASN memiliki peluang untuk membuktikan birokrasi bukanlah ruang yang stagnan, melainkan bisa menjadi wahana strategis bagi inovasi, transformasi pelayanan publik, dan pembangunan yang lebih berdampak. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News















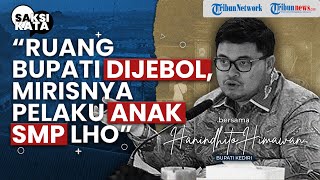





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.