Opini
Opini: Mengajar dan Tren Melaporkan
Dahulu, otoritas guru ditopang oleh nilai sosial yang menempatkan guru sebagai orang tua kedua di sekolah.
Oleh: Goldy Ogur
Alumnus Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM - Berangkat dari viralnya kasus guru yang takut menegur siswa karena risiko hukum, tulisan ini mengangkat isu kebebasan mengajar dan iklim belajar yang sehat.
Dalam masyarakat modern yang semakin sensitif terhadap pelanggaran hak asasi, pendidik kini berjalan di atas garis tipis antara mendidik dan dituduh.
Apakah ini pertanda kemunduran atau justru momen untuk menata ulang relasi antara guru, siswa, dan masyarakat?
Fenomena ini menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam cara kita memaknai relasi kuasa di ruang kelas.
Ketika sistem hukum atau persepsi publik lebih cepat menghakimi guru daripada mendengar duduk perkaranya, maka profesi guru kehilangan tempat berpijak yang aman.
Ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga refleksi dari mentalitas masyarakat yang tidak siap hidup dalam masyarakat pendidikan yang dewasa.
Terlebih ketika media sosial sering kali menjadi hakim tanpa proses, maka pendidikan berubah menjadi tontonan, bukan lagi proses pertumbuhan.
Krisis Kepercayaan di Ruang Kelas
Ki Hajar Dewantara sejak awal telah menekankan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.
Namun bagaimana menuntun jika sang penuntun justru diragukan niat dan otoritasnya?
Di sinilah letak paradoks zaman ini: kita ingin pendidikan yang bermutu, tetapi meragukan mereka yang menjalankan prosesnya.
Jika terus berlangsung, relasi antara guru dan siswa akan kehilangan dimensi moralnya.
Guru menjadi takut berinteraksi secara mendalam, dan siswa kehilangan figur otoritatif yang menuntun dengan keteladanan.
Masyarakat kehilangan ekosistem pendidikan yang sehat. Maka kini saatnya kita bertanya, bukan hanya apakah guru salah, tetapi juga apakah masyarakat sudah benar dalam memperlakukan guru.
Dahulu, otoritas guru ditopang oleh nilai sosial yang menempatkan guru sebagai orang tua kedua di sekolah.
Dalam budaya Timur, khususnya di Indonesia, guru bukan sekadar profesi, melainkan figur yang dihormati.
Kini otoritas tersebut goyah, digerus oleh paradigma legalistik yang memperlakukan guru bukan sebagai pendidik, melainkan sebagai pelayan administrasi dan target pelaporan.
Ketika anak merasa lebih berhak melaporkan daripada belajar mendengarkan, maka yang hilang bukan hanya wibawa guru, tetapi juga makna pendidikan.
Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidik harus menjadi panutan, pemberi semangat, dan pengarah yang arif.
Dalam semboyannya, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, terkandung pesan tentang kehadiran guru sebagai teladan moral, bukan hanya penyampai materi.
Namun dalam situasi kini, guru dipaksa mundur dari posisi ini oleh tekanan hukum dan kekhawatiran sosial.
John Dewey, tokoh pendidikan progresif, percaya bahwa pendidikan adalah proses sosial yang bergantung pada komunikasi timbal balik.
Ia menolak pendekatan otoriter, tetapi bukan berarti menolak kehadiran otoritas pendidik. Yang ditolak adalah kekuasaan yang membungkam, bukan bimbingan yang memanusiakan.
Sayangnya, dewasa ini, semua bentuk otoritas guru sering disalahpahami sebagai represi. Padahal yang kita butuhkan adalah otoritas yang mendewasakan, bukan dominasi yang menindas.
Hak Asasi Manusia (HAM) yang semestinya menjamin kebebasan dan martabat semua pihak, kini justru diterjemahkan secara terbalik.
Seringkali yang lebih kuat secara hukum justru adalah siswa dan orang tua, sementara guru yang rentan karena ketidakseimbangan posisi justru tak mendapat perlindungan.
Ketika HAM kehilangan akhlak, maka yang terjadi adalah HAM sebagai alat balas dendam, bukan jaminan keadilan. Ini bukan sekadar ironi, tapi kemunduran peradaban pendidikan.
Ketakutan yang dirasakan para guru hari ini lahir dari pengalaman konkret: pelaporan sepihak, penyebaran video tanpa konteks, tekanan dari orang tua, hingga rasa waswas terhadap interpretasi hukum yang kaku.
Guru bukan lagi merasa sebagai pendidik, melainkan seperti pesakitan yang berjalan di lorong pengadilan sosial.
Padahal, esensi pendidikan adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan terhadap guru, maka pendidikan menjadi aktivitas yang hampa dan mekanistik.
Menimbang Ulang Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan
Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan adalah praktik pembebasan. Dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, ia menggugat sistem pendidikan yang memperlakukan siswa sebagai bejana kosong yang harus diisi.
Freire mengajak guru dan murid membangun hubungan dialogis, di mana kedua belah pihak adalah subjek yang saling mencipta makna.
Tapi ketika guru hidup dalam ketakutan, tidak ada ruang untuk dialog, apalagi pembebasan.
Ketakutan ini menjelma menjadi sensor diri. Guru memilih diam daripada bicara, memilih menghindar daripada mendidik secara utuh.
Mereka menghindari isu-isu kritis yang sebenarnya penting bagi pembentukan karakter murid.
Akibatnya, siswa tumbuh dalam suasana semu: seolah merdeka, padahal kehilangan pemandu. Pendidikan menjadi miskin nilai dan miskin arah.
Ketika guru tak lagi berani menjadi manusia seutuhnya di kelas, maka siswa pun kehilangan teladan yang otentik.
Mereka mungkin menguasai rumus dan teori, tetapi kehilangan arah moral dan kedalaman berpikir. Ini adalah bentuk lain dari ketimpangan HAM, hak anak untuk dibimbing direnggut oleh sistem yang menakuti gurunya.
Kita tengah menciptakan generasi yang pintar, tetapi tak matang secara batin.
Jika kita ingin memulihkan pendidikan, maka langkah pertama adalah memulihkan martabat guru.
Martabat itu bukan diperoleh dari seremoni Hari Guru, tetapi dari penghormatan dalam praktik: perlindungan hukum, ruang untuk mendidik secara utuh, dan kepercayaan publik.
Guru yang dihargai akan mendidik dengan hati. Guru yang dicurigai hanya akan menyampaikan hafalan.
John Dewey percaya bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat. Maka jika kita ingin masyarakat yang adil, demokratis, dan bermoral, maka ruang kelas harus menjadi tempat di mana nilai-nilai itu dihidupi.
Namun bagaimana mungkin itu terwujud jika guru diperlakukan sebagai tersangka sejak awal? Tanpa perlindungan struktural, kita hanya menuntut tanpa memberi jaminan yang adil.
HAM dalam konteks pendidikan tidak bisa dimaknai secara sempit. Ia harus mengakomodasi kebutuhan untuk mendidik secara otentik.
Kita memerlukan HAM yang berwajah manusiawi, yang mengakui bahwa mendidik adalah hak sekaligus tanggung jawab yang butuh ruang, bukan hanya pengawasan.
Guru tidak sedang meminta hak istimewa, melainkan hak dasar untuk menjalankan fungsinya tanpa rasa takut.
Jika bangsa ini ingin membangun masa depan yang beradab, maka mendudukkan guru secara bermartabat adalah syarat mutlak. Pendidikan bukan tempat perang kuasa, tetapi ladang tumbuhnya nilai.
Kita memerlukan keberanian bersama untuk mengakui bahwa dalam banyak kasus, pemaknaan HAM telah terbalik arah: dari alat pembelaan menjadi alat penindasan diam-diam.
Saatnya kita kembali pada esensi: memanusiakan pendidikan, dengan terlebih dahulu memanusiakan gurunya. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Goldy Ogur
Opini Pos Kupang
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
POS-KUPANG. COM
profesi guru
kekerasan terhadap anak
Ki Hajar Dewantara
| Opini: Prada Lucky dan Tentang Degenerasi Moral Kolektif |

|
|---|
| Opini: Drama BBM Sabu Raijua, Antrean Panjang Solusi Pendek |

|
|---|
| Opini: Kala Hoaks Menodai Taman Eden, Antara Bahasa dan Pikiran |

|
|---|
| Opini: Korupsi K3, Nyawa Pekerja Jadi Taruhan |

|
|---|
| Opini: FAFO Parenting, Apakah Anak Dibiarkan Merasakan Akibatnya Sendiri? |

|
|---|










![[FULL] Pidato Perpisahan Sri Mulyani seusai Sertijab ke Purbaya Yudhi, Minta Privasinya Dihormati](https://img.youtube.com/vi/ldVpruUf-Gk/mqdefault.jpg)



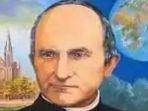

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.