Opini
Opini: Satu Dekade Dana Desa di NTT: Pelajaran untuk Koperasi Merah Putih
Jika dihitung efektivitas investasi, setiap 1 triliun rupiah Dana Desa di NTT hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,14%.
Oleh: Maria Dolorosa Bria, S.Pi., MEnv.Sc
(Pengurus KoalaNTT, bekerja pada Dinas PMD Rote Ndao Tahun 2019 – 2023)
POS-KUPANG.COM - Sepuluh tahun sudah sejak Program Dana Desa diluncurkan pada tahun 2015. Dengan dana hampir 25 triliun rupiah yang mengalir ke Nusa Tenggara Timur (NTT), harapan untuk transformasi besar di desa sangatlah tinggi.
Namun, realitas berbicara lain. Berdasarkan data BPS, kemiskinan di NTT hanya turun 3,56 persen, dari 22,58 persen di tahun 2015 menjadi 19,02 persen di Tahun 2024.
NTT tetap berada di posisi ketiga provinsi termiskin di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat. Posisi yang masih sama persis seperti sepuluh tahun lalu.
Untuk memahami seberapa lambat laju pengentasan kemiskinan di NTT, mari bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia Timur. Papua berhasil turun dari 28,40 % di tahun 2015 ke 17,26 % di tahun 2024—sebuah penurunan signifikan 11,14 % atau rata-rata 1,24 % per tahun.
Papua Barat juga menunjukkan kinerja lebih baik dengan penurunan 6,80 % selama satu dekade. Sedangkan rata-rata penurunan di NTT hanya 0,36 % per tahun.
Jika dihitung efektivitas investasi, setiap 1 triliun rupiah Dana Desa di NTT hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,14 % . Padahal kita tahu bahwa selain dana desa, masih ada alokasi dana lain ke NTT.
Dalam bahasa sederhana, dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk mengangkat sedikit saja masyarakat dari kemiskinan. Timbul pertanyaan besar: di mana letak masalahnya?
Ketika Kebijakan Pusat Bertemu Realitas Desa
Di balik angka-angka ini, tersembunyi kisah tentang betapa rumitnya menerjemahkan kebijakan yang dibuat di Jakarta ke dalam kehidupan nyata di desa-desa sangat tertinggal di NTT.
Setiap tahun, Kementerian Desa PDTT mengeluarkan peraturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia.
Pendekatan ini, meski terdengar logis untuk koordinasi dan standarisasi nasional, ternyata menciptakan paradoks di tingkat desa. Pada Kementrian ini juga memiliki Data Indeks Desa Membangun (IDM) yang membagi desa dalam lima kategori desa: sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.
Indikator – indikator pembentuk IDM harusnya menjadi acuan penetapan prioritas pembangunan desa.
Bayangkan sebuah desa di pedalaman NTT yang dihadapkan pada kenyataan bahwa 40 % anak di desanya mengalami gizi buruk, namun memilih membangun lapangan olahraga karena masuk dalam prioritas sesuai peraturan Menteri. Atau, desa lain dengan banyak anak putus sekolah karena tidak ada transportasi ke sekolah, tetapi lebih memilih ‘memagari pantai.
Kekacuan Koordinasi Anggaran
Permasalahan menjadi semakin kompleks karena tidak adanya tools atau sistem yang memadai untuk sinkronisasi program pembangunan yang didanai oleh dana desa dengan sumber anggaran lain, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Tidak jarang terjadi tumpang tindih program yang mengakibatkan pemborosan sumber daya.
Sebagai contoh, sebuah desa mendapat alokasi anggaran untuk bantuan bibit rumput laut dari dana desa, namun di tahun anggaran yang sama ada bantuan serupa dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau dari LSM.
Akibatnya, satu desa bisa mendapat bantuan berlipat untuk komoditas yang sama. Koordinasi yang buruk ini tidak hanya mengakibatkan inefisiensi, tetapi juga menciptakan ketimpangan distribusi bantuan antar desa.
Drama Ketergantungan: Ketika Bantuan Menjadi Candu
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah mentalitas ketergantungan yang tercipta akibat pola pemberian bantuan yang terus-menerus.
Bantuan atau hibah seringkali dianggap sebagai hak absolut dari pemerintah desa, bukan sebagai stimulus untuk membangun kemandirian.
Ada kisah nyata dari sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai penenun. Sejak adanya dana desa hingga sekarang, setiap tahun para penenun selalu mendapat bantuan benang secara gratis.
Ketika pemerintah desa diminta untuk menghentikan pemberian bantuan ini dan mengalihkannya ke program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, kepala desa berkata, "Jika tidak diberi bantuan, mereka tidak akan menenun."
Fakta ini mengungkap betapa dalamnya ketergantungan yang telah tercipta. Yang seharusnya menjadi stimulus untuk mengembangkan usaha, malah menciptakan mental "tunggu bantuan".
Masyarakat kehilangan inisiatif untuk mandiri dan lebih memilih menunggu bantuan gratis dari pada berusaha mengembangkan usaha secara mandiri.
Drama Sumber Daya Manusia
Jika paradoks kebijakan adalah tantangan struktural, maka krisis sumber daya manusia adalah tantangan yang lebih fundamental.
Di desa-desa terpencil NTT, terjadi drama kehilangan yang terus berulang: setiap kali ada anak muda yang berhasil menyelesaikan pendidikan, mereka pergi meninggalkan desa, membawa serta harapan dan potensi yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan.
Fenomena brain drain ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Desa kehilangan SDM terbaiknya, sementara yang tertinggal kurang memiliki kapasitas untuk menjalankan program pembangunan secara optimal.
Hasilnya, program yang dirancang dengan baik di atas kertas berubah menjadi rutinitas administratif yang tidak berdampak signifikan.
Kisah Pahit BUMDes: Ketika Harapan Tak Selaras dengan Kenyataan
Salah satu wujud nyata persoalan ini adalah nasib BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Berdasarkan data LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT tahun 2023, terdapat 3.137 BUMDes yang tersebar di NTT.
Dari jumlah ini hanya 1.476 yang merupakan BUMDes aktif. Sementara data dari Kemendes PDTT menyebutkan BUMDes di NTT yang terdaftar pada Kementerian Desa PDTT berjumlah 624 BUMDes (20 % ).
Lebih mengkhawatirkan lagi, monitoring Senator NTT Abraham Liyanto pada 2021 menunjukkan bahwa kurang dari 10 % BUMDes di NTT yang benar-benar berhasil menjalankan fungsinya sebagai unit usaha produktif.
Situasi BUMDes ini bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif ekonomi kolektif.
Masyarakat menjadi skeptis terhadap program-program sejenis di masa depan, dan ini bisa berdampak pada program serupa seperti Koperasi Merah Putih (KMP) yang baru dikerjakan Tahun 2025 ini.
Pembelajaran untuk Koperasi Merah Putih
Pengalaman satu dekade Dana Desa di NTT harusnya menjadi pelajaran berharga bagi KMP. Pelajaran pertama adalah pentingnya kontekstualisasi program.
Setiap desa memiliki DNA unik yang membutuhkan pendekatan khusus. KMP bisa memanfaatkan data IDM atau Indeks Desa sehingga pendekatan one-size-fits-all harus hindari.
Menggunakan model yang sama untuk semua daerah tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal telah terbukti tidak efektif dalam kasus Dana Desa.
KMP harus resisten terhadap godaan untuk menstandarisasi semua prosedur dan layanan. Meskipun standarisasi memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan kontrol kualitas, namun dalam konteks daerah yang sangat beragam di Indonesia, fleksibilitas dan adaptasi lokal menjadi lebih penting.
Mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, Gubernur dan Bupati harus mengeluarkan aturan khusus yang kontekstual sesuai dengan prioritas pembangunan di wilayahnya.
Pelajaran kedua adalah terkait SDM dan kapasitas lokal. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di desa terpencil dan atau tertinggal bukan sekadar hambatan teknis, tetapi tantangan fundamental.
Mengabaikan kapasitas local dan memaksakan target dan program yang melebihi kapasitas SDM lokal terbukti telah menyebabkan program pembangunan (seperti BUMDes) gagal.
KMP harus realistis dalam menetapkan target dan mengembangkan program yang sesuai dengan kapasitas yang ada. Ini bukan berarti menurunkan standar, tetapi mengembangkan capacity building yang bisa meningkatkan kapasitas secara bertahap.
Investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM adalah krusial. SDM di desa sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah urban tentu berbeda.
Operasionalisasi sistem harus dirancang sederhana sehingga bisa dijalankan oleh SDM dengan kapasitas terbatas, sambil terus mengembangkan kapasitas mereka secara bertahap.
Pelajaran ketiga adalah pentingnya membangun sistem koordinasi yang kuat untuk menghindari tumpang tindih program. KMP perlu mengintegrasikan dirinya kedalam sistem perencanaan pembangunan desa dan pembangunan daerah yang ada dan memastikan tidak ada duplikasi atau tumpeng tindih dengan program lain.
Pelajaran keempat, KMP jangan menjadi kompetitor bagi institusi yang sudah ada, apalagi menjadi ladang garapan baru stakeholders yang telah terbukti gagal pada program serupa seperti BUMDes. KMP harus hadir untuk memperkuat dan mendorong berkembangnya institusi organic yang telah berjalan di desa.
Pelajaran kelima adalah menghindari terciptanya ketergantungan. KMP harus dirancang sebagai lembaga yang mendorong kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan.
Pengalaman dana desa menunjukkan pendekatan supply driven gagal menciptakan impact signifikan. KMP harus menerapkan pendekatan demand driven untuk efektivitas optimal.
Membangun Masa Depan dari Pembelajaran Masa Lalu
Untuk memutus paradoks pembangunan desa dan kemiskinan di NTT, diperlukan revolusi paradigma dalam desain program pembangunan.
Program harus bergeser dari pendekatan charity-based menjadi empowerment-based, dari uniform approach menjadi contextual approach, dan dari short-term impact menjadi sustainable development.
Pembangunan ekonomi di daerah terpencil bukanlah sprint, melainkan marathon yang membutuhkan napas panjang dan strategi yang matang.
"Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime." - Lao Tzu
Pengalaman Dana Desa menunjukkan bahwa kita terlalu lama memberi ikan, hingga melupakan esensi mengajar memancing.
Koperasi Merah Putih harus kembali ke filosofi dasar pemberdayaan ini. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS















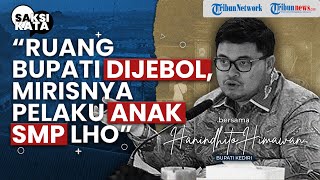





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.