Opini
Opini: Antara Surga yang Membuka dan Jalan yang Tak Juga Terbuka
“Jubah” dalam kisah ini bukan sekadar simbol kain tua yang diwariskan. Ia adalah simbol legitimasi dan kesiapan spiritual.
Oleh: John Mozes Hendrik Wadu Neru
Pendeta GMIT, berkarya di Kabupaten Sabu Raijua - NTT
POS-KUPANG.COM - Tulisan ini merupakan refleksi kritis dan teologis atas situasi sosial, spiritual, dan politik di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam kaitan antara iman dan keadilan sosial.
Dengan mengangkat tafsir naratif dari II Raja-Raja 2:1–18 dan peringatan Hari Lahir Pancasila, opini ini berusaha menunjukkan urgensi pewarisan nilai-nilai kenabian dalam kehidupan gereja dan masyarakat.
Membuka Langit yang Tertutup: Tafsir atas II Raja-Raja 2:1–18
Ada masa ketika langit tidak hanya berfungsi sebagai atap alam semesta, melainkan terbuka sebagai panggung peralihan besar: momen ketika Elia diangkat ke surga dalam badai, dan Elisa — sang penerus - tidak menangis atau mengabadikan momen dengan sorotan kamera, melainkan menuntut roh dua bagian. Bukan pusaka. Bukan jabatan. Tapi roh.
Tafsir ini bukan sekadar sentimentalitas perpisahan seorang nabi tua, melainkan pernyataan keras tentang transmisi kuasa, pewarisan tanggung jawab, dan kemampuan membedakan waktu ilahi.
Elisa tidak menanti dengan pasrah, ia menanti dengan kesiapan rohani. Ia tahu, ketika badai datang, bukan waktunya berlindung tapi menjemput panggilan.
“Jubah” dalam kisah ini bukan sekadar simbol kain tua yang diwariskan. Ia adalah simbol legitimasi dan kesiapan spiritual.
Dan menanti dengan setia bukan berarti diam di tepi sungai, tetapi bersiap untuk menyeberang—meski air masih tenang, dan langit belum bicara.
Maka pertanyaannya: jika Elia hari ini naik dari Pulau Sabu atau Gunung Mutis, siapakah Elisa?
Ataukah negeri ini hanya penuh dengan lima puluh orang yang berseragam, sibuk mencari-cari tubuh, tapi tak mengerti makna kehadiran Roh?
Gereja dan Rakyat NTT
Di Nusa Tenggara Timur, kita menanti bukan saja Roh Kudus, tapi juga air bersih yang tak dijual dengan proposal, harga hasil tani yang tak terus dipermainkan kartel, keadilan bagi anak-anak yang tubuhnya dirobek oleh para pelindung yang melukai.
Dan ironisnya, kita tetap menyanyikan lagu tentang “Negeri Surgawi” sambil berdiri di lumpur birokrasi yang menyumbat saluran hidup sehari-hari.
“Menanti dengan setia” di sini bukan sekadar spiritualitas bertahan hidup, melainkan tindakan melawan lupa. Lupa bahwa janji konstitusi dan Injil sama-sama bicara soal keadilan.
Bahwa Injil tidak pernah mewartakan keselamatan yang steril dari realitas sosial, dan Pancasila bukan sekadar hafalan upacara bendera.
Seperti kata Bung Hatta, “Indonesia merdeka bukan untuk jadi panggung permainan elite, tapi tempat rakyat mendapatkan harga diri.”
Namun kini, rakyat harus menonton pejabat ber-selfie ria di lokasi bencana sambil menyalahkan cuaca dan membagi bantuan hanya untuk konten.
Bahkan ibadah pun kadang lebih sering jadi dekorasi protokoler ketimbang perjumpaan kudus.
Di ruang-ruang seminar gerejawi, jubah kenabian kadang lebih sering dilelang dalam bentuk paket pelatihan, bukannya dipakai untuk memukul sungai realitas.
Apakah kita Elisa? Atau justru hanya asisten akuntan kenabian, yang mencatat berapa banyak seminar dan pelatihan yang telah diikuti?
Dua Lidah Api, Satu Panggilan
Setiap tanggal 1 Juni, kita mengenang kelahiran Pancasila, lima sila yang seharusnya menjadi pancaran api moral bangsa ini.
Namun, sila demi sila kini terdengar seperti gema di gedung kosong: nyaring, tapi hampa.
Seperti kata Soren Kierkegaard (filsuf dan teolog), "Faith sees best in the dark".
Dan dalam kegelapan sosial kita hari ini—kekerasan terhadap perempuan, korupsi struktural, elitisme agama, dan pemiskinan yang dilembagakan —iman bukan sekadar suluh kecil, tapi seharusnya api yang membakar ketidakadilan.
Lidah api Roh Kudus dan sila Pancasila adalah simbol transformasi. Tapi nyala itu kini hanya cukup untuk penerangan panggung-panggung upacara dan baliho besar para pejabat.
Kita lupa bahwa api tidak pernah dimaksudkan hanya untuk lampu sorot—ia harus membakar ketimpangan dan menyalakan keberanian.
“Ketuhanan yang Maha Esa” bukan hanya pengakuan lisan, tapi panggilan untuk menjadikan keadilan sebagai tindakan nyata.
Jika kita mengaku bangsa yang menjunjung “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, maka sikap membisu terhadap kekerasan seksual anak adalah penghinaan terhadap sila kedua.
Hamba yang Menanti
Dalam realitas NTT hari ini, “menanti dengan setia” bukanlah spiritualitas pasrah di atas tikar doa, melainkan keberanian berdiri di tanah retak yang menjerit - merawat harapan dan melawan apatisme dengan kerja konkret.
Ia bukan sekadar harapan yang melayang ke langit, tetapi tubuh yang turun ke bumi—yang masuk ke ruang kelas tanpa guru, berdiri di pesisir yang robek oleh tambang pasir, dan menyaksikan anak-anak yang kehilangan tubuh dan martabatnya di ruang-ruang yang semestinya aman.
Masih ada sekolah-sekolah yang tiap pagi berdiri tanpa cukup guru, hanya ada papan tulis tua, murid-murid yang lebih banyak dari bangku, dan kepala sekolah yangrangkap jadi pengajar dan pemungut iuran.
Di tempat lain, pesisir-pesisir Sabu, Rote, dan Alor perlahan hilang ditelan abrasi dan keserakahan.
Bukannya ditanami mangrove, ia digali untuk bahan bangunan hotel, yang katanya demi pariwisata rohani. Di mana suara gereja saat bumi tempat gereja berpijak justru disayat-sayat oleh investasi yang menipu?
Dan yang paling sunyi, namun paling menyayat: anak-anak perempuan dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan yang menyebut diri “komunitas rohani.” Kita sering terlalu cepat mengampuni, terlalu lambat melindungi.
Apakah ini yang disebut menanti dengan setia? Atau sebenarnya kita sudah menyerah tanpa mengaku?
Seperti dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno, "Tanggung jawab moral bukanlah pilihan; ia adalah konsekuensi dari eksistensi bersama."
Maka setiap langkah gereja yang memilih diam di hadapan kekerasan adalah pengkhianatan terhadap eksistensinya sendiri.
Elisa mengerti bahwa waktu transisi bukan waktu panik—melainkan waktu kesiapan.
Dalam sejarah bangsa pun, seperti kata Soekarno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri."
Maka dalam transisi kekuasaan, dalam musim kampanye, dalam janji-janji pembangunan yang tak menyeberangi laut, siapa yang memegang jubah dan memukul sungai?
Menjadi Elisa: Gereja, Rakyat, dan Kuasa Roh
Puncak dari refleksi ini bukanlah pujian atas masa lalu atau kenangan indah kenabian. Tapi seruan: jadilah Elisa.
Bukan hanya dengan memungut jubah secara simbolik, tetapi dengan mewarisi roh keberanian, keadilan, dan aksi.
Jangan hanya menjiplak gaya kenabian, tapi hidupkan kembali semangatnya dalam konteks lokal: membela petani rumput laut, mendampingi korban kekerasan seksual, memperjuangkan desa-desa yang dilupakan dalam rencana pembangunan.
Jika Pancasila adalah proklamasi moral kebangsaan, dan Roh Kudus adalah energi Ilahi, maka gereja dan rakyat adalah agennya.
Kita dipanggil bukan untuk menunggu, tapi untuk bertindak, melintasi sungai-sungai stagnasi dan kemapanan palsu.
Seperti kata Tan Malaka, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda." Gereja pun demikian: ketika kehilangan idealismenya, ia kehilangan relevansinya.
Penutup: Elia Sudah Naik. Giliran Kita
Elia tidak kembali. Ia sudah naik. Dan Tuhan tidak sedang merekrut nabi baru dari surga.
Ia menunggu dari bumi—dari antara rakyat—orang-orang yang siap menanti dengan setia dan bertindak dengan jubah roh yang diwariskan.
Menanti dengan setia adalah memegang jubah kenabian di tangan, dan memukul sungai zaman—hingga airnya terbelah dan jalan terbuka bagi perubahan. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
| Opini: Cegah Stunting, Kunci NTT Keluar dari Kemiskinan |

|
|---|
| Opini: Kepemimpinan Melki-Johni dan Mutu Pendidikan NTT |

|
|---|
| Opini: Mencari Hati yang Enggan Membenci di Balik Puing-puing Gereja Keluarga Kudus Gaza |

|
|---|
| Opini: Antara Ngopi dan Hipertensi, Gaya Hidup yang Menyesatkan Generasi Muda |

|
|---|
| Opini: Dilema Energi Hijau di Poco Leok, Pemerintah Perlu Perbaiki Pola Komunikasi |

|
|---|










![[FULL] Pakar: Indonesia Terlibat Israel Caplok Gaza, Deal-dealan dengan Trump Obati 2.000 Korban](https://img.youtube.com/vi/5sKhHBVJjUg/mqdefault.jpg)

















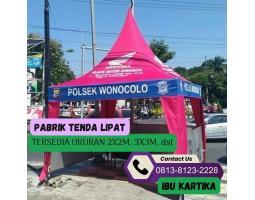
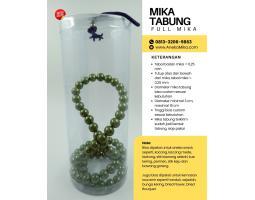







Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.