Opini
Opini: Menggugat Kurikulum Hari ini dari Ki Hajar Dewantara ke Generasi Z
Ki Hajar Dewantara pernah menegaskan bahwa pendidikan bukan semata proses transfer ilmu, melainkan upaya memanusiakan manusia secara utuh.
Ki Hajar menolak pendekatan yang memaksakan kehendak kepada anak didik. Sebaliknya, ia mendorong pendidikan yang mendengarkan suara anak, mengembangkan daya kritis, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial dan moral mereka.
Namun, dalam praktiknya hari ini, semangat emansipatoris ini tampak semakin mengabur.
Sistem pendidikan cenderung menjadikan peserta didik sebagai objek yang harus mengikuti standar dan ujian, alih-alih subjek yang aktif dalam proses belajar.
Pendidikan menjadi birokratis dan berorientasi angka—nilai ujian, indeks kelulusan, atau peringkat sekolah yang sering kali mengebiri dimensi kemanusiaan pendidikan itu sendiri (Sahlberg, 2015).
Ironisnya, ketika Generasi Z menunjukkan kreativitas, kemerdekaan berpikir, dan kemampuan adaptif yang tinggi di luar ruang kelas, misalnya melalui media sosial, komunitas kreatif, atau dunia digital pendidikan formal justru sering kali mengekang potensi itu dengan kurikulum yang
kaku dan metode yang satu arah.
Untuk itu, penting bagi kita untuk kembali ke akar pemikiran Ki Hajar. Pendidikan bukan untuk mencetak manusia seragam, tetapi membentuk manusia yang merdeka, berkarakter, dan mampu hidup dalam dunia yang plural dan dinamis.
Seperti yang ia tegaskan: “Anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu” (Dewantara, 1935).
Generasi Z dan Ketertinggalan Kurikulum
Generasi Z—anak-anak yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Mereka adalah digital native; yang sejak kecil telah terbiasa dengan internet, media sosial, dan perangkat teknologi pintar.
Informasi bagi mereka bukan barang langka, melainkan sesuatu yang dapat diakses dalam hitungan detik.
Mereka belajar melalui YouTube, menjelajahi dunia lewat TikTok, dan membentuk komunitas lintas batas di dunia maya.
Di tengah realitas ini, sistem Pendidikan formal Indonesia justru masih berkutat dengan pendekatan belajar konvensional yang tidak sejalan dengan cara belajar generasi ini.
Menurut Trilling dan Fadel (2009), generasi abad ke-21 memerlukan keterampilan berpikir kritis, komunikasi kolaboratif, kreativitas, dan literasi digital, semua hal yang sayangnya belum menjadi arus utama dalam kurikulum Nasional.
Model pembelajaran yang menekankan hafalan dan jawaban tunggal tidak lagi relevan di tengah dunia yang menuntut fleksibilitas dan inovasi.
| Opini: Prada Lucky dan Tentang Degenerasi Moral Kolektif |

|
|---|
| Opini: Drama BBM Sabu Raijua, Antrean Panjang Solusi Pendek |

|
|---|
| Opini: Kala Hoaks Menodai Taman Eden, Antara Bahasa dan Pikiran |

|
|---|
| Opini: Korupsi K3, Nyawa Pekerja Jadi Taruhan |

|
|---|
| Opini: FAFO Parenting, Apakah Anak Dibiarkan Merasakan Akibatnya Sendiri? |

|
|---|














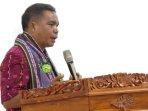
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.