Opini
Opini: Hyperrealitas Pilkada dan Ilusi Kekuasaan Baru
Janji-janji kampanye yang disampaikan dengan retorika heroik menjadi bahan bakar optimisme ini, tetapi apakah itu semua realistis?
Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Dosen Administrasi Publik pada FISIP Undana Kupang, Koordinator Program Studi Magister Studi Pembangunan Undana, dan Alumni Program Doktor FISIPOL Universitas Gajah Mada
POS-KUPANG.COM - Ketika hasil pilkada serentak diumumkan, suasana euforia meliputi masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT.
Harapan akan perubahan besar seolah terlahir kembali, menghidupkan optimisme bahwa kepala daerah terpilih mampu membawa daerah ini keluar dari berbagai persoalan kronis seperti kemiskinan, stunting, dan infrastruktur yang terbengkalai.
Janji-janji kampanye yang disampaikan dengan retorika heroik menjadi bahan bakar optimisme ini, tetapi apakah itu semua realistis?
Jean Baudrillard menyebutkan bahwa dalam era modern, apa yang kita anggap sebagai realitas sering kali tidak lebih dari simulasi—konstruksi simbolik yang mengaburkan kenyataan.
Pilkada di NTT telah menjadi laboratorium nyata dari konsep ini, di mana narasi kampanye menciptakan citra pemimpin ideal yang jauh dari realitas kompleks birokrasi dan pembangunan daerah.
Masyarakat terbuai dalam janji-janji ini, menerima mereka sebagai kebenaran mutlak tanpa mempertanyakan bagaimana janji tersebut akan diwujudkan.
Hyperrealitas ala Baudrillard dan Dominasi Narasi Ilusi
Jean Baudrillard, dalam karyanya Simulacra and Simulation (1981), menjelaskan hyperréalité (hyperrealitas) sebagai kondisi di mana realitas asli digantikan oleh simulacra, yaitu representasi buatan yang tampak lebih nyata dari kenyataan itu sendiri.
Dalam konteks pilkada, janji-janji politik sering kali merupakan konstruksi mental yang dirancang untuk menarik emosi, bukan mencerminkan veritas (kebenaran) kondisi nyata.
Misalnya, janji menghapus kemiskinan dalam waktu singkat adalah bentuk illud fictum (fiksi itu sendiri) yang mengabaikan kompleksitas masalah seperti struktur ekonomi dan birokrasi.
Fenomena ini menyerupai "bayangan dalam gua" Plato di Politeia (The Republic), di mana masyarakat terpesona oleh simulacra politik sebagai realitas sejati.
Kondisi ini menghasilkan ketergantungan pada kekuatan eksternal, di mana masyarakat kehilangan kemandirian rasionalitas untuk berpikir kritis.
Mereka menerima narasi tanpa pengujian rasional, menciptakan circulus vitiosus (lingkaran setan) euforia yang memperkuat ilusi.
Akibatnya, ekspektasi yang tidak realistis terhadap kepala daerah muncul, mengaburkan tantangan struktural dan fundamental.
Baudrillard mengingatkan bahwa ketika simulacra mendominasi, realitas digantikan oleh ilusi, menjadikan narasi politik sebagai pusat kontrol persepsi masyarakat.
Mata dan Tangan di Balik Kekuasaan
Ketika kepala daerah terpilih mulai memegang kendali, fase baru dalam siklus kekuasaan politik dimulai.
Tekanan dari tim sukses dan kelompok kepentingan muncul sebagai konsekuensi logis dari quid pro quo, sebuah hubungan timbal balik yang sering kali bercampur dengan kepentingan transaksional.
Mereka yang merasa berjasa dalam memenangkan pemilu menuntut “imbalan” berupa proyek strategis atau jabatan penting, yang dalam filsafat politik disebut sebagai fenomena rent-seeking.
James Buchanan menyebut ini sebagai ekspresi dari homo economicus dalam arena politik, di mana aktor bertindak untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, mengorbankan bonum commune (kebaikan bersama).
Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai ratio proiectiva atau "nalar proyek," suatu paradigma di mana kebijakan publik dirancang bukan untuk mengatasi masalah secara mendalam (sub ratione veritatis), tetapi untuk menciptakan peluang keuntungan bagi elite tertentu.
Proyek semacam ini sering kali tidak membawa manfaat nyata (utilitas publica) bagi masyarakat luas dan malah memperparah iniquitas socialis (ketimpangan sosial).
Max Weber, melalui konsep rationalisierung, memperingatkan bahwa birokrasi yang terjebak dalam rasionalitas formal tanpa memperhatikan substantia justitia (keadilan substantif) akan kehilangan orientasi terhadap telos (tujuan akhir) dari keberadaan birokrasi itu sendiri, yakni melayani res publica (kepentingan publik).
Dalam kondisi ini, birokrasi tidak lagi menjadi instrumen untuk ars boni et aequi (seni yang baik dan adil), tetapi justru menjadi instrumen kekuasaan politik yang memperkuat dominasi kelompok tertentu atas masyarakat luas.
Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menjadi alat transformasi sosial berubah menjadi instrumentum alat reproduksi ketimpangan menjauhkan pembangunan dari prinsip aequitas socialis (keadilan sosial) yang seharusnya menjadi tujuan utama.
Menuju Kebijakan Publik yang Rasional dan Objektif
Untuk menghindari jebakan hyperrealitas dan rent-seeking, masyarakat NTT harus mengembangkan kritisisme terhadap janji-janji kampanye.
Immanuel Kant dengan konsepnya, sapere aude (berani berpikir sendiri), menyerukan agar setiap individu berani mempertanyakan narasi-narasi yang beredar.
Sikap kritis ini harus menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan baru.
Di sisi lain, kepala daerah terpilih harus berkomitmen untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan.
Kebijakan publik harus berbasis data, melibatkan partisipasi masyarakat, dan fokus pada solusi jangka panjang.
Masalah-masalah seperti kemiskinan dan stunting tidak bisa diselesaikan dengan program sementara; mereka membutuhkan pendekatan holistik yang menyentuh akar masalah.
Masyarakat juga harus memanfaatkan ruang-ruang publik untuk berdiskusi dan menyuarakan pandangan mereka.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Habermas, ruang publik adalah tempat di mana rasionalitas dan demokrasi dapat berkembang.
Dengan kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pemerintah, janji kampanye dapat diwujudkan menjadi kebijakan publik yang berkeadilan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Mengingatkan Masyarakat untuk Tetap Kritis
Euforia pasca-pilkada adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh mengaburkan realitas.
Masyarakat harus memahami bahwa perubahan tidak datang hanya dari pergantian pemimpin, tetapi juga dari partisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik.
Sikap kritis terhadap kekuasaan baru adalah langkah awal untuk memastikan bahwa janji-janji kampanye tidak hanya menjadi retorika kosong.
Dengan menghindari jebakan hyperrealitas, NTT memiliki peluang untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kepala daerah terpilih harus menjadi pemimpin yang berani menempatkan kepentingan publik di atas tekanan politik, sementara masyarakat harus terus menjadi pengawas yang aktif dan kritis.
Hanya dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, mimpi untuk mengatasi kemiskinan, stunting, dan tantangan lainnya dapat menjadi kenyataan. (*)



















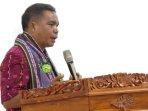

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.