Opini
Opini: Dari Freire ke Pendidikan Vokasi
Pola semacam itu merupakan salah satu kekhasanyang bisa kita temukan ketika membaca tulisan-tulisan Adrianus yang terbit di koran sejak 2009.
Oleh: Mario F Lawi
Editor Membongkar dari Dalam dan Docendo Discere
POS-KUPANG.COM - Rubrik “Opini” Pos Kupang edisi Selasa, 21 Mei 2024 menerbitkan artikel Adrianus Ngongo berjudul “Kompetensi Abad ke-21 dan Kerja Kolaborasi”.
Dalam tulisan tersebut, Adrianus memperkenalkan empat kompetensi yang mesti dimiliki pada abad ke-21, masalah-masalah dalam mengimplementasikannya, serta pihak-pihak yang menurutnya berkontribusi dalam penerapannya.
Pola semacam itu merupakan salah satu kekhasanyang bisa kita temukan ketika membaca tulisan-tulisan Adrianus yang terbit di koran sejak 2009.
Sebagian besar artikel tersiar tersebut telah dibukukan dalam dua judul. Buku pertama adalah Docendo Discere (2021), yang memuat artikel-artikel pendidikannya dalam rentang tahun 2009—2021.
Buku kedua, Membongkar dari Dalam, yang baru saja terbit bulan ini, memuat artikelnya dalam rentang tahun 2021—2024. Kedua buku tersebut diterbitkan oleh Penerbit Dusun Flobamora.
Sebagai buku-buku bertema pendidikan, Docendo Discere dan Membongkar dari Dalam juga mengingatkan kita pada buku Sekolah Itu Candu, karya terkenal Roem Topatimasang (terbit pertama kali pada 1998).
Dalam cetakan terakhir terbitan Insist Press (2020), Sekolah Itu Candu telah mendapat tambahan empat esai, sehingga memiliki total 16 esai selain prolog dan epilog.
Ke-16 esai dalam buku tersebut adalah esai-esai yang menggugat dan menggugah kesadaran dan kemapanan berpikir kita selama ini tentang sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia.
Roem membuka bukunya dengan esai yang menunjukkan sejarah singkat lembaga pendidikan, dengan menelusuri etimologi kata “sekolah” dan praktiknya sejak zaman Yunani Kuno hingga abad ke-18 di Eropa, dan kilasan tradisi yang berkembang di Indonesia.
Dari esai tersebut, ia kemudian bergerak ke esai-esai yang menunjukkan permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan yang melanda Indonesia, dan dampak ikutannya.
Esai paling penting dalam buku yang mengikat keseluruhan tulisan adalah esai berjudul “Involusi Sekolah”, yang secara jitu mempertanyakan dan menunjukkan kelemahan-kelemahan birokratisasi dan sloganisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, serta masih relevan hingga saat ini, meskipun esai tersebut ditulis
pada 10 Januari 1984 atau 40 tahun lalu.
Membaca esai tersebut pada hari ini menyadarkan kita bahwa gerak pendidikan kita belum beranjak ke mana-mana, dan usaha-usaha mengelabui mandeknya kemajuan dengan mengutak-atik angka-angka kuantitatif telah menjadi penyakit birokrasi yang berulang.
Esai-esai Roem dalam buku tersebut memang bersandar pada gagasan-gagasan sejumlah filsuf pendidikan yang populer di Indonesia, misalnya Paulo Freire.
Karya monumental Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas) dibuka dengan pembedaan antara kaum penindas dengan kaum tertindas. Kaum tertindas mengalami dehumanisasi karena ditindas.
Lewat penindasan tersebut, kaum penindas ikut mengalami dehumanisasi karena menyebabkan dehumanisasi terhadap kaum tertindas. Untuk memperjuangkan kebebasan, kaum tertindas harus mulai memiliki kesadaran.
“Perjuangan dimulai dengan lahirnya kesadaran manusia bahwa mereka ditindas,” tulis Freire. Cara efektif melahirkan kesadaran adalah melalui pendidikan kemanusiaan yang dialogis. Bagaimana caranya?
Pada bagian kedua bukunya, bergerak dari dikotomi antara penindas dan tertindas, Freire menampilkan dikotomi lain, yakni sistem pendidikan gaya bank (banking education) dan sistem pendidikan hadap-masalah (problem posing education). Freire menunjukkan poin-poin pendidikan bergaya bank:
1. Guru mengajar dan murid diajar;
2. Guru mengetahui segalanya dan murid tidak mengetahui apa-apa;
3. Guru berpikir dan murid dipikirkan;
4. Guru berbicara dan murid patuh mendengarkan;
5. Guru disiplin dan murid didisiplinkan;
6. Guru memilih dan memaksa pilihannya, dan murid menerima;
7. Guru berbuat dan murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya;
8. Guru memilih isi pelajaran, dan murid (tanpa diminta pendapatnya) menerima pelajaran itu;
9. Guru mencampuradukkan kewenangan ilmu pengetahuan dengan kewenangan jabatannya, yang dia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid;
10. Guru adalah subjek proses belajar, sementara murid hanya sekadar objek. Poin terakhir adalah inti dari pendidikan bergaya bank.
Freire memandang pendidikan semacam itu, yang melihat siswa sebagai tabula rasa untuk diisi, sebagai manifestasi dari nekrofilia.
Pendidikan seperti itu menjadikan siswa pasif, menjauhkannya dari realitas di sekitarnya, dan membunuh kreativitasnya.
Dalam konsep pendidikan semacam itu, pengetahuan adalah anugerah yang diberikan oleh mereka yang menganggap diri berilmu kepada orang-orang yang dianggap tidak tahu apa-apa.
Bergerak dari dikotomi penindas dan tertindas, Freire menunjukkan bahwa bentuk pengabaian mutlak terhadap kemampuan seseorang merupakan karakteristik ideologi penindasan.
Ideologi penindasan yang mendehumanisasi tidak memungkinkan pendidikan dan pengetahuan menjadi sebuah proses penelusuran dan penyelidikan.
Dengan meminjam gagasan Erich Fromm, Freire menyatakan bahwa pendidikan bergaya bank justru tidak berangkat dari kecintaan terhadap kehidupan, tetapi sebaliknya.
Gaya yang melayani penindasan berangkat dari kecintaan terhadap kematian, nekrofilia, karena fungsinya mengerangkeng dan melenyapkan kesadaran, kekritisan, dan kreativitas.
Freire berpendapat bahwa gaya tersebut harus ditinggalkan. Untuk itu, pendidikan hadap-masalah ditawarkan.
Pendidikan hadap-masalah diajukan sebagai upaya konsientisasi. Pendidikan hadap-masalah melihat manusia bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai makhluk yang sadar dan merespons dunia sekitarnya.
Pendidikan hadap-masalah bertumpu pada aktivitas memahami informasi, bukan pada aktivitas memindahkan informasi seperti yang terjadi dalam pendidikan gaya bank. Siswa bukan lagi merupakan tabula rasa.
Jika pendidikan gaya bank berangkat dari asumsi bahwa siswa tidak tahu apa-apa dan karena itu tugas guru adalah menjelaskan hal-hal yang diketahuinya, pendidikan hadap-masalah justru melihat hal-hal yang ada sebagai bahan diskusi antara siswa dan gurunya.
Jika pendidikan gaya bank menuntut siswa menghafal pelajaran yang dijejalkan guru ke pikirannya, pendidikan hadap-masalah memberikan keleluasaan pertukaran gagasan antara siswa dan guru, memungkinkan guru merumuskan kembali gagasannya berdasarkan gagasan pembanding siswa.
Jika pendidikan gaya bank selalu berupaya menenggelamkan kesadaran, pendidikan hadap-masalah berupaya mengangkat kesadaran ke permukaan untuk melakukan intervensi kritis terhadap realitas.
Jika dalam gaya bank pendidikan digunakan sebagai praktik penindasan, dalam hadap-masalah pendidikan adalah praktik pembebasan. Melalui kedekatan dengan realitas, siswa sadar akan posisinya dan berusaha menjawab tantangan-tantangan yang ditemuinya.
Siswa bukan lagi orang yang terpisah atau terisolasi dari dunianya. Ia adalah orang yang secara aktif menanggapi dunianya.
Jika pendidikan bergaya bank anti-dialog, pendidikan hadap-masalah melahirkan dialog. Bagi Freire, dialog mesti dilakukan secara setara. Pihak yang inferior karena dehumanisasi harus mengambil kembali hak mereka yang hilang akibat dehumanisasi.
Dialog semacam itu lahir dari cinta yang mendalam terhadap kemanusiaan dan kehidupan, kerendahan hati, serta keyakinan terhadap hubungan horisontal saling percaya.
Gagasan tentang pendidikan hadap-masalah yang mengemukakan harapan terus dilanjutkan Freire di karya-karya yang terbit belakangan, misalnya dalam Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan.
Melanjutkan gagasannya dalam Pendidikan Kaum Tertindas, Freire menulis dalam salah satu suratnya di buku Pendidikan sebagai Proses: Surat-menyurat Pedagogis dengan Para Pendidik Guinea-Bissau:
“Pendidik harus secara konsisten menemukan dan terus mencari cara-cara yang memudahkan peserta didik untuk melihat objek yang harus diketahui dan akhirnya dipelajari, sebagai sebuah masalah. Tugas pendidik ini bukannya menggunakan alat dan cara tersebut untuk menemukan objek pengetahuan dan kemudian menawarkannya secara paternalistik kepada peserta didik, karena ini berarti mengingkari usaha peserta didik untuk memperoleh pengetahuan.
Dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik yang dimediatori oleh objek pengetahuan yang harus disingkap, faktor yang paling penting adalah perkembangan sikap kritis terhadap objek, bukannya apa yang diajarkan pendidik
tentang objek.”
Sejarah pendidikan formal di Indonesia, terutama pendidikan vokasi, tidak bisa tidak mesti menyinggung kelahiran dan perkembangan sekolah-sekolah di era kolonial.
Meski pendidikan formal merupakan dampak dari politik etis pemerintah kolonial, praktiknya politis dan tidak bebas nilai.
Sejumlah formasi, termasuk formasi dalam pendidikan vokasi, dibentuk berdasarkan standar yang ditetapkan kolonial, serta untuk melayani kebutuhan pemerintah kolonial.
Kita bisa membaca perkembangan pendidikan pada era tersebut misalnya dalam Sejarah Pendidikan Indonesia karya S. Nasution, dan Guru Kita: Artis Karakter & Kecerdasan karya H.A.R. Tilaar.
Menurut Robertus Robert, sebagai institusi yang tidak netral, sekolah mengembangkan ideologi organisasinya sendiri dengan mereproduksi relasi kekuasaan yang sudah melekat di dalam masyarakat.
Dengan demikian, kegagalan dan ketidaksetaraan sosial bisa ditamengi sebagai kegagalan pribadi siswa.
Hegemoni semacam itu, bersembunyi dalam perspektif pendidikan vokasi, membuat kita enggan mempertanyakan mengapa sekolah bisa tetap berfungsi untuk melayani permintaan kapital ketika ketimpangan-ketimpangan lain justru menganga lebar sebagai hasil dari model pendidikan semacam itu.
Meski demikian, hegemoni bisa juga dilihat dalam perspektif menguntungkan dengan mengembangkan pendidikan kritis dalam sekolah vokasi.
Dengan mengkaji pemikiran-pemikiran Gramsci, Apple, dan Giroux, John Hoben mengajukan pendapat bahwa dimensi budaya hegemoni memberikan peluang bagi posisi unik pendidikan vokasi sebagai ruang perlawanan terhadap kesenjangan yang kian melebar antara kepentingan ekonomi sempit dan konsepsi menyeluruh kebaikan publik.
Dengan pendidikan kritis, siswa sekolah vokasi justru bisa melihat diri mereka berbeda dari para siswa lain, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan begitu beragam sekaligus merupakan bagian dari konstruksi masyarakat.
Kesadaran terhadap keberagaman merupakan modal awal untuk mengidentifikasi masalah sehari-hari secara kontekstual, unik, dan spesifik.
Sebagai penulis sekaligus pendidik sekolah vokasi, Adrianus dalam kedua bukunya menyediakan solusi-solusi praktis bagi sebagian besar masalah yang dikomentarinya, dan bisa kita temukan tersebar sepanjang kedua buku tersebut.
Melalui tulisan ini, saya membawa perbincangan ke konteks yang lebih luas sekaligus menampilkan sedikit benang merah dengan konteks tersebut, menawarkan bagi kita salah satu perspektif untuk membaca tulisan-tulisan dalam kedua bukunya. (*)
| Opini: IKK NTT Terendah Ketiga, Harapan atau Tantangan di Tengah Pemangkasan TKD? |

|
|---|
| Opini: Jalan Terjal Menuju Generasi Emas NTT |

|
|---|
| Opini: Kearifan Lokal Menuju Demokrasi Berkeadaban |

|
|---|
| Opini: Menjaga Demokrasi Kampus dari Politik Zero-Sum Game |

|
|---|
| Opini: Saat Komunikasi Publik Menjadi Kunci Layanan Kesehatan Daerah |

|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Mario-F-Lawi-penyair.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Dody-Kudji-Lede2.jpg)








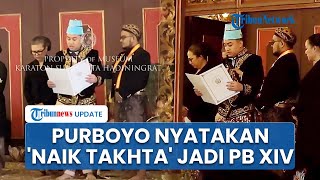





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.