Opini
Opini: Kontroversi Harga Beras
Di sinilah arti strategis program Nawacita yang menggariskan kedaulatan pangan sebagai model pembangunan pertanian dan pangan.
Oleh Habde Adrianus Dami
Mantan Sekda Kota Kupang, Pengamat Kebijakan Publik
POS-KUPANG.COM - Eskalasi harga beras yang tidak terkendali, telah menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah, yakni Rp 18.000/kg.
Perkembangannya cenderung mencemaskan jika mengacu pada pernyataan, Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi, (Kompas.com,18/3/2024), mengungkapkan harga beras diprediksi akan tetap bertahan dan diperkirakan tidak turun kembali ke harga seperti semula.
Padahal, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan melalui Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023, harga eceran tertinggi (HET) beras medium berlaku sejak Maret 2023, masing-masing adalah Rp 10.000,- per kg, sementara beras premium Rp 13.900,- per kg, untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Sedangkan pada zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET untuk beras medium dipatok Rp 11.500 per kg dan beras premium Rp 14.400,- per kg.
Selanjutnya, di zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800 per kg dan beras premium sebesar Rp 14.800 per kg.
Dalam situasi ini, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah nyaris nihil.
Sebab upaya mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul sangat lamban dan kurang menyentuh akar permasalahan. Jika mau jujur, hulu aneka permasalahan perberasan yang menyeruak saat ini adalah problem kebijakan keberpihakan.
Sehingga, tantangan ekonomi beras Indonesia amatlah berat. Beberapa dimensi penting ekonomi saling berhubungan sehingga, jika salah satu dimensi bermasalah, dimensi lain seakan saling mengunci.
Akibatnya, permasalahan kompleks sering kali menimbulkan distorsi ekonomi dan inefisiensi yang cukup akut.
Kedaulatan pangan
Persoalan pangan adalah persoalan hidup-matinya suatu bangsa. Di sinilah arti strategis program Nawacita yang menggariskan kedaulatan pangan sebagai model pembangunan pertanian dan pangan.
Kedaulatan pangan mengubah paradigma sebelumnya yang dikenal dengan ketahanan pangan. (Santosa, 2015).
Karena itu, pelaksanaan kedaulatan pangan dapat dinilai dari tujuh indikator utama yang meliputi: peningkatan kesejahteraan petani, produksi pertanian berkelanjutan berbasis agroekologi, proteksi harga dan penurunan impor pangan, renegosiasi semua perjanjian internasional dan regional terkait sektor pertanian dan pangan, redistribusi lahan untuk petani kecil, diversifikasi dan pembangunan pangan lokal, serta demokratisasi pertanian melalui pelibatan petani kecil dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan di semua tingkatan.
Sesuai janji Pemerintah melakukan revitalisasi pertanian tidak sekadar ingin meningkatkan produksi dan produktivitas guna mewujudkan kedaulatan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.
Namun demikian, pada kenyataannya situasi ini diperburuk dengan adanya faktor penyumbat kebangkitan pertanian selama ini adalah politik pangan yang masih berpihak kepada kepentingan konsumen, bukan kepentingan petani, termasuk petani yang setelah panen menjadi net-consumer pangan.
Bahkan yang membingungkan, ada kesan menggampangkan implementasi pemenuhan stok cadangan beras dengan jargon dan obral angka bombastis.
Padahal, rerata kebutuhan konsumsi beras per bulan adalah sebesar 2,55-2,56 juta ton.
Sementara produksi beras pada Januari-Pebruari 2024 sebesar 0,91-1,39 juta ton. Sehingga, terdapat defisit produksi dibandingkan konsumsi sebesar 2,8 juta ton beras. (mediakeuangan.kemenkeu.go.id, 1/3/2024).
Oleh karena itu, Pemerintah menugaskan Badan Pangan Nasional untuk mengimpor beras sebanyak 1.6 juta ton guna mengatasi kondisi produksi padi nasional yang terpuruk.
Sekalipun BPS mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton, meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022 impor sebanyak 429,21 ribu ton, 2021 sebesar 407,74 ribu ton, 2020 sebanyak 356,29 ribu ton, dan 2019 impor sebesar 444,51 ribu ton. (CNN Indonesia, 28/2/2024).
Sementara itu, dari perspektif ekonomi, pertanyaan yang segera mengemuka adalah siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan impor beras? Secara common sense para pemilik modal yang akan memperoleh keuntungan terbesar.
Artinya, data ini tergolong spektakuler sekaligus mempertegas tampilnya relasi kapitalistik yang dominan dalam kuasa pangan dan menggagalkan klaim kenaikan produksi beras.
Sehingga, ada anekdotal karena dalam sistem yang terbuka ini, mengandalkan rantai pasokan nilai didalam negeri tak selalu menguntungkan.
Namun, merancang mata rantai pasokan dengan mempertimbangkan impor bukan berarti harus mengorbankan produsen domestik, apalagi kedaulatan domestik.
Destruksi pasar
Destruksi pasar beras menggambarkan keadaan pasar secara tepat; pasar adalah refleksi dari ekistensi kekuasaan sehingga pasar tidak hanya mengontrol, tetapi juga dikontrol (Miller, 1998 dalam Yustika, 2015).
Pasar mengontrol keseimbangan pasokan dan permintaan lewat sinyal harga. Jika harga naik, itu tanda pasokan mesti ditambah. Begitu pula sebaliknya.
Seluruh proses itu bisa dikoordinasi secara rapi oleh pasar, tanpa perlu intervensi negara, jika situasi pasar bersaing sempurna. Akan tetapi, mengandaikan situasi pasar seperti deskripsi itu seringkali membuat frustasi karena pasar persaingan sempurna lebih layak disebut fatamorgana.
Ada anomali pasar beras. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, (2024), harga beras secara global mengalami penurunan 6,5 persen sebagai akibat ketidakpastian harga komoditas, sebaliknya harga beras dalam negeri justru mengalami kenaikan 21 persen.
Pertanyaannya, mengapa perilaku harga beras begitu rentan terhadap siklus harga terutama pasca Pilpres?
Pertama, tentu karena permintaan naik. Sebab, kedua, tak ada pengelolaan pasokan. Proyeksi produksi dalam negeri tak dilakukan secara akurat sehingga data pasokan tak realistis. Akibatnya, terjadi kerentanan dalam keseimbangan produksi dan konsumsi.
Selain soal penawaran dan permintaan sebagai faktor fundamental, ada pula faktor ketiga (non-ekonomi) yakni Pemerintah menggunakan stok beras milik Bulog sampai 1,3 juta ton terkait Bansos di saat-saat bulan-bulan Pemilu. (Kompas.com, 26/02/2024).
Dengan kata lain, beras (impor) mestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk kebijakan Bansos. Sehingga, membuat kondisi pasokan beras dipasaran menjadi semakin kritis.
Tak perlu menunggu waktu lama, destruksi pasar akhirnya terjadi. Dalam tempo cepat, harga beras melonjak tak terkendali.
Implikasinya, berdampak langsung terhadap anjloknya daya beli masyarakat yang berimbas pada upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang menjadi target pemerintah.
Padahal, salah satu kunci untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga adalah harga pangan yang stabil. Sebab, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, diikuti komponen pembentukan inflasi.
Melihat kondisi ini, pemerintah perlu menjaga harga pangan karena saat ini inflasi volatile food (harga pangan) telah melebihi kenaikan upah pegawai.
Secara historis sejak 2020-2023, rerata inflasi bahan pangan sebesar 5,2 persen, sementara pangan dalam kue inflasi memiliki bobot yang cukup besar, yaitu 33,5 persen terhadap inflasi total.
Disamping itu, sepanjang 2019-2024 gaji ASN yang naik rata-rata 6,5 persen dan UMR buruh bahkan naik tak lebih dari 5 persen.
Jika dilihat dari perspektif supply chain dan value chain, kita akan dapat melihat saling ketergantungan antara proses ekonomi dan non ekonomi pada setiap segmen.
Pada kondisi inilah, pasar dikontrol pemilik kuasa akan menjadi penentu dalam kebijakan perberasan dan celakanya sistem pangan tergolong liberal dan distribusi pangan (beras) adalah oligopolistik.
Tiga hal
Kinerja ekonomi pangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari belum stabilnya kinerja pertumbuhan semua subsektor dalam sektor pertanian dalam arti luas. Situasi itulah yang sekarang terjadi pada pasar beras nasional.
Untuk itu, tak berlebihan jika nilai dasar sosial-ekonomi-politik perberasan harus menjiwai setiap kehendak dalam mengonstruksi kebijakan stabilisasi harga beras.
Karena strategi stabilisasi harga beras merupakan keharusan demi menyelamatkan tiga hal sekaligus, yakni stabilitas ekonomi warga miskin, pendapatan petani (beras), dan makroekonomi.
Penalaran semacam ini menisyaratkan bahwa rangkaian instrumen stabilisasi harga beras merupakan satu kesatuan strategi yang terintegrasi dan terukur.
Maksudnya, dari kinerja produksi, pengadaan beras, referensi harga, manajemen stok, subsidi harga, sampai operasi pasar tidak dapat dilaksanakan sepotong-sepotong.
Pada titik ini, yang penting adalah perlu ada upaya serius membenahi kredibilitas data statistik beras terkait pola produksi, stok, dan konsumsi.
Apalagi, ketiga data beras itu tidak banyak berubah setiap tahun, sehingga dapat dipelajari dan dikaji dengan tepat guna pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. (*)

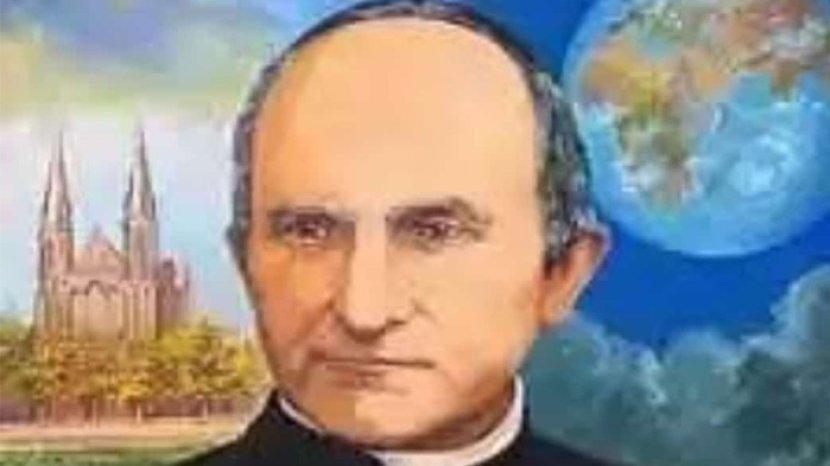



















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.