Opini
Opini: FABC dan Indigenisasi Kepemimpinan Miomafo Madhi Wasi untuk Uskup Hironimus Pakaenoni
Beliau adalah orang Dawan dari wilayah budaya Miomafo, TTU, Formator Seminari Tinggi Interdiosesan St. Mikhael, Penfui, dan Dosen Dogmatik.
Oleh Dr. Watu Yohanes Vianey, M.Hum
Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
POS-KUPANG.COM - FABC atau Federation of Asian Bishops` Conference adalah Konferensi Wali Gereja di tingkat Asia, yang resmi berdiri pada November 1972.
Salah satu misi dari FABC, sejak tahun 70-an itu adalah memajukan dialog dengan budaya-budaya lokal di Asia yang eviden multikultur, dan tujuannya adalah untuk membangun persekutuan antar bangsa-bangsa Asia, yang masih diancam oleh ketimpangan-ketimpangan dalam berbagai gatra kehidupan, seperti gatra budaya, politik, dan ekonomi (Vianey, 2023 a).
Ketiga gatra ini sudah menjadi keprihatinan Bunda Maria dalam Magnificatnya (Luk 1:51-53).
Solusi yang ditawarkan FABC adalah mengajak segenap lapisan umat beragama, berjalan bersama seraya berjuang untuk membangun jembatan-jembatan solidaritas, moderasi, dan perdamaian di Asia, demi berkembangnya relasi persaudaraan (Dawan: relasi feto-mone/olif-tataf/).
Hal mana mengalir dari salah satu visi FABC yaitu berjuang membangun Gereja Katolik yang mengejahwantah dalam budaya masyarakat Asia, termasuk kita di Asia Tenggara.
Setiap masyarakat Asia mempunyai kulturnya yang khas, menandai dan membedakannya dengan Gereja-Gereja setempat yang lain, dalam bingkai katolisitasnya.
Baca juga: Biodata Uskup Hironimus Pakaenoni
Maka sesuai dengan keanekaan kultural itu, akan ada unsur kenanekaragaman perwujudan iman dan perayaannya, pada Gereja-Gereja setempat, kendati mereka bertumpu pada Batu Penjuru dan Air Kehidupan Sakral (Fatu Le'u, Oe Le'u) yaitu Yesus Kristus.
Ini mengandaikan adanya proses inkulturasi dalam dinamika misteri Paskah, dan proses indigeniasi dalam dinamika misteri Natal.
Madhi Wasi Kepemimpinan Miomafo
Indigenisasi adalah nilai kearifan lokal yang diintegrasikan ke dalam Gereja Katolik yang universal (Vianey, 2023 b). Uskup Agung Kupang yang baru terpilih adalah RD. Hironimus Pakaenoni, LTh.
Beliau adalah orang Dawan dari wilayah budaya Miomafo, TTU, Formator Seminari Tinggi Interdiosesan St. Mikhael, Penfui, dan Dosen Dogmatik.
Ia mengampu Mariologi (sejak 2004) dan Ekklesiologi (sejak 2005), dan pernah menjadi pimpinan tertinggi di Fakultas Filsafat Unwira, yaitu sebagai Dekan selama 8 tahun.
Menyambung epilog saya pada buku terbaru beliau, tentang KUB (Pakaenoni, 2023), yang merupakan modifikasi thesis Licentiat Teologi Dogmatik-nya di Universitas Urbaniana Roma dalam judul: ”Building The Basic Christian Communities in Indonesia Today In The Light Of The Ecclesiology Of Vatikan II.”

Saya madhi wasi agar dilakukan aplikasi fruktualitasnya. Aplikasi kontekstualitasnya bisa menggunakan strategi indigenisasi nilai-nilai budaya lokal Flobamoratas di Keuskupan Agung Kupang.
Madhi wasi itu sejatinya adalah tindakan komunikasi budaya, semacam katekese kultural, yang saya serap dari tradisi Bajawa, yaitu duduk bersama untuk sharing pengalaman iman, harapan, dan kasih yang nyata.
Dalam tulisan ini, secara khusus di-madhi wasi-kan tentang kepemimpinan para agen pastoral yang mengambil bagian dalam kepemimpinan apostolik bapa Uskup.
Dan diskursus ini mengerucut pada pentingnya para agen pastoral di wilayah Keuskupan Agung Kupang untuk melakukan discernment tentang akar kepemimpinan dan keperwiraan kulturalnya, yang secara psikologis dan spiritual ada sumbangan dari bibit kepemimpinan dan keperwiraan leluhurnya; dan dalam terang iman adalah anugerah Tuhan dalam rentangan rencana keselamatanNya (Kis 17:28).
Beberapa penelitian fundamental yang dilakukan di wilayah Dawan terdahulu (Vianey dkk., 2015; 2017) menegaskan bahwa tipe ideal keperwiraan dan kepemimpinan yang menyejarah dalam narasi suci dan artefak peninggalannya adalah kaum ”Meo” dari berabagai suku di subetnik Dawan.
Penelitian internasional dari Tim Fakultas Filsafat di wilayah Perbatasan Wini dan Secato (2023) kembali memberikan afirmasi tentang hal itu. Narasi suci dan artefak keperwiraan mereka dalam bentuk ”Suni” (pedang pusaka) ada di rumah adat nan sakral (Ume Le’u) suku-suku Dawan yang ada di wilayah Timor Leste maupun di wilayah Indonesia.
Kembali ke judul dalam opini ini. Bagamana indigenisasi kepemimpinan Miomafo? Untuk itu pertama-tama kita madhi wasi tentang arti ”nama” Miomafo itu sendiri.
Dari sisi refleksi budaya tetang misteri sebuah ”nama”, seperti yang ditawarkan filsuf budaya Ernst Cassirer (Cassirer,1925), ia bekerja pada level artikulasi antara “ekspresi” (Ausdruck) dan “(re)presentasi” (Darstellung), untuk menemukan struktur dan penyesuaian mikro, yaitu mikro-péréquations” (Strauss, 1962).
Dengan kata lain, makna dan nilai dari nama Miomafo itu tidak pernah sepenuhnya bergantung atau tidak dapat diprediksi sepenuhnya jika tidak dikonteksualisasikan dengan penyesuaian (adaptasi) mikro tertentu, baik yang memuat makna dan nilai biasa maupun makna dan nilai luarbiasa.
“Miomafo” itu dari kata Dawan: ”meo” dan ”mafo”. Meo merujuk pada salah satu pemimpin struktural dalam suku, yang arif, bertanggung jawab, adil, berani, dan disiplin, setia berkorban di bidang pertahanan dan keamanan.
Makna luar biasannya adalah bahwa mereka memiliki kualitas kepahlawanan dan kepemimpinan, yang ambil bagian dalam kepemimpinan Uis Neno – Uis Pah dalam analogia entis seekor kucing sakral. Kata ’meo’, sebagai ”kucing”, juga sama isi ungkapannya dalam banyak bahasa di Flobamoratas.
Bapak Drs. Kornelis Bria, MSi (pensiunan dosen Unwira), Rm. Moses Olin, dan alm Rm. Maxi Bria pernah memperkenalkan jurus silat warisan para Meo tahun 1983-85-an di Seminari Tinggi Ritapiret.
Jurus-jurusnya bisa mengimbangi jurus dari Merpati Putih yang diperkenalkan oleh Rm. Dr. Marsel Bria, prefek kami pada tahun tersebut. Singkatnya Meo dibekali dengan kemampuan beladiri dalam dua belas jurus dan sebilah pedang, dan karena itu mereka bisa membela komnitasnya.
Dengan keutamaan etis, dalam perilaku yang tegas dalam prinsip dan lembut dalam sikap, mereka tampil perkasa dan profesional, dan karenanya dapat menangkap mangsa dan melindungi rumah dari para musuh dan ’tikus’ pencuri, penyebar penyakit, dan pembunuh.
Hal mana secara metafisik terkait dengan makna pemimpin yang memiliki karakter keperwiraan yang membela komunitasnya dari berbagai bentuk ketidakadilan.
Selanjutnya, kata ”mafo” yang berarti ”naung/naungan, teduh/peneduh, ibarat pohon yang dedaunannya rimbun dan buahnya lebat, yang memberi naungan atau keteduhan dan energi kehidupan bagi sesama makhluk.
Menarik, kata ”mafo” dalam bahasa Dawan sama dengan kata ”mawo” dalam bahasa Sumba dan Bajawa. Dalam tuturan Pata Dela, pemimpin itu harus mawo lai liko oge (Vianey, 2010).
Dalam konteks ini, Meo dalam tradisi lokal dibaratkan seperti pohon kokoh yang melindungi komunitasnya dari terik matahari dan sekaligus memberikan kenyamanan hidup bagi dunia sekitarnya.
Kepemimpinannya yang memberi inspirasi, motivasi, dan keteladanan, membuat pengikutnya untuk ada dan menjadi mahuma – mamata (Dawan: ’memiliki wajah dan mata’) manusia katolik sejati, yang dalam terang visi pastoral FABC di atas, mereka bertumbuh mejadi umat yang interkultural, yang sungguh menghayati missio Dei yang intergentes, hic et nunc.
Berjalan bersama semua ciptaan-Nya sebagai saudara dan sahabat dalam iman, harapan dan kasih Injili, untuk senantiasa Laudato Si – Laudato Deum, dalam 15 indikator dan pada 4 level pengahayatannya (1 Kor: 1-13).
Level kasih kekeluargaan (stroge), kasih kimiawi (eros), kasih persahabatan (philia), dan memuncak pada level agape (pengorbanan).
Kasih yang ditunjukkan Yesus kepada dunia, kasih yang diserahkan Yesus kepada Bunda Maria dan Rasul Yohanes di kaki Salib, dan kasih yang dipertanyakan Yesus yang bangkit kepada Rasul Petrus dan kasih yang dijawab lantang oleh Rasul Petrus, Uskup Roma, Paus pertama (Mat 16) dalam tradisi Gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik, kepada Sang Guru dan Tuhan (Yoh13:13), dan sahabatnya (Yoh 15:13-15), dalam perjalanan bersama di seluruh Galilela dan Yudea, khususnya dalam penampakan ke-7 sebelum Ia naik ke Surga, di tepi danau kehidupan itu (Yoh 19).
Simpulannya adalah sebagai berikut. Miomafo itu adalah ”Meo Peneduh”. Dan untuk semakin mengakarkan dan mebuahkan makna keperwiraan dan kepemimpinan para Meo yang sigap melindungi dan meneduhkan komunitasnya, kiranya diskursus ini diperkaya dengan merefleksikan terus menerus kisah perwira dalam Injil Mateus 8 dan kisah Pohon Anggur Yoh 15.
Bapa Uskup baru, RD Hironimus Pakaenoni, Pr, L.Th dan para pastor projo dan biarawan, dan juga para katekis di Keuskupan Agung Kupang kiranya mengindigenisasikan kearifan lokal Flobamoratas, seraya mengkotekstualisasikan nilai-nilai Injil selaras zaman.
Semoga dengan doa Bunda Maria dan St. Hironimus, Bapa Uskup boleh menggembalakan umat dengan Pedang Roh yaitu Firman Allah (Ibr 4: 12-13; Ef 6:17), dalam spirit Meo Mafo yang ambil bagian dalam kuasa Totum Christi dan Cosmic Christ (Why 1:8) di era kontemporer. (*)
Watu Yohanes Vianey
Hironimus Pakaenoni
Uskup Agung Kupang
Unwira Kupang
Opini Pos Kupang
Opini
Dawan
| Opini: Menalar Demonstrasi |

|
|---|
| Opini: Green Chemistry, Solusi Praktis Melawan Krisis Lingkungan di NTT |

|
|---|
| Opini - Drama Penonaktifan Anggota DPR: Siapa yang Sebenarnya Berkuasa, Rakyat atau Partai? |

|
|---|
| Opini: Anomali Tunjangan Pajak DPR RI, Sebuah Refleksi Keadilan Fiskal |

|
|---|
| Opini: Paracetamol Publik Menyembuhkan Demam Bukan Penyakit |

|
|---|














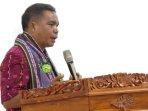

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.