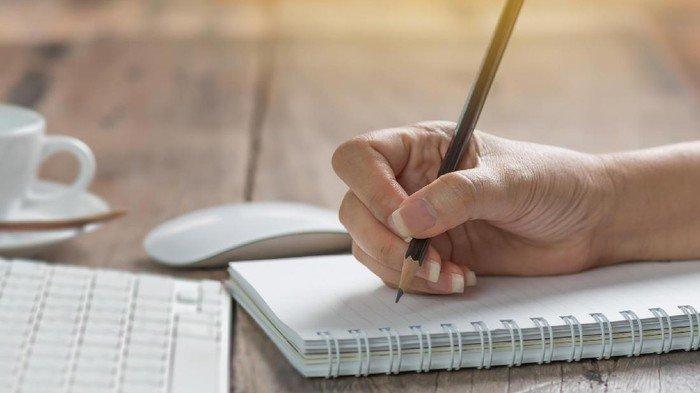Opini
Kebijakan Publik Bias Gender
kartini milenial musti mewarisi nafas perjuangan silam untuk mendekonstrusi ragam dominasi yang menindas
KEBIJAKAN PUBLIK BIAS GENDER
Oleh : Veronika Ina Assan Boro dan Emanuel Kosat*
Momentum hari Kartini 2022 yang ke-57 (berdasarkan tanggal pertama kali ditetapkan) kali ini oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema, Dare to Speak up: Dimulai dari Keluarga. Persis RA Kartini era kolonial berupaya untuk meruntuhkan sekat-sekat kultur patriarkal. Kala itu Kartini muda menginisiasi kesetaraan akses pendidikan bagi kaumnya; menentang perjodohan paksa, pingitan, dan kekerasan.
Olehnya, kartini milenial musti mewarisi nafas perjuangan silam untuk mendekonstrusi ragam dominasi yang menindas. Gerakan emansipasi diperluas pada seluruh jenis marginalisasi dalam masyarakat. Artinya tidak sekadar pada kesetaraan martabat antara tuan dan puan, tapi juga kaum LGBT, ODGJ, kelompok difabilitas, kaum miskin dan aliran-aliran minoritas lainya. Universalitas kesadaran manusia tentang Hak Asasi Manusia menjangkau semua kaum/golongan tanpa mendiskreditkan yang lain. Setiap pihak terbukakan ruang publiknya untuk dapat mengekspresikan hak dan kebebasan secara orisinil-eksistensial.
Pemerintah sering hanya mengenal merek-merek keadilan dan kebenaran sesuai tafsir tunggal budaya dan kekuasaan. Jika itu dibiarkan, maka sampai kapan pun pemerintah tidak akan sanggup memahami situasi dan pengalaman kebatinan dari kelompok minoritas. Logika yang digunakan musti pula dibalikan mengikuti alam pikiran para kelompok minoritas. Artinya keadilan dan kebenaran itu tidak lagi dipahami secara tunggal, umum, dan universal karena sejatinya kebenaran dan keadilan bersifat plural, partikular dan relatif. Setiap pihak punya kesempatan yang sama untuk dibenarkan dan menenggak keadilan.
Seringkali terminologi mayoritas dan minortas menjadi alat paksa untuk membenarkan tindakan penindasan secara halus. Mayoritas merasa benar karena eksistensi minoritas ada berkat belas kasihan mayoritas. Apabila minoritas terlalu berlebihan maka mayoritas akan terusik.
Satu tata bahasa yang dapat menyelamatkan manusia ialah solidaritas (solidarity). Hubungan didasarkan secara setara. Tidak ada konsekuensi hirarkis. Semua orang merasa bertanggung jawab secara asimetris, sebab bersikap solider dengan rekan tidak pernah bersifat pamrih. Prinsip ini dilakukan karena menyadari martabat manusia yang berkepribadian dan bernurani luhur. Dalam problem kaum LGBT, sejauh mana mereka mendapat tempat secara sosial di masyarakat.
Keberadaan mereka disimplifikasi sebagai suatu penyimpangan dan konon dianggap sebagai golongan orang dengan kelainan. Warisan kebencian dan perendahan mengendap dalam psiko-sosial masyarakat sehingga kerap kali merampas ruang publik mereka. Dan yang terjadi mereka bergerak secara diam-diam. Namun kini mereka berani mengakui status diri salah satunya dengan cerita suka duka komunitas LGBT di hotel Kristal beberapa waktu lalu. Mereka berdialog dengan representasi kelompok LGBT dari tiap provinsi di Indonesia.
Lantas, bagaimana dengan kelompok difabel dan ODGJ. Mereka terlahir dengan keterbatasan jasmani dan rohani. Perlakuan pada mereka mesti memperhitungkan kondisinya. Kaum difabel punya motivasi dan tekad yang sama, hanya dalam perebutan ruang hidup mereka terpaksa tersingkirkan. Tidak bisa dinafikan bahwa beberapa akses ruang pelayanan publik secara arsitektur telah dapat mengakomodasi kepentingan kaum difabel.
Tetapi ada pula ruang publik yang masih belum ramah difabel. Belum lagi soal pemberdayaan dan skill yang mesti terus-menerus dibenahi. Dengan pelatihan dan pemberdayaan paling tidak dapat membesarkan jiwa mereka bahwasanya makna kehidupan itu ialah berkarya dan berguna. Kelompok ODGJ lain lagi, mereka dipasung secara fisik dan mental oleh kebijakan publik. Pemisahan kewarasan dan kegilaan menjadi wujud penaklukan kegilaan oleh yang waras sebagai mekanisme pendisiplinan. Padahal kegilaan tidak dapat dijelaskan secara utuh.
Perluasan Gerak Emansipasi
Konsep laki-laki baru sekarang sebagai suatu kesadaran rekonsiliatif kaum lelaki sekaligus jalan pikiran partnership bersama para kartini milenial untuk coba merenovasi ciri penindasan selama berabad-abad silam. Peradaban itu diawali ketika Arsitoteles (384-322 SM) memisahkan secara diametral antara wilayah polis dan oikos. Polis adalah wahana ekspresif bagi kaum laki-laki berargumentasi secara rasional. Sedangkan oikos sebagai lokasi perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak mengutamakan perasaan atau emosi.
Pembagian peran kemudian berafirmasi di Romawi Kuno, Cicero (106-43 SM) yang menarik garis demarkasi antara res publica dengan logic of goodness dan res priva dengan logic of survival. Itu artinya sejak dahulu kala peran itu diletakan berbasis kontruksi sosial. Hanya karena perempuan dianggap mengandalkan emosi maka dia lebih layak urus rumah tangga, mencuci, memasak, menyapu, merawat anak, dan menata rumah. Dan para laki-laki baru mencoba menanggalkan atribut peran itu, dan kini mengerti bahwa fakta given; menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui saja yang tidak bisa dipertukarkan, sementara peran yang lain bisa berganti.
Berbagai problem bias gender itu merupakan konstruksi sosial yang harus diakui turut melatari pembuatan kebijakan (policy-making). Penerapan quota minimal 30 persen keterlibatan perempuan dalam parlemen masih berarak secara nominal dan belum secara ideal. Sebab boleh saja jumlah itu memaksa perempuan untuk berpolitik tapi sayangnya perempuan terlanjur hidup, mengadopsi, dan menikmati kepemimpinan kultur patriarki. Alhasil suaranya tidak lagi benar-benar merepresentasikan kaumnya melainkan sekedar mengafirmasi budaya patriarki. Namun kita menanti sejauh mana dampak rekonstruktif dari Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG) gagasan 13 anggota perempuan DPRD NTT yang kini sedang berproses.
Adapun belum nampak kebijakan LGBT yang kalau diperhatikan masih berbenturan dengan karakter religius dari masyarakat ketika melihat praktek LGBT sebagai suatu penyimpangan. Sehingga perjuangan kaum ini masih akan dihalangi oleh kelompok hetero yang lebih banyak bertindak sebagai pembuat kebijakan (policy-makers). Perjuangan kaum LGBT dalam negara demokrasi paralel dengan Hak Asasi Manusia.