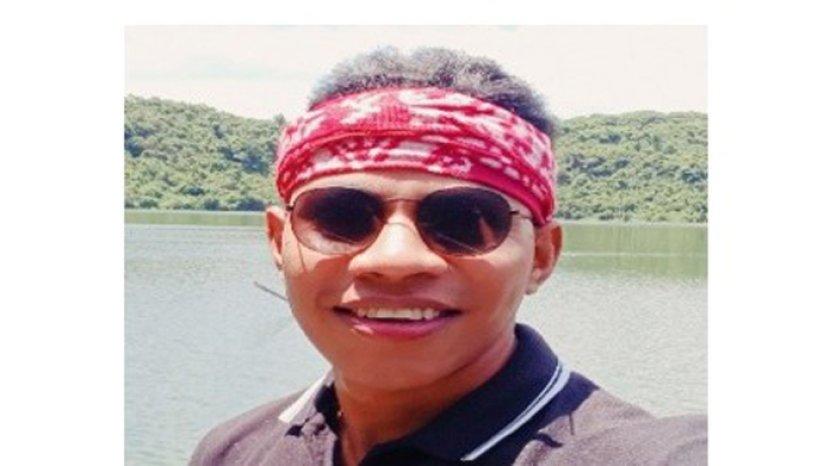Talkshow Pancasila FKUB Provinsi NTT
Nilai-nilai Pancasila dan Trilogi Kerukunan (Bagian 3)
Semua agama yang hidup di Indonesia tidak menghendaki adanya konflik di antara penganutnya, melainkan menekankan kerukunan antara penganutnya.
Nilai-nilai Pancasila dan Trilogi Kerukunan (Bagian 3)
Oleh: Dr. Norbertus Jegalus
(Dosen tetap pada Fakultas Filsafat Agama Unika Widya Mandira Kupang)
Materi yang dipresentasikan dalam acara “Talk Shaw Pancasila”, bersama anggota FKUB Provinsi NTT, utusan komunitas agama, serta tokoh masyarakat, yang diselenggarakan oleh FKUB Provinsi NTT, di Kupang, 24 November 2020.
Proyek Moderasi Beragama
Dari bingkai teologi kerukunan itu kita melihat bahwa semua agama yang hidup di Indonesia tidak menghendaki adanya konflik di antara penganutnya, melainkan menekankan kerukunan antara penganutnya.
Lalu, kalau kemudian terjadi konflik, maka asal-muasalnya tidak dapat dicari pada hakikat dan ajaran agama itu sendiri, tetapi pada penganut-penganutnya yang menyimpang dari perintah dan ajaran agamanya demi mencapai tujuan-tujuan yang tidak luhur yang bertentangan dengan keluhuran agama-agama itu sendiri.
Menghadapi kondisi ini, Menteri Agama, Fachrul Razi, memberi solusi strategis dengan proyek barunya moderasi beragama, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
Apa itu moderasi beragama?
Secara kamus kata moderasi (moderation) berarti sikap sedang, sikap di tengah, sikap tidak berlebihan, sikap tidak ekstrem kiri ataupun kanan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi diartikan sebagai “pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme”.
Dengan demikian moderasi beragama adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang sehingga terhindar dari perilaku ekstrem dan radikal dalam menjalankankan ajaran agama. Tekanan di sini adalah pada para penganut yaitu pada pemahaman dan pelaksanaan setiap penganut agama yang bersifat moderat.
Karena itu, moderasi beragama bukan berarti moderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Tidak ada institusi agama yang mengajarkan kekerasan dan kebencian. Jadi, agama tidak perlu dimoderasi lagi.
Yang perlu dimoderasi adalah orang-orang yang menganut agama itu, karena cara mereka beragama tidak selamanya sejalan dengan ajaran agama. Karena itu proyek strategis ini diberi nama bukan moderasi agama, melainkan moderasi beragama, yaitu moderasi para penganutnya agar tidak jatuh dalam ekstremisme dan radikalisme yang merusak kerukunan beragama, dengan targetnya menyangkut empat bidang sosial-religius berikut ini: (1) komitmen kebangsaan; (2) antikekerasan; (3) tidak antibudaya lokal; dan (4) toleransi.
Kaum agama dan komitmen kebangsaan
Negara Bangsa (nation state) adalah buah dari etika politik modern yang mengajarkan bahwa negara modern yang semuanya majemuk suku dan agama haruslah berdasarkan atas faham kebangsaan, bukan faham suku (etnonasinalisme), juga bukan berdasarkan faham agama (religionasionalisme). Dan sejak tahun 1945 kita bersepakat untuk menganut faham negara bangsa berdasarkan Pancasila, bukan negara agama, juga bukan negara suku.
Di dalam negara bangsa berdasarkan Pancasila itu dijamin bahwa antara cita-cita umum negara dan cita-cita khusus agama-agama tidak ada usaha untuk saling mengeksklusi. Tidak demi eksisnya cita-cita umum, cita-cita khusus setiap golongan harus dilenyapkan. Karena cita-cita umum itu baru sungguh-sungguh eksis kalau ada yang namanya cita-cita khusus dari setiap golongan. Itulah prinsip filsafat ex pluribus unum dari Pancasila.
Itu berarti, setiap kaum agama harus memahami dan menghayati kekhususan dirinya di dalam semangat bersama dari cita-cita umum. Karena itu, kalau kita mau membangun RI sebagai negara bangsa berdasarkan Pancasila, di mana semua golongan bisa krasan dan merasa seperti di rumah sendiri, maka pembangunan negara RI tidak bisa berdasarkan faham suatu golongan saja betapa pun besarnya golongan itu, melainkan berdasarkan pandangan dan cita-cita yang dimiliki semua golongan. Hal ini haruslah menjadi komitmen setiap kaum agama dalam menghayati ajaran agamanya.
Kaum agama dan antikekerasan
Apakah betul bahwa agama yang satu berkonflik dengan agama yang lain berdasarkan ajaran agama? Padahal semua agama melalui pemimpinnya mengatakan bahwa tak satu agama pun yang mengajarkan kebencian, permusuhan apalagi kekerasan dan pembunuhan. Tetapi mengapa ada pertentangan antara kelompok, sampai kepada tindakan kekerasan, yang mengatasnamakan agama mereka masing-masing?
Dalam kasus Ambon, misalnya: Kristen dan Islam sudah lama hidup berdampingan secara damai sebagai Ambon Sarani di satu pihak dan Ambon Salam di pihak lain, tiba-tiba berkonflik. Apakah betul konflik itu dipicu oleh perbedaan dalam cara mereka menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan?
Padahal semua kaum beragama tahu dan percaya bahwa setiap agama besar menginginkan dua hal utama, yaitu keselamatan manusia penganutnya dan kemuliaan yang makin besar bagi Tuhan. Masalah kita terletak di sini, bahwa agama yang menurut hakekatnya berfungsi sebagai sarana dan jalan untuk menyelamatkan manusia dan memuliakan Tuhan kemudian berubah wujud dalam kesadaran penganutnya menjadi tujuan itu sendiri. Dengan demikian, signum berubah menjadi significatum; cara berubah menjadi tujuan.
Hal ini terbukti dalam sikap penganutnya yang membela agamanya dengan mengorbankan keselamatan orang lain. Pembunuhan dan kebencian dilarang oleh agama, tetapi justru pembunuhan dan kebencian dilakukan atas nama agama.
Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi penyimpangan itu? Jawabannya adalah bahwa kita harus merenungkan kembali secara fenomenologis pengalaman keagamaan itu dan mengembalikannya kepada kedudukannya yang asli sesuai dengan tujuan dan tuntutannya yang otentik. Untuk itu dibutuhkan examination of conscience yang lebih teliti dan jujur.
Itu berarti, fanatisme agama harus diuji: Apakah yang dibela di sana adalah keselamatan manusia dan kemuliaan Tuhan, ataukah kemegahan diri sendiri dalam mencari suatu kepuasan dan kebanggaan dengan mengatasnamakan agama?
Kaum agama dan budaya
Tantangan kita saat ini adalah munculnya gerakan puritanisasi agama. Puritanisasi agama adalah usaha untuk membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asaliah agama itu.
Puritanisasi dapat berkembang dari suatu usaha yang wajar dan hakiki bagi setiap agama wahyu, yaitu bahwa umat itu senantiasa kembali ke paham-paham asalnya untuk memastikan apakah mereka masih setia kepada Sabda Allah atau tidak. Setiap agama wahyu tentu harus setia pada wahyu asal, itu jelas kita terima.
Akan tetapi, yang menjadi masalah dalam hal ini adalah bahwa usaha pemurnian agama itu membuat agama itu tercabut dari konteks sosio-kultural manusia penganutnya pada setiap zamannya. Maka walaupun kelompok agama itu setia pada wahyu Allah, namun cara menghayati iman kaum agama terlepas dari nilai-nilai budaya sezaman dan setempat yang semestinya ikut menentukan cara kaum beriman menghayati agamanya.
Kondisi saat ini, di era globalisasi ini, yang bertebaran pelbagai nilai baru, ditanggapi oleh kaum puritan dengan sikap membersihkan semua itu terhadap kehidupan beragama. Maka unsur-unsur baru dari luar, termasuk nilai-nilai budaya setempat, yang sebenarnya bernilai positif bagi manusia dipandang oleh kaum puritan sebagai ancaman terhadap kemurnian agama. Dengan itu, kaum puritan cenderung menjadi fundamentalis, berhadapan dengan nilai-nilai budaya lokal. Perjumpaan antara agama dengan budaya lokal pun menjadi sebuah perjumpaan yang konfliktual dan akhirnya menciptakan kondisi sosial-religius yang tidak harmonis.
Kaum agama dan toleransi
Kaum puritan atau fundamentalis tidak mampu atau tidak rela menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada, lalu mengucilkan diri menjadi kelompok eksklusif. Bahaya lebih jauh adalah bahwa di dalam kelompok yang eksklusif ini selalu ada tendensi kepada intoleransi terhadap segala yang bersifat lain dari identitas mereka.
Di dalam sebuah masyarakat tradisional yang homogen dengan tatanan nilai dan pranata sosial yang diterima umum, segala yang lain dari tradisi sendiri masih dipandang sebagai sesuatu yang menarik. Sedangkan di dalam masyarakat eksklusif segala yang lain dari identitas kelompok dipandang sebagai suatu ancaman dan karena itu menjadi objek kebencian. Maka konflik antarbudaya, konflik antaragama menjadi lebih mudah terjadi justru di era modern daripada pada masyarakat tradisional.
Karena itulah maka yang perlu dibangun dalam kesadaran kaum beragama adalah sikap menerima orang lain, keberadaan agama lain dengan baik, mengakui dan menghormati keberadaan mereka dalam keunikan mereka. Itulah toleransi.
Akan tetapi, untuk bersikap toleran terhadap agama lain tidak diandaikan anggapan dangkal bahwa semua agama sama saja. Bagaimana pun semua agama tidak sama. Justru karena tidak sama itulah maka semua agama harus bersikap toleran. Toleransi hanya ada artinya kalau semua agama itu tidak sama. Toleransi berarti mengakui perbedaan, menghormati seratus persen identitas masing-masing agama. Toleransi tidak menuntut agar kaum beragama merelativisasi ajaran agamanya.
Penutup
Pancasila adalah hasil kompromi politik pendiri negara RI tahun 1945, yaitu sebuah titik temu antara kaum agama yang ingin mendirikan Negara Islam dan kaum kebangsaan yang ingin mendirikan Negara Bangsa.
Akan tetapi, kita juga harus tetap bersikap realistis bahwa meski kita telah memiliki Pancasila sebagai basis bersama dalam bernegara, namun masing-masing pihak masih mempunyai harapan dan cita-cita khusus mereka sesuai dengan ajaran atau paham kelompok seperti ajaran agama.
Tetapi karena kita sudah mendasarkan negara ini pada paham negara bangsa (nasionalisme modern), bukan negara agama (religionasionalisme) seperti diperjuangkan oleh golongan Islam sejak 1945, juga bukan negara suku (etnonasionalisme) seperti diperjuangkan oleh gerakan daerahisme RMS (Republik Maluku Selatan) dan Gerakan Paupua Mereka, maka bagaimanapun cita-cita khusus masing-masing komponen masyarakat, entah itu agama atau suku, justru karena kekhususannya itu, tidak bisa menjadi dasar negara.
Akhirnya, kita semua harus mencatat dalam kesadaran kita sebagai orang beragama bahwa ada identifikasi total antara Indonesia dan Pancasila. Menyebut Indonesia berarti menyebut Pancasila dan menyebut Pancasila tidak lain berarti memaksudkan Indonesia. Itulah karakter politik yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1945.
Itu artinya sama kalau kita mengatakan: Negara Indonesia adalah Negara Pancasila; atau Negara Pancasila adalah Negara Indonesia. Negara Pancasila bubar berarti Negara Indonesia bubar. Dan kata-kata ini harus menjadi kenyataan dalam hidup setiap kaum beragama di Indonesia. (selesai)
Baca juga: Nilai-nilai Pancasila dan Trilogi Kerukunan (Bagian 1)
Baca juga: Nilai-nilai Pancasila dan Trilogi Kerukunan (Bagian 2)
NONTON JUGA VIDEO TALKSHOW PANCASILA BERIKUT INI: