Opini
Opini: Menakar Proyek Geotermal Dari Aspek Keadilan Sosial dan Ekologis
Yang dibutuhkan adalah keseimbangan keduanya melalui tata kelola energi yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan
Oleh : Joni K Tiran, SH
Konsultan Hukum dan Pemerhati Isu Lingkungan dengan fokus pada keadilan sosial, ekologis, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
POS-KUPANG.COM - Sangat menarik untuk menyimak Siaran Pers dari Team Advokasi Geothermal Keuskupan Agung Ende tertanggal 18 Agustus 2025 lalu.
Dikutip dari Harian Pos Kupang, Ketua Team, RD Reginaldus Piperno dalam siaran pers tersebut menyampaikan beberapa hal yang merupakan catatan kritis atas hasil uji petik Tim Satgas bentukan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena menyangkut keberlanjutan proyek geotermal di Pulau Flores.
Catatan itu antara lain menyangkut pelaksanaan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang seyogianyalah menjadi pilar utama sebelum pelaksanaan proyek geotermal tersebut.
Kehadiran siaran pers ini menunjukkan bahwa polemik geotermal bukan sekadar persoalan teknis energi, melainkan berkaitan langsung dengan hak konstitusional masyarakat, legitimasi sosial, serta kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan berkelanjutan.
Bahwa Free, Prior and Informed Consent atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) adalah hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk menerima atau menolak setiap proyek yang dapat berdampak pada tanah dan lingkungan serta mata pencaharian mereka.
Prinsip tersebut mencakup tiga elemen utama, yaitu pertama, bahwa masyarakat harus menerima informasi yang lengkap tentang proyek tersebut terutama menyangkut dampaknya terhadap lingkungan.
Selanjutnya yang kedua, masyarakat dalam memberikan persetujuan, haruslah dengan sukarela, tanpa paksaan ataupun tekanan dan intimidasi dari siapapun.
Ketiga, persetujuan dari masyarakat haruslah didapatkan sebelum sebuah proyek dimulai yang tentu saja guna mencegah konflik saat pelaksanaan proyek tersebut.
Dengan kata lain, FPIC tidak sekadar formalitas administrasi, tetapi mekanisme partisipasi substantif yang menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus meminimalisir potensi kriminalisasi masyarakat yang menolak.
Sudahkah FPIC dilaksanakan dengan baik dan benar? Sebuah pertanyaan besar yang muncul di kalangan publik saat ini adalah, sudahkah FPIC dilaksanakan dengan baik dan benar?
Jawabannya tentu saja adalah : Tidak, sebagaimana termuat dalam poin (2) siaran pers tersebut yaitu "bahwa sejak awal masyarakat tidak diberi ruang untuk menentukan secara bebas sikapnya terhadap proyek geotermal tersebut."
Penulis cenderung sependapat oleh karena jika FPIC telah dijalankan dengan baik dan benar, tidak mungkin akan ada penolakan seperti saat ini yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.
Kondisi ini menandakan adanya defisit demokrasi dalam proses pengambilan keputusan.
Alih-alih menjadi subjek pembangunan, masyarakat ditempatkan sekadar sebagai objek kebijakan.
Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang menerbitkan izin pelaksanaan proyek tersebut?
Secara hukum, seharusnyalah pemerintah membatalkan atau minimal menunda pelaksanaan proyek tersebut sampai dengan adanya pelaksanaan FPIC yang baik dan benar.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya harus mematuhi United Nation Declaration on the Rights of Indigenous of Peoples (UNDRIP), yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007.
Deklarasi ini menetapkan hak-hak kolektif dan individu masyarakat adat di seluruh dunia dan menjadi standar untuk menjamin kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan mereka.
Mengabaikan FPIC sama artinya dengan mereduksi kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan identitas kultural mereka, sehingga proyek energi yang sejatinya untuk kepentingan publik justru berpotensi menjadi instrumen perampasan hak.
Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, telah mengatur secara jelas bahwa untuk soal tanah, pemegang izin proyek harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan pemegang hak tanah, baik melalui jual beli, hibah ataupun bentuk ganti rugi yang layak dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tanpa ada tekanan, paksaan maupun intimidasi dari siapapun.
Artinya, hukum nasional sudah menyediakan kerangka normatif yang tegas.
Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi deviasi karena kuatnya kepentingan modal dan lemahnya komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum.
Hal ini sangat penting, karena jika pemerintah tetap memaksakan dilanjutkannya proyek tersebut tanpa memperhatikan pelaksanaan FPIP yang baik dan benar, maka bukan hanya prinsip-prinsip dalam Deklarasi PBB tersebut saja yang dilanggar akan tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat dan juga tentu saja pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Panas Bumi.
Dengan demikian, proyek geotermal Flores dapat menjadi preseden buruk yang memperlihatkan inkonsistensi negara antara komitmen konstitusional, instrument hukum nasional, dan standar internasional yang telah diratifikasi.
Akhirnya, kita semua tentu berharap agar pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT dapat bersikap adil dan bijaksana menyikapi hal tersebut, demi bukan hanya terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat, tetapi juga demi keadilan ekologis dan lingkungan yang wajib kita wariskan kepada generasi mendatang.
Keadilan sosial tanpa keadilan ekologis hanya akan melahirkan pembangunan semu, sedangkan keadilan ekologis tanpa keadilan sosial berisiko mengorbankan manusia atas nama alam.
Yang dibutuhkan adalah keseimbangan keduanya melalui tata kelola energi yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Semoga! (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
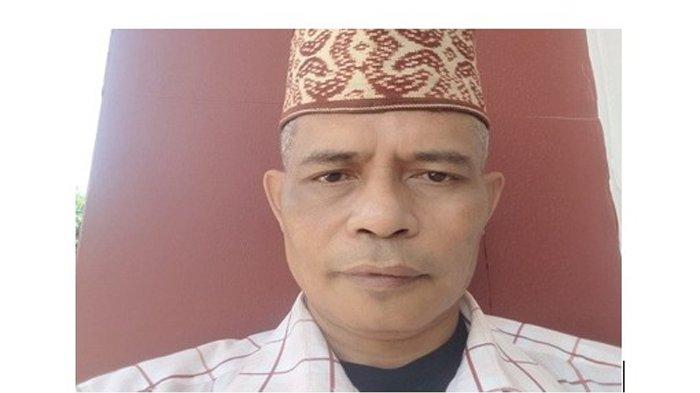




















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.