Opini
Opini: Ketika Anak Prajurit Gugur di Tangan Sesama
Kekerasan, meski dibungkus dengan dalih pembinaan karakter, tetap meninggalkan jejak traumatis yang panjang.
Oleh: Yoseph Yoneta Motong Wuwur
Warga Lembata, Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM- Dalam dunia militer, seragam tak hanya simbol tempur, tetapi lambang kehormatan, disiplin, dan solidaritas.
Namun, ketika seorang anak prajurit tewas dianiaya seniornya, makna simbolik itu tercoreng.
Seragam yang seharusnya melindungi justru menjadi saksi bisu atas kekerasan sistemik yang mengakar, memunculkan pertanyaan besar: apakah warisan militansi tak cukup kuat untuk menjaga darah sendiri?
Asumsi bahwa anak tentara siap menghadapi kerasnya dunia militer adalah keliru danberbahaya.
Baca juga: Sebelum Hembuskan Nafas Terakhir, Prada Lucky Namo: Saya Rindu Mama, Mama Datang Nagekeo Ko
Kekerasan, meski dibungkus dengan dalih pembinaan karakter, tetap meninggalkan jejak traumatis yang panjang.
Ketika rasa sakit dianggap bagian wajar dari proses didikan, maka kekerasan berubah dari metode menjadi budaya.
Dalam kondisi ini, siapa pun bisa menjadi korban, bahkan mereka yang berasal dari jantung institusi itu sendiri.
Tragedi ini bukan hanya soal pelanggaran individu, tapi cerminan kegagalan sistemik. Kita tak bisa lagi menormalisasi kekerasan sebagai tradisi atau warisan.
Saat nyawa melayang dalam proses pendidikan, itu menandakan sistem telah gagal menjalankan fungsi perlindungan dan pembinaan. Dan dalam setiap kegagalan sistem, ada tanggung jawab kolektif yang tak boleh diabaikan.
Kekerasan dalam Barak
Budaya senioritas dalam dunia militer sering kali menjadi dalih pembenaran atas praktik kekerasan fisik maupun psikis.
Namun, ketika praktik itu menelan korban, kita harus bersikap jujur: ini bukan lagi pembinaan, melainkan pengkhianatan terhadap nilai luhur militerisme itu sendiri. Yang seharusnya menjadi tempat membentuk patriot, justru berubah menjadi arena pemakaman mimpi.
Tindakan kekerasan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia dilanggengkan oleh sistem, dibenarkan oleh budaya, dan didiamkan oleh ketakutan.
Senior yang menganiaya bukan hanya pelaku, tapi juga produk dari lingkungan yang memupuk dominasi atas nama "pembentukan karakter".
Jika kekerasan adalah warisan, maka militer sedang mewariskan luka yang akan membusuk hingga generasi mendatang.
Dalam analisis psikologis, kekerasan tidak menciptakan ketangguhan, tetapi memperpanjang siklus dendam dan trauma.
Individu yang pernah disakiti sering kali menjadi pelaku di kemudian hari, meneruskan pola beracun itu pada juniornya. Maka, jika hari ini satu nyawa melayang, kita tidak bisa hanya menghukum individu. Sistem pun harus diadili.
Institusi yang bangga dengan kedisiplinan dan kehormatannya seharusnya menjadi garda depan melawan kekerasan.
Tapi bila kekerasan justru dianggap "bagian dari proses", maka institusi itu telah mengkhianati misinya.
Barak bukan tempat penebusan dendam, tetapi rumah lahirnya para penjaga bangsa. Jika rumah itu dipenuhi kekerasan, maka bangsa ini sedang membiarkan luka menjadi warisan.
Mentalitas Kekuasaan di Balik Seragam
Seragam sering kali memberi ilusi kekuasaan. Dalam lingkungan militer, mereka yang lebih senior kerap merasa memiliki hak untuk
"mendidik" dengan cara yang keras.
Tapi kekuasaan tanpa kontrol akan berubah menjadi kezaliman. Ketika rasa berkuasa tak dibarengi empati, maka lahirlah para penindas berbaju kehormatan.
Kematian seorang anak tentara di tangan seniornya menunjukkan bahwa ada yang salah dengan struktur kekuasaan dalam pendidikan militer. Para senior bukan lagi pembimbing,tapi menjadi predator.
Mereka menikmati kekuasaan sesaat, tanpa peduli dampak jangka panjang dari setiap tamparan, tendangan, atau cacian yang mereka lemparkan.
Psikologi kekuasaan menjelaskan bagaimana manusia cenderung menyalahgunakan wewenang saat tak ada kontrol atau konsekuensi.
Ketika sistem tidak memberi sanksi tegas atas kekerasan, maka perilaku itu akan dianggap wajar. Para pelaku pun merasa aman, bahkan bangga, karena merasa menjalankan "tugas".
Yang dibutuhkan bukan hanya pelatihan fisik, tapi pelatihan karakter yang menekankan empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Militer harus mencetak pemimpin, bukan algojo.
Jika hari ini satu anak gugur karena arogansi seragam, maka sudah saatnya kita mengevaluasi kembali: apakah seragam masih pantas disebut kehormatan?
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaan besar yang muncul dari tragedi ini adalah: siapa yang bersalah? Senior pelaku kekerasan tentu harus dihukum.
Tapi apakah cukup hanya berhenti di situ? Dalam system pendidikan, setiap peristiwa tak berdiri sendiri.
Selalu ada pembiaran, ada kelalaian, ada struktur yang longgar atau bahkan mendukung terjadinya kekerasan.
Komandan, pengawas, pelatih, bahkan institusi sebagai entitas hukum, semuanya harus masuk dalam lingkaran evaluasi.
Jika pengawasan lemah, maka mereka turut menyumbang kematian itu. Jika budaya diam masih kuat, maka banyak orang dewasa sebenarnya menjadi pengecut yang membiarkan anak-anak menjadi korban.
Hukum harus berjalan. Tapi lebih dari itu, harus ada kesadaran moral dan reformasi kultural.
Tidak cukup menghukum pelaku langsung jika akar kekerasan masih dibiarkan tumbuh subur.
Rantai komando yang diam adalah bagian dari masalah. Institusi yang menutup-nutupi fakta adalah pengkhianat kebenaran.
Ketika satu anak meninggal di barak, itu bukan sekadar “kecelakaan” atau “peristiwa tragis”.
Itu adalah indikator kegagalan sistemik. Maka kita perlu membongkar semua rantai yang terkait: dari siapa yang tahu tapi diam, siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan, hingga siapa yang membuat sistem ini tetap berputar.
Transparansi menjadi kata kunci. Proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan saja.
Evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum pelatihan, sistem senioritas, dan metode pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak eksternal yang independen.
Ini bukan hanya tentang keadilan bagi korban, tapi tentang penyelamatan generasi berikutnya.
Karena jika hari ini kita gagal menjawab pertanyaan "siapa yang bertanggung jawab?", maka besok akan lahir lebih banyak korban. Dan ketika kematian menjadi hal biasa, kita bukan lagi bangsa yang merdeka, tapi bangsa yang menormalisasi kekejaman atas nama disiplin. Dalam diam kita bersalah, dalam pembiaran kita bersekongkol.
Saatnya Militer Berubah
Duka memang dalam, tapi dari luka selalu ada peluang untuk pembenahan. Tragedi ini, meski menyakitkan, harus menjadi titik balik.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari kehilangan. Dan militer yang kuat bukan yang menutupi boroknya, melainkan yang berani menyembuhkannya dengan reformasi sejati.
Sudah saatnya militer Indonesia membuka lembaran baru—sebuah paradigma pembinaan yang mengedepankan martabat manusia. Kekuatan sejati bukan lahir dari ketakutan, tapi dari kepemimpinan yang menginspirasi.
Keteladanan yang lahir dari empati dan profesionalisme akan jauh lebih kuat daripada kepatuhan karena intimidasi.
Bila kita ingin mencetak generasi prajurit yang tangguh dan berintegritas, maka metode pembinaan harus ditata ulang.
Bangunlah sistem yang menjunjung nilai kemanusiaan, yang tidak hanya mencetak fisik yang kuat, tapi juga hati yang bijak.
Karena musuh terbesar prajurit bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam dirinya sendiri: rasa superior palsu yang mematikan.
Mari jadikan tragedi ini bukan sekadar berita duka, tapi cambuk untuk bangkit.
Sebab setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari luka yang tak tertahankan. Jangan biarkan anak-anak bangsa gugur di tangan sesama.
Sudah cukup darah yang tumpah bukan di medan perang, melainkan di ruang didik yang seharusnya suci. Saatnya militer berubah—demi kehormatan sejati. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News















![[FULL] Pakar: Indonesia Terlibat Israel Caplok Gaza, Deal-dealan dengan Trump Obati 2.000 Korban](https://img.youtube.com/vi/5sKhHBVJjUg/mqdefault.jpg)

















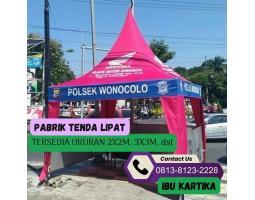
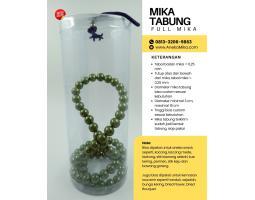







Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.