Opini
Opini: Membangun Kebijakan Publik Berkeadilan
Namun di Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, narasi indah itu retak di hadapan kenyataan sosial.
Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Dosen Pada Program Doktor Ilmu Administrasi FISIP Undana Kupang, Koordinator Program Studi Magister Studi Pembangunan Undana, Alumni Program Doktor Ilmu Administrasi Publik FISIPOL UGM
POS-KUPANG.COM - Di tengah ancaman krisis iklim global, dunia seakan berlomba mengejar transisi menuju energi hijau.
Indonesia pun berkomitmen menggenjot bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025. Geothermal, sebagai sumber energi rendah karbon, menjadi tulang punggung strategi ini.
Namun di Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, narasi indah itu retak di hadapan kenyataan sosial.
Sejak 2023, ribuan warga adat Poco Leok menolak proyek geothermal yang digarap PT Geo Dipa Energi.
Bagi mereka, ini bukan sekadar proyek energi, melainkan ancaman bagi tanah leluhur, situs sakral, dan harmoni ekologis yang diwariskan lintas generasi.
Baca juga: Opini: Dari Taupo ke Poco Leok, Menimbang Kembali Co-Management dalam Proyek Geotermal Flores
Bagaimana mungkin proyek yang dijanjikan sebagai energi bersih justru memicu konflik?
Di sinilah kepala daerah ditantang untuk memperkaya cara pandang kebijakan publik.
Konteks ini menuntut pemahaman yang melampaui kalkulasi teknokratik, yakni membaca konflik geothermal lewat dialektika antara perspektif kiri Political Ecology dan Public Policy Instrumentalism yang lebih berhaluan rasional.
Pembangunan sebagai Proyek Kuasa
Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Robbins (2012), Political Ecology mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak pernah steril dari politik.
Di balik jargon teknokratik dan retorika keberlanjutan, pembangunan seringkali menjadi alat bagi aktor dominan untuk mereproduksi kekuasaan.
Konsep green grabbing yang dikembangkan oleh James Fairhead, Melissa Leach, dan Ian Scoones (2012) memperjelas fenomena ini: lahan, hutan, dan sumber daya komunitas sering diambil alih atas nama konservasi atau transisi energi hijau.
"What appears green on the surface," tulis mereka, "often masks dispossession and exclusion underneath."
Lebih tajam lagi, David Harvey (2003) dalam konsep accumulation by dispossession menyingkap logika kapitalisme kontemporer yang terus merampas hak-hak komunitas demi akumulasi modal.
Dalam konteks Poco Leok, lahan adat yang selama berabad-abad menjadi bagian dari ontologi hidup masyarakat, dalam logika pembangunan diperlakukan sebagai sekadar resource.
Penolakan warga Poco Leok pun berakar pada perasaan kehilangan kendali atas ruang hidup.
"Kami tidak anti pembangunan," ujar perwakilan masyarakat dalam sebuah forum publik. "Tapi kami menolak pembangunan yang mengusir kami dari tanah leluhur."
Ironisnya, proses konsultasi publik yang mestinya menjadi ruang deliberatif kerap dijalankan sebagai formalitas.
Jurgen Habermas (1996) dalam Between Facts and Norms mengingatkan, demokrasi deliberatif mensyaratkan komunikasi yang bebas dari dominasi.
Ketika negara atau korporasi memaksakan narasi tunggal, dialog sejati menjadi mustahil.
Rasionalitas Instrumentalis: Efisiensi sebagai Kompas
Di sisi lain, Public Policy Instrumentalism menggarisbawahi bahwa kebijakan publik harus dirancang sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan kolektif.
Dalam perspektif ini, negara punya kewajiban menggenjot transisi energi demi kepentingan nasional dan global.
Sebagaimana diuraikan oleh Michael Howlett (2009), kebijakan dipandang sebagai policy instrument, sekumpulan alat yang digunakan untuk memengaruhi perilaku aktor dan mencapai hasil kebijakan.
Dalam kerangka ini, geothermal adalah instrumen yang rasional: mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan energi, dan membuka peluang ekonomi daerah.
Bagi kepala daerah, pendekatan ini memegang pesona kuat. Di tengah tekanan target nasional, aliran investasi, dan insentif fiskal, menggenjot proyek energi terbarukan tampak sebagai pilihan rasional.
Risiko sosial dianggap dapat dikelola melalui compensation schemes, benefit sharing, atau corporate social responsibility.
Namun di sinilah Habermas kembali memperingatkan: rasionalitas instrumental cenderung mengabaikan dimensi moral dan nilai.
Jika kebijakan direduksi menjadi kalkulasi efisiensi, maka aspek identitas, spiritualitas, dan keadilan prosedural masyarakat akan terpinggirkan.
Nancy Fraser (2005) dalam Reframing Justice menegaskan pentingnya recognition, redistribution, dan representation dalam mewujudkan keadilan sosial.
Dalam kasus Poco Leok, pengakuan atas identitas masyarakat adat serta partisipasi sejati mereka dalam pengambilan keputusan adalah prasyarat mutlak bagi legitimasi kebijakan.
Merajut Dialektika: Jalan Tengah yang Lebih Adil
Konflik geothermal Poco Leok mengajarkan bahwa kebijakan publik tak bisa dirumuskan dengan lensa tunggal.
Political Ecology mengingatkan kepala daerah bahwa pembangunan adalah proses politis yang sarat relasi kuasa.
Public Policy Instrumentalism menawarkan pendekatan rasional untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan.
Tantangan kepala daerah adalah merajut dialektika keduanya. Beberapa prinsip dapat menjadi pegangan: Pertama, membangun keadilan prosedural yang kuat.
Dalam konteks geothermal Poco Leok, penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Bebas, Didahului dengan Informasi Lengkap, dan Tanpa Paksaan menjadi kunci keadilan prosedural.
Proses ini bukan sekadar ritual sosialisasi atau pengumpulan tanda tangan, melainkan mekanisme deliberatif yang sungguh-sungguh menghormati hak masyarakat adat untuk menerima atau menolak proyek yang berpengaruh pada ruang hidup mereka.
Habermas memberi kita etika diskursus: dialog harus berlangsung dalam situasi komunikasi yang bebas, setara, dan terbuka.
Kedua, memperkuat governance kolaboratif. Kepala daerah bisa memfasilitasi ruang deliberasi multipihak yang otentik, di mana masyarakat adat bukan sekadar pendengar, melainkan co-producer kebijakan.
Ketiga, merumuskan model benefit sharing yang berkeadilan dan partisipatif.
Sebagaimana ditunjukkan oleh studi-studi Political Ecology, skema kompensasi moneter semata tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah pengakuan dan penguatan kedaulatan masyarakat atas ruang hidup mereka.
Keempat, mendorong kepala daerah untuk menjadi mediator etis, bukan sekadar fasilitator investasi.
Antonio Gramsci mengingatkan bahwa peran intelektual organik adalah membangun kesadaran kritis.
Dalam konteks ini, kepala daerah mesti menjadi aktor yang mampu menjembatani rasionalitas pembangunan dengan aspirasi dan hak-hak komunitas.
Menuju Wawasan Kebijakan yang Lebih Berkelas
Konflik geothermal Poco Leok adalah cermin wicked problems di era transisi energi. Ia menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah arena kontestasi makna dan kuasa.
Bagi kepala daerah, memperkaya wawasan kebijakan berarti berani membaca kebijakan dalam dialektika antara Political Ecology dan Public Policy Instrumentalism.
Tanpa itu, pembangunan energi yang adil dan berkelanjutan hanya akan menjadi jargon kosong.
Seperti ditulis David Harvey: “The freedom to make and remake our cities and ourselves is one of the most precious yet most neglected of our human rights.”
Demikian pula, kebijakan energi seharusnya tidak hanya memajukan angka dalam bauran energi, tetapi juga memajukan martabat dan kedaulatan seluruh warga. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News


















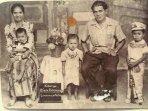
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.