Opini
Opini: Posisi Agama dalam Ruang Publik
Agama tidak lagi sibuk konflik doktrin teologis, sesat dan benar, surga dan neraka, tetapi saling merangkul menjalankan misi kemanusiaan.
Oleh: Fransiskus Momang
Anggota Forum Pemuda NTT Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Berdomisili di Kutai Timur.
POS-KUPANG.COM - Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat religius. Pengakuan akan religiositas ini dimuat dalam sila pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Harapannya bahwa fondasi ini, agama memiliki kontribusi transformasi etis di ruang publik.
Istilah ruang publik yang dalam bahasa Jerman “Öffentlichkeit” ini, merujuk istilah yang dipakai Jurgen Habermas, filsuf asal Jerman, generasi kedua mazhab Frankfurt, yakni keadaan yang bisa diakses semua orang.
Keadaan yang bisa diakses semua orang ialah negara atau komunitas politis. Patologis konflik agama yang rentan mengorbankan sesama dan berdampak krisis kemanusiaan merupakan dasar keprihatinan saya.
Bahwasannya di balik peliknya persoalaan agama, ada tugas etis agama yang mesti diperjuangkan bersama dalam ruang publik yakni membela martabat luhur manusia.
Agama tidak lagi sibuk konflik doktrin teologis, sesat dan benar, surga dan neraka, tetapi saling merangkul menjalankan misi kemanusiaan.
Agama tidak sekadar berkotemplatif melulu, tetapi terlibat dalam menyelesaikan persoalaan bangsa.
Sengkarut Agama
Beberapa potret sengkarut agama menjadi stimulus untuk melihat lagi posisi agama dalam ruang publik.
Persoalaan-persoalaan itu ialah bom Bali, konflik Poso dan Ambon, pembubaran mahasiswa yang sedang melaksanakan doa rosario, dan berita yang saling melecehkan agama yang beredar di media sosial sekarang ini dan pelbagai konflik agama lainnya.
Sengkarut agama tersebut sudah berdampak pada krisis kemanusiaan. Tidak sedikit orang yang menjadi korban, kehilangan tempat tinggal, kelaparan sampai kehilangan nyawa.
Selain itu, konflik agama ini berdampak pada krisis psikologis umat beragama yakni menjadi takut, cemas dan enggan mengekspresiakan hidup beragama di ruang publik. Tentu kita sepakat, ini fakta dan sejarah kelam bangsa Indonesia.
Membela martabat manusia
Posisi etis agama dalam ruang publik adalah membela martabat manusia. Konsep martabat manusia merupakan basis etis paham hak asasi manusia yang bersifat universal.
Sifat universalitas ini memungkinkan membela martabat manusia menjadi tindakan etis setiap suku, budaya, ras dan agama.
Bahwa setiap agama dipanggil untuk membela martabat manusia yang dilecehkan oleh penganut agama itu sendiri, seperti kaum fundamentalisme, intoleran maupun struktur ekonomi, politik, sosial dan kulutral yang tidak adil serta pembangunan main stream.
Agama sebagai bagian dari entitas bangsa dituntut tidak sekadar mempertajamkan kesalehan ritualistik, tetapi lebih dari itu kesalehan sosial yakni nilai moral diungkapkan dalam tindakan praksis.
Namun dalam menerjemahkan nilai moral setiap agama dan diterima oleh semua warga
negara instrumen yang digunakan ialah bahasa dan konsep yang bersifat publik.
Bahasa dan konsep publik ini untuk mencegah setiap agama berkonflik, masing-masing mengklaim ajaran agamanya paling baik untuk disumbangkan dalam menata hidup bersama yang lebih baik.
Oleh karena itu mesti ada jembatan untuk menemukan suatu orientasi tunggal dalam mencapai konsensus etis bersama.
Berhadapan dengan persoalaan ini, saya sepakat dengan gagasan Jhon Rawls dan Abdullahi A.an’Naim, pemikir Islam liberal. Jhon Rawls memproposalkan gagasan tentang nalar publik (public reason).
Publik reason berkenaan dengan konsepsi politik yang hanya berlaku di forum publik atau negara.
Meskipun doktrin teologis setiap agama secara substabsial tidak diterima di ruang publik, tetapi bisa diterima jika melalui argumen politik dalam bentuk nalar publik.
Sebab subjek utama dari nalar publik adalah kebaikan publik, dan isi dari nalar publik adalah keadilan (justice).
Jadi, dalam kerangkan pemikiran Jhon Rawls untuk menerjemahkan ajaran moral di ruang publik setiap agama menggunakan bahasa dan konsep publik, seperti keadilan, solidaritas, subsidaritas, kesetaraan dan bonnum commune.
Ini adalah konsep nalar publik yang berisi konsepsi politik yang berlaku umum di negara.
Rawls di sini mau mengatakan, semua agama terlibat dalam diskursus persoalaan publik, khususnya menjaga martabat manusia agar tidak diabaikan apalagi oleh keangkuhan iman yang dangkal.
Demikian halnya Abdullahi A.an’Naim menganjurkan civic reason-nalar sivik. Civic reason adalah bahasa bersama dalam dialog setiap agama untuk mencapai konsensus. Konsensus itu berkaitan dengan kebijakan publik.
Menurut Abdullahi, agama bisa terlibat dalam ruang publik asalkan dalam terang kewarganegaraan yang beragam bukan pemaksaan atas doktrin-doktrin setiap agama.
Terkait civic reason, ia batasi dalam tiga aspek, pertama nalar sivik berkaitan dengan konstitusional, kedua, nalar sivik berkaitan dengan HAM, ketiga, nalar sivik berkaitan dengan kewarganegaraan setara. (Feliks Baghi, editor, Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi).
Jadi, public reason dan civic reason adalah jembatan yang memungkinkan agama bisa terlibat dalam diskurus persoalan publik. Apalagi sekarang ini Indonesia dalam masa darurat.
Persoalaan semakin menumpuk mulai dari korupsi, demokrasi, keadilan, konflik agama sampai pada pelanggaran hak asasi manusia.
Persoalaan-persoalaan seperti ini agama butuh terlibat. Keterlibatan agama ialah dengan berkerjasama menyuarakan kebenaran dan menegakan keadilan publik.
Konteks NTT
Provinsi NTT merupakan wilayah target utama pembangunan di pelbagai sektor sejak era pemerintahan Jokowi. Pembangunan ini dengan alasan untuk mengentaskan kemiskinan.
Tentu sebagai warga NTT, ini angin segar, agar taraf hidup warga NTT sama seperti wilyah lain di Indonesia yang dikategori sudah maju.
Namun, harapan itu pupus di tengah jalan ketika pembanguan itu dalam praktiknya pemanfaatannya bukan untuk warga NTT melainkan untuk para penguasa dan investor.
Sering terjadi adanya ketidakadilan dan pemiskinan sistematik serta mengabaikan HAM, seperti pembangunan pariwisata Labuan Bajo yang membuat masyarakat merasa terasing dan ruang hidup terancam.
Selain itu, baru baru ini pada tanggal 2 Oktober 2024 ada dugaan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Polri dan TNI di Poco Leok, Kabupaten Manggarai dalam kasus geotermal.
Ada tindakan represif aparat keamanaan kepada warga Poco Leok dan satu jurnalis pimpinan media Floresa.co, ditangkap saat peliputan bersama dengan tiga warga Poco Leok.
Penangkapan ini lantaran warga Poco Leok menolak keras geotermal karena dinilai mengancam ruang hidup mereka.
Penangkapan jurnalis media Floresa.co, Herry Kabut dan tindakan represif terhadap warga Poco Leok adalah bentuk pelanggaran HAM.
Justru pelaku pelanggaran HAM ini ialah negara. Hal ini benarlah yang dikatakan Karl Marx, negara adalah perpanjangan tangan penguasa.
Persoalaan-persoalaan seperti ini, dibutuhkan kerjasama antaragama demi misi kemanusiaan.
NTT adalah kota kurva toleransinya tinggi. Sering adakan dialog antar agama. Namun, dialog antargama ini hanya sebatas saling keterbukaan doktrin teologis, tetapi mesti ada dialog transformatif yakni dialog kemanusiaan universal.
Selain itu, lembaga-lembaga advokasi setiap agama dikerahkan dan mesti turun gunung menyelesaikan persoalaan ini dengan basis martabat luhur manusia.
Tentu yang harus menjadi pioner aksi misi kemanusiaan ini ialah pemuka pada setiap agama. (*)















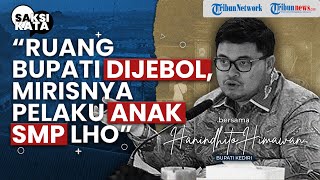



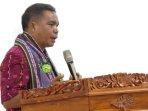

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.