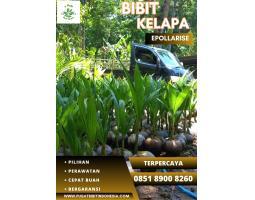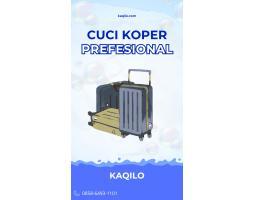Inspirasi Kartini: Pena yang Bermata Tajam, Inilah Maksudnya
Para pelajar putri di sekolah-sekolah, pegawai, penyiar dan pekerja lainnya berlomba-lomba tampil elegan dalam
Oleh: Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum
Ketua LPPM-STKIP Santu Paulus Ruteng
POS KUPANG.COM - Salah satu tradisi yang lazim dalam peringatan Hari Kartini, setiap tanggal 21 April, adalah perempuan berdandan cantik, mengenakan kebaya dan konde.
Para pelajar putri di sekolah-sekolah, pegawai, penyiar dan pekerja lainnya berlomba-lomba tampil elegan dalam balutan pakaian tradisional dan tata rambut yang dibuat mirip dengan foto profil Kartini. Kebiasaan ini berakar dalam potret yang digambarkan oleh pemerintah Orde Baru mengenai Kartini sebagai ibu. Dia adalah ibu yang ideal dan sejati.
Potret sebagai ibu tentu bukan suatu masalah dan bukan pula suatu yang negatif. Hanya saja, diskursus mengenai ibu dalam era Soeharto mempunyai warna yang cenderung domestik saja; seorang perempuan yang mengurus rumah tangga, setia mendukung suami, santun dan tunduk pada adat dan aturan keluarga, seorang yang manis dan cantik memainkan peran internal. Kebaya, konde, cara berdandan dan duduk yang sopan dan anggun menjadi simbol penting. Sekali lagi ini bukan peran jelek.
Hanya saja, gambaran ini kurang pas dan berbeda dengan jiwa dan spirit R.A. Kartini yang sebenarnya. Kartini menjadi dikenal bukan karena peran internal melainkan intelektual; bukan tugas domestik melainkan kritis dan futuristik. Keanggunan Kartini bukan pada kecantikannya, bukan soal dandanannya, bukan aspek feminimnya. Ia diakui dunia karena kata-katanya, karena suratnya, karena tulisannya dan pemikirannya.
Kartini lahir tahun 1879 dari seorang ayah turunan ningrat dan ibu warga biasa. Ketika ayahnya hendak diangkat sebagai bupati, status istri dari ibu Kartini menjadi suatu masalah. Adalah tak pantas bagi seorang bupati untuk beristrikan perempuan dari kalangan biasa. Maka sesuai dengan adat-tradisi, ayah Kartini diharuskan menikah lagi dengan perempuan ningrat. Dengan demikian secara publik ia memiliki istri utama dari kalangan terhormat. Kartini menyaksikan pergulatan ibunya di bawah tradisi Jawa.
Kartini harus hidup di bawah aturan adat yang membelenggu. Relasi perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang, ketimpangan perlakuan antara yang ningrat dengan rakyat jelata, dan antara yang tua/senior dengan yang muda. Kartini memang menikmati keistimewaan sebagai anak bupati, ia mendapat kesempatan untuk bersekolah di Europese Lagere School (ELS), sekolah bagi orang Belanda.
Namun ia harus menerima kenyataan bahwa setelah umur 12 tahun ia harus berhenti sekolah. Padahal ia sangat ingin sekolah lanjut. Ia dipingit dan berdiam di dalam rumah saja sampai ia akan dinikahkan dengan suami yang dijodohkan baginya. Di usianya yang ke-24, ia dipaksa menikah dengan Bupati Rembang sebagai istri ke empat. Ia meninggal dunia, empat hari setelah kelahiran putranya yang pertama, ketika usianya baru 25 tahun.
Di masanya, Kartini perempuan biasa dan sederhana. Ia bukan aktivis yang bergerak bebas di ruang publik. Karena kemurahan hati suaminya, ia diizinkan mengumpulkan beberapa perempuan untuk belajar bersama di salah satu sudut kompleks rumahnya. Itupun ia tidak sendirian, ia dibantu dua adiknya mengajar perempuan di desanya. Ia juga mengajar hanya sekitar satu tahun saja. Tidak ada yang mengenang Kartini di desanya.
Kematiannya ditanggapi biasa-biasa saja. Kehidupannya dianggap sama dengan kebanyakan orang lainnya.
Lantas apa yang istimewa dari Kartini? Perempuan desa, sederhana, mengalami masa dipingit, menjadi istri keempat, dan menjalani hidup dalam budaya patriarkal dengan kungkungan dan belenggu adat ini adalah seorang visioner dan intelektual. Kehidupan domestiknya tidak menghalangi pemikirannya yang brilian.
Bahkan, justru keadaan masyarakat dan kehidupan sosial sekitarnya menjadi lokus dimana intelektualismenya berkembang. Kartini merefleksikan kejanggalan-kejanggalan dan aneka ketimpangan pada budayanya sendiri. Itu dilakukannya dengan mengangkat pena dan menulis surat. Ya, menulis surat!
Kesempatan bersekolah di ELS, benar-benar dimanfaatkan Kartini dengan baik. Di situ ia belajar bahasa Belanda. Ia tahu penguasaan bahwa bahasa asing ini akan mengantarnya pada dunia intelektual yang lebih luas. Bacaan-bacaan bermutu pada masa itu ditulis dalam Bahasa Belanda. Hanya dengan menguasai bahasa penjajah ini ia akan masuk dalam jendela dunia yang lebih lebar.
Selama bersekolah, Kartini rajin membaca. Ia juga intens berdiskusi dengan teman kelasnya. Ia mengamati dengan serius perbedaan gaya hidup Jawa dan kebiasaan teman-temannya orang Belanda. Dari situlah ia mulai mengkritisi. Selama masa dipingit, jiwa intelektual Kartini tetap bergerak.
Kesempatan belajar formal di sekolah lanjutan, di Semarang atau Belanda ditolak ayahnya. Namun, ia tidak berhenti belajar. Di dalam kotak pingitannya ia membaca, membaca dan membaca. Dari sanalah ia mulai menulis, menulis dan menulis. Dua aktivitas kunci inilah yang membuat Kartini "ada", yang menyebabkan ia "eksis" dan selalu memiliki "kekinian".
Saat dirumahkan/dipingit, Kartini rajin menulis surat kepada kawan-kawannya di Belanda. Ia juga berkontribusi mengirim tulisan pada majalah perempuan Belanda. Isi tulisannya menggigit, kritikannya keras, analisanya tajam, walau dikemas dalam bentuk surat-surat pribadi serupa prosa. Tema suratnya beragam: ada masalah perempuan, emansipasi, masalah Hak Asasi Manusia, kritik budaya, kritik agama dan kritik tentang perkawinan dan lembaga keluarga dan macam-macam soal berkaitan dengan masalah sosial masyarakat.







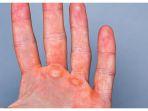

![[FULL] Sengketa Ambalat Malaysia vs RI, Pakar: TNI Tak Boleh Lengah, Jangan Senasib Sipadan Ligitan](https://img.youtube.com/vi/YcKqjph-Pqs/mqdefault.jpg)