Opini
Opini: Jalan Panjang NTT Menuju Masyarakat Pembelajar
Di tengah keterbatasan akses buku, listrik, dan internet, NTT masih mencari jalan panjang menuju masyarakat pembelajar sejati.
Oleh: Dr. Rikardus Herak, S.Pd., M.Pd
Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM - Setiap kali pagi merekah di tanah Timor, Sumba, Flores, dan Lembata, suara anak-anak berlarian di jalan setapak menuju sekolah seolah menjadi musik harapan bagi masa depan Nusa Tenggara Timur ( NTT).
Namun di balik tawa mereka, tersimpan paradoks: provinsi dengan semangat tinggi untuk belajar ini masih berjuang menghadapi kenyataan pahit rendahnya budaya literasi.
Di tengah keterbatasan akses buku, listrik, dan internet, NTT masih mencari jalan panjang menuju masyarakat pembelajar sejati.
Harapan memang tumbuh di setiap langkah kecil, tetapi perjalanan ini masih dipenuhi jurang kesenjangan yang dalam antara keinginan belajar dan kemampuan untuk benar-benar mengakses pengetahuan.
Baca juga: Literasi Menyeruak di Rote Ndao, Relawan Gelar Aksi Baca di Ruang Publik
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat NTT baru mencapai 8,02 tahun, atau setara dengan kelas dua SMP.
Angka itu memang meningkat dibandingkan 2019 (7,8 tahun), tetapi masih jauh di bawah rata-rata nasional 9,1 tahun.
Artinya, banyak anak di NTT yang belum sempat menyelesaikan pendidikan menengah.
Literasi menjadi masalah mendasar yang bukan hanya soal membaca teks, tetapi membaca dunia di sekitar mereka.
Ketika pendidikan formal berhenti di tengah jalan, literasi menjadi alat bertahan hidup kemampuan memahami informasi, menafsirkan realitas, dan mengambil keputusan dalam hidup sehari-hari.
Lebih memprihatinkan lagi, hasil survei Indeks Aktivitas Literasi Membaca (IALM) tahun 2024 menempatkan NTT di peringkat ke-12 nasional, dengan skor 67,81 dari 100.
Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah cermin dari jarak antara sekolah formal dan budaya membaca di rumah.
Ketika buku menjadi barang mewah dan perpustakaan lebih sering dikunci daripada dibuka, semangat belajar kerap mati pelan-pelan di pelosok.
Ironisnya, anak-anak yang sebenarnya haus akan pengetahuan sering kali harus berjuang mencari bacaan sendiri, sementara arus digital yang masuk justru lebih banyak membawa hiburan ketimbang pencerahan.
Masalahnya tidak tunggal. Geografis NTT yang tersebar di lebih dari 500 pulau membuat distribusi buku, guru, dan fasilitas belajar menjadi tantangan logistik yang luar biasa.
Di beberapa desa di Flores Timur atau Alor, siswa harus berjalan dua jam hanya untuk sampai ke sekolah.
Ketika jarak dan hujan menjadi penghalang, membaca bukan lagi aktivitas harian, tetapi kemewahan yang sulit dijangkau.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa literasi bukan hanya isu pendidikan, tetapi juga persoalan infrasiruktur, pemerataan, dan keadilan sosial bagi warga di pulau-pulau kecil.
Kemiskinan juga berperan besar. Data BPS 2024 mencatat tingkat kemiskinan NTT mencapai 19,29 persen, tertinggi ketiga di Indonesia.
Di banyak keluarga, prioritas bukan membeli buku, tetapi memastikan nasi di meja. Literasi menjadi korban dari kebutuhan dasar.
Anak-anak pun sering kali berhenti sekolah lebih awal untuk membantu orang tua di ladang atau laut.
Dalam situasi seperti ini, membaca dianggap tidak produktif secara ekonomi, padahal justru literasilah yang bisa memutus rantai kemiskinan antargenerasi jika dibangun dengan kesadaran dan dukungan berkelanjutan.
Namun, di tengah keterbatasan itu, tumbuh benih harapan dari bawah dari masyarakat sendiri.
Gerakan literasi akar rumput muncul seperti mata air di tengah tandus.
Salah satunya adalah Komunitas Lakoat Kujawas di Molulo, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Dengan ruang baca sederhana, komunitas ini menghidupkan budaya membaca lewat cerita rakyat, teater, dan penerbitan buku lokal.
Mereka tidak hanya mengajarkan anak-anak membaca, tapi juga menulis kisah tentang kampung mereka sendiri.
Dari situ, lahirlah kebanggaan baru: menjadi anak NTT yang mampu bercerita tentang budayanya sendiri.
Di Atambua, Taman Bacaan Masyarakat Akar Cinta berdiri di halaman rumah sederhana.
Setiap sore, puluhan anak datang membaca buku sumbangan dan belajar menulis puisi.
Pendiri taman baca itu, seorang guru honorer bernama Maria, mengatakan dengan senyum, “Kalau mereka bisa membaca, mereka bisa bermimpi. Dan kalau bisa bermimpi, mereka bisa keluar dari kemiskinan."
Kalimat sederhana itu adalah manifesto literasi sejati. Ia membuktikan bahwa perubahan besar sering dimulai dari hati yang kecil dari orang-orang yang tidak menunggu kebijakan, tetapi menciptakan perubahan dari lingkungannya sendiri.
Kisah serupa juga datang dari Sumba. Di sana, Rumah Baca Prailiu menggabungkan tradisi lokal dengan literasi modern.
Anak-anak membaca buku cerita dalam bahasa Indonesia, lalu mendengarkan kembali versi lokalnya dalam bahasa Sumba.
Ini bukan sekadar translasi bahasa, tapi jembatan budaya - agar literasi tidak terasa asing bagi anak desa.
Dengan cara itu, mereka belajar bahwa membaca bukan berarti meninggalkan akar budaya, melainkan memperkuat identitas melalui kata dan makna.
Gerakan seperti ini membuktikan bahwa literasi tidak selalu harus dimulai dari gedung tinggi atau proyek besar.
Ia bisa tumbuh dari rumah, dari halaman gereja, dari bale-bale bambu di bawah pohon asam.
Akar rumputlah yang menjaga nyala api belajar di NTT, saat sistem formal masih sibuk dengan laporan dan program tahunan.
Di tempat-tempat itu, literasi tidak diajarkan, melainkan dihidupi - menjadi bagian dari keseharian masyarakat yang masih percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya penuntun hidup.
Namun, pertanyaannya: sampai kapan masyarakat dibiarkan berjuang sendiri?
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Tetapi di banyak tempat di NTT, implementasinya masih setengah hati. Buku datang tanpa panduan, perpustakaan dibangun tanpa pustakawan, dan pelatihan guru kadang berhenti di seminar.
Literasi tidak bisa tumbuh di atas formalitas; ia butuh ekosistem yang berdenyut yang menyatukan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam satu semangat belajar.
Padahal, UNESCO sejak 2018 menegaskan bahwa literasi adalah hak dasar abad ke-21, sejajar dengan hak atas pendidikan dan teknologi.
Negara harus hadir tidak hanya dengan buku, tapi dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat pinggiran.
Jika literasi adalah jantung pembangunan manusia, maka NTT harus mendapat transfusi energi kebijakan yang nyata.
Mengabaikan literasi berarti menunda kemajuan, karena masa depan provinsi ini tidak akan dibangun oleh beton dan aspal semata, melainkan oleh pikiran yang tercerahkan.
Salah satu masalah besar adalah ketimpangan digital. Menurut data Kominfo 2025, hanya 38 persen wilayah NTT yang memiliki akses internet stabil.
Di era di mana literasi digital menjadi bagian dari literasi dasar, kesenjangan ini membuat anak-anak di pedalaman semakin tertinggal.
Buku digital dan e-learning hanya menjadi mimpi bagi mereka yang bahkan tidak punya sinyal.
Ketika anak-anak kota bisa belajar lewat YouTube atau e-book, anak-anak desa masih menyalin catatan dari papan tulis ke kertas lusuh simbol nyata kesenjangan belajar di abad modern.
Namun, literasi bukan hanya tentang membaca huruf dan layar. la juga tentang membaca kehidupan: memahami informasi, berpikir kritis, dan berani berpendapat.
Di NTT, banyak komunitas literasi kini mulai melatih siswa menulis opini, membuat zine, hingga mengelola media sosial kampung.
Ini menandakan bahwa literasi sudah berkembang dari "membaca" menjadi "berpikir dan berkarya."
Dalam konteks ini, literasi menjadi alat pemberdayaan sosial menjadikan anak muda bukan sekedar penerima informasi, tetapi produsen pengetahuan bagi lingkungannya.
Sebuah riset Universitas Nusa Cendana tahun 2024 menemukan bahwa siswa yang aktif dalam kegiatan literasi komunitas memiliki tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar lebih tinggi hingga 35 persen dibandingkan siswa yang tidak terlibat.
Artinya, gerakan literasi bukan hanya soal buku, tapi membangun karakter dan rasa percaya diri anak-anak NTT.
Anak-anak yang terbiasa membaca dan menulis juga lebih berani berpartisipasi dalam diskusi kelas dan kegiatan sosial, menunjukkan bahwa literasi sejatinya adalah pondasi bagi partisipasi warga negara yang kritis dan demokratis.
Meski begitu, tantangan ke depan masih besar. Tanpa dukungan kebijakan yang sistemik, gerakan-gerakan kecil ini akan kelelahan.
Mereka butuh akses buku murah, dukungan logistik, pelatihan bagi relawan, dan jaringan distribusi antar-pulau.
Literasi tak bisa hanya mengandalkan semangat voluntarisme, ia perlu infrastruktur sosial yang kokoh.
Dukungan jangka panjang akan memastikan bahwa setiap taman baca tidak mati setelah semangat pendirinya padam, melainkan tumbuh menjadi pusat pembelajaran masyarakat yang berkelanjutan.
Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu mulai melihat komunitas literasi sebagai mitra strategis, bukan pelengkap.
Alih-alih sekadar membuat program seremonial, akan lebih baik jika anggaran literasi dialokasikan langsung untuk mendukung komunitas di lapangan misalnya melalui skema hibah terbuka bagi taman baca dan kelompok literasi desa.
Pendekatan kolaboratif seperti ini telah terbukti berhasil di beberapa provinsi lain, di mana pemerintah menjadi fasilitator yang mempercayai masyarakat untuk memimpin perubahan di wilayahnya sendiri.
Selain itu, kolaborasi dengan universitas dan sekolah-sekolah perlu diperkuat.
Mahasiswa bisa menjadi agen literasi di desa-desa melalui program KKN tematik "Literasi untuk Kehidupan".
Dengan cara ini, kampus tidak hanya menjadi menara gading, tapi turut membangun ekosistem pengetahuan yang berakar pada masyarakat.
Kolaborasi ini juga dapat mempertemukan pengetahuan akademik dan kearifan lokal - dua hal yang sering terpisah tetapi sejatinya saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat pembelajar.
Gereja, masjid, dan lembaga adat juga punya peran penting. Di banyak daerah di NTT, tempat-tempat ini adalah pusat kehidupan sosial.
Bayangkan jika setiap khotbah, doa, atau upacara adat juga menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran membaca dan menulis.
Literasi bisa tumbuh seiring doa dan tradisi menjadi gerakan spiritual dan kultural sekaligus.
Di titik inilah, literasi tidak lagi sekadar aktivitas intelektual, melainkan bentuk ibadah sosial untuk memuliakan martabat manusia melalui pengetahuan.
Pada akhirnya, membangun budaya baca di NTT bukan semata soal buku, tetapi tentang memulihkan martabat manusia.
Literasi adalah jembatan dari keterbatasan menuju kebebasan berpikir, dari kemiskinan menuju kemandirian.
Saat masyarakat belajar membaca dunianya, mereka juga sedang belajar menulis masa depannya sendiri.
Sebab masyarakat yang literat bukan hanya mereka yang cerdas membaca huruf, tetapi juga peka membaca realitas, dan berani menuliskan perubahan.
Di jalan panjang menuju masyarakat pembelajar, NTT mungkin berjalan lebih lambat, tapi langkahnya pasti.
Dari Molulo ke Maumere, dari Sumba ke Soe, nyala kecil itu terus menyala.
Dan selama masih ada satu anak yang membaca dengan semangat di bawah cahaya pelita, kita tahu bahwa masa depan NTT masih ditulis dengan tinta harapan.
Karena literasi bukan sekadar kemampuan, melainkan bentuk perlawanan terhadap keterbelakangan sebuah ikrar bahwa ilmu pengetahuan akan selalu menjadi cahaya yang tak padam di ufuk Timur Indonesia. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Rikardus Herak
Nusa Tenggara Timur
masyarakat pembelajar
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Opini Pos Kupang
literasi
| Opini: Trading Valas GOLD dan AI Jadi Sumber Uang Baru Generasi Digital |

|
|---|
| Opini: Konflik Israel-Palestina dan Dekontruksi Hati Nurani |

|
|---|
| Opini: Warisan Sehat dari Leluhur, Saatnya Kembali ke Akar Budaya Nusantara |

|
|---|
| Opini: Pendidikan Katolik dan Dunia yang Tabola Bale: Footnote dari Muspas KAK 2025 |

|
|---|
| Opini: Bahasa Multimedia |

|
|---|

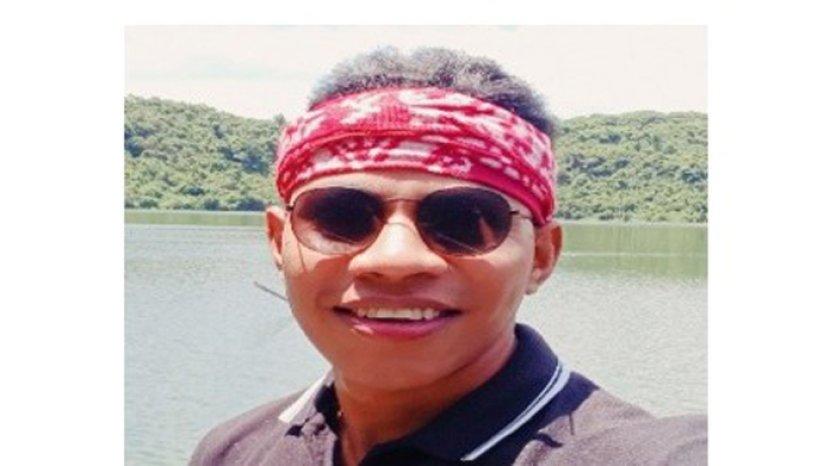








![[FULL] Ulah Israel Buat Gencatan Senjata Gaza Rapuh, Pakar Desak AS: Trump Harus Menekan Netanyahu](https://img.youtube.com/vi/BwX4ebwTZ84/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.