Opini
Opini: FAFO Parenting, Apakah Anak Dibiarkan Merasakan Akibatnya Sendiri?
Anak menolak pakai jaket saat hujan? Silakan, biarkan dia kedinginan sebentar, agar lain kali ia tahu pentingnya menjaga diri.
Oleh : Dr. Elinda Rizkasari.,S.Pd.,M.Pd
Dosen prodi PGSD Universitas Slamet Riyadi ( Unisri) Surakarta
POS-KUPANG.COM - Beberapa minggu terakhir, jagat media sosial diramaikan oleh istilah baru dalam dunia pengasuhan: FAFO parenting.
Konsep ini meledak di TikTok dan Instagram lalu diulas oleh berbagai media internasional.
Intinya sederhana tapi kontroversial yaitu biarkan anak belajar dari konsekuensi nyata atas perbuatannya sendiri.
“Find Out by Fucking Around” begitu singkatan yang tidak sopan itu dipopulerkan di luar negeri, meski tentu dalam konteks parenting maknanya dilunakkan menjadi “biarkan anak tahu akibat dari tindakannya.”
Bagi sebagian orang tua, konsep ini terasa menyegarkan. Tidak perlu berpanjang-panjang menasihati, cukup biarkan anak merasakan konsekuensi dari pilihan mereka.
Baca juga: Opini: Urgensitas Digital Parenting Bagi Generasi Alfa
Anak menolak pakai jaket saat hujan? Silakan, biarkan dia kedinginan sebentar, agar lain kali ia tahu pentingnya menjaga diri.
Anak lupa mengerjakan PR? Jangan buru-buru membantu, biarkan ia mendapat teguran guru.
Namun, di sisi lain, banyak psikolog memperingatkan konsekuensi yang terlalu keras bisa melukai kepercayaan diri anak dan bahkan meninggalkan trauma jangka panjang.
Pertanyaannya, sampai sejauh mana orang tua boleh melepas kontrol, dan kapan mereka tetap harus hadir sebagai “rem pelindung”?
Dari “Gentle” ke “FAFO”: Pergeseran Tren Parenting
Tren parenting selalu berputar mengikuti zaman. Setelah lama digandrungi, gentle parenting yang menekankan kelembutan, komunikasi empatik, dan validasi emosi, kini dinilai sebagian orang tua terlalu permisif.
Generasi Alpha anak-anak yang lahir di era digital serba cepat sering kali dianggap “kurang disiplin” karena terlalu sering ditenangkan, bukan ditegaskan.
Di sinilah FAFO parenting muncul sebagai reaksi. Alih-alih terus-menerus mengingatkan dengan nada lembut, orang tua lebih memilih membiarkan anak menanggung konsekuensi nyata.
Pendekatan ini terasa cocok di tengah dunia yang keras dan kompetitif.
Namun, benarkah dengan membiarkan anak “jatuh”, mereka otomatis akan bangkit lebih kuat? Atau justru kita sedang mempertaruhkan kesehatan mental generasi mendatang?
Kisah Nyata
Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang remaja SMP di Semarang menolak bangun pagi meski sudah diingatkan berkali-kali. Alih-alih dimarahi atau dibangunkan berulang kali, orang tuanya membiarkan ia terlambat masuk sekolah.
Akibatnya, ia mendapat hukuman piket tambahan. Sejak hari itu, ia belajar mengatur alarm sendiri dan tak pernah lagi bangun kesiangan.
Kasus ini menunjukkan bahwa konsekuensi nyata bisa lebih ampuh daripada seribu kata nasihat. Anak belajar bukan dari kata-kata, tetapi dari pengalaman.
Dalam psikologi perkembangan, ini sejalan dengan teori experiential learning: pengalaman langsung memperkuat pembelajaran lebih daripada instruksi verbal.
Tetapi bayangkan jika yang terjadi adalah konsekuensi yang membahayakan. Anak menolak pakai helm saat naik sepeda motor lalu benar-benar jatuh dan cedera.
Di sini, jelas orang tua tidak bisa hanya “membiarkan.” Ada garis batas tipis antara konsekuensi yang mendidik dan risiko yang merusak.
Apa Kata Psikolog?
Menurut penelitian dari American Psychological Association (2024), anak-anak yang dididik dengan keseimbangan antara disiplin dan empati cenderung lebih resilient.
Mereka mampu menghadapi tantangan tanpa kehilangan rasa percaya diri.
Sebaliknya, anak yang terlalu sering “dibiarkan” tanpa pendampingan emosional berisiko mengalami kecemasan sosial dan merasa kurang dicintai.
Di Indonesia, KPAI mencatat bahwa kasus anak yang mengalami tekanan akademik dan emosional meningkat setiap tahun.
Tekanan dari sekolah saja sudah cukup berat; jika di rumah anak juga dibiarkan menanggung konsekuensi keras tanpa penyangga kasih sayang, risiko gangguan kesehatan mental makin besar.
Artinya, FAFO parenting tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Ia butuh adaptasi sesuai konteks budaya, usia anak, dan kapasitas emosional orang tua.
Parenting Bukan Hitam-Putih
Salah kaprah terbesar dalam parenting adalah menganggap ada satu “metode sakti” yang cocok untuk semua.
Padahal setiap anak unik. Ada anak yang justru berkembang pesat ketika diberi konsekuensi tegas. Tapi ada juga anak yang semakin terpuruk jika dibiarkan jatuh tanpa dukungan.
Orang tua perlu peka membaca karakter anak. Konsekuensi boleh diberikan, tetapi tetap dalam bingkai kasih sayang.
Alih-alih sekadar melepas, orang tua bisa hadir sebagai fasilitator refleksi: “Tadi kamu telat ya? Rasanya gimana? Apa yang bisa kamu lakukan supaya besok tidak terulang?”
Dengan begitu, anak bukan hanya merasakan konsekuensi, tapi juga belajar mengambil hikmah.
Konsekuensi yang Edukatif
Kuncinya adalah memastikan konsekuensi tetap edukatif, bukan destruktif. Itu berarti orang tua harus menempatkan keselamatan anak di atas segalanya.
Tidak semua konsekuensi layak dibiarkan terjadi; risiko yang membahayakan nyawa jelas tidak bisa dijadikan bahan pembelajaran.
Selain itu, usia anak juga menentukan jenis konsekuensi yang pantas. Anak usia TK membutuhkan pendampingan lebih intens, sementara remaja bisa diberikan ruang untuk menanggung akibat dari keputusannya.
Di titik ini, pendampingan orang tua tetap penting, bukan sekadar melepas. Setelah anak merasakan akibat, diskusi ringan untuk merefleksikan pengalaman akan jauh lebih bermakna daripada sekadar membiarkannya lewat begitu saja.
Konsistensi juga menjadi kunci. Anak belajar dari pola yang jelas, bukan dari hukuman atau konsekuensi yang diberikan secara tiba-tiba.
Namun, ketegasan itu harus tetap dibungkus dalam kasih sayang. Tegas tidak sama dengan dingin.
Anak perlu merasakan bahwa meski ada konsekuensi atas kesalahannya, cinta orang tua tidak berkurang sedikit pun.
Menyeimbangkan Kasih dan Konsekuensi
FAFO parenting mungkin terdengar keren di TikTok, tapi dalam praktiknya ia bukanlah resep ajaib.
Membiarkan anak belajar dari konsekuensi memang penting, tetapi orang tua tetap harus menjadi jangkar kasih sayang.
Anak yang tumbuh dengan keseimbangan disiplin dan empati akan lebih siap menghadapi kerasnya dunia, tanpa kehilangan rasa aman di rumah.
Pada akhirnya, parenting bukan soal mengikuti tren, melainkan soal menemukan cara terbaik agar anak tumbuh sehat, tangguh, dan bahagia. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News

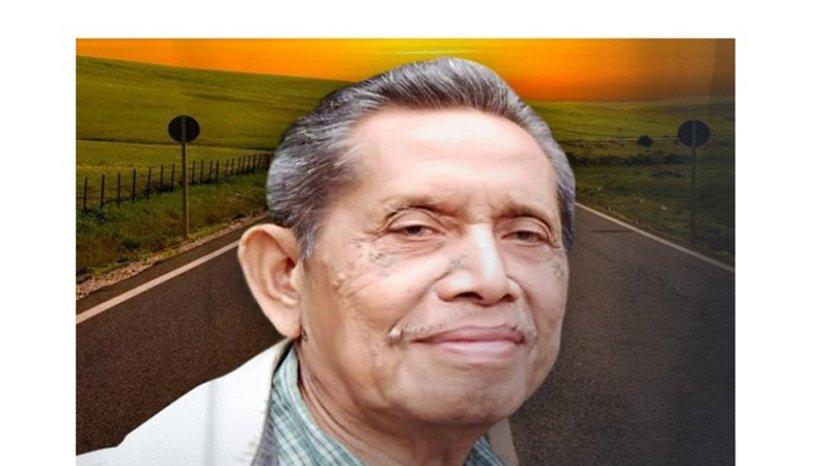



















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.