Opini
Opini: Turbulensi Politik dan Hegemoni Republikanisme Pasca-Pemilu
Ataukah yang terjadi adalah vote minus voice, karena pemilu sekadar instrumen oleh elite politik untuk menuai legitimasi dari rakyat?
Oleh: B Mario Yosryandi Sara
Aktivis HAM dan Pegiat Demokrasi, tinggal di Jakarta
POS-KUPANG.COM - Pasca pemilu 14 Februari 2024 ruh demokrasi tengah terdiagnosa kronis value, usai dibabat distorsi elektoral dalam hegemoni perebutan kepingan kekuasaan antar-politisi dan bandit korporasi, dalam pandangan Jeffrey Winters diglorifikasi sebagai “oligark”.
Fenomena itu berkembang dan menggerogoti etika res publica, serta turut memperlemah ranah kebebasan sipil lantaran disebabkan beberapa faktor, antara lain; (1) absennya pertarungan ideologi dalam kompetisi politik, (2) terjadinya krisis moral dan kepimpinan,
(3) pembajakan demokrasi, (4) ambivalensi dan inkonsistensi negara dalam penegakan hukum serta penyelesaian masalah sosial-politik yang berbasis primordial.
Letak kontradiksi di atas, tak dapat dihindari bilamana akan membawa Indonesia bermuara pada tiga dimensi persoalan; yakni (1) ketimpangan sumber daya yang krusial, (2) ketimpangan ekonomi, dan (3) ketimpangan ekologi.
Beragam penilaian telah dikemukakan para akademisi dalam mengartikulasi capaian reformasi politik dan kualitas demokrasi tanah air selama satu dekade kekuasaan rezim Presiden Jokowi.
Sebagian pakar politik berlatar mazhab positivisme, cenderung menitikberatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang sukses memperlihatkan capaian dengan status stable democracy (demokrasi stabil), lantaran praktik demokrasi yang dijalankan secara relatif telah merefleksikan sistem demokrasi liberal.
Namun yang menjadi pertanyaan, apakah vote-suara yang diamanahkan masyarakat pada pemilu, kemudian berbuah voice pada fase pasca-pemilu dalam bentuk kebijakan pemerintah yang merefleksikan aspirasi rakyat?
Ataukah yang terjadi adalah vote minus voice, karena pemilu sekadar instrumen oleh elite politik untuk menuai legitimasi dari rakyat?
Untuk mengkontekstualisasi kedua pokok pertanyaan ini, menjadi penting menelisik lagi lorong-lorong realitas politik guna men-devosikan kembali, mengutip istilah Agamben, “bios politikos” dalam “arcanum imperii” republikanisme.
Vulgarisasi politik
Hakekatnya, pemilu adalah sarana melegitimasi dan memperkuat basis kedaulatan rakyat, menentukan nasib serta masa depan negara secara demokratis.
Akan tetapi, pemilu 2024 yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berasal dari suara rakyat, berakhir dramatis akibat banalitas elite politik dan kecurangan yang terjadi.
Kandasnya supremasi hukum, hampir mustahil dapat tegak di tengah tata kelola pemerintahan yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut. Konstitusi direkayasa sedemikian rupa demi melanggengkan dinasti politik dan memperkuat tirani.
Sejak awal semua pihak sudah mencurigai proses mengawali tahun politik dengan beragam langkah pengkondisian. Di antaranya dimulai revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU IKN, isu presiden tiga periode, dan penundaan pemilu.
Banyak yang mengendus proses tersebut sebagai bagian dari praktek kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Terutama saat keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang mengantar anak sulung Presiden Jokowi menjadi Cawapres.
Proses penunjukkan penjabat kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) sarat akan masalah. Setidaknya, terdapat 101 kepala daerah sudah berakhir masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah berakhir 2023.
Kekosongan jabatan publik diduga menjadi ladang dan bancakan intervensi Presiden untuk memastikan hasil pemilu 2024.
Menurut laporan Ombudsman, ada sejumlah maladministrasi yang menjadi masalah krusial dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah.
Rocky Gerung dalam Intelektual dan Kondisi Politik, menerangkan bila politik hari-hari ini kita petakan secara geologis, tampak ada tiga ”susunan” kualitas.
Pertama, yang paling dangkal, yaitu yang ada di permukaan bumi politik kita, adalah politik ”dagang sapi”, kegiatan tukar tambah kepentingan diantara partai-partai politik, tanpa visi ideologis.
Kedua, politik sudah dilembagakan dalam hukum dan institusi. Di sini transaksi politik berlangsung dalam kerangka pelembagaan negara hukum dan diselenggarakan sebagai rutinitas demokrasi.
Dan ketiga, yang terdalam, politik adalah perjuangan keadilan yang diselenggarakan dalam distingsi ideologis yang jernih, melalui kesadaran etis yang tinggi (Prisma, Vol. 28 Juni 2009).
Meski pada 22 April lalu, MK telah memutuskan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, tapi tak dapat dipungkiri kemenangan Paslon dengan visi Asta Cita itu penuh anomali, dengan raihan suara sebesar 58,59 persen atau 96.214.691 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU.
Terdapat dua hal yang bisa menjelaskan fenomena tidak linearnya suara calon presiden dengan partainya.
Adanya vote buying dan perilaku klientelistik yang lumayan masif mendeviasi afeksi pemilih.
Kemudian, berkaitan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih calon legislatif (caleg) mendominasi proporsi pemilih partai sebanyak 75 persen pada 2019. Kontribusi suara partai itu berasal dari pemilih caleg.
Terdapat juga distribusi pembagian bantuan sosial (Bansos) oleh Presiden Jokowi pada momentum kampanye Pemilu 2024, menunjukkan tingginya efektivitas klientelisme di Indonesia.
Pasalnya, lebih dari separuh pemilih pemilu 2024 rentan terhadap mekanisme-mekanisme klientelistik.
Berdasarkan laporan Kompas, kontroversi bansos pada tahun politik sangat seksi karena melibatkan jumlah dana fantastik, yakni Rp 496,8 triliun, dan rawan konflik kepentingan atau disalahgunakan (Kompas, 3/2/2024).
Alhasil, rakyat kemudian dipaksa mengamini hasil pemilu dengan berbagai “prosedur legal” tapi tidak legitimate. Dikarenakan prosesnya secara terang-terangan telah menabrak berbagai aturan, etika, dan kepatutan berdemokrasi.
Bahkan, menghalalkan segala cara melalui politik Bansos yang bersumber dari APBN, mobilisasi aparatur TNI, Polri dan ASN untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.
Pemilu sekadar ajang konsolidasi melanggengkan penguasaan atas sumber daya alam yang menjadi hajat hidup rakyat. Jadi tidak sulit mengatakan, jika pemilu 14 Februari kemarin, merupakan pemilu paling brutal pasca-reformasi.
Di sisi lain, barangkali dapat kita terangkan peta politik hari ini berdasarkan teori Jacques Ranciere, yang diuraikan dalam La Mesentente (1995) kemudian disarikan Slavoj Zizek dalam “Afterword” buku Jacques Ranciere, The Politics of Aesthetics (2006).
Pertama Ranciere menyebut “archi-politics”, yaitu politik komunitarian yang mengorganisasi kebudayaan secara organis dan homogen, sehingga tak ada ruang sosial lagi bagi perjuangan politik tandingan.
Kedua, “para-politics”, merupakan politik yang justru didepolitisasi melalui pelembagaan dengan maksud menidurkan potensi konflik. Inilah politik regularisasi yang meredam kondisi historis dari politik, yaitu antagonisme perjuangan ideologis.
Ketiga, ”meta-politics”, yaitu politik yang ”kebenarannya” diterangkan dari luar dirinya, misalnya dari kondisi infrastruktur ekonomi, seperti pada marxisme.
Keempat, ultra-politics, adalah politik di bawah kekuatan militer, dengan alasan menyelesaikan konflik politik, menciptakan stabilitas, oleh karena itu sentralisasi dipakai merumuskan dan memusnahkan musuh politik.
Apologi
Bahwa benar demokrasi lahir dari keadaan darurat, itu tak terbantahkan. Dalam beberapa kasus, demokrasi merupakan anak kandung revolusi dan reformasi.
Dengan alasan keadaan darurat, tatanan lama diruntuhkan, konstitusi ditangguhkan, kekerasan dibenarkan guna membentuk suatu tatanan baru, katakanlah tatanan demokrasi (Agus Sudibyo;2019).
Oleh karena itu, harapannya setelah revolusi atau reformasi, kekuasaan secara konsekuen harus dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi; distribusi kekuasaan, check and balancing, supremasi hukum, dan kesetaraan-keadilan bagi semua warga negara tanpa kecuali—rule of law.
Namun di era reformasi, Indonesia telah melewati enam kali tahapan pemilu. Seyogianya kualitas demokrasi lebih bermartabat, berintegritas, dan berdiri tegak di atas etika ideologis.
Bukan sebaliknya, rakyat diberi asupan demagogi untuk bersekongkol merapuhkan pilar-pilar bernegara dan political ethics. Sebagaimana kondisi sekarang, komitmen reformasi terancam erosi, dan tak dapat dipungkiri jika demokrasi Indonesia dikategorikan flawed democracies (demokrasi cacat).
Bahkan situasi untuk kembali ke Orde Baru sangat mungkin terjadi. Lantaran pengaruh oligarki tak kunjung surut setelah Soeharto tumbang, melainkan sekadar berkamuflase dengan realitas politik yang ada.
Dinamika demikian menandakan demokrasi yang telah dibangun lebih dari dua dekade, kini berada di tepian totalitarianisme.
Meski keadaan demokrasi dan perpolitikan tengah berada di ujung tanduk, sepatutnya kondisi ini dijadikan trigger, pemicu, dan pendobrak bagi seluruh kekuatan demokrasi yang tersisa untuk menjalankan fungsinya sebagai aktor-aktor yang mampu menjadi pelita dan melakukan pencerahan.
Melalui Homo Saccer (2020), Agamben memandang kedaruratan demokrasi dengan rasionalisasi politis-yuridis dan rasionalitas manajerial-administratif dalam kekuasaan berdaulat, sehingga dalam praktiknya dapat membuat kehendak bersama (the general will) dan juga hak konstitusional rakyat (legislative capacity) menjadi tak terpisahkan.
Robertus Robert dalam Republikanisme (2021), memperjelas bahwa “Res-Publica” adalah suatu wahana tindakan yang di mana manusia menunjukkan eskistensial atau mengekspresikan dirinya secara deliberative.
Individu konkret sebagai subjek harus diposisikan secara filosofis setidaknya supaya pengertian ideologi bisa dioperasionalkan. Jika subjek terhapus, maka The Ideological Subject kehilangan marwahnya.
Singkatnya, antara subjek dan ideologi terbangun hubungan fungsional yang timbal balik. Politik jadi kehilangan segi politiknya.
Sebagaimana keyakinan Aristoteles akan pentingnya republik yang faktual dan kuat menjadi rujukan akhir sebagai tujuan dari politik.
Dikarenakan dengan ideologi yang kuat, meyakini begitu pentingnya warga yang terdidik dan jiwa revolusioner sebagai fondasi dari republik.
Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus akhir-akhir ini dengan anggapan bahwa demokrasi perlu diperkuat guna menjamin keteraturan publik sekaligus mendorong transformasi ke arah pembentukan struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal dan matang, di bawah payung institusi pemerintah yang bersih, bebas KKN sebab yang demokratis semakin diyakini dapat menjadi model tatanan yang realistik dan diharapkan bisa mencegah lahirnya pemerintahan yang represif dan dominatif pasca rezim Jokowi.
Robert Dahl (2001) menyebutnya upaya mencegah gila kebesaran, kelainan jiwa, kepentingan pribadi sesuai emosi kata hati, mengeskploitasi kemampuan negara dan kekerasan untuk mencapai tujuan pribadi mereka—oligarki. (*)
| Opini: Prada Lucky dan Tentang Degenerasi Moral Kolektif |

|
|---|
| Opini: Drama BBM Sabu Raijua, Antrean Panjang Solusi Pendek |

|
|---|
| Opini: Kala Hoaks Menodai Taman Eden, Antara Bahasa dan Pikiran |

|
|---|
| Opini: Korupsi K3, Nyawa Pekerja Jadi Taruhan |

|
|---|
| Opini: FAFO Parenting, Apakah Anak Dibiarkan Merasakan Akibatnya Sendiri? |

|
|---|

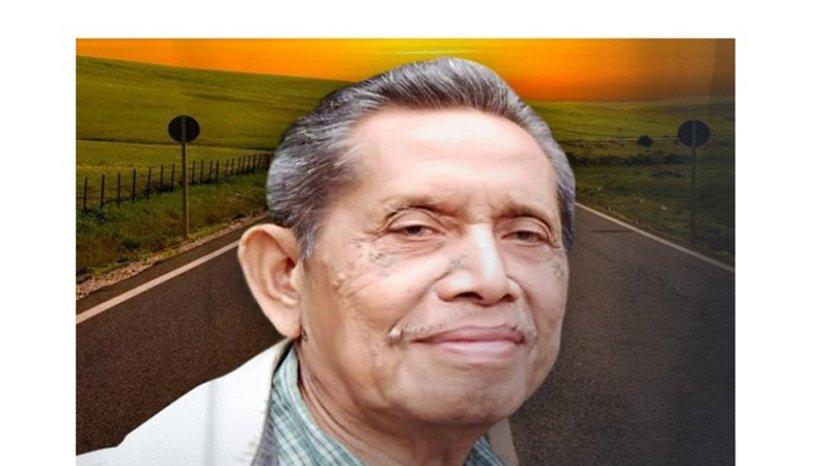














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.