Opini
Membaca dan Berpikir: Yang terakhir dari Toko Buku Terakhir
Kegelisahan ini dimunculkan oleh penulis karena kecintaannya pada kegiatan membaca, menulis dan berpikir.
Oleh: Romo Dr. Leo Mali, Pr
Pengajar di Seminari Tinggi St. Mikael, Kupang
POS-KUPANG.COM - Awal bulan November tahun lalu saya membaca Toko Buku Terakhir karya Usman Kansong. Sebagai seorang pembaca dan seorang guru, saya merasakan kegelisahan penulis mengenai dua hal. Pertama ancaman menghilangnya buku-buku fisik.
Kedua, budaya baca masyarakat kita masih tetap lemah di tengah gempuran perangkat digital.
Kegelisahan ini dimunculkan oleh penulis karena kecintaannya pada kegiatan membaca, menulis dan berpikir.
Dalam refleksi ini, seperti tertulis pada judul, saya ingin memberi catatan mengenai hubungan antara membaca dan berpikir.
Pada saat membaca kita mengarahkan pikiran kita pada sebuah teks. Text adalah sebuah tenunan (Latin; tessere).
Kalau sebuah kain ditenun dari jalinan benang, maka sebuah teks yang dibaca ditenun oleh jalinan huruf yang membentuk kata dan jalinan kata yang membentuk makna.
Kata dalam setiap bahasa memberi wujud sebuah ide yang berumah dalam pikiran seorang penulis.
Melalui tujuh bagian buku Toko Buku Terakhir, Usman Kansong, menuliskan dengan ringan isi ringkas sekalian serta pesan tertentu dari buku-buku yang dikejarnya di berbagai rak toko buku yang ada, dibacanya dan dituliskan kembali.
Mata air dari pengejaran penulis pada buku-buku adalah minat dan kecintaannya pada buku dan pengetahuan.

Maka bergerak dari “Mata Air” Azra, Air mata kita, sebuah tulisan pada bagian pertama tentang Buku dan Obituarium, tentang berpulangnya Asyumardi Azra, penulis melanglangbuana dan menerobos jauh, melewati ruang dan waktu, menyapa banyak sosok dan tokoh hingga tiba di akhir pencarian, pada sebuah tempat di Los Angeles, California, sebuah toko buku bekas, The Last Bookstore, (Toko Buku Terakhir).
Penulis menempatkannya di akhir, sekalian sebagai judul seluruh buku.
Struktur buku ini memperlihatkan tujuh bagian pokok: Buku dan Obituarium; Buku dan Agama; Buku, Kafe, Kopi; Buku dan Politik; Buku dan Aku; Buku, Perjalanan, Kebahagiaan; toko Buku Terakhir.
Saya tidak ingin membahas satu persatu tujuah bagian itu. Karena saya lebih tertarik pada kesan yang saya tangkap berupa nuansa kepedihan dan kesenduan sejak awal ketika penulis, pada bagian Buku dan obituarium, menempatkan tulisannya untuk mengenang kepergian Azyumardi Azra dengan judul yang impresif, Mata air Azra, Air mata Kita.
Kesenduan ini kemudian dijawabi dengan harapan yang kuat sejak awal ketika Penulis menempatkan dirinya dalam dialog yang hidup dengan tokoh-tokoh historis dan pemikir yang nyata, seperti Azyumardi Azra, Mona Lohanda, Ong Hok Ham, Jalaludin Rachmat, Bahtiar Efendi, Ridwan Saidi, Buya Syafii Maarif atau sejumlah sosok lain yang disebut pada bagian buku selanjutnya.
Pepatah Latin mengatakan Homo est liber vivus; manusia adalah buku yang hidup. Buku yang hidup, dibedakan dengan buku yang ditulis (Liber scriptus).
Tokoh-tokoh dalam buku merupakan buku yang hidup, yang menjelmakan gagasan-gagasan yang diyakini dari ribuan teks dan buku yang mereka baca atau mereka tulis (Liber scriptus).
Penulis mengkomunikasikan gagasan-gagasan para pemikir yang dihadapinya, menjahitnya dalam jalinan gagasan yang saling melingkungi.
Tidak cuma itu, penulis sendiri menempatkn diri di antara para tokoh dalam buku ini sebagai sesama pencari kebenaran.
Dan, dengan cara ini, ia menunjukkan sekaligus bahwa bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan tertentu, tetapi lebih dari itu pertama-tama bahasa adalah alat berpikir yang memungkinkannya “duduk semeja”, paling kurang secara imaginer bersama para tokoh dan berpikir bersama dan bertukar pikiran dengan mereka.
Orang Latin klasik menamai berpikir dengan cogitare. Descartes memakainya dalam ungkapan yang terkenal, cogito ergo sum; saya berpikir maka saya ada.
Dengan cogito; saya berpikir, Descartes memaksudkan sebuah proses mental manusia yang semata-mata bersifat rohaniah dan imaterial. Subyek yang berpikir dan berkesadaran (res cogitans) adalah kebenaran pertama yang utama.
Sementara res atau the things, hal-hal yang tentangnya pikiran manusia mengarahkan diri (Res extensa) adalah hal-hal sekunder; bisa ada, bisa juga diabaikan.
Cara berpikir idealis Descartes mendapat penegasan optimum dalam filsafat Kant yang melalui kritik roh murni (kritik der reinen vernunft) -nya, meyakini bahwa manusia in se adalah subyek yang sanggup berpikir dari dirinya sendiri.
Pada budi setiap manusia ada kategori-kategori pengetahuan yang membuatnya sanggup bernalar atas nama dirinya sendiri.
Posisi berpikir seperti ini menjadi jejak dasar yang sedang ditapaki oleh antroposentrisme post truth yang melihat manusia konkrit yang berpikir sebagai subyek konkrit menyerupai “roh murni” yang otonom dan mampu berpikir sendiri.
Sehingga Kebenaran yang dicari manusia dalam semua giat pengetahuannya termasuk dalam membaca, tidak lain dari affirmasi atas pikirannya sendiri.
Dengan begitu kenyataan yang dicari dalam teks semata-mata ditilik dari kaca mata pikiran semata-mata. Lex entis, ordo kenyataan dalam dirinya tunduk pada lex mentis atau hukum berpikir.
Dalam teori interpretasi kemudian dikenal otonomi semantik yang membuat teks menjadi sangat terbuka, multidimensional dan polyinterpretable. Pada satu sisi kenyataan ini menunjukkan betapa kayanya makna sebuah teks.
Tapi di sisi lain, tampak pula bahwa menemukan sebuah pemahaman bersama atas sebuah teks adalah hal yang tidak mudah karena setiap orang jatuh dalam klaim kebenarannya sendiri.
Kita tidak akan berbicara lebih jauh mengenai konflik yang timbul sebagai akibat dari kerumitan teori interpretasi atau hermeneutic. Yang ingin kita tegaskan di sini adalah bahwa bahasa adalah alat berpikir melalui mana seorang penulis dan pembaca bekerja. Bahasa itu terbatas.
Karena dalam sejarah peradaban, seperti kata Giambattista Vico, The history of things, selalu mendahulu the history words.
Karena itu itu jauh sebelum ini, masyarakat Latin menerjemahkan kata cogitare dengan pensare yang berarti andar raccogliendo; pergi mengumpulkan hal atau barang-barang yang ada dalam realitas.
Tindakan berpikir dengan begitu, sama dengan membaca yang berarti menghubung-hubungkan kata-kata yang membentuk sebuah teks. Selanjutnya mengerti/memahami dengan baik satu hal berarti menyatukan semua elemen dari hal tersebut. Sehingga berpikir merupakan sebuah dialog terbuka dan hidup dengan kenyataan.
Dalam nuansa pemikiran Kantian teks adalah representasi dari sebuah Phenomenon yang kelihatan dan dapat dicerap oleh pengalaman manusia. Sementara itu di belakangnya ada Noumenon (Das ding an sich); apa yang ada dalam dirinya sendiri, yang tetap misterius.
Dengan begitu sebuah teks memiliki dua wajah sekaligus; yang kelihatan dan yang dapat dijangkau pada satu sisi serta yang tidak kelihatan dan misterius. Hubungan antara makna yang kelihatan dan yang tidak kelihatan tidak bersifat linear karena bersifat multidimensional, demikian juga ia tidak hitam putih karena sangat majemuk.
Teks bisa menyingkapkan sebuah gagasan mengenai hal tertentu. Tetapi ia juga bisa menyembunyikannya. Demikian pula ia bisa mengungkapkan dengan cara menyembunyikannya atau bahkan menyembunyikan satu hal dengan cara mengungkapkan hal yang lain.
Keserentakan sifat yang tampak dan tersembunyi dari sebuah teks ini membuat teks menjadi hidup dan dinamis. Karena itu membaca sebuah teks berarti berdialog dengan dunia idee dan gagasan, menyelami pemikiran seorang penulis dan berpartisipasi dalam jalinan semesta gagasan yang saling melingkungi.
Toko Buku Terakhir adalah contoh dari proses berpikir itu sendiri yang bersifat terbuka di mana Penulis memakai pendekatan yang bersifat lintas konteks dari sisi ruang, waktu demikian lintas thema seperti agama, budaya, politik, seni dan sastra, sejarah.
Membaca Toko Buku Terakhir berarti menempuh sebuah dialog of mind yang terus berulang dan mendalam antara seorang pembaca yang juga seorang penulis melalui bahasa sebagai alat berpikir.
Dialog of mind seperti ini mengandaikan sebuah kesediaan untuk membaca secara mendalam, sebuah kebiasaan yang kerap bertolakbelakang dengan kebiasaan pencarian informasi pada era digital yang serba instant dan cepat.
Banyak orang beralih dari buku fisik ke buku daring karena keinginan untuk mendapatkan informasi dengan cepat.
Tapi kecenderungan ini dengan mudah mengabaikan keharusan akan kedalaman berpikir yang didapat dari buku-buku fisik. Dengan alasan ini saya, seperti juga penulis, lebih memilih buku-buku fisik ketimbang buku digital (hal. 140-142).
Toko buku terakhir, menjadi semacam ramalan bahwa “toko buku fisik bakal berakhir riwayatnya lantaran orang beralih ke toko buku daring.”(hal. 213). Ada nada kesedihan, terutama bagi para pencinta buku tetapi juga ada harapan.
Sikap narsisme di era digital menjadi alasan kesedihan ini. Tapi tetap ada optimisme dan idealisme (hal. Ix-x). Sebagai seorang pencinta buku, saya tidak yakin bahwa gempuran perangkat digital akan sepenuhnya menggantikan buku fisik.
Karena keduanya adalah sarana yang terbentuk oleh daya pikir manusia. Kendati begitu, Toko Buku Terakhir menantang kita untuk menggalakkan dengan sadar kegiatan olah pikir melalui menulis dan membaca sebagai bentuk literasi paling dasar.
Dengan membaca, menulis dan berpikir setiap peradaban terbentuk dan dengan cara yang sama akan tetap terjaga dan waras. Ini adalah harapan terakhir dari Toko Buku Terakhir, tetapi juga tugas pertama setelah halaman-halamannya kita tutup.
*) Materi ini disampaikan Romo Leo Mali, Pr dalam diskusi bertajuk Literasi di Era Digital dan Diskusi Buku Toko Buku Terakhir di aula Dinas Kominfo Provinsi NTT, Jl. Palapa Kupang, Sabtu 13 Januari 2024.















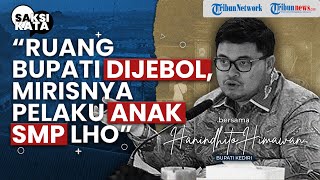





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.