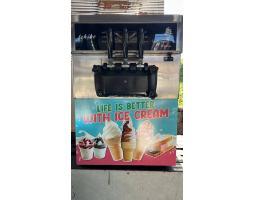Oleh Pius Weraman
AKI, Siapa yang Bertanggung Jawab?
WORLD Health Organization (WHO) memperkirakan 585.000 perempuan meninggal setiap hari akibat komplikasi kehamilan, proses kelahiran dan aborsi yang tidak aman. Sekitar satu perempuan meninggal setiap menit. Hampir semua kasus kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah. Beberapa situasi dan kondisi serta keadaan umum seorang ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas akan memberikan ancaman pada kesehatan jiwa ibu dan janin yang ada di dalamnya.
Angka kematian ibu (AKI) sebagai salah satu indikator derajat kesehatan ibu dewasa ini masih tinggi di Indonesia bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kematian ibu pada tahun 1998 - 2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini paling tinggi di ASEAN. Di Singapura dan Malaysia, tingkat kematian ibu masing-masing hanya sekitar lima dan 70 orang per 100.000 kelahiran.
Tingginya AKI di Indonesia Tersebut erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan selama kehamilan atau persalinan. Selain itu faktor usia, paritas dan juga pendidikan berpengaruh terhadap kematian ibu di seluruh kabupaten/kota.
Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi saat hamil, bersalin atau dalam 42 hari paska persalinan dengan penyebab yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap kehamilan. Di beberapa negara terutama negara berkembang, kehamilan dengan komplikasi merupakan penyebab kematian pada perempuan. Sebagian besar penyebab kematian ibu secara langsung (SDKI 2001 sebesar 90%) adalah komplikasi yang terjadi pada saat persalinan dan segera setelah bersalin. Penyebab tersebut yaitu perdarahan (28%), eklampsi (24%), dan infeksi (11%). Sedangkan penyebab tidak langsungnya antara lain adalah ibu hamil yang menderita Kurang Energi Protein (KEP) dan anemia, dimana kejadian tersebut dapat meningkatkan risiko kematian ibu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, kematian ibu pada tahun 2004 hanya terdapat satu kasus yang disebabkan oleh perdarahan. Sedangkan pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan kasus yaitu menjadi sebanyak 11 kasus dan 10 kasus. Di mana pada tahun 2005 sebesar 72,7% (tujuh kasus perdarahan) di antaranya meninggal akibat perdarahan dan sisanya 27,3% (empat kasus) meninggal akibat penyebab lainnya. Sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 70% (tujuh kasus perdarahan) dari total kematian ibu terjadi akibat perdarahan, dan sisanya 30% (tiga kasus) kematian ibu disebabkan oleh penyebab lainnya (Dinkes Kota, 2006). Sedangkan keseluruhan jumlah kematian ibu hamil/bersalin akibat perdarahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2005 sebanyak 156 kematian (Dinkes Provinsi, 2005).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik RSUD Prof. Dr. WZ Yohanes Kupang, jumlah kasus perdarahan pada ibu hamil/bersalin sebesar 119 kasus pada tahun 2005 dengan jumlah kematian dua kasus. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah kasus perdarahan pada ibu hamil/bersalin sebesar 142 kasus dengan jumlah kematian delapan kasus.
Namun di balik semua penyebab langsung itu terdapat banyak faktor lain yang selama ini juga justeru hadir menjadi akar permasalahan yang sesungguhnya, yakni faktor kemiskinan, termasuk miskinnya pengetahuan, yang dalam banyak aspeknya telah membatasi akses mereka untuk memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan.
Karena kemiskinannya sebagian di antara mereka tak jarang harus terlambat memperoleh pelayanan hanya karena keliru memilih dan menentukan keputusan. Wujud konkritnya meskipun mungkin bidan desa ada didesa tempat tinggalnya sebagian di antara mereka cenderung lebih memilih dukun bersalin yang diharapkan bisa menolong persalinannya. Dalam konteks ini kita semua berdosa karena tidak mampu, bahkan tidak layak disebut gagal dalam mendekatkan pelayanan yang terjangkau lapisan masyarakat.
Fakta berikut lebih tragis dan memrihatinkan adalah seorang ibu X dalam keadaan kritis akibat perdarahan hebat saat melahirkan hanya bisa dengan angkot untuk membawanya ke rumah sakit, pengalaman pahit yang lain adalah ibu Z yang harus dibawa pulang secara paksa dan meninggal di rumah karena memang tidak mampu menyediakan sejumlah biaya yang dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwanya.
Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami oleh kedua ibu tersebut karena selama ini kebijakan-kebijakan belum menyentuh sekaligus menjawab tututan kebutuhan masyarakat miskin.
Alasan yang menyebut bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas setumpuk undang-undang, termasuk berbagai kesepakatan internasional cukup memberikan ketegasan bahwa 'sehat itu adalah hak', bahkan merupakan 'Hak Azasi Manusia' sehingga pemerintah punya kewajiban yang tidak bisa tawar untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kesehatan setiap anggota masyarakatnya sebagai sebuah pertanggungjawaban moral dan politik, bahkan pertanggungjawaban sosial. Bahkan bila kita mencermati Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, pemerintah juga punya kewajiban yang jauh lebih berat lagi karena harus mampu memberikan perhatian khusus kepada kelompok penduduk yang dianggap rentan, yaitu anak dan kaum perempuan.
Sebagai implikasi dari adanya kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi, hak-hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan yang mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau sehingga tidak ada lagi masyarakat yang paling miskin atau bertempat di wilayah terpencil sekalipun, yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan.
Landasan lain tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam pasal yang lain dikatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Tidak saja dituntut untuk tidak saja mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau masyarakat, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang bisa memberi kepuasan kepada masyarakat yang menjadi pelanggannya (customer-driven government). Dalam konteks itulah pemerintah wajib untuk melaksanakan apa yang disebut dengan standar pelayanan minimal (SPM).
Jawaban dari semua ini tidak gampang seperti membalik telapak tangan. Tetapi tidak berarti sulit, apalagi dianggap mustahil untuk dipecahkan. Di situlah peran strategis para wakil rakyat sekarang dan yang akan datang yang melalui tiga fungsinya diharapkan bisa memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam memecahkan sekaligus menjawab masalahnya. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan desentralisasinya yang telah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam bidang kesehatan.
Melalui fungsi legislasinya, pertama, saatnya kini dipikirkan kemungkinan bisa dirumuskannya sebuah peraturan daerah (Perda) yang bisa memastikan bahwa pemerintah daerah yang didukung oleh seluruh kekuatan masyarakat, bahkan didukung pula oleh budaya dan nilai-nilai lokalnya, termasuk kepercayaannya, bisa melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum ibu dan anak dari keluarga miskin yang masih sering terpinggirkan.
Jangan lupa, perda yang mesti dirumuskan itu tidak saja mampu memastikan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, tetapi juga mampu menggugah partisipasi masyarakat, termasuk dunia usaha atau pihak swasta untuk memberikan sumbangan nyatanya dalam pembangunan kesehatan ibu dan anak itu tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah yang memang mempunyai keterbatasan, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pihak swasta.
Melalui fungsi anggarannya, kedua, peran DPRD juga memiliki arti penting tersendiri dalam menjamin pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan kewajibannya melindungi dan melayani hak-hak rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan warganya. Bahkan semua pihak tahu bahwa salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat selama ini bukan miskinnya undang-undang atau rumusan kebijakan yang mengaturnya, melainkan lebih karena masalah anggaran yang belum mendukung implementasinya.
Melalui fungsi pengawasan, ketiga, DPRD juga bisa menyumbangkan peran strtegis untuk melakukan kontrol secara politik guna memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuatnya bisa dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan operasional termasuk aturan pelaksanaannya oleh unsur eksekutif di semua tingkat pemerintahan. *
Dosen FKM Undana & Pengda IAKMI NTT