Opini
Opini: Menyelamatkan Desa Pesisir dari Regulasi Setengah Hati
Artinya, Perdes yang disusun hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif tanpa diiringi dengan komitmen implementasi yang nyata.
Oleh: Try Suriani Loit Tualaka
Peneliti Junior di Institute of Resource Governance and Social Change/IRGSC - Kupang, Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM - Ketika ombak menggulung pantai, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah masyarakat pesisir.
Begitu pula dengan regulasi: ketika kebijakan desa hanya hadir sebagai formalitas, warga pesisirlah yang paling dulu menanggung akibatnya.
Padahal, Peraturan Desa (Perdes) bukan sekadar teks hukum di atas kertas, melainkan simbol otonomi sekaligus instrumen kemandirian desa.
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam mengelola wilayah pesisir yang sarat tantangan sosial, ekonomi, dan ekologi.
Dasarnya kokoh: Perdes diakui dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijabarkan dalam PP 43/2014, hingga teknisnya diatur lewat Permendagri 111/2014.
Baca juga: Opini: Pahlawan yang Terlupakan di Balik Janji Generasi Emas
Namun, semua itu akan sia-sia jika Perdes berhenti sebagai regulasi setengah hati.
Artinya, Perdes yang disusun hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif tanpa diiringi dengan komitmen implementasi yang nyata.
Regulasi yang tidak dijalankan dengan konsisten hanya akan menjadi dokumen formalitas yang tersimpan di laci, tidak mampu menjawab persoalan masyarakat pesisir.
Tanpa dukungan anggaran, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif warga desa, Perdes akan kehilangan daya dorongnya sebagai instrumen tata kelola.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena aturan yang dibuat tidak membawa perubahan konkret bagi kehidupan mereka.
Janji Otonomi dan Realitas yang Membelenggu
Di banyak desa pesisir, lahirnya Perdes justru dibelenggu oleh problem klasik: aparatur yang minim kapasitas, partisipasi publik yang seremonial, dan tarik-menarik kepentingan antara nelayan tradisional, investor pariwisata, hingga elite lokal.
Alih-alih menjadi payung perlindungan bagi masyarakat, Perdes kerap berubah menjadi instrument kompromi politik yang lebih menguntungkan segelintir pihak.
Ironisnya, Perdes yang digadang sebagai wujud nyata otonomi desa justru berulang kali direduksi menjadi aturan yang kehilangan daya paksa karena tumpang tindih dengan regulasi di level kabupaten hingga nasional.
Ketiadaan mekanisme koordinasi dan keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan warga membuat Perdes mandek di atas kertas, sementara ketidakadilan struktural di desa pesisir terus berlangsung tanpa solusi.
Jika dibandingkan, wajah Perdes di pesisir NTT dan Sulawesi Selatan memperlihatkan kontras yang mencolok.
Di NTT, data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023 mencatat sebagian besar Perdes pesisir khususnya di Rote Ndao dan Manggarai Barat berhenti di tahap pengesahan tanpa diikuti implementasi.
Contohnya, Perdes tentang tata kelola rumput laut di Desa Oeseli (Rote Ndao) tidak berjalan karena aparatur desa kesulitan menyusun mekanisme pengawasan dan tidak ada dukungan anggaran yang memadai.
Sebaliknya, di Sulawesi Selatan, beberapa desa di Kabupaten Pangkep dan Takalar berhasil menjadikan Perdes sebagai instrumen nyata.
Perdes zonasi tangkap nelayan di Desa Mattiro Deceng, misalnya, mampu mengurangi konflik antar nelayan karena disusun Bersama nelayan lokal dengan pendampingan perguruan tinggi dan LSM lingkungan.
Fakta ini menegaskan bahwa keberhasilan Perdes bukan semata soal otonomi desa, melainkan bergantung pada kapasitas birokrasi lokal, kualitas partisipasi, dan kuatnya jejaring pendukung di luar desa.
Membaca Tata Kelola Lebih Jauh
Dalam perspektif administrasi negara, Peraturan Desa (Perdes) tidak semata-mata merupakan produk hukum, melainkan cermin dari tata kelola desa.
Ia menggambarkan bagaimana proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dijalankan di tingkat lokal.
Karena itu, kualitas Perdes tidak cukup diukur dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana ia lahir melalui proses yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Administrasi negara menekankan pentingnya policy cycle yang utuh: mulai dari tahap identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi dan pengawasan.
Siklus ini seharusnya berjalan berulang (iteratif) agar kebijakan dapat diperbaiki sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.
Namun, pada banyak desa pesisir, siklus ini kerap terhenti di tengah jalan misalnya hanya sampai tahap perumusan atau pengesahan tanpa diikuti implementasi efektif maupun evaluasi.
Akibatnya, Perdes sering gagal menjadi instrumen keberpihakan dan hanya berakhir sebagai “arsitektur di atas kertas”.
Padahal, idealnya Perdes hadir sebagai wahana penyelarasan kepentingan yang menyeimbangkan kebutuhan nelayan kecil, perempuan pesisir, dan pemuda desa dengan derasnya arus investasi besar yang masuk ke wilayah mereka.
Lebih jauh, Perdes juga menjadi ujian atas sejauh mana desa mampu mempraktikkan good governance di tingkat paling bawah.
Di satu sisi, desa dituntut membuka ruang partisipasi yang bermakna; di sisi lain, ada risiko kooptasi oleh elit lokal atau intervensi kepentingan eksternal, seperti tekanan dari investor besar, arahan sepihak pemerintah supra-desa, atau bahkan pengaruh organisasi politik yang memiliki agenda tertentu.
Bentuk intervensi semacam ini seringkali lebih kuat dibandingkan suara warga biasa. Inilah yang membuat Perdes kerap berada di persimpangan: apakah ia benar-benar menjadi instrument demokratisasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat, atau sekadar perpanjangan tangan
kepentingan segelintir pihak.
Dari kacamata administrasi negara, dinamika ini menegaskan bahwa Perdes bukan hanya teks normatif, melainkan arena politik administratif yang sarat tarik-menarik kepentingan.
Di sinilah kapasitas aparatur desa, budaya birokrasi, dan kesadaran warga berperan penting.
Tanpa kombinasi ketiganya, Perdes sulit keluar dari jebakan proseduralisme sekadar memenuhi kewajiban formal tanpa menciptakan perubahan substantif bagi masyarakat.
Strategi Menguatkan Tata Kelola Desa
Kelemahan tata kelola desa bukanlah sebuah keniscayaan. Administrasi negara menawarkan pisau analisis sekaligus strategi perbaikan.
Untuk menghidupkan Perdes sebagai instrumen politik pembangunan desa, setidaknya ada tiga langkah strategis yang mendesak ditempuh.
Pertama, penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis dalam penyusunan regulasi yang berbasis hukum, data, dan analisis kebijakan.
Kedua, transformasi partisipasi warga dari sekadar formalitas menjadi ruang deliberatif, sehingga suara nelayan, perempuan, dan pemuda menjadi fondasi kebijakan.
Ketiga, sinkronisasi lintas level regulasi, agar Perdes tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan kerangka pembangunan daerah maupun nasional.
Dengan demikian, pisau administrasi negara tidak berhenti pada kritik, melainkan juga membuka jalan strategis.
Keberhasilan Perdes bukan hanya ditentukan oleh aspek legalitas, melainkan sejauh mana ia mampu menjadi instrumen keberpihakan dan tata Kelola desa yang tegak di tengah benturan kepentingan.
Karena itu, penguatan tata kelola desa harus dilihat sebagai investasi jangka panjang: ketika Perdes disusun dengan legitimasi sosial dan basis analisis yang kuat, ia tidak sekadar menjadi aturan tertulis, melainkan menjadi kontrak sosial yang menjaga keberlanjutan pembangunan desa.
Perdes adalah benteng terakhir masyarakat pesisir untuk menjaga ruang hidup, sumber daya, dan masa depan mereka.
Jalan menuju Perdes yang ideal memang tidak sederhana: birokrasi yang rapuh, tarik-menarik kepentingan, hingga kerumitan regulasi kerap menghadang.
Namun, justru di situlah letak strategisnya karena sebuah kebijakan yang lahir dari pergulatan nyata akan jauh lebih berakar dan relevan.
Ketika desa pesisir berani menjadikan Perdes sebagai instrumen keberpihakan, otonomi desa tidak lagi berhenti pada jargon administratif.
Ia menjelma sebagai kenyataan yang bisa dirasakan: desa yang berdaulat atas regulasinya sendiri, teguh menghadapi intervensi, dan berani menata masa depan dengan visi kolektif.
Sebab pada akhirnya, desa yang kuat bukanlah desa tanpa ombak, melainkan desa yang tahu bagaimana menaklukkan gelombang dengan dayung kebijakannya sendiri. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News



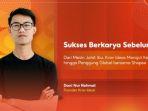










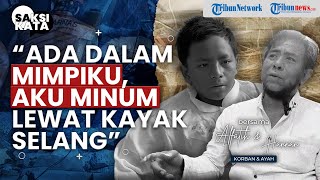




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.