Opini
Opini: Melawan Politik Devide et Impera
Dua kenyataan ini yakni kebodohan dan banyaknya kerajaan dalam wilayah Nusantara dilihat oleh Belanda sebagai peluang untuk menguasai Indonesia.
Oleh: Arnoldus Nggorong
POS-KUPANG.COM - Ketika saya masih duduk di bangku SD, salah seorang guru pernah berkisah tentang keberhasilan Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang begitu lama. Awal mula kedatangan Belanda, ceritanya, adalah mencari wilayah jajahan baru yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya.
Indonesia, ternyata, memenuhi harapan Belanda untuk maksud tersebut. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia sangat kaya. Buktinya adalah penjajah Belanda membawa banyak rempah-rempah ke negerinya yang merupakan hasil dari bumi persada ini.
Pada waktu itu, kondisi rakyat Indonesia masih banyak yang belum mengenal pendidikan. Kompas.com mencatat, pendidikan formal di Indonesia baru mulai sekitar tahun 1901, saat Belanda menduduki Indonesian. Sistem pendidikan ini dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan (kompas.com 17/8/2021). Dengan demikian tidak semua rakyat dapat mengenyam pendidikan.
Ditambah lagi dalam wilayah Nusantara terdapat banyak kerajaan. Dalam sebuah pulau bisa terdiri dari beberapa kerajaan. Ada kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat luas dan ada pula yang wilayahnya kecil. Setiap kerajaan mempunyai otoritasnya sendiri-sendiri.
Dua kenyataan ini yakni kebodohan dan banyaknya kerajaan dalam wilayah Nusantara yang masing-masing memiliki otonomi, tidak tunduk-takluk pada yang lain, dilihat oleh Belanda sebagai peluang untuk menguasai Indonesia. Belanda pun, dengan kecerdikannya, menerapkan politik devide et impera untuk mewujudkan cita-citanya itu.
Dengan lain perkataan, terdapat dua unsur potensial yang membuat persada Nusantara ini dengan mudah dikuasai dan selanjutnya dijajah oleh Belanda yakni warga Nusantara masih terkotak-kotak dalam sistem kerajaan (kurangnya kebersatuan kerajaan-kerajaan) dan keterbelakangan pendidikan warga pribumi Nusantara.
Cerita ini diperoleh pada saat mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (jika tidak salah ingat) sedang berlangsung pada waktu itu, yang dikisahkan oleh ibu guru bernama Agustina Dimu.
Kondisi Indonesia kini
Jika dikaitkan dengan situasi saat ini, kedua faktor tersebut masih menghantui persada Nusantara ini, namun dalam model dan kadar yang berbeda. Di sini ditambahkan lagi satu faktor yaitu kemiskinan. Dengan demikian ada tiga faktor yang masih menemani Indonesia hingga saat ini yakni kebodohan, kemiskinan, dan keterbelahan (yang memiliki padanannya dengan keterpecahan, keterpilahan, disintegrasi).
Kondisi ini menjadi palagan implementasi politik devide et impera yang diperankan kelompok elite tertentu. Pertunjukan politik devide et impera yang amat jelas dan terang benderang adalah dalam peristiwa Pemilu.
Sebagai contoh, sudah umum diketahui bahwa politik uang begitu masif dipraktikkan dalam setiap peristiwa Pemilu terutama sejak diselenggarakannya pemilihan langsung. Bahkan pemilihan kepala desa tak luput dari permainan politik uang, cerita seorang teman.
Dalam hal keterbelahan, Pilpres 2019 menjadi contoh yang sempurna yang mendeskripsikan situasi keterbelahan itu, dan tak kalah paripurna juga adalah Pilkada Jakarta 2017 (lihat tulisan saya ‘Peran Elite Mematangkan Demokrasi’, posku-pang.com 20/4/2023). Perbedaan pilihan politik telah menjerumuskan para pendukung dalam kubu-kubu yang saling bertentangan.
Polarisasi itu tercermin dalam terminus kampret, cebong, kadrun. Setyo Widagdo mengatakan, narasi-narasi yang kontraporduktif justru memperkeruh dan mempertajam keterbelahan itu. Manuver-manuver politik yang dilakukan segerombolan elite pun turut memberi kontribusi di dalamnya (detiknews.com 2/1/2023).
Perihal dukung-mendukung dalam alam demokrasi, pada hakikatnya adalah lumrah. Malah dukungan merupakan suatu keharusan. Namun dukungan baru menjadi masalah mana kala para pendukung sudah terperangkap dalam kondisi yang membuatnya terobsesi yang berlebihan pada pasangan calon yang didukungnya.
Apalagi kalau dukungan yang diberikan pemilih kepada calon kandidat berbasis pada etnis, suku, daerah, agama, budaya, hubungan kekerabatan, baik karena perkawinan maupun hubungan darah, berpenampilan sederhana, tampak ramah, murah senyum.
Kondisi tersebut dalam istilah akademiknya disebut fanatisme. Sebab mereka sudah kehilangan akal sehat dan yang lebih dominan adalah sentimen. Bagi mereka, yang ada adalah hanya dan hanya pilihan (dukungan) saya yang lebih baik.
Pemilu 2024 pun tak lepas dari praktik-praktik kecurangan, keterpisahan para pendukung, termasuk pelanggaran terhadap etika. Demikian pula halnya dengan Pilkada serentak 2024 yang sebentar lagi akan segera dimulai. Dugaan terhadap praktik kecurangan pun akan terus menemaninya.
Yang menarik adalah Pilkada serentak 2024 terdiri dari Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati/Wali Kota-Wakil Wali Kota di seluruh Indonesia. Detik.com merilis, seturut laporan data dari KPU, ada 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada (detik.com 25/4/2024).
Sudah umum pula diketahui, praktik kecurangan selalu menghiasi setiap pemilu dan sudah ‘dipandang’ sebagai hal yang biasa. Lalu mulai ‘berasumsi’ bahwa kecurangan itu dapat pula diterima oleh khalayak. Sebab ada kebenaran umum yang mengatakan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dengan kata lain, alasan tidak ada yang sempurna ‘dianggap’ sebagai pembenaran terhadap praktik kecurangan.
Etika
Sehubungan dengan etika, patut diingat bahwa ia tidak memiliki seperangkat aturan yang tertulis seperti hukum positif dengan urutan 1,2,3, dan seterusnya. Etika lebih sebagai sebuah konsep, yang menjadi penuntun dalam perilaku hidup. Dalam arti yang lebih dalam dan luas, etika tercatat di dalam hati nurani setiap pribadi. Secara intrinsik, etika berpautan dengan adab. Ini mengandaikan adanya kesadaran dari pribadi yang bersangkutan (subjek).
Kesadaran ini hanya diperoleh lewat proses pendidikan. Itulah sebabnya kata terdidik dikenakan pada orang atau sekelompok orang yang telah mengenyam pendidikan dan membatinkannya. Sejumlah pengetahuan yang telah diperoleh dan dipelajarinya, yang kemudian diolah dan diinternalisasi, mengangkatnya menjadi pribadi yang utuh.
Termasuk ajaran tentang pendidikan moral yang paling sederhana itu didapat dari orangtua (mama-bapa) di rumah (keluarga). Pengalaman ajaran dan didikan dalam keluarga sebagai fondasi pertama dan utama pembentukan diri akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan diri individu yang bersangkutan di kemudian hari.
Itu pula yang membedakan manusia dari binatang secara tegas. Aspek kesadaran, keinsyafan inilah yang memberi nilai lebih dan bobot nilai yang tinggi pada manusia yang memiliki martabat yang lebih tinggi daripada segala ciptaan lainnya. Sebab hanya manusia dianugerahi kelebihan itu.
Maka dari itu, ketika ada yang melanggar etika, tidak ada hukuman fisik yang dapat dikenakan kepadanya. Sebab pelanggaran itu berhubungan erat dengan disposisi batin subjek/pelaku yang telah melanggar etika tadi. Bila si pelaku merasa tidak melanggar etika, menurut kata hatinya, maka dia akan merasa nyaman-nyaman saja dan tidak terusik sedikit pun.
Namun patut disadari bahwa kesadaran etis tertinggi dibarengi dengan keyakinan religius yang mendalam akan membuat seseorang merasa tidak nyaman (hatinya selalu terusik) terhadap setiap model kesalahan yang telah dilakukan. Suara hatinya (hati yang bening, jernih) akan selalu menegurnya kapan pun dan di mana saja dia berada. Itulah hukuman untuk dirinya yang bersalah.
Model penjajahan baru
Dengan deskripsi ringkas tentang Pemilu sebagai medan praktik politik devide et impera gerombolan elite tertentu, yang berakar dalam kebodohan, kemiskinan, dan keterbelahan, menemukan maknanya dalam model ‘penjajahan baru’, yang dilakukan oleh sesama warganya sendiri. Dalam formula yang ekstrem, praktik ‘hukum rimba’ ala modern mendapatkan momentumnya. ‘Yang kuat’ menindas ‘yang lemah’. Yang punya uang, kuasa, menguasai yang fakir, tidak beruntung, terpinggirkan.
Kawanan elite itu diakui ‘pintar’ yang didukung pula oleh setumpuk gelar baik akademik maupun gelar kehormatan yang ditempelkan pada namanya. Kepintaran itu ditampakkan dalam kemampuan mengemas isu kesejahteraan sambil mengutip ayat-ayat suci.
Benar bahwa de jure, Indonesia sudah merdeka yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta dengan gagah berani atas nama bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi apakah dengan itu serta merta penjajahan pun sirna dari muka bumi Indonesia?
Bila dicermati secara saksama, penjajahan yang telah berhasil dihapus dari bumi Pertiwi adalah penjajahan dari bangsa asing. Secara faktual, penjajahan oleh sesama bangsa sendiri masih berlangsung hingga saat ini. Model penjajahan baru ini, terkesan, malah semakin menguat. Seolah-olah ‘dibiarkan’. Seakan-akan pula bukan sebuah persoalan. Oleh karena ‘dianggap’ bukan masalah, maka tidak perlu pula ditanggapi secara serius.
Padahal konstitusi kita dengan amat jelas dan terang benderang mengatakan, penjajahan di atas dunia, dalam bentuk apa pun, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan merupakan negasi terhadap pemuliaan martabat manusia.
Pendidikan
Bentuk perlawanan yang paling elegan dan bermartabat adalah meningkatkan kapasitas diri. Peningkatan kapasitas diri dilakukan dengan belajar. Hal yang kelihatannya sederhana. Memang amat sederhana.
Saya teringat lagi akan cerita lanjutan dari sang guru di atas. Pada zaman kemerdekaan ini, katanya, kita tidak perlu lagi mengangkat senjata seperti dilakukan oleh para pejuang sebelum kemerdekaan dahulu.
Kita telah menghirup udara kebebasan untuk mengenyam pendidikan, yang pada zaman penjajahan dahulu susah didapatkan dengan seleluasa sekarang, demikian dia memotivasi. Tuntutlah ilmu sejauh itu dapat dijangkau. Jadikan ilmu sebagai sarana membebaskan diri dari kebodohan, kemiskinan, dan keterceraiberaian. Belajarlah pada ‘ilmu padi’. Semakin berisi semakin merunduk, nasihatnya.
Persis model inilah yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan dahulu. Para tokoh pejuang kemerdekaan adalah mereka yang memanfaatkan pendidikan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka meninggalkan ‘ego’-nya. Mereka tidak mengejar kehormatan, harta-kekayaan. Padahal mereka mendapat tawaran dari Pemerintah Kolonial Belanda untuk bekerja di instansi-instansi Pemerintah.
Yang mereka upayakan adalah kebebasan sebagai nilai tertinggi yang tidak dapat ditakar secara material. Perjuangan untuk memperoleh kebebasan adalah tujuan satu-satunya. Sebab dalam alam kebebasan mereka menemukan jati diri sebagai manusia yang sesungguhnya, sejati, autentik.
Maka dari itu, mereka belajar hingga ke negeri ‘Penjajah’. Mereka mengasah kemampuan diri dengan terus-menerus belajar, sekali lagi, BELAJAR. Pembelajaran itu pun menghasilkan kesadaran kritis dalam diri bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang ditulis dalam preambule UUD 1945.
Penutup
Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk membebaskan diri dari penjajahan dalam bentuk apa pun, termasuk dari praktik politik devide et impera dari sebagian kawanan elite tertentu. Pendidikan pula yang telah membangun kesadaran para pejuang kemerdekaan untuk membebaskan diri dari penjajahan.
Maka dari itu, senjata paling ampuh untuk membebaskan diri dari kondisi itu adalah meningkatkan kemampuan diri dengan belajar. Cukup sederhana. Bukankah karena kebodohan, kemiskinan, dan keterbelahan (disintegrasi) kita mudah dikelabui, suara kita mudah dibayar, kita mudah dimobilisasi, diagitasi, dan diadudomba untuk membenci kelompok di luar kita, hanya untuk membela kepentingan elite tertentu?
Bila kita tidak cepat sadar akan kondisi ini, maka kita akan mudah dipermainkan oleh sekelompok elite tertentu untuk kepentingannya. Kita pun akan gampang terprovokasi untuk membela mereka mati-matian, bahkan mengorbankan nyawa, untuk kepentingan mereka. Lalu mereka menghibur rakyat dengan kata-kata manis seperti “Kemenangan Rakyat, bukan kemenangan kami (elite, partai)”.
Dengan demikian TINGKATKANLAH KECERDASANMU, jangan membiarkan orang lain menunggangi kebodohanmu.
Arnoldus Nggorong adalah alumnus STFK Ledalero, tinggal di Labuan Bajo, Manggarai Barat
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

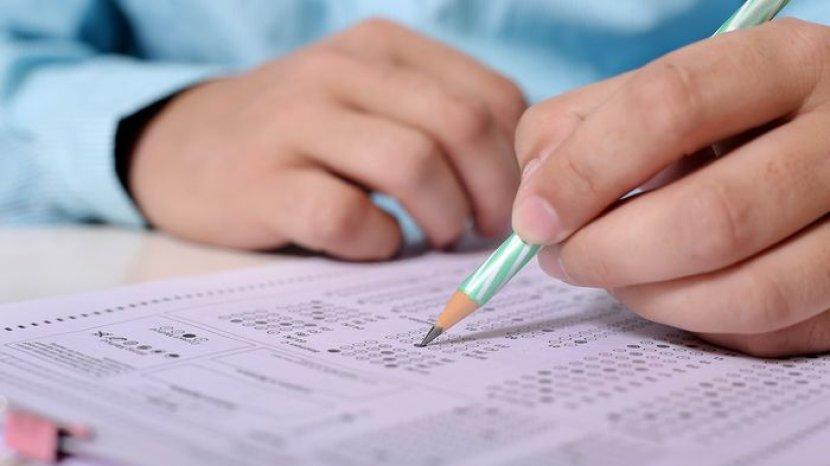














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.