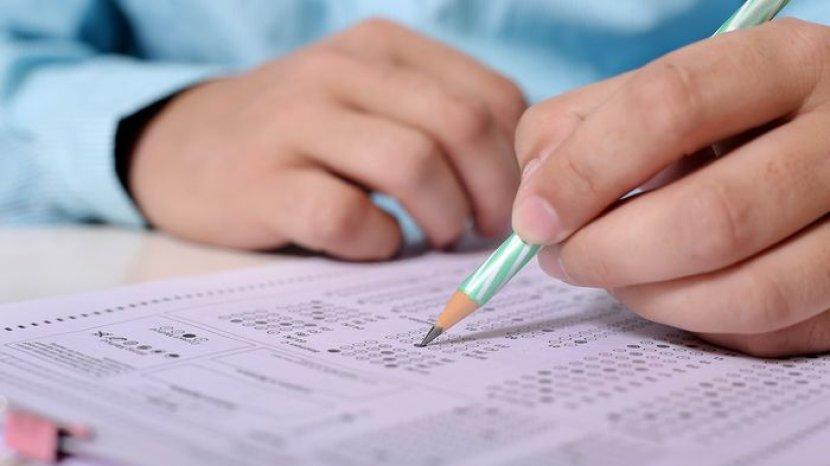Resensi Buku
Iba Anak Sulung Aidit (Resensi Buku)
Membaca buku Iba kita mulai mengerti sesuatu yang saya anggap teramat penting: bahwa orang Komunis pun orang normal-biasa-tidak biadab-manusiawi
Pengalaman paling mengesan didapatinya pada hari buruh tanggal 1 Mei 1970. Iba dan Ilya diundang menyaksikan kembang api di Tian An Men dari tribun VIP. Mendadak ada petugas memanggil mereka, mereka naik lift. Di lantai paling atas mereka ternyata sudah ditunggu oleh Perdana Menteri "kawan" Zhou Enlai yang membawa mereka langsung menemui Mao Zedong Sang Ketua Agung sendiri (Pembesrevnya Revolusi Kebudayaan) yang antara lain didampingi oleh Pangeran Sihanouk, raja Kamboja (yang baru saja dikudeta oleh Jenderal Lonnol dengan dukungan Amerika Serikat), dan istrinya Ratu Monique.
Mao memandang Iba dan Ilya dengan ramah dan hanya mengungkapkan kalimat "Melawan revisionisme adalah baik, harus terus berjuang melawan revisionisme" (revisionisme tentunya "dosa" PKUS).

Dengan tetap menerima perlakuan istimewa sebagai anak Ketua PKI yang dianggap martir Iba dan adiknya kemudian juga ikut bersama dengan pemuda-pemudi Indonesia lain yang terdampar di Tiongkok komunis dikirim ke daerah untuk bekerja di desa. Iba belajar akupunktur dan selama beberapa waktu bekerja dalam rumah sakit pemberontak komunis di Myanmar. 1979 Iba nikah dengan Budiman Sudharsono ("Mas Bud"). Mereka memutuskan pindah ke Makao di mana mereka betul-betul harus hidup dari pekerjaan tangan mereka. Akhirnya perjalanan Iba sebagai pengungsi politik berakhir di Paris.
Buku ini kadang-kadang mengharukan. Kita mendapat pandangan intim ke komunitas orang-orang yang diasingkan karena tak dapat pulang ke tanah air. Iba adalah pengamat yang tajam, dan seperti Ibunya ia tegas dan tidak bersedia berubah haluan dan tetap yakin akan cita-cita ayah, ibu dan partainya. Ia tidak berdebat.
Ia sekali-sekali menyebutkan bahwa di negara-negara komunis juga terjadi hal-hal yang buruk, misalnya dalam Revolusi Kebudayaan di Tiongkok pimpinan Mao. Namun, barangkali ada yang kecewa karena Iba tidak pernah mendiskusikan keberatan-keberatan orang-orang serius non-atau anti-komunis terhadap komunisme, Marxisme-Leninisme, kepemimpinan Mao Zedong di Tiongkok komunis dan lainnya. Iba tidak masuk ke dalam suatu debat teoretis.
Menurut saya itu sebenarnya sesuai logika bukunya. Iba bicara sebagai manusia. Ia tidak mempersoalkan nasib PKI di Indonesia dari sudut politik atau ideologi, tetapi ia mengangkat kejahatan kemanusiaan, keherannya kok orang-orang komunis bisa diperlakukan begitu. Ia kagum dengan sikap tegas ibunya Soetanti. Iba sendiri -tanpa sedikit pun menonjolkan diri -muncul sebagai orang yang berbudi luhur, kuat karakternya, dengan perhatian nyata mendalam untuk orang-orang lemah, dengan rasa keadilan yang tak goyah.

Membaca buku ini saya merasa diperkaya. Buku ini sangat tepat diterbitkan dan diharapkan dibaca banyak orang. Buku ini tidak akan memperdalam perpecahan dalam bangsa Indonesia, melainkan sebaliknya bisa membuat kita sadar bahwa sesuatu seperti yang terjadi sesudah peristiwa Gerakan 30 September tidak boleh terulang lagi, atau, lebih aktual, sadar agar sisa-sisa kecurigaan dan kebencian yang sampai sekarang masih mengancam setiap usaha untuk bersama-sama merefleksikan peristiwa-peristiwa mengerikan itu hendaknya kita lepaskan.
Justru karena buku itu bebas dari segala hasutan dan kebencian serta tenang dan objektif dalam bahasanya, buku ini merupakan sumbangan penting ke arah suatu rekonsiliasi nasional yang hanya mungkin kalau kita berani melihat masa lampau dengan mata, budi dan hati terbuka. *
Data Buku
Judul: Ibarruri Putri Alam, Anak sulung D.N. Aidit
Editor: Joesoef Isak
Pengantar: Goenawan Muhamad
Penerbit: Ledalero 2015
Tulisan ini pernah tayang di Pos Kupang pada 13 September 2015