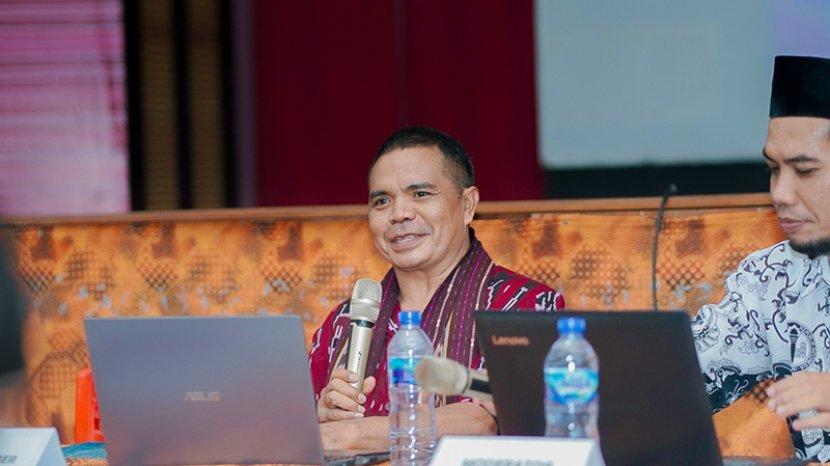Begini Potret Politik Kelas Menengah di NTT
Memotret politik kelas menengah di NTT, tulisan ini mengajukan beberapa argumentasi. Pertama, politik lokal
Oleh: Bene Dalupe
Alumnus Undana, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
POS KUPANG.COM -- Tulisan ini hendak memotret suatu golongan kelompok sosial yang begitu berpengaruh di tingkat lokal. Di antaranya mereka yang paling berkepentingan dalam hajatan politik hari-hari ini.
Penjelasan yang gamblang akan menghantarkan kita untuk menemukan jawaban terkait persoalan kemiskinan atau perubahan sosial yang sepertinya tidak kelihatan.
Memotret politik kelas menengah di NTT, tulisan ini mengajukan beberapa argumentasi. Pertama, politik lokal di NTT merupakan politik elit yang didukung atau bersumber dari kelas menengah.
Kedua, distribusi kesejahteran sosial yang bersumber dari ruang politik negara banyak mengalami hambatan (bahkan pembusukan) di kelas ini. Ketiga, kecenderungan sebagian besar anggota kelas ini terhadap status quo (kemapanan).
Potret Kelas Menengah di NTT
Tidak ada definisi universal mengenai kelas menengah, sebab tidak ada kategori baku yang disepakati para ilmuwan sosial untuk membedakannya dengan kelompok lain.
Tetapi penulis meminjam hasil studi Gerry Van Klinken,dkk (In Search of Middle Indonesia, 2016).
Klinken menyebut kelas menengah dengan istilah "kelas menengah bawah" (lower middle class). Mereka yang ditemukan di kota-kota menengah di Indonesia.
Kota Kupang, merupakan salah satu locus studi Klinken. Jumlah anggota kelas ini tidak sedikit, terdiri dari wiraswastawan atau pengusaha menengah, pegawai swasta dan di sektor publik/milik negara. Anggota-anggota masyarakat terkaya dari kelas ini adalah pengusaha sukses, profesional pendidikan, tokoh agama, dan pejabat senior (birokrat/politisi).
Pada tingkat nasional, posisi tersebut sebagian besar termasuk kelas menengah bawah. Namun di kota mereka sendiri, mereka lebih cenderung dilihat sebagai "elit".
Perdagangan dan pemerintahan mendominasi ekonomi mereka. Mereka boleh disebut sebagai kelas yang beruntung karena pendidikan, status, pendapatan, akses terhadap negara yang mereka dapatkan dibandingkan yang lain.
Temuan Klinken di kota-kota menengah itu mirip dengan di kota-kota kecil kabupaten seperti di Sumba. Jacqueline Vel (Uma Politics, 2008) menyebut dengan istilah `kelas politik' untuk suatu golongan kelompok sosial di Sumba, dimana negara adalah sumber pekerjaan bergaji paling penting dan menjadi sektor utama ekonomi bagi mereka.
Istilah Vel tersebut kiranya jelas membatasi `kelas menengah' yang dimaksud. Karena itu politik lokal adalah tentang distribusi sumber daya negara dan strategi untuk mendapatkan posisi atau akses di/ke pemerintahan
Menurut Klinken, negara merupakan sumber utama pekerjaan mayoritas kelas ini. Keuntungan yang didapatkan umumnya tidak dengan mengontrol alat-alat produksi, tetapi mengontrol rente yang mereka peroleh dari negara atau dari posisi manajerial.
Mereka terlibat aktif dalam politik dengan motivasi untuk mendapatkan kontrol yang lebih langsung atas sumber daya negara. Akses ke kekuasaan melalui jalur birokrasi formal dan sering pula tampak dengan cara-cara informal; pendekatan sosial dan budaya.
Bagi keuntungan atas jabatan formal dilakukan berdasarkan balas jasa politik, kedekatan personal atau atas referensi etnik, agama dan kekerabatan, meluas di kelas ini.
Mereka umumnya tahu atau terlibat dalam praktik manipulasi peraturan, anggaran dan tidak menyukai adanya transparansi dalam penyelenggaraan negara atau urusan yang bersifat publik.
Banyak aktivitas ekonomi ilegal yang berkembang dan berkelindan dalam jaringan sosial dan budaya. Praktik korupsi dan bisnis penjualan manusia (human trafficking), menjadi contoh yang kini sulit diatasi.
Tidak dipungkiri bahwa di luar area formal politik negara, terdapat `masyarakat sipil' (civil society) yang kemunculannya dapat dilihat sebagai bentuk transformasi politik kelas menengah dalam demokrasi (Jati, 2017).
Belum ada argumentasi lain yang cukup kuat selain bahwa kelompok-kelompok ini terfragmentasi (terpecah-pecah) dalam kepentingan, orientasi dan ruang gerak di arena sosial.
Selain bahwa harus diakui banyak di antaranya eksis karena pertalian dengan politik negara atau soal-soal lain yang butuh penjelasan lebih lanjut.
Kepentingan di Pilkada
Pilkada merupakan arena kontestasi politik yang konkret memperlihatkan politik kelas menengah di tingkat lokal.
Pilkada seperti pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati (pilbub) di NTT kelihatan lebih tampak sebagai festival pengulangan janji `elit lokal' lima tahunan. Janji-janji diakselerasi dalam ruang publik oleh mereka yang mayoritas merupakan kelas menengah.
Mereka yang karena pengetahuan, akses, peran dan posisi menjadi orang-orang utama, atau yang paling sibuk dalam kontestasi politik. Di antaranya ada politisi, kontraktor, pengusaha, dan birokrat lintas level, yang langsung maupun tidak, memobilisir dukungan akar rumput pada patronnya.
Politik identitas yang menghantui setiap perhelatan pilkada merupakan politik khas kelas ini. Karena itu pilkada lebih tampak merupakan `politik kekuasaan' dari mereka sering kita sebut sebagai `elit lokal' atau anggota dari kelas menengah ini.
Mereka sangat berkepentingan atas rezim lokal, sebab struktur kekuasaan dan anggaran serta keuntungan yang didapatkan dari keterlibatan dalam politik amatlah jelas.
Struktur anggaran sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, yang merupakan konsumsi utama anggota kelas ini.
Dalam proses birokratik dan politik, praktik korupsi lintas level dan institusi merajalela. Distribusi kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada kantong-kantong kemiskinan di lapisan sosial terbawah menjadi tidak terasa.
Tulisan ini tidak bermaksud menunjukkan pesimisme, bahwa tidak ada sedikitpun politik kerakyatan yang bersumber dari bawah. Tetapi memang, secara politik, peran mereka paling minimal, seperti hanya memberi suara saat pemilu.
Rueschemeyer,dkk (Klinken, 2016) menyatakan bahwa penjelasan tunggal yang paling penting bagi kekurangan dalam demokratisasi di Indonesia adalah peran minimal yang dimainkan orang miskin dalam reformasi pasca 1998.
Perubahan sosial membutuhkan revolusi mental yang nyata dari dalam ruang politik negara, dalam jaringan instisusi formal dan ruang sosial.
Hal itu dapat dimungkinkan bila ada suatu kepemimpinan politik dan birokratik di NTT yang transformatif, bersih dan profesional, yang menginiasi paradigma baru.
Pada sisi yang lain dibutuhkan penguatan peran masyarakat sipil, dengan pelibatan yang lebih nyata dalam arena kebijakan dan pemberdayaan sosial.
Pada aspek yang lebih konkret dibutuhkan aneka cara mengakselerasi pertumbuhan kelas menengah baru di sektor swasta. Mobilitas sosial itu misalnya dengan memaksimalkan potensi kreatif lokal di desa, di jantung kemiskinan kita. *