Timor Leste
Bagaimana Timor Leste Lolos dari Kutukan Sumber Daya Politik
Negara termuda di Asia ini telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak perlu menghambat perkembangan demokrasi yang stabil.
Oleh Moritz Schmoll dan Geoffrey Swenson
POS-KUPANG.COM - Di tengah kemerosotan demokrasi di Asia Tenggara, keberhasilan Timor Leste sungguh mengesankan.
Pada bulan Mei (2023), negara tersebut memilih parlemen baru. Pada bulan Juli, kekuasaan dialihkan secara damai dari Fretilin ke koalisi yang dipimpin oleh Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang dipimpin oleh Xanana Gusmao.
Ini merupakan pemilu parlemen keenam di negara ini sejak kemerdekaannya dari Indonesia pada tahun 2002, dimana pada saat itu para petahana selalu menerima kekalahan di kotak suara dan menyerahkan kekuasaan kepada lawan-lawannya.
Sejak pemilu tahun ini, para pemimpin Timor Leste juga semakin vokal dalam menentang junta militer di Myanmar, meskipun hal tersebut menimbulkan risiko serius terhadap upaya jangka panjang negara tersebut untuk mendapatkan keanggotaan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Komitmen demokratis ini jauh lebih mengesankan dan mengejutkan karena Timor Leste adalah kandidat utama yang terkena “kutukan sumber daya” politik, dimana kekayaan minyak berfungsi untuk menopang pemerintahan otoriter.
Di wajahnya, minyak seharusnya menjadi berkah. Hal ini memberi negara-negara sumber daya yang penting untuk mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi yang sehat dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang populer.
Sayangnya, kenyataannya seringkali berbeda. Dalam banyak kasus, minyak tetap berada dalam pemerintahan otoriter.
Sumber daya seringkali digunakan untuk membangun aparat represif yang kuat dan menyalurkan uang kepada elite politik dan ekonomi.
Banyak negara, mulai dari Venezuela, Equatorial Guinea, hingga Kazakhstan, telah menderita akibat apa yang dikenal sebagai “kutukan sumber daya” secara politik.
Bahayanya nyata, namun tidak bisa dihindari. Negara-negara yang sudah demokratis dan memiliki pemerintahan yang baik sebelum minyak ditemukan seringkali bisa “lolos” dari kutukan tersebut.
Norwegia, misalnya, telah lama menjadi negara demokrasi sebelum mencapai kesuksesan pada tahun 1969.
Alternatifnya, tata kelola sumber daya alam yang baik juga dikatakan dapat membantu.
Dana perminyakan yang dikelola secara teknokratis yang mengisolasi kekayaan sumber daya alam negara tersebut dari para politisi, birokrat, dan jenderal memastikan bahwa dana tersebut tidak dapat digunakan untuk menekan demokrasi atau untuk tujuan jahat lainnya.
Dalam kedua kasus tersebut, negara-negara tersebut cenderung berada di negara-negara Utara.
Namun bagaimana dengan sebagian besar negara kaya minyak di belahan bumi selatan, seperti Timor Leste? Negara-negara ini tidak memiliki sejarah panjang pemerintahan yang demokratis atau baik, maupun konsensus politik yang diperlukan untuk mempertahankan rezim pengelolaan sumber daya yang tidak memihak dan teknokratis.
Ketika Timor Leste memperoleh kemerdekaannya, demokrasi menghadapi banyak rintangan. Negara ini menduduki peringkat sebagai salah satu negara termiskin dan paling terbelakang di dunia.
Terlebih lagi, wilayah ini telah mengalami kolonialisme Portugis selama berabad-abad dan pendudukan brutal dan berdarah selama beberapa dekade oleh Indonesia.
Ketika kemerdekaan akhirnya tercapai, milisi (pro) Indonesia telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara.
Selain itu, sebagai salah satu negara yang paling bergantung pada sumber daya alam, Timor Leste tampaknya sangat rentan terhadap kutukan sumber daya politik.
Baca juga: PM Xanana Gusmao dari Timor Leste Hadiri Forum Negara Kepulauan Denpasar Bali Indonesia
Sejak tahun 2000an, pendapatan hidrokarbon menyumbang rata-rata 40 persen PDB tahunan negara tersebut dan lebih dari 85 persen pengeluaran negara.
Jadi, bagaimana Timor Leste berhasil membangun demokrasi yang dinamis dan mengalahkan kutukan sumber daya politik?
Penjelasan konvensional tidak banyak memberi tahu kita. Ketika minyak ditemukan, negara ini tidak merdeka dan tidak demokratis.
Negara ini menderita akibat penindasan kolonial yang brutal yang berakhir dengan runtuhnya hampir semua institusi fungsional.
Ketika uang minyak benar-benar mulai mengalir ke kas negara yang baru merdeka pada awal tahun 2000an, negara tersebut baru saja merdeka dan tentu saja belum ada sistem demokrasi yang terkonsolidasi.
Memang benar, pada tahun 2006, negara ini menghadapi krisis politik yang sangat parah sehingga pasukan penjaga perdamaian internasional harus dikerahkan untuk mengakhirinya.
Pengelolaan sumber daya alam di negara ini jelas tidak optimal. Negara Timor Leste memiliki kendali penuh atas pendapatan hidrokarbon.
Awalnya, mereka membentuk dana minyak nasional untuk mengelolanya secara berkelanjutan. Pemerintah dilarang mengambil uang lebih cepat daripada dana yang dapat diisi kembali.
Namun meskipun mendapat pujian luas dari para pengamat internasional, pengaturan ini tidak bertahan lama.
Dengan cepat, pemerintah mulai menarik dana dalam jumlah besar untuk hal-hal seperti pensiun bagi para veteran perjuangan kemerdekaan – sebuah konstituen politik utama – atau pekerjaan baru di sektor publik.
Ironisnya, justru pada fase awal pengelolaan sumber daya minyak yang “berkelanjutan” inilah ketidakpuasan di kalangan tentara berkembang menjadi kekacauan dan kekerasan yang meluas sehingga eksperimen demokrasi di Timor Leste berada di ambang kehancuran pada tahun 2006.
Setelah itu, pemerintah membuka diri dana minyak bumi, dan sejak itu, demokrasi semakin kuat.
Jika penjelasan dominan tidak bisa menjelaskan kisah sukses Timor Leste, lalu apa yang bisa menjelaskannya?
Melihat lebih dekat aktor-aktor politik yang muncul dari perjuangan kemerdekaan dapat membantu.
Pertama, karena Fretilin dan CNRT – dua partai politik dominan – memiliki akar yang kuat dalam perjuangan melawan pendudukan Indonesia, keduanya mempunyai legitimasi rakyat yang tinggi.
Namun tidak seperti gerakan pembebasan kolonial lainnya, mereka selalu berkomitmen tinggi secara ideologis terhadap demokrasi liberal.
Hal yang sama tidak berlaku pada beberapa tokoh kemerdekaan pasca-kolonial seperti Gamal Abdel Nasser dari Mesir atau Robert Mugabe dari Zimbabwe.
Selain itu, fakta bahwa tidak ada faksi politik yang hegemonik dalam lingkup politik Timor Leste terbukti menjadi keuntungan bagi masa depan negara tersebut.
Di negara-negara lain, para pemimpin dan gerakan kemerdekaan secara efektif memonopoli perwakilan politik, sehingga memudahkan terbentuknya sistem otoritarian.
Sebaliknya, sifat gerakan kemerdekaan Timor Leste yang terfragmentasi mendorong para aktor untuk mencari lembaga-lembaga politik yang tidak bersifat pemenang-ambil-semua.
Ketakutan akan kepresidenan yang kuat atau parlemen dengan mayoritas yang tidak proporsional sangatlah kuat.
Lagi pula, tidak ada politisi yang mau mengambil risiko dikesampingkan dalam beberapa tahun pertama setelah kemerdekaan.
Sebaliknya, kekuatan politik Timor Leste memilih sistem semi-presidensial di mana presiden yang relatif lemah harus berhadapan dengan parlemen kuat yang dipilih melalui perwakilan proporsional.
Meskipun pemerintahan koalisi kadang-kadang terpecah, sistem ini sangat stabil, dan partai-partai politik selalu tunduk pada kekalahan dalam pemilu, salah satunya karena mereka yakin akan ada peluang untuk merebut kembali kekuasaan di masa depan.
Tentu saja, dalam konteks pasca-konflik, dan khususnya ketika akses terhadap sumber daya alam dipertaruhkan, aktor-aktor eksternal sering kali berupaya untuk mempengaruhi hasilnya.
Sekali lagi, yang cukup mengejutkan, di Timor Leste, komunitas internasional secara umum memainkan peran yang konstruktif.
Hal ini memberikan keamanan penting selama transisi menuju kemerdekaan melalui penyediaan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Hal ini juga memberikan bantuan yang sangat berharga dalam membangun kembali infrastruktur yang ada, membangun lembaga-lembaga baru, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
Pada saat yang sama, aktor-aktor asing menahan diri untuk tidak ikut campur dalam politik nasional dengan memilih pemenang yang tidak populer atau tidak sah, seperti yang mereka lakukan di Afghanistan atau Irak.
Dalam hal ini, Timor Leste mungkin beruntung karena dianggap “biasa-biasa saja” – menjadi sebuah negara yang tidak memiliki kepentingan tertentu oleh negara-negara besar.
Singkatnya, Timor Leste tentu saja terus menghadapi tantangan ekonomi, pembangunan, dan politik yang serius.
Demikian pula, korupsi terus menghadirkan tantangan yang sangat nyata.
Ini bukanlah utopia. Namun fakta bahwa Timor Leste telah mengkonsolidasikan demokrasi melawan segala rintangan memberikan pesan optimis bagi negara-negara lain.
Timor Leste yang demokratis juga menantang ortodoksi yang ada mengenai apa yang disebut kutukan sumber daya politik. Sebuah negara yang sangat bergantung pada sumber daya dan tidak memiliki sejarah pemerintahan yang “baik” masih dapat mengkonsolidasikan demokrasi.
Terlebih lagi, pengelolaan kekayaan minyak yang sangat hati-hati dan teknokratis tampaknya juga tidak diperlukan.
Ya, pendapatan minyak bisa digunakan untuk penindasan dan patronase.
Namun Timor Leste mengajarkan kepada kita bahwa jika kekayaan sumber daya tidak memberikan manfaat nyata bagi warga negara, maka masyarakat hanya akan melihat sedikit manfaat dari transisi demokrasi.
Pada akhirnya, kekayaan minyak adalah hasil keuntungan negara.
Memang benar, kisah Timor Leste menunjukkan kekuasaan atas takdir. Pelaku dalam negeri diberi insentif untuk memilih institusi yang kondusif bagi demokratisasi seperti perwakilan proporsional, namun mereka juga memilih untuk mematuhi aturan dan benar-benar berkomitmen pada demokrasi liberal.
Komunitas internasional juga harus menaruh perhatian. Ketika mereka serius dalam mendukung pemerintahan demokratis, Timor Leste menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan dampak positif bahkan dalam kondisi yang sangat sulit.
Tentang penulis:
Moritz Schmoll adalah Asisten Profesor Ilmu Politik di Universitas Politeknik Mohammed VI di Rabat, Maroko, dan Visiting Fellow non-residen di Departemen Pembangunan Internasional London School of Economics.
Geoffrey Swenson adalah Associate Professor Politik Internasional di City, Universitas London, British Academy Mid-Career Fellow, dan Non-Resident Fellow di Eurasia Group Foundation.
(thediplomat.com)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

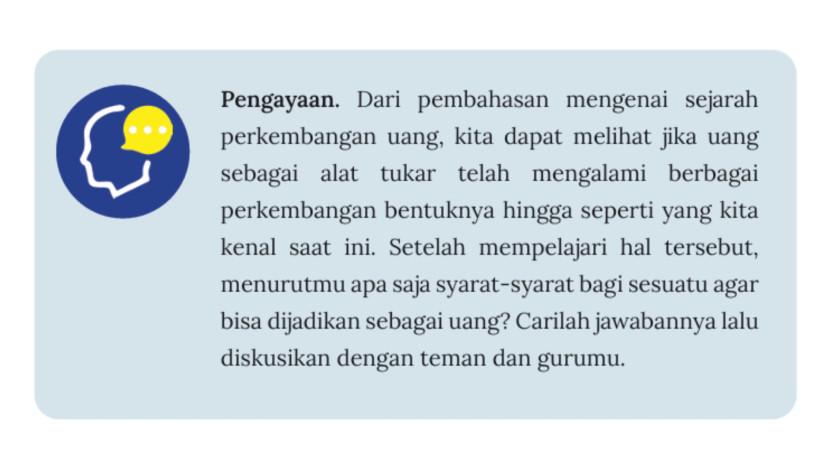









![[FULL] Kursi Menpolkam Budi Gunawan yang Belum Diisi Presiden saat Reshuffle, Pakar: Ada Prof Mahfud](https://img.youtube.com/vi/1heRJr2NdnY/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.