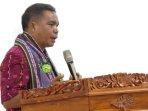Menegakkan Moralitas Pembangunan
Pembangunan di berbagai bidang telah membawa dampak positif maupun negatif bagi manusia.
Oleh: Dr. Rahmat Laan, MM
Dosen FE Universitas Muhammadiyah Kupang
PEMBANGUNAN, dalam lintasan sejarah kehidupan manusia, selalu hadir dalam dua wajah yang berbeda. Di satu sisi ia mengantarkan manusia dalam sebuah suasana kehidupan yang maju, sejahtera, dan menyenangkan, tetapi di sisi lain ia seperti "monster" yang melibas habis siapapun yang ada di depannya tanpa mengenal ampun. Terhadap sisi positifnya, hampir semua kita tidak berbeda pendapat bahwa pembangunan harus terus berlangsung. Namun ketika diperhadapkan pada dampak negatifnya, masyarakat mulai terpecah dalam pandangan yang saling berlawanan. Ada kelompok yang berpandangan pembangunan harus tetap dilaksanakan dengan argumentasi: pembangunan memiliki dampak ekonomi jangka panjang yang sangat menguntungkan masyarakat dan pemerintah, seperti bertambahnya pemasukan melalui pajak, terbukanya lapangan pekerjaan, dan hadirnya potensi usaha baru bagi masyarakat. Pandangan seperti ini biasanya muncul dari kalangan kelas atas yang punya kepentingan, dan kelas menengah yang memandang pembangungan merupakan kemajuan, maka sudah semestinya tetap berjalan sebagaimana adanya. Pengorbanan merupakan konsekuensi dari adanya pembangunan yang dapat dicarikan jalan keluarnya. Disamping itu, mereka beranggapan bahwa pembangunan akan mendatangkan keuntungan di masa depan seperti akses transportasi dan distribusi yang mudah, serta menjadi suatu kebanggaan tersendiri atas kemunculan "landmark" baru di tempat dimana pembanguan itu dilakukan.
Sementara kelompok yang menolak beranggapan bahwa pembangunan yang dijalankan mengabaikan nilai kemanusiaan dan ketidakpedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Kelompok yang didominasi oleh kelas menengah terdidik ini sadar bahwa korporasi akan menempuh segala daya dan upaya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sehingga lebih banyak "menindas" daripada membangun. Masih segar dalam ingatan kita kasus kebakaran hutan di Sumatra, yang diduga didalangi oleh 276 perusahaan, telah menyebabkan hilangnya aset pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kasus reklamasi Teluk Jakarta yang bukan berorientasi kesejahteraan rakyat, tetapi konglomerasi disinyalir telah memporakporandakan ekosistem laut dan cenderung menghancurkan Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi kawasan strategis nasional. Tidak dapat disangkal bahwa kasus terbunuhnya Salim Kancil di Desa Selok Awar-awar Probolinggo berkaitan erat dengan kegiatan penambangan pasir besi yang merusak lingkungan di sekitar daerah tersebut. Kasus vaksin palsu yang masih terus bergulir hingga saat ini justru melibatkan pelaku-pelaku pembangunan di bidang kesehatan, tampaknya telah mengorbankan kesehatan ratusan bahkan ribuan generasi masa depan, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa.
Reaksi penolakan terhadap pembanguanan yang mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan bukan hal yang baru. Jauh sebelumnya, reaksi serupa sudah ada. Sebut saja Rachel Louise Carson, Donella H. Meadows, dkk dan René Dubos dan Barbara Ward adalah sosok-sosok yang tampil mengingatkan dunia tentang ancaman kemanusiaan dan kerusakan lingkungan sebagai akibat pola pembangunan big government yang diterapkan baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju pasca Perang Dunia II. Carson mengingatkan dalam bukunya The Silent Spring (1962) : (1) alam terbatas kemampuannya dalam hal meresap polusi yang dihasilkan pembangunan yang tidak terkendali; (2) penggunaan DDT (dichloro-diphenyl-trichloroethane) sebagai pestisida di bidang pertanian mengakibatkan malapetaka yang mengancam kehidupan; (3) DDT menyebabkan kanker dan menghambat reproduksi burung karena kulit telurnya menipis. Dalam nada relatif sama, Meadows, dkk mengetuk hati manusia dalam buku The Limits to Growth (1972) bahwa kemungkinan terjadi malapetaka akibat hubungan saling mempengaruhi antara kegiatan industrialisasi, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, malnutrisi, terkurasnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan kerusakan lingkungan. Jika kecenderungan pertumbuhan yang ada pada jumlah penduduk dunia, industrialisasi, polusi, produksi bahan makanan, dan penghancuran sumberdaya tidak berubah, maka batas pertumbuhan di bumi ini akan dicapai dalam 100 tahun mendatang. Kemungkinan yang paling mungkin terjadi ialah penurunan tiba-tiba yang tidak terkendali pada jumlah penduduk dan kapasitas industri. Sementara Dubos dan Ward dalam buku Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet (1972), selain membunyikan lonceng tanda bahaya tentang dampak kegiatan pembangunan terhadap biosfir, juga menginginkan kepedulian bersama terhadap planet bumi yang membentuk masa depan bersama yang diidamkan.
Di samping itu tampil juga berbagai kelompok pendukung kelestarian lingkungan seperti The Club of Rome (1968), Greenpeace di Kanada (1971) dan International Institute for Environment and Development (IIED) di Inggris (1971). The Club of Rome bertujuan mencapai pemahaman menyeluruh tentang masalah-masalah dunia, yang tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri oleh individu dan negara nasional. Kelompok ini menggagaskan model kajian pada tingkat global tentang interaksi antara produksi industri, jumlah penduduk, kerusakan lingkungan, konsumsi makanan dan penggunaan sumberdaya alam. Kelompok Greenpeace melancarkan kegiatan yang agresif untuk menghentikan kerusakan lingkungan melalui berbagai unjuk rasa dan intervensi tanpa kekerasan terhadap pemerintah dan dunia usaha/korporasi. Sedangkan IIED bertujuan mencari cara mencapai kemajuan ekonomi tanpa merusak lingkungan sebagai pemasok sumber daya.
Aspirasi dan "tekanan" yang disalurkan melalui buku dan kelompok-kelompok tersebut akhirnya mencapai klimaksnya pada tahun 1983 dimana PBB membentuk The World Commission on Environment and Development di bawah komando Gro Harlem Brundtland, mantan perdana menteri Norwegia, dengan tujuan mempelajari lingkungan hidup yang kian tercemar, terkurasnya sumberdaya alam dan dampak negatifnya pada pembangunan ekonomi dan sosial. Hasil kajian komisi ini disampaikan dalam laporan yang berjudul Our Common Future. Laporan ini menjadi dasar diadakannya Pertemuan Puncak tentang Bumi (Earth Summit Meeting) yang pertama di Rio de Janeiro tahun 1992, yang melahirkan Rio Declaration yang memuat konvensi keanekaragaman hayati, kerangka konvensi tentang perubahan iklim, prinsip-prinsip pengelolaan hutan, agenda 21 dan deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan. Pertemuan di Rio de Janeiro 1992, selanjutnya dilaksanakan di New York tahun 1997, di Johannesburg Afrika tahun 2002, dan berbagai pertemuan lainnya dan akhirnya bermuara di Copenhagen pada tahun 2009. Pertemuan Copenhagen ini adalah salah satu tonggak sejarah dalam pemikiran manusia yang akan menentukan perkembangan masa depan bumi.
Pertanyaannya, mengapa pembangunan yang cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan terus saja terjadi di Indonsia, padahal penolakan terhadap pola pembangunan semacam itu sudah menjadi perhatian dunia dan sudah berlangsung sejak dahulu kala. Banyak pilihan jawaban yang mungkin untuk pertanyaan ini, tetapi satu yang pasti adalah para pelaku pembangunan tampaknya telah mengabaikan moral dan etika dalam proses pembangunan. Pelaku pembangunan seperti lebih terfokus pada "kitab suci" korporasi yaitu profit, sehingga tidak tersisa sedikitpun akal sehat dan nurani yang menyadarkan bahwa boleh saja membangun untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi jangan mengorbankan kebutuhan generasi masa depan, karena dunia ini hanya satu saja.
Moral dan etika dalam pembangunan (Siagian, 2008) antara lain mencakup hal berikut: pertama, tidak membenarkan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuan, karena akan merusak dasar dan tujuan mulia dari pembangunan; kedua, hendaklah seseorang bersikap setia terhadap negara, bangsa, pemerintah, organisasi tempat seorang melakukan kegiatan, atasan, rekan setingkat dan juga kepada mereka yang berada di lapisan bawah; ketiga, jujur terhadap diri sendiri, organisasi, mitra kerja, dan masyarakat luas. Implementasi kejujuran ini adalah menjaga komitmen dalam semua bidang kegiatan dan profesi; keempat, adanya iklim keterbukaan yang intinya adalah keinginan untuk saling mendukung dan mempercayai. Iklim keterbukaan itu mencakup perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, tanggung gugat (accountability) dan pengenaan sanksi disiplin kepada siapapun warga negara yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati; kelima, ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Apabila ketaatan terhadap perundang-undangan telah menjadi bagian dari sikap hidup dalam pembangunan, maka hal itu berarti setiap orang telah dapat memiliki kemampuan kontrol internal dalam dirinya untuk meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan.
Tumbuhnya kesadaran terhadap moral dan etika tidak cukup kuat apabila hanya mengandalkan kekuatan logika dan rasionalitas. Kepribadian yang dibangun atas pertimbangan logika semata hanya akan melahirkan cara pandang pragmatisme, yaitu melihat ukuran kebenaran hanya pada kepentingan sesaat, sepanjang membawa keuntungan materi. Hal ini disebabkan karena jangkauan pemikiran manusia yang berpola pikir pragmatis hanya mengejar tujuan yang bersifat materi. Akibatnya berbagai alat kendali pembangunan tidak cukup mampu melakukan kontrol terhadap perilaku para penyelenggara pembangunan.
Oleh karena itu, solusinya tidak lagi memadai sekedar membangun kecerdasan dan keterampilan. Diperlukan pendekatan lain, yaitu agama, sesuatu yang bersifat holistik dan komprehensif yang menjelaskan arti dan tujuan hidup. Agama adalah pedoman hidup yang menjelaskan rangkaian tiga kehidupan yaitu alam embriologi azali, alam dunia dan alam akhirat. Akhirat adalah tempat pembalasan terhadap semua perilaku yang diperbuat manusia ketika berada di alam dunia. Namun, agar agama dapat menjadi solusi bagi masyarakat modern, maka selayaknya metode penyajian agama disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Kebahagiaan hidup bukan diukur dari materi yang melimpah, akan tetapi semata-mata terletak pada kedekatan diri kepada Tuhan dengan menjunjung tinggi segala perintah dan menjauhi segala laranganNya.
Persepsi pembangunan demikianlah yang akan mengantarkan kepada kehidupan pembangunan yang berangkat dari moral dan etika guna menghasilkan pembangunan yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin.*