Opini
Opini: Potensi Cacat Hukum dalam Penetapan Tersangka Nadiem Makarim
Timbul pertanyaan serius mengenai dasar hukum dan prosedur formil yang digunakan dalam penetapan tersebut.
Oleh: Fakhlur
Direktur Humanity Law Firm, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
POS-KUPANG.COM- Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dituduh telah melakukan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022.
Penyidik menduga ada beberapa modus yang terjadi dalam kasus itu antara lain penggelembungan harga, dan pemaksaan penggunaan produk tertentu dengan kerugian negara sekitar Rp 1,92 triliun.
Atas perbuatannya, Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 untuk Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Meski demikian, penetapan tersangka terhadap menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berpotensi cacat hukum.
Pra Peradilan
Dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Baca juga: Jadi Tersangka, Nadiem Makarim: Tuhan Melindungi Saya, Kebenaran akan Keluar
Pembahasannya adalah, Pertama, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan.
Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan.
Prof M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), menyebut praperadilan sebagai pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum.
Praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilandengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung.
Hukum acara dirancanguntuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan.
Setiap prosedur dalam due process of law menguji dua hal: Apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur dan jika menggunakan prosedur?
Apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process?
Sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, yang pada halaman 30 menyatakan, “...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;”.
Dengan kata lain, Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, Terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Tiga Perspektif
Penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Makarim (NAM), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook tahun 2019–2022, yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta diklaim menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,98 triliun.
Timbul pertanyaan serius mengenai dasar hukum dan prosedur formil yang digunakan dalam penetapan tersebut.
Keraguan itu cukup beralasan apabila dikaitkan dengan fakta empiris bahwa kebijakan pengadaan Chromebook pada dasarnya merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan pendidikan nasional.
Pertama, dari perspektif anggaran. Chromebook lebih ekonomis dibandingkan perangkat konvensional, sehingga sejalan dengan keterbatasan alokasi dana pendidikan.
Kedua, dari aspek implementasi. Teknologi berbasis cloud yang melekat pada Chromebook memungkinkan efisiensi distribusi sekaligus mempercepat realisasi program, terutama dalam konteks darurat pandemi COVID-19.
Ketiga, dari segi relevansi kebutuhan. Spesifikasi Chromebook dinilai cukup memadai untuk mendukung pembelajaran daring secara luas.
Berikutnya persoalan yuridis mengenai keabsahan alat bukti, bahwa dalam hukum pidana Indonesia, penetapan tersangka wajib didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dipertegas dalam ketentuan pasal 1 butir 14 KUHAP dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 halaman 109 yang berbunyi frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
Lebih jauh, klaim kerugian negara Rp1,98 triliun tidak ditopang oleh hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), padahal Pasal 23E UUD 1945 juncto Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan bahwa BPK adalah lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Hal ini juga dipertegas melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam rumusan hukum keenam menyatakan bahwa instansi lain tidak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan kerugian negara.
Selaras dengan itu, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan temuan instansi berwenang, sehingga klaim sepihak tidak dapat dijadikan dasar sah dalam penetapan tersangka.
Apabila dikaitkan dengan pasal yang disangkakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dipidana, sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan juga dapat dipidana.
Kedua pasal tersebut sama-sama mengandung unsur “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” yang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, harus dimaknai bahwa kerugian negara wajib dibuktikan secara nyata serta harus dapat dihitung oleh ahli di bidang keuangan negara, perekonomian negara, maupun ahli yang mampu menganalisis hubungan kausal antara perbuatan seseorang dengan timbulnya kerugian negara.
Dengan demikian, tanpa adanya pembuktian kerugian negara yang sah dan pasti, unsur delik dalam pasal yang disangkakan menjadi tidak terpenuhi secara hukum.
Tak Terima SPDP
Selanjutnya apabila diduga benar Kejaksaan Agung menetapkan NM sebagai tersangka pada 4 September 2025 bertepatan dengan keluarnya SPRINDIK, tetapi hingga kini NM tidak pernah menerima SPDP, maka terdapat persoalan serius terkait sah atau tidaknya proses penyidikan.
Pertama, sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dimulainya suatu penyidikan.
Kewajiban tersebut kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa SPDP juga wajib disampaikan kepada tersangka dan korban dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya perintah penyidikan.
Artinya, tidak disampaikannya SPDP kepada tersangka merupakan bentuk pelanggaran prosedur hukum acara pidana.
Kedua, secara logika hukum, jika tersangka tidak menerima SPDP, maka ia kehilangan hak fundamental untuk mengetahui dasar penyidikan terhadap dirinya.
Akibatnya, hak membela diri (right to defense) menjadi terlanggar, karena tersangka tidak mendapat kesempatan yang adil untuk menyiapkan pembelaan sejak awal.
Penetapan tersangka seharusnya dilakukan dalam tahap penyidikan, sebab penyidikan merupakan proses pro justitia yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti, menentukan tersangka, serta melakukan upaya paksa apabila diperlukan.
Dengan demikian, apabila penetapan tersangka dilakukan pada saat masih berada dalam tahap penyelidikan, maka tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan KUHAP, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip due process of law.
Selain itu, penyelidik secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka, karena kewenangan itu baru lahir pada tahap penyidikan dengan syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tersebut memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta agar memenuhi asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup.
Oleh karena itu, secara argumentatif dapat ditegaskan bahwa penetapan tersangka yang hanya didasarkan pada hasil penyelidikan merupakan bentuk penyimpangan prosedural.
Tindakan demikian dapat dikualifikasi sebagai cacat hukum karena mengaburkan batas yang telah ditetapkan oleh KUHAP antara penyelidikan dan penyidikan.
Dengan kata lain, secara yuridis, penetapan tersangka hanya sah apabila dilandasi bukti permulaan yang cukup yang diperoleh pada tahap penyidikan, bukan berdasarkan hasil penyelidikan yang hanya berfungsi sebagai tahap awal untuk memastikan keberadaan suatu peristiwa pidana.
Lebih lanjut, penetapan tersangka tanpa memenuhi syarat bukti yang memadai merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, prinsip equality before the law, serta asas in dubio pro reo, sehingga praperadilan hadir sebagai instrumen konstitusional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Preseden yurisprudensi juga menunjukkan hal serupa, seperti dalam kasus Budi Gunawan (PN Jaksel No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.) di mana hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak memenuhi syarat bukti, serta kasus Hadi Poernomo (PN Jaksel No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.) yang membatalkan penetapan tersangka akibat cacat formil dan material.
Dari perspektif kerangka berpikir hukum, pemenuhan sekurang-kurangnya dua alat bukti merupakan suatu keharusan yang memiliki landasan yuridis yang kokoh.
1. Dari sudut asas legalitas, setiap tindakan penegak hukum harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip nulla poena sine lege menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas.
Dalam konteks ini, Pasal 184 KUHAP secara tegas mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga pengabaian terhadap ketentuan tersebut sama dengan mengingkari hukum itu sendiri sekaligus melanggar prinsip legalitas dalam hukum pidana.
2. Dari perspektif asas kepastian hukum dan keadilan, hukum pidana tidak boleh dijadikan instrumen untuk menekan atau merugikan individu tanpa dasar bukti yang jelas dan memadai.
Asas ini selaras dengan prinsip equality before the law yang menjamin setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, serta asas in dubio pro reo yang menghendaki agar setiap keraguan dalam pembuktian harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa.
Dengan demikian, terpenuhinya dua alat bukti bukan hanya syarat formil, melainkan juga jaminan substansial agar proses peradilan berjalan adil, transparan, dan tidak menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri.
3. Berdasarkan asas perlindungan hak asasi manusia, keberadaan standar pembuktian minimum menjadi mekanisme penting untuk mencegah potensi kriminalisasi maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Dalam konteks ini, hak-hak tersangka juga dijamin melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, maupun penetapan status tersangka.
Dengan demikian, prinsip dua alat bukti bukan hanya persoalan teknis dalam pembuktian, melainkan juga merupakan jaminan fundamental atas tegaknya hukum yang adil, sekaligus bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat.
Hukum Publik Administrasi
Prinsip tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kasus pengadaan Chromebook yang dijadikan dasar penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka.
Pada hakikatnya, pengadaan tersebut merupakan bagian dari tindakan hukum publik administratif, bukan perbuatan pidana.
Dalam doktrin hukum administrasi negara, pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi kebijakan (beleid discretion) dalam menjalankan tugas pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Diskresi ini merupakan instrumen sah untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat dan memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945.
Sejalan dengan itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum.
Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam implementasi kebijakan pengadaan Chromebook, mekanisme penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui jalur administratif, yakni audit BPK, evaluasi kebijakan, atau pengawasan inspektorat, bukan melalui kriminalisasi pejabat publik.
Lebih lanjut, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menegaskan pemisahan ranah hukum administrasi dari hukum pidana.
Pemisahan ini ditegaskan melalui Pasal 21 UU AP yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentukan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan.
Artinya, forum yang tepat untuk menguji dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pengadaan Chromebook adalah PTUN, bukan peradilan pidana.
Dengan demikian, menempatkan kebijakan publik yang bersifat administratif sebagai dasar penetapan tersangka jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, karena telah mengaburkan batas yurisdiksi antara hukum administrasi dan hukum pidana.
Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip due process of law, tetapi juga melanggar asas ultimum remedium, di mana hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum lain telah terbukti tidak memadai.
Oleh sebab itu, dalam situasi ketika penetapan tersangka dilakukan tanpa memenuhi standar minimum pembuktian dan bahkan mendasarkan diri pada kebijakan administratif yang sah, maka pengajuan praperadilan bukan sekadar pilihan, melainkan menjadi sebuah keharusan.
Praperadilan berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, sekaligus memberikan perlindungan yuridis terhadap hak-hak individu agar tidak dikorbankan oleh tindakan sewenang-wenang.
Dengan demikian, praperadilan hadir sebagai mekanisme yang tidak hanya menjamin tegaknya prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan, tetapi juga memastikan bahwa hukum pidana tidak disalahgunakan untuk tujuan di luar semangat penegakan hukum yang adil.
Apabila dikabulkan, putusan praperadilan tersebut akan menjadi langkah yang tepat demi menjaga integritas sistem peradilan pidana, mencegah kriminalisasi kebijakan publik, dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (rule of law) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News







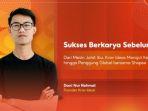












Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.